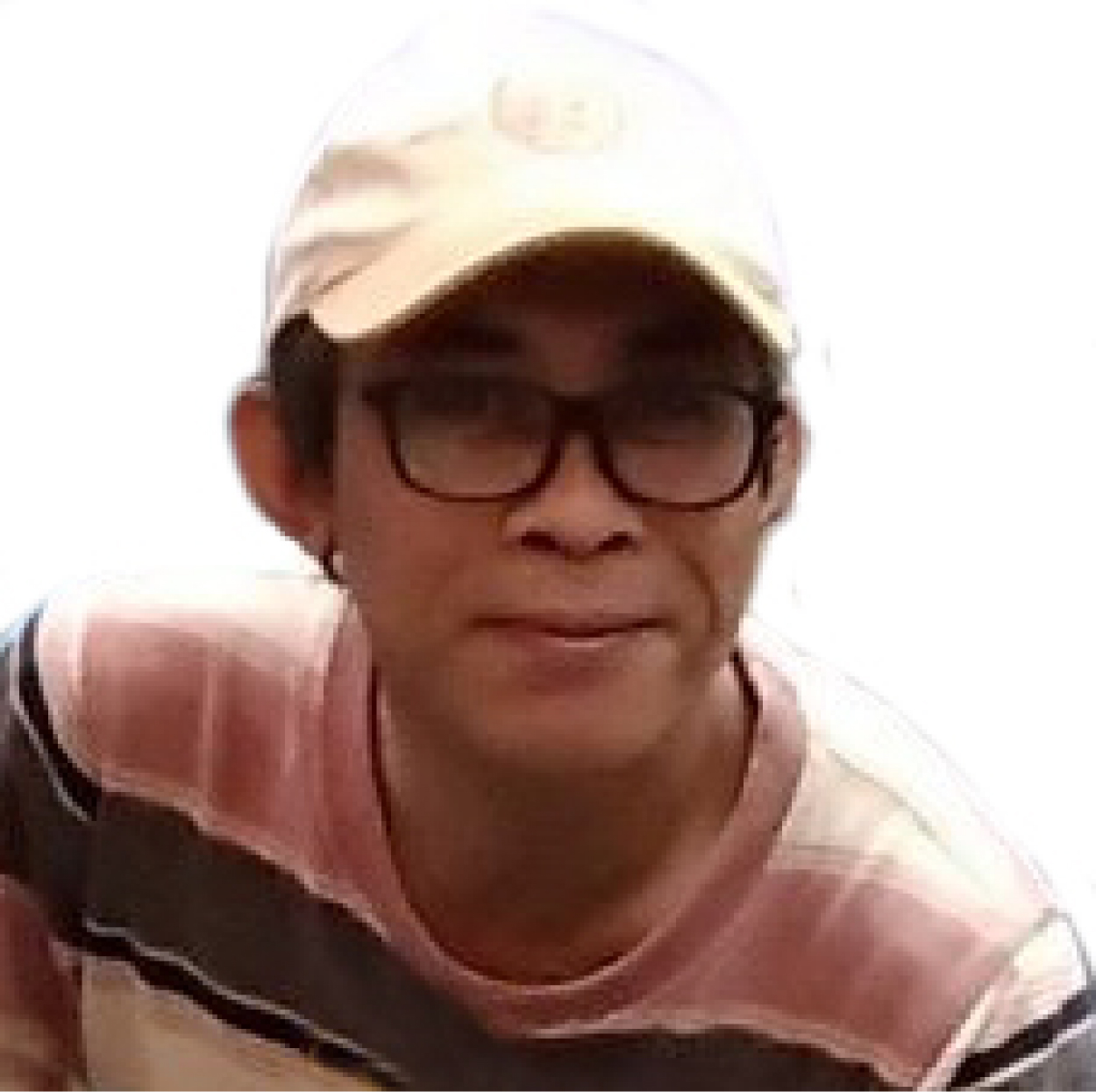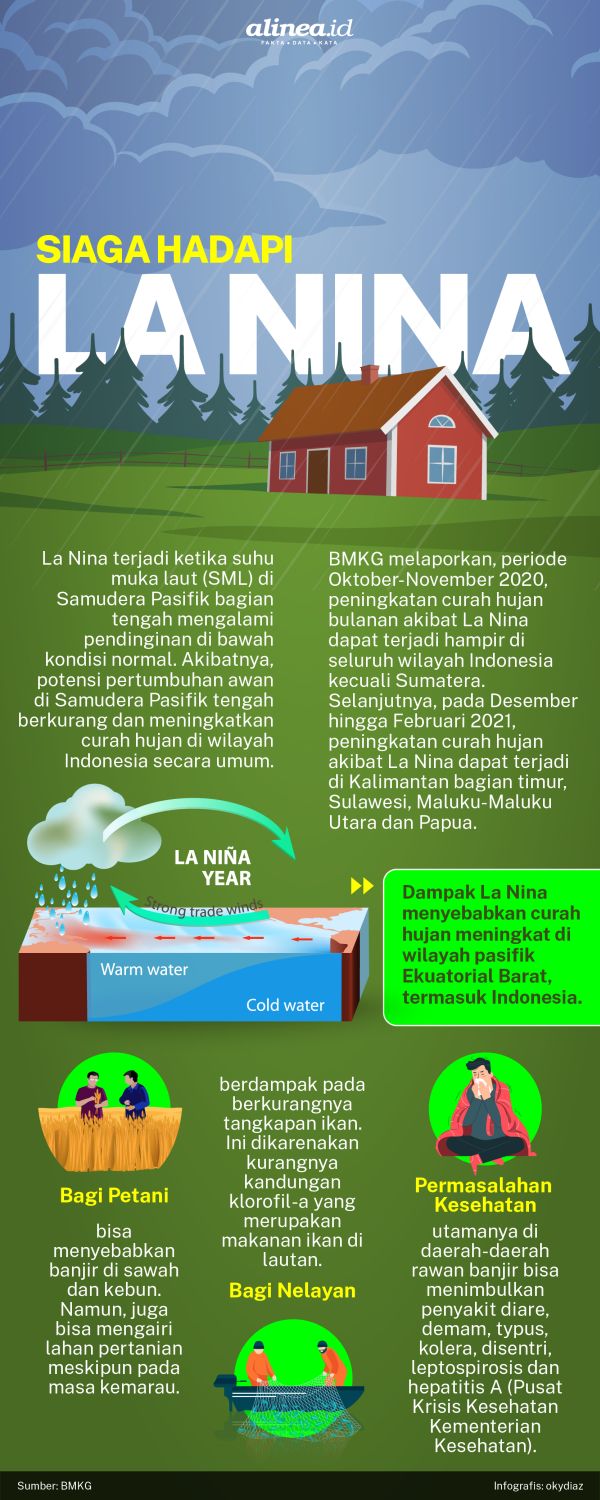Kesepakatan iklim US$20 M Indonesia buntu, Vietnam dan India tertunda
Pada bulan November lalu, para pemimpin G20 di Bali memuji apa yang mereka katakan sebagai kesepakatan pendanaan perubahan iklim yang transformasional untuk membantu menghentikan penggunaan batubara di Indonesia. Sembilan bulan kemudian, tidak ada satu dolar pun dari paket US$20 miliar yang dihabiskan untuk menutup proyek bahan bakar fosil.
Ketika belahan bumi utara mengalami salah satu musim panas tertinggi yang pernah terjadi di bumi, dan para pemimpin G20 siap berkumpul lagi di India bulan ini, proyek yang seharusnya memberikan model terobosan dalam membuka jalan bagi negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang mencapai tujuan mengurangi karbon sementara perekonomian mereka tumbuh masih terjebak dalam pertemuan mengenai rincian operasional.
Rencana investasi untuk mengaktifkan pendanaan 'Kemitraan Transisi Energi yang Adil' (JETP) yang sangat dibutuhkan Indonesia masih belum ada setelah para perunding melewatkan tenggat waktu pada pertengahan Agustus. Meski pun Amerika Serikat dan Jepang telah memimpin dalam menjamin kemauan politik dan janji pendanaan, tantangan praktis yang dihadapi adalah menentukan target mana yang memenuhi syarat untuk investasi, menyepakati mekanisme pendanaan swasta atau publik untuk mendukung target tersebut – dan menjembatani perbedaan pandangan mengenai pembayaran kembali tarif pinjaman.
Seiring berjalannya waktu, prospek JETP di negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik, yang menyumbang sekitar setengah emisi karbon global, masih jauh dari harapan. JETP senilai US$15,5 miliar untuk Vietnam yang disetujui pada bulan Desember 2022 masih dalam tahap awal, sementara JETP lebih lanjut yang diperdebatkan untuk India – penghasil emisi karbon terbesar ketiga di dunia – masih dalam tahap awal.
“Kita perlu mengetahui, misalnya, kebutuhan listrik Indonesia di masa depan untuk menghitung berapa banyak dana yang perlu dialokasikan untuk melakukan dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan sekaligus menyediakan energi secara memadai,” kata seorang pejabat kementerian keuangan Jepang yang bertanggung jawab atas negosiasi tersebut kepada Nikkei Asia.
“Data baru berdasarkan prasyarat yang berbeda dan dari berbagai sumber datang setiap saat, dan pendapat berbeda di antara pihak-pihak mengenai data mana yang harus digunakan untuk membuat proyeksi yang akurat,” kata pejabat tersebut, yang berbicara tanpa menyebut nama karena sensitivitas urusan data. “Kami memerlukan lebih banyak waktu untuk memikirkannya secara matang.”
Perubahan iklim, dan pendanaan iklim, kemungkinan besar akan menjadi agenda utama pertemuan puncak para pemimpin G20 dan negara-negara ASEAN bulan ini. Kemajuan dalam JETP Indonesia – yang digambarkan tahun lalu oleh John Morton, yang saat itu menjabat sebagai konselor iklim AS, sebagai “kemitraan investasi iklim spesifik negara terbesar yang pernah ada” – akan menjadi hal yang besar.
JETP Indonesia bermaksud untuk memobilisasi US$20 miliar selama tiga sampai lima tahun ke depan. Untuk mengakses pendanaan tersebut, Indonesia diharuskan untuk memajukan janji nol karbon bersihnya selama 10 tahun dari tahun 2060 hingga 2050, mencapai puncak total emisi sektor ketenagalistrikan pada tahun 2030 – tujuh tahun lebih awal dari perkiraan sebelumnya – dan membatasi emisi karbon dioksida sebesar 290 megaton pada tahun itu, turun dari nilai dasar sebesar 357 megaton.
Tanpa menjelaskan lebih lanjut, sekretariat JETP Indonesia mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 16 Agustus bahwa batas waktu publikasi “rencana investasi dan kebijakan komprehensif” telah “disesuaikan” karena “data tambahan telah diidentifikasi yang perlu diintegrasikan ke dalam model teknis". Rencana tersebut akan diluncurkan “akhir tahun ini” setelah mendapatkan waktu untuk memberikan komentar publik, katanya, tanpa menentukan jangka waktu yang rinci.
Menurut pernyataan bersama saat peluncuran kemitraan ini, Indonesia akan “menggandakan total penggunaan energi terbarukan selama dekade ini dibandingkan dengan rencana saat ini.” Hal ini berarti energi terbarukan menyumbang 34% dari total pembangkit listrik di Indonesia pada tahun 2030, naik dari 13% saat ini. Mempercepat penghentian dini pembangkit listrik tenaga batu bara, yang bergantung pada dukungan internasional, juga merupakan “elemen penting untuk mencapai target di atas,” menurut kesepakatan tersebut.
Perlakuan terhadap pembangkit listrik tenaga batu bara masih menjadi isu penting dalam diskusi, menurut Fabby Tumiwa, direktur eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), lembaga penelitian berbasis di Jakarta yang memberi nasihat dan melakukan pekerjaan pemodelan dalam menyusun rencana investasi.
Indonesia saat ini memperoleh lebih dari separuh listriknya dari batu bara. Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang ambisius pada tahun-tahun awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo menyebabkan banyak pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara. Saat ini, kelebihan pasokan pada jaringan listrik menjadi hambatan bagi rencana pengembangan energi terbarukan.
Secara khusus, mengatasi emisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara yang digunakan dan dikelola oleh industri, bukan untuk penggunaan umum, “memerlukan penyelidikan lebih lanjut,” kata Tumiwa kepada Nikkei. Data yang diperbarui menunjukkan bahwa emisi “sangat besar, melampaui perkiraan sebelumnya ketika negara-negara menyepakati target JETP, dan mengubah persamaan” mengenai bagaimana seharusnya armada batubara pada tahun 2030 – dan solusi apa yang perlu diberikan.
Hambatan besar lainnya adalah “tercapainya kesepakatan mengenai struktur pembiayaan yang adil dan berdampak bagi kesepakatan tersebut,” kata Melissa Cheok, Associate Director di Sustainable Fitch, yang memberikan informasi bagi komunitas ESG.
Dana JETP akan menggunakan campuran hibah, pinjaman lunak, pinjaman dengan suku bunga pasar, jaminan dan investasi swasta. Sekitar $10 miliar akan berasal dari janji sektor publik, sementara separuh lainnya akan difasilitasi dalam investasi swasta dari sejumlah lembaga keuangan swasta yang dikoordinasikan oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero, yang mencakup nama-nama global seperti Bank of America, Citi, BlackRock, HSBC, Macquarie, MUFG dan Standard Chartered.
“Setiap sumber pendanaan mungkin berasal dari berbagai lembaga keuangan yang dapat memprioritaskan keuntungan dibandingkan dampaknya,” kata Cheok kepada Nikkei. “Menyeimbangkan permintaan kelompok investor global yang besar dan beragam dengan pembiayaan yang adil dan dampak lingkungan bagi Indonesia akan menimbulkan tantangan.”
Bagi Indonesia, pembiayaan harus dilakukan dengan syarat yang menguntungkan. Luhut Pandjaitan, pejabat senior Indonesia yang bertanggung jawab atas perundingan JETP, mengulangi kepada wartawan pada bulan Juni apa yang dia katakan kepada para pejabat AS setelah pertemuan di Washington bulan sebelumnya: “Jika Anda memberi kami pinjaman dengan tingkat bunga pinjaman komersial, lupakan saja - - kita bisa melakukan ini sendiri... [jika tidak] Anda akan mengganggu perekonomian kita."
“Kurangnya definisi global mengenai transisi” di antara kelompok investor mungkin menjadi penghalang, kata Cheok dari Sustainable Fitch.
Perbedaan-perbedaan tersebut “mungkin membuat pelaksanaan kesepakatan menjadi sulit karena adanya kebingungan dan kurangnya kejelasan mengenai apa yang dapat dianggap sebagai proyek transisi yang layak,” kata Cheok. “Kurangnya kejelasan juga dapat menimbulkan kekhawatiran akan dituduh melakukan transisi atau greenwashing dan mungkin memberikan ruang bagi investor untuk jeda sejenak.”
Namun, pejabat Kementerian Keuangan Jepang yang menangani perundingan JETP mengatakan, pihak-pihak yang terlibat "mengincar tujuan yang sama, yaitu membuat rencana yang efektif dan praktis bermanfaat bagi Indonesia, sehingga tidak ada kontroversi pada tingkat dasar." Para pihak tetap berdedikasi untuk meluncurkan rencana investasi “sesegera mungkin,” kata pejabat itu.
Penundaan juga terjadi di Vietnam, yang kesepakatan JETP-nya diperoleh pada bulan Desember lalu dari negara-negara maju yang dipimpin oleh Uni Eropa di sela-sela KTT ASEAN-UE yang pertama.
Hanoi hanya mengumumkan sedikit rincian sejak saat itu, kecuali pembentukan sekretariat pada bulan Juli – tiga bulan terlambat dari jadwal. Para pengamat di Vietnam mengatakan prospeknya menjadi kabur karena negara satu partai tersebut memenjarakan aktivis anti-batubara, yang dikritik oleh para pejabat Uni Eropa pada tahun 2022 sebagai “pelecehan terhadap pembela hak asasi manusia.”
Walaupun Vietnam berharap untuk tidak menggunakan tenaga batubara dan mencapai emisi nol pada tahun 2050, rencana energi yang ada saat ini memperhitungkan peningkatan kapasitas listrik berbasis batubara pada tahun 2030. Bagaimana realitas tersebut akan selaras dengan target JETP untuk mempercepat puncak emisi gas rumah kaca Vietnam sebesar lima tahun, hingga tahun 2030, dan mempercepat penerapan energi terbarukan hingga mencapai hampir separuh pembangkitan listrik pada tahun yang sama, masih belum jelas.
Meskipun kemajuan yang lambat dalam JETP saat ini, antusiasme terhadap kesepakatan baru dari negara lain tetap tinggi. “Uni Eropa ingin membuat lebih banyak perjanjian serupa dengan negara-negara ASEAN,” kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen kepada wartawan pada bulan Desember.
India, yang menggantikan Indonesia sebagai presidensi G20 tahun ini, kini sedang berdiskusi dengan negara-negara maju untuk mengembangkan JETP sendiri.
Namun hal yang sulit bagi negara ini adalah bahwa dengan bergabung dalam JETP "Anda akan menggunakan pendanaan ini untuk mempercepat pertumbuhan energi bersih, namun Anda tidak boleh memperluas penggunaan bahan bakar fosil atau sumber daya berbasis batu bara," kata Sunil Dahiya, analis Center for Research on Energy and Clean Air. Hal ini bertentangan dengan klaim New Delhi yang terus menerus bahwa mereka harus meningkatkan pembangkit listrik tenaga batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi yang sangat besar guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat.
Negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia ini telah melakukan perlawanan terhadap AS dan Jerman – yang merupakan salah satu pemimpin perundingan JETP bagi pihak investor – dalam memasukkan batas waktu untuk menghentikan penggunaan batubara karena kekhawatiran akan hilangnya lapangan kerja dan gangguan listrik terkait batubara. Kesepakatan kemungkinan besar tidak akan tercapai tahun ini selama India menjabat sebagai presiden G20, kata para pengamat India.
Namun demikian, para ahli pendanaan iklim memperkirakan kesepakatan JETP pada akhirnya akan mengkatalisasi kebutuhan investasi yang lebih luas dan besar untuk mengubah sistem energi intensif karbon di negara-negara berkembang. Dalam kasus Indonesia, lembaga pemikir IESR di Jakarta memperkirakan diperlukan dana minimal $150 miliar untuk benar-benar mencapai tujuan yang digariskan dalam JETP.
“Bagaimanapun struktur kesepakatan Indonesia pada akhirnya akan berdampak pada negara-negara berkembang lainnya seperti Vietnam dan India,” kata Cheok dari Sustainable Fitch.(nikkeiasia)