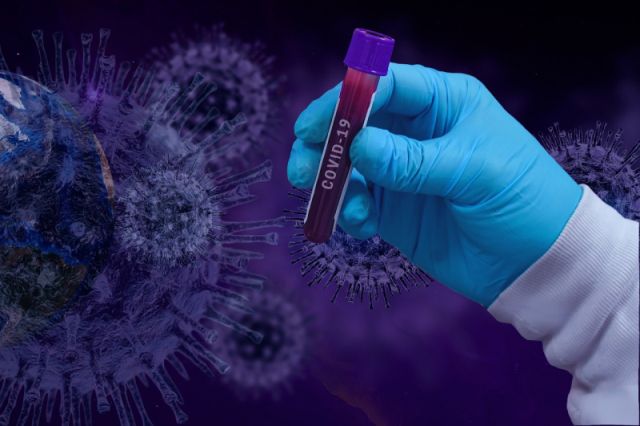Rapid test, demi kesehatan atau cuan?
Suara tangis terdengar dari ruang tunggu operasi Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Permata Hati Mataram, Jalan Mahapahit No 8, Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Gusti Ayu Arianti (23 tahun), yang masih dalam pengaruh obat bius mengenali suara tangis itu.
Itu adalah suara tangis suaminya I Nyoman Yudi Prasetya Jaya (24 tahun). Tanpa sadar, air mengalir dari kedua mata wanita yang baru saja melahirkan tersebut. Arianti belum mengetahui apa yang terjadi. Namun firasatnya mengatakan, pasti ada yang tidak beres dengan persalinannya.
Dia lantas meminta perawat untuk membawanya kepada sang suami. Tetapi perawat dengan alat pelindung diri (APD) lengkap itu hanya memintanya bersabar.
“Sampai akhirnya saya nangis, benar-benar nangis. Itu bener suara suami saya atau ndak? Karena (pengaruh obat) biusnya masih kan. Jadi samar-samar,” ujar Arianti saat berbincang dengan Alinea.id melalui sambungan telepon, (28/8).
Selasa (18/8), Arianti melahirkan anak kedua. Kelak, anak itu akan diberi nama I Made Arsya Prasetya Jaya dengan panggilan Acha. Keinginan Arianti sederhana, hanya ingin mencocokkan nama anak keduanya itu dengan panggilan kakaknya I Putu Tychi Athalia Jaya (6 tahun) yang dipanggil Ichi.
Namun, harapan tinggal harapan. Acha tak sempat melihat dunia. Prosedur penanganan rumah sakit yang berbelit karena pandemi Covid-19, membuat nyawa Acha melayang. Arianti dan suaminya harus bolak-balik dari satu rumah sakit (RS) ke RS lain saat akan melahirkan anak keduanya itu.
Arianti ‘dipingpong’ terkait kewajiban rapid test (tes cepat antibodi). Bahkan saat ia sudah merasakan kontraksi, bidan Puskemas menolak memeriksa dan menanganinya hanya karena ia belum mengantongi hasil rapid test. Ketika akhirnya ia mendapat penanganan, nyawa sang jabang bayi sudah tak bisa diselamatkan.
Wakil Direktur Medik RSIA Permata Hati, Arief Rahman membenarkan. Arianti memang sempat menjalani operasi kelahiran di RSIA Permata Hati pada 18 Agustus 2020. Dia diminta untuk melakukan pemeriksaan darah sebelum persalinan. Namun, hal tersebut dilakukan hanya sebagai persiapan kelahiran, bukan rapid test ulang.
Sementara, hasil rapid test pasien telah dibawa oleh keluarga yang bersangkutan dari Puskesmas Pagesangan. “Tidak ada kalimat dan pernyataan dari tim dokter hingga perawat IGD yang meminta dilakukan rapid test ulang,” ujar Arief melalui keterangan tertulis yang dikirim kepada Alinea.id.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Usman Hadi mengatakan, pihaknya telah memberikan catatan penting atas kejadian tersebut. Ia meminta agar segala prosedur rapid test bisa dikesampingkan terlebih dahulu kepada ibu hamil yang dalam keadaaan darurat.
Saat ini, pihak Dinkes Mataram juga tengah melakukan audit maternal prinata guna mencegah kejadian serupa terulang. Audit dilakukan untuk menguji kausa-kausa kematian ibu dan bayi selama masa pandemi. “Jangan sampai prosedur itu mengalahkan pelayanan. Administrasi itu nanti dululah, bisa belakangan, yang penting pasien itu segera ditangani dulu," tegasnya.
Preseden buruk
Kasus Arianti menjadi preseden buruk bagi RS yang terlalu kaku menangani pasien dalam kondisi darurat. Namun Kementerian Kesehatan berdalih, aturan terkait persalinan di masa pandemi sudah diatur dalam surat edaran (SE) Dirjen Yankes nomor HK.02.02/III/2878/2020 tentang Kesiapsiagaan Rumah Sakit Rujukan dalam Penanganan Rujukan Maternal dan Neonatal dengan Covid-19.
“Jadi jika amanat SE dijalankan diharapkan tidak akan ada lagi kasus semacam ini,” ujar Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan (Dirjen Yankes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Abdul Kadir kepada Alinea.id.
Aturan yang dimaksud adalah ibu hamil wajib melakukan skrining Covid-19 setidaknya 7 hari sebelum tanggal melahirkan. Padahal sebulan sebelum SE ini diterbitkan, World Health Organization (WHO) sudah mengeluarkan surat rekomendasi terkait persalinan di masa pandemi. Dalam surat rekomendasi ini, WHO menyebut bahwa seluruh ibu hamil, baik yang positif Covid-19 atau tidak, berhak mendapatkan perawatan yang berkualitas tinggi oleh pihak RS.
Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyesalkan isi dari SE Dirjen Yankes ini. Menurut Pandu, SE ini mestinya mengatur juga bagaimana petugas RS menerapkan situasi kedaruratan untuk semua proses persalinan di masa pandemi.
“Anggap saja setiap orang mempunyai kemungkinan membawa virus (SARS-Cov2). Jadi kita semua sifatnya kehati-hatian. Kalau sudah mau melahirkan ya ditolonglah, tapi pakai alat pelindung yang lengkap,” ujar Pandu saat dihubungi Alinea.id.
Tak ada kajian
Sejak awal, tak ada kajian yang lengkap dan mendalam terkait rapid test ini. Eks Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto sempat mengungkapkan, pihaknya masih meragukan efektivitas diagnosa Covid-19 dengan menggunakan metode tes cepat tersebut.

Kala itu, Kemenkes dan pihak terkait juga masih terus melakukan kajian terhadap metode diagnosis tes cepat ini dari negara lain. Menurut Yuri, metode tes cepat yang digunakan di negara lain berbeda dengan tes yang selama ini digunakan di Indonesia.
Satu-satunya keuntungan dari tes cepat ini hanya karena sarana pemeriksaannya tidak membutuhkan laboratorium biosecurity level 2. Artinya, pelaksanaan tes cepat bisa dilaksanakan di semua laboratorium kesehatan di rumah sakit yang ada di Indonesia.
“Hanya permasalahannya adalah bahwa karena yang diperiksa adalah imonoglobulin, maka kita membutuhkan reaksi imonoglobulin dari seseorang yang terinfeksi paling tidak seminggu,” imbuh Yuri, dinukil dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI. Kalau infeksinya kurang dari seminggu, kemungkinan pembacaan imonoglobulinnya akan memberikan gambaran negatif.
Ahli epidemiologi Pandu Riono juga menjelaskan, bahwa rapid test sebetulnya tidak bisa dijadikan alat diagnosa Covid-19. Pasalnya, tes ini tak bisa mendeteksi ada atau tidaknya virus SARS-Cov2 dalam tubuh. Tes ini hanya mendeteksi ada atau tidaknya imun yang muncul setelah sembuh dari infeksi virus.
Sebuah hasil studi yang dipublikasi Chrocane Library pada 25 Juni 2020 lalu menunjukkan bagaimana cara tes cepat antibodi bekerja. Riset ini mengambil 54 sampel tes antibodi di daratan Asia, Eropa, Amerika dan China. Hasilnya menampilkan tingkat akurasi tes antibodi untuk mendeteksi adanya sistem imun dalam tubuh yang muncul setelah terjangkit Covid-19.
Di minggu pertama, akurasi tes antibodi ini menunjukkan tingkat akurasi 30%. Angkanya kemudian meningkat di minggu kedua menjadi 70%. Lantas pada minggu ketiga, tingkat akurasinya bertambah menjadi 90%. Tapi yang perlu diingat, alat tes ini hanya mengukur ada atau tidaknya antibodi dalam tubuh manusia, bukan untuk mendiagnosa virus.
Artinya, jika seseorang dinyatakan reaktif saat tes cepat antibodi, bukan berarti orang tersebut sedang terinfeksi Covid-19. Sebaliknya, boleh jadi orang tersebut malah sudah sembuh dari Covid-19.
Dalam riset Chrocane Library, ada istilah yang disebut sebagai ‘positif palsu’ dan ‘negatif palsu’. Istilah ini mengacu pada tingginya tingkat eror dalam sistem deteksi antibodi terhadap virus SARS-Cov2. Ketika Chrocane Library melakukan tes PCR pada 58 orang yang dinyatakan reaktif dengan tes antibodi, ternyata 21% di antaranya terdeteksi negatif atau positif palsu.
Ini menunjukkan bukti bahwa tes antibodi sebetulnya sama sekali tidak berguna untuk mendiagnosa virus SARS-Cov2. Sebab dalam sudut pandang sains, tingkat eror maksimal yang dapat ditoleransi hanya 10%.
.jpg)
WHO pada April 2020 juga merekomendasikan agar tes cepat antibodi atau imunodiagnostik tidak lagi digunakan untuk mendiagnosa virus SARS-Cov2. Tes ini hanya bisa digunakan untuk surveilens atau pemantauan pada orang-orang yang sudah sembuh dari Covid-19.
Sayangnya, rekomendasi WHO ini baru ditandaklanjuti Kemenkes dua bulan kemudian saat kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 76.981 orang. Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 baru diteken Menkes Terawan Agus Putranto pada 13 Juli 2020.
Aturan baru itu menyebut, alat tes antibodi tidak digunakan lagi untuk upaya diagnostik Covid-19. Namun dalam kondisi keterbatasan kapasitas pemeriksaan PCR, tes antibodi masih dapat digunakan untuk skrining pada populasi spesifik dan situasi khusus.
Situasi khusus yang dimaksud ditujukan kepada pelaku perjalanan jauh, serta pelacakan kontak di wilayah kepadatan tinggi seperti panti jompo, panti rehabilitasi, asrama, pondok pesantren, dan kelompok rentan.
Aturan baru ini sekaligus juga sebagai penegas atas SE Nomor HK.02.01/Menkes/382/2020 tentang Protokol Pengawasan Pelaku Perjalanan dalam Negeri di Bandara Udara dan Pelabuhan. Dalam aturan ini, setiap pelancong diwajibkan untuk melampirkan surat hasil rapid test dan/atau polymerase chain reaction (PCR) yang berlaku 14 hari sebelum dan sesudah perjalanan.
Tetapi, aturan itu justru dianggap Pandu Riono terlalu mengada-ada. Sebab, aturan ini sama saja dengan pemerintah tetap menggunakan rapid test sebagai alat deteksi Covid-19. Padahal, sudah jelas betul hasil riset dari Chrocone Library dan rekomendasi WHO membuktikan bahwa tes antibodi tersebut tidak bisa digunakan untuk diagnosa virus SARS-Cov2.
Sehingga wajar jika Pandu dan sebagian kalangan mempertanyakan motif di balik ngototnya pemerintah terkait aturan soal wajib rapid test ini. Muncul kecurigaan, aturan ini sengaja terus diberlakukan lantaran ada pihak-pihak yang menangguk untung dari aturan tersebut.
Pemborosan Anggaran
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) hingga 28 Agustus 2020, pemerintah telah mendistribusikan sebanyak 1,17 juta alat rapid test ke sejumlah lembaga dan provinsi di Indonesia. Angka ini hampir setengahnya dari distribusi alat reagen PCR yang mencapai 2,2 juta lebih.
Kalau dilihat secara kasat mata tentulah orang boleh curiga bahwa negara telah melakukan pemborosan atas pembelian alat tes antibodi ini. Apalagi, waktu awal pandemi, harga alat ini masih cukup mahal sekitar Rp220 ribu/pcs. Dengan hitungan kasar, berarti negara telah mengeluarkan Rp257,4 miliar hanya untuk membeli alat tes antibodi yang tidak efektif ini.
Namun, Kepala BNPB Doni Monardo membantah dugaan tersebut. Menurut dia, BNPB tidak pernah membeli alat tes antibodi pada masa awal pandemi. Alat tes antibodi yang didistribusikan itu, semuanya merupakan sumbangan atau bantuan. BNPB hanya membeli alat tes cepat antigen pada April 2020. Jumlahnya sekitar 250 ribu buah. Harga satuannya ditaksir Rp185 ribu per unit. Jika dikalkulasi, maka total Rp46,25 miliar telah dikeluarkan BNPB untuk membeli alat tes antigen ini.
Untuk diketahui, alat uji tes antigen bekerja dengan swab atau menggunakan liur untuk mendeteksi adanya virus. Tingkat akurasinya sekitar 70-80%, lebih rendah dibanding metode PCR namun mempunyai hasil lebih cepat. “Intinya pemerintah tidak membeli yang antibodi karena nilai akurasinya rendah. Tetapi itu pun dibutuhkan selama tidak ada mesin PCR-nya,” ujar Doni menegaskan.
Doni menyebut sejak awal, rapid test hanya digunakan untuk skrining saja, bukan alat diagnosa. Penggunaan rapid test sendiri diperlukan mengingat tidak semua daerah di Indonesia mempunyai fasilitas tes PCR. "Karena beberapa daerah yang belum punya PCR karena pedalaman. Jadi selama masih terbatas ya mungkin rapid test masih dibutuhkan," tambahnya.
| Nama lembaga | Jumlah |
| Merpati Halim | 0,00 |
| Kelapa Gading dan BGR | 1,21 juta pcs |
| Crisis Center | 2.080 pcs |
| Cold Storage | 987.320 pcs |
Kepala Pusat Krisis Kemenkes Budi Sylvana menyampaikan hal serupa. Dia menyebut, Kemenkes tidak pernah membeli alat tes antibodi pada awal masa pandemi. Namun dia mengakui, pada Juli 2020, Kemenkes mengeluarkan uang Rp200 miliar untuk membeli 1,6 juta alat tes antibodi.
Uang ini digunakan untuk membeli alat tes antibodi dari PT Hepatica Mataram dan PT Indec Diagnostic yang merupakan perusahaan penyedia alat kesehatan lokal. Harga satuan alat tes antibodi yang dibeli dari Hepatica Mataram Rp83.600. Sementara harga tes antibodi dari Indec Diagnostic Rp108.000 per unit.
“Kemenkes hanya membeli produk dalam negeri untuk rapid test. Kedua penyedia produksi RDT (rapid diagnostic test) Covid lokal, bukan impor,” tuturnya.
Namun, ketika Alinea.id melakukan kroscek melalui laman www.sirup.lkpp.go.id, rupanya ada selisih angka yang cukup besar dalam pembelian alat tes antibodi ini. Dari penelusuran dengan menggunakan kata kunci ‘rapid test Covid-19’ di laman tersebut, Alinea.id menemukan data bahwa sebetulnya Kemenkes telah membeli alat tes antibodi pertama kali pada 20 April 2020 dengan nilai Rp22,99 juta.
Jenama alat tes antibodi yang dibeli adalah Biozek. Majalah Tempo pernah menulis laporan panjang terkait merek ini karena dugaan klaim yang tidak tepat. Pemerintah mengklaim Biozek berasal dari Belanda, padahal sebetulnya alat ini diproduksi oleh Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd di China. Belanda hanya mengemas ulang.
Selanjutnya, pembelian alat tes antibodi juga dilakukan pada Mei, Juni dan Juli 2020 dengan total dana yang dikeluarkan Rp200,85 miliar. Jika dilihat dari hasil perhitungan ini, maka ada selisih Rp850 juta lebih dari data yang disampaikan Budi sebelumnya.
Itu hanya data alat tes antibodi yang dibeli Kemenkes. Alat tes antibodi yang yang dibeli kementerian dan lembaga lain beda lagi. Setidaknya, Rp22 miliar juga telah dikeluarkan kementerian dan lembaga untuk membeli alat tes antibodi. Jika digabung, maka negara telah mengeluarkan dana pembelian barang dan jasa untuk tes antibodi Rp223,94 miliar.
Menangguk Untung
Sikap pemerintah yang keukeuh terkait penggunaan alat tes antibodi dalam sejumlah aktivitas juga ditengarai sebagai upaya menyembuhkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang sakit. PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) (Persero) yang anak usahanya yakni PT Rajawali Nusindo ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengimpor alat tes antibodi, tiba-tiba saja menangguk untung besar di semester I 2020.
Dari keterangan resmi manajemen RNI pada Juli lalu, perusahaan terkonfirmasi membukukan laba bersih setelah pajak Rp42 miliar. Nilai ini melonjak 124% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan ini cukup signifikan mengingat pada penutupan tahun buku 2019, perseroan masih mencatatkan rugi Rp64,5 miliar.
PT RNI selama ini dinilai sebagai perusahaan ‘sakit’ karena eks direktur utamanya, Didik Prasetyo sempat diduga memainkan laporan keuangan perusahaan pada 2018 agar terlihat untung. Berdasarkan nota laporan keuangan RNI 2018 yang dirilis pada laman resminya, perseroan tercatat mencetak laba bersih Rp188,3 miliar.
Angka ini melebih target perusahaan (RKAP) yang telah ditetapkan sebelumnya, Rp178,79 miliar. Laba bersih tersebut salah satunya disokong oleh pendapatan dari revaluasi aset perusahaan Rp502,4 miliar. Tetapi apabila pendapat dari revaluasi aset ini dikeluarkan, maka RNI dipastikan bakal merugi Rp319,1 miliar.
Saat Alinea.id mengonfirmasi kepada manajemen RNI, mereka mengakui bahwa perolehan laba perseroan sebagian besar disumbang oleh penjualan alat kesehatan (alkes) dan farmasi. Namun mereka tidak menyebutkan berapa pendapatan yang didapatkan RNI dari hasil penjualan alat tes antibodi.
Hanya satu yang pasti, RNI telah membeli sekitar 2,5-3 juta alat tes antibodi impor. Harga satuannya diperkirakan Rp55.000 per unit. Nilai satuan ini sempat diungkapkan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon melalui akun twitternya.
General Manager Marketing Institusi PT Rajawali Nusindo Christiarsih mengaku, perusahaannya menjual alat tes antibodi ini dengan harga Rp85.000 per unit. Harga ini berlaku untuk penjualan langsung kepada perusahaan dan lembaga yang bekerja sama dengan RNI, seperti PT KAI (Persero), Jakarta Railway Center, PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) dan Kejaksaan Agung.
“Alat rapid test yang dibeli PT Rajawali Nusindo merupakan produk rapid test yang sudah memiliki izin edar dari dinas terkait,” ujar Christiasti melalui keterangan tertulis kepada Alinea.id.
Dengan harga yang diungkapkan Christiasti itu, maka bisa diasumsikan bahwa RNI kini telah mengantongi omzet setidaknya Rp255 miliar hanya dari penjualan alat tes antibodi. Jika angka ini ditarik lagi sebagai laba kotor, maka keuntungan RNI untuk penjualan tes antibodi ini sekitar Rp90 miliar.
Melihat hasil keuntungan yang cukup menggiurkan ini, pantaslah jika aturan terkait tes antibodi ini terkesan diulur-ulur penghapusannya. Setidaknya hingga Selasa (25/8), Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa aturan terkait tes antibodi ini masih dikaji.
“Kami di Satgas sedang melakukan review terhadap rapid test untuk pelaku perjalanan, dan kajian belum selesai,” ujar Wiku menanggapi pertanyaan Alinea.id dalam sebuah konferensi pers bersama media di Istana Negara, Jakarta Pusat.
.jpg)
Komersialisasi di RS
Di samping itu, syarat wajib tes antibodi ini juga disinyalir sebagai ladang komersialisasi bisnis bagi sejumlah rumah sakit. Pasalnya, pada masa awal pandemi, harga rapid test dibanderol cukup mahal sekitar Rp200 ribu – Rp500 ribu.
Dwi (27 tahun) dan Hens (37 tahun), pasangan suami-istri asal Surabaya pun mengaku sempat kecele dengan mahalnya harga tes antibodi tersebut. Pada 13 Juli 2020, keduanya terpaksa melakukan rapid test lantaran harus pulang ke Medan untuk menghadiri acara pemakaman sang nenek.
Keduanya melakukan rapid test di Siloam Hospital, Surabaya. Saat itu, kata Dwi, harga tes antibodi di Siloam Hospital masih dipatok Rp360 ribu per orang. Harga ini cukup mahal mengingat Kemenkes sebetulnya telah mengeluarkan aturan terkait harga maksimal rapid test yakni Rp150 ribu pada 8 Juli 2020.
“Mau protes sih, tapi bingung karena dadakan. Dikabarin malam, besok pagi harus berangkat. Jadi mau enggak mau harus gue ambil. Jadi kena Rp700 ribuan deh,” tutur Dwi saat berbincang dengan Alinea.id, (28/9).
Hingga artikel ini diterbitkan, harga rapid test di Siloam Hospital belum ada perubahan. Tes antibodi tanpa adanya surat rujukan dokter masih dipatok Rp360 ribu. Adapun tes serologi tanpa basis antibodi maupun antigen dibanderol Rp150 ribu.
“Semua rumah sakit rata-rata segitu, bapak,” kata customer service Siloam Hospital saat dihubungi Alinea.id, (28/9).
Meski begitu, ada beberapa RS yang sudah mengoreksi harga tes antibodinya. Di RS Advent Bandung, harga tes antibodi kini sudah dibanderol Rp150 ribu dari sebelumnya Rp300 ribu – Rp368 ribu. Sementara di Rumah Sakit Pusat (RSP) Pertamina, harga tes antibodi yang semula dipatok Rp350 ribu kini telah dikoreksi menjadi Rp150 ribu – Rp250 ribu.
“Yang Rp150 ribu untuk hasil yang ditulis tangan, yang Rp175 ribu untuk yang di-print, yang Rp250 ribu untuk yang disertai keterangan dokternya,” ujar costumer service RSP Pertamina, (20/9).
Pada 8 September lalu, sebetulnya kabar dihapuskannya tes antibodi untuk syarat perjalanan jauh sempat mencuat. Isu ini muncul usai viral di sosial media bahwa syarat tes antibodi dan tes PCR akan digantikan dengan pengisian Health Alert Card (HAC) dan pengecekan suhu tubuh.
Namun kemudian, Achmad Yurianto membantah isu tersebut. Menurutnya, tes antibodi dan PCR akan tetap menjadi persyaratan perjalanan jauh dengan masa berlaku 14 hari.
“Para penumpang dan awak alat angkut yang akan melakukan perjalanan dalam negeri tetap wajib memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif atau surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen/antibodi nonreaktif,” tegas Yuri seperti dinukil dari laman Kemkes.go.id, (10/9).
Alinea.id sempat mengonfirmasi soal komersialisasi tes cepat ini kepada Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan (PKR) Kemenkes Try Hesty Widyastuti. Tapi dia mengaku tidak begitu paham ikhwal ini.
“Bisa minta tolong ke P2P (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) Kemenkes atau Litbangkes (Badan Penilitian dan Pengembangan Kesehatan),” tutur Hesty.
Sebaliknya, Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan P2P Kemenkes Vensya Sitohang malah mengembalikan permasalahan ini ke PKP Kemenkes. “Loh, urusan rumah sakit itu ada di beliau,” ucap Vensya saat dihubungi.
Walau begitu, sebetulnya pada Juli lalu Hesty sempat membantah soal kormesialisasi alat tes antibod ini di depan awak media. Menurutnya, penetapan harga maksimal tes cepat Rp150 ribu sudah merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah adanya komersialisasi rapid test.
“Itu yang menjadi alasannya. Kita menciptakan kewajaran harga-harga itu. Sehingga, tidak ada komersialisasi intinya,” pungkas Hesty.
Tulisan ini merupakan hasil kolaborasi Alinea.id bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Knowledge Sector Initiative (KSI).