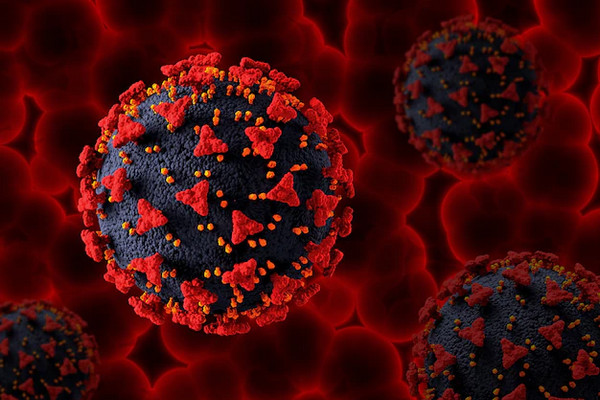Dunia usai Covid-19: China dominan, Indonesia bakal terpukul
Seratus sembilan tahun silam, ketika pes alias sampar menghantam Jawa, tatanan sosial-politik berubah. Menurut dosen sejarah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang pernah meneliti pes di Jawa, Martina Safitri, wabah penyakit menular yang disebabkan bakteri Yersinia pestis dari tikus kala itu, ikut andil melahirkan elite baru pribumi di bidang kesehatan.
Mereka adalah para mantri yang mendapat pendidikan kedokteran Barat, perlahan menggantikan peran dukun dalam usaha menyembuhkan seseorang.
“Para elite baru lulusan beragam sekolah mantri tersebut menyokong berbagai penyuluhan, dari kota hingga pelosok desa,” kata Martina saat dihubungi reporter Alinea.id, Senin (6/4).
Untuk mengatasi wabah pes, para mantri—yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah kolonial—mengajarkan kebersihan kepada pribumi, seperti menganjurkan mereka menjemur kasur untuk mengusir kutu hingga membangun rumah berdinding batu.
Ketika wabah pes mengancam penduduk Kota Malang, Jawa Timur pada 1911-1916, tatanan pemerintahan di sana pun beralih rupa. Saat itu, dibentuk gemeente (kotamadya), yang secara administratif bisa mengambil kebijakan mandiri menangani pes, tanpa perlu ada komando dari Batavia.
Wabah pes pun memukul perekonomian di Hindia Belanda karena kebanyakan korbannya pekerja perkebunan. “Ekspor komoditi gula terganggu,” ujar Martina.
Pandemi flu Spanyol, yang masuk ke Hindia Belanda pada 1918 pun turut menghantam perekonomian. Menurut kandidat PhD di University of Melbourne, Ravando Lie, flu Spanyol menyebabkan kelaparan akibat gagal panen.
Kala itu, flu Spanyol muncul saat Hindia Belanda dilanda musim kemarau panjang. Imbasnya, harga beras tak terjangkau. Di sana-sini muncul tengkulak yang memanfaatkan kesempatan menjual beras dengan harga berkali-kali lipat.
“Pemerintah kolonial pun mengesahkan Influenza Ordonnantie. Salah satu aturannya memperketat pemeriksaan di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi titik temu dari dalam maupun luar Hindia Belanda,” ujar sejarawan yang fokus meneliti sejarah kesehatan ini saat dihubungi, Rabu (8/4).
Covid-19 dan masa depan dunia

Beberapa bulan ini, dunia dibuat kacau balau karena pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19). Jutaan orang terinfeksi, nyaris 100.000 orang lainnya meregang nyawa. Di tengah kecemasan akan masa depan dunia, sejumlah ilmuwan memaparkan prediksi mereka.
Sejarawan dan penulis buku Sapiens: A Brief History of Humankind (2014) Yuval Noah Harari, menulis dua artikel terkait pandemi Covid-19 di TIME dan Financial Times. Di TIME edisi 15 Maret 2020, tulisannya terbit dengan judul “In the Battle Against Coronavirus, Humanity Lacks Leadership”.
Di dalam tulisannya itu, ia menggarisbawahi bahwa isolasi jangka panjang malah akan menyebabkan keruntuhan ekonomi, tanpa adanya usaha nyata menangani penyakit menular. Penangkalan utama epidemi, menurut Yuval, bukan pemisahan, tetapi kerja sama.
Selain itu, yang tak kalah penting melawan pandemi, menurut Yuval adalah informasi ilmiah. Ia mengatakan, selama beberapa abad terakhir, para ilmuwan, dokter, dan perawat di seluruh dunia mengumpulkan informasi dan bersama-sama berhasil memahami mekanisme di balik epidemi, serta cara melawannya.
“Hanya butuh waktu dua minggu bagi para ilmuwan untuk mengidentifikasi coronavirus jenis baru, mengurutkan genomnya, dan mengembangkan tes yang bisa diandalkan untuk mengidentifikasi orang yang terinfeksi,” tulis Yuval.
Yuval mencontohkan kemenangan manusia melawan “predator ganas” yang tak terlihat saat terjadi wabah cacar pada 1967. Ketika itu, ada 15 juta orang yang terinfeksi dan dua juta orang meninggal dunia.
Namun, pada dekade selanjutkan, kampanye global vaksinasi cacar sangat berhasil. Sehingga pada 1979, World Health Organization (WHO) menyatakan cacar sudah sepenuhnya bisa diberantas.
“Pada 2019, tak ada satu orang pun yang terinfeksi atau dibunuh cacar,” kata Yuval.
Ia menekankan pentingnya vaksinasi, antibiotik, menjaga kebersihan, dan membangun infrastruktur medis untuk melawan pandemi.
Solidaritas global penting pula dilakukan. Ketika satu negara dilanda epidemi, kata dia, mereka harus bersedia dengan jujur berbagi informasi tentang wabah. Negara-negara lain pun harus bisa mempercayai informasi itu dan bersedia memberikan bantuan.
“Saat ini, China dapat mengajarkan banyak pelajaran penting tentang coronavirus ke negara-negara di seluruh dunia, tetapi ini menuntut tingkat kepercayaan dan kerja sama internasional yang tinggi,” katanya.
Karantina dan penguncian wilayah, kata dia, sangat penting menghentikan penyebaran epidemi. Namun, jika negara-negara saling tidak percaya dan masing-masing merasa menang sendiri dan pemerintahnya ragu mengambil langkah drastis, maka akan berbahaya.

“Dalam perang melawan virus, manusia perlu menjaga perbatasan dengan cermat. Tapi bukan perbatasan antarnegara,” ujarnya.
Celakanya, saat ini pun dunia kehilangan pemimpin global yang bisa menginspirasi, mengatur, dan membiayai masalah global yang terkoordinasi. Ia mengatakan, selama epidemi Ebola pada 2014 dan krisis keuangan global pada 2008, Amerika Serikat tampil sebagai pemimpin dunia.
Namun, kata dia, beberapa tahun terakhir Amerika Serikat sudah mengundurkan diri dari perannya sebagai pemimpin global. Saat ini, pemerintah Amerika Serikat sudah memotong dukungan untuk organisasi internasional, seperti WHO.
“Bahkan jika pada akhirnya mencoba untuk mengambil alih kepemimpinan, kepercayaan pada pemerintahan Amerika Serikat saat ini telah terkikis sedemikian rupa, sehingga hanya sedikit negara yang mau mengikutinya,” ujarnya.
Yuval prihatin, yang ada sekarang justru xenofobia, isolasionisme, dan ketidakpercayaan. Padahal, kata dia, pandemi sesungguhnya membantu umat manusia menyadari bahaya akut: perpecahan global.
“Di saat krisis ini, perjuangan krusial terjadi di dalam kemanusiaan itu sendiri. Jika epidemi ini menghasilkan perpecahan yang lebih besar dan ketidakpercayaan di antara manusia, itu akan menjadi kemenangan terbesar virus,” tuturnya.
Satu artikel lagi yang ditulis Yuval berjudul "The world after coronavirus," dalam Financial Times edisi 20 Maret 2020. Inti tulisan ini serupa dengan yang ditulis di TIME.
Penulis Homo Deus: A Brief History of Tomorrow (2015) itu menawarkan dua opsi utama mengatasi pandemi, yakni pengawasan totaliter atau penguatan warga negara serta isolasi nasionalis atau solidaritas global.
Di dalam pengawasan totaliter atau penguatan warga negara, Yuval menekankan beberapa poin penting, yakni pemerintah memonitor orang dan menghukum siapa saja yang membangkang; pemanfaatan teknologi sebagai alat pengawasan orang-orang yang diduga terinfeksi coronavirus; membangun kembali kepercayaan pada sains, pejabat, dan media; mengadakan tes menyeluruh; dan membagi informasi yang baik dan laporan yang jujur, sehingga masyarakat mau bekerja sama.
Sementara di dalam isolasi nasionalis atau solidaritas global, ia menekankan untuk berbagi informasi secara global; kerja global untuk memproduksi dan mendistribusikan alat-alat medis, serta mengirim tenaga medis; antarnegara bersedia terbuka tentang informasi, meminta nasihat, dan percaya data yang diterima; serta kerja sama antarnegara untuk mengizinkan ilmuwan, dokter, jurnalis, politisi, dan pengusaha melintasi perbatasan.
Selain Yuval, peneliti bidang ekonomi ekologis dari Centre for the Understanding of Sustainable Prosperity, University of Surrey, Simon Mair memprediksi empat kemungkinan masa depan dunia usai pandemi, dari perspektif ekonomi. Tulisan Simon terbit dengan judul “What will the world be like after coronavirus? Four possible futures” di The Conversation, 30 Maret 2020.
Empat skenario itu, antara lain kapitalisme negara, barbarisme, sosialisme negara, dan saling membantu.
Kapitalisme negara berwujud negara akan memberlakukan stimulus besar-besaran, dengan memberikan kredit dan pembayaran langsung ke bisnis. Skenario ini kemungkinan berhasil, jika pandemi bisa dikontrol dalam waktu yang singkat.
Barbarisme adalah negara menerima risiko besar karena kesalahan dalam penanganan pandemi. Terjadi kekacauan, perekonomian hancur, dan rakyat kelaparan. Konsekuensinya, harus melakukan penghematan besar-besaran agar bisa kembali normal.
Sosialisme negara adalah negara menasionalisasi rumah sakit dan pembayaran pekerja bukan dipandang sebagai alat untuk melindungi pasar, tetapi cara untuk melindungi kehidupan. Negara mengambil langkah, melindungi sektor ekonomi penting, seperti produksi makanan, energi, dan tempat tinggal.
Menurut Simon, sosialisme negara muncul sebagai konsekuensi kegagalan kapitalisme negara dan dampak pandemi yang berkepanjangan. Namun, skenario ini berisiko melahirkan pemerintahan yang otoriter.
Terakhir, saling membantu. Di dalam skenario ini, negara tak mengambil peran yang menentukan. Sebaliknya, individu dan kelompok kecil mulai mengorganisir dukungan.
Risikonya, kelompok-kelompok kecil tak bisa dengan cepat memobilisasi jenis sumber daya yang diperlukan dan secara efektif meningkatkan kapasitas layanan kesehatan. Bentuk masa depan skenario ini adalah munculnya struktur demokrasi baru.

Pengaruh kuat China dan nasib Indonesia
Menurut pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Teuku Rezasyah, pandemi Covid-19 seharusnya bisa memaksa berbagai negara bekerja sama untuk menciptakan solidaritas nasional dan global.
Di sisi lain, Rezasyah melihat, peta politik dunia mulai mencari pola baru saat pandemi. “Misalnya, meredanya konflik di Laut China Selatan, mengendurnya pengaruh Amerika Serikat di Asia Timur,” kata dia saat dihubungi, Rabu (8/4).
Pandemi mengakibatkan semua negara yang terpapar babak belur. Bahkan, menurut Rezasyah, membuat negara adidaya seperti Amerika Serikat kewalahan. Anggaran negara mereka banyak tersedot untuk program kesehatan, birokrasinya tidak siap, serta tentaranya dialihkan untuk membantu mengatasi Covid-19.
China, kata dia, menjadi negara yang menonjol. Dalam hal manajemen krisis, Rezasyah menilai, China unggul jauh dibandingkan Amerika Serikat.
“China bisa membagikan pengalaman terbaiknya mengatasi pandemi dan membantu negara-negara lain,” ujar dia.
China mendapatkan reputasi karena keberhasilan menangani Covid-19. Sehingga, kata Rezasyah, beberapa negara dunia ketiga lebih menaruh kepercayaan terhadap China ketimbang Amerika Serikat.
Selain itu, China unggul dalam strategi kemitraan dan sudah menciptakan beragam ketergantungan baru di negara-negara dunia ketiga. Ketika pandemi berakhir, ujar dia, bila dibandingkan negara lainnya, China lebih siap menciptakan stimulus perdagangan baru.
“Dominasi China akan semakin menguat, bahkan mampu mengklaim teritorial negara lain. Terutama di kawasan Laut China Selatan,” tuturnya.

Akan tetapi, pengaruh China tidak bisa menjangkau Italia dan Spanyol, dua negara di Eropa yang saat ini paling parah terdampak coronavirus. Menurutnya, dua negara itu masih terlindungi sebagai negara anggota Uni Eropa.
“Yang saya khawatirkan ke depan malah China berada dalam posisi donatur terbesar di Indonesia,” ujarnya.
Negara-negara yang memiliki kebiasaan berutang, seperti Indonesia, menurutnya, akan semakin jatuh setelah pandemi berakhir. Ia memprediksi, negara-negara semacam ini akan semakin miskin karena anggarannya menipis.
“Jika rakyat mengeluhkan kondisi perekonomian, bisa berpotensi kaos,” ucapnya.