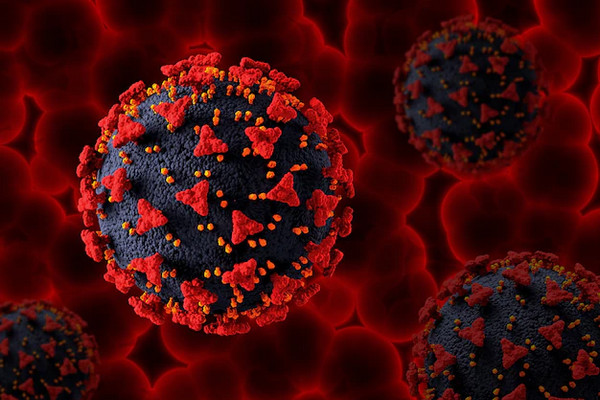Ahli hukum bisnis dan perdagangan internasional Universitas Islam Indonesia (UII), Nandang Sutrisno, menilai, gugatan hukum terhadap China terkait pandemi coronavirus baru (Covid-19) sukar dilakukan. Apalagi, jika melalui mekanisme peradilan setingkat negara bagian di Amerika Serikat (AS).
"Tidak bisa menggugat sebuah negara berdaulat seperti China. Pemerintah China jelas dilindungi oleh doktrin kekebalan kedaulatan sebuah negara bangsa, sama seperti pemerintahan negara lain," ujarnya saat dihubungi, baru-baru ini.
Sekalipun China dianggap terbukti bersalah, belum tentu bersedia membayar ganti kerugian kepada negara-negara penggugat. "Itu merupakan masalah tersediri," ucap dia.
Jika gugatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dilayangkan ke Mahkamah Internasional, terlebih dulu meminta persetujuan "Negeri Tirai Bambu" sebagai sebuah negara. Pengadilan berlangsung setelah ada persetujuan kedua pihak, penggugat dan tergugat. "Apakah China bersedia untuk digugat?" tanya Nandang.
Dirinya mengingatkan, pelaporan pengadilan HAM internasional bersandar pada perjanjian global dan berdasarkan dua hal. Perjanjian HAM internasional (The Treaty Based Mechanism) dan Piagam PBB (The Charter Based Mechanism).
Dalam perjanjian HAM internasional, mekanisme pengaduan dibentuk berdasarkan perjanjian atau konvensi HAM internasional. Namun, hanya berlaku dan mengikat bagi negara yang telah menandatangani dan meratifikasinya.
Pelaporannya pun mesti diajukan kepada Komite Hak Asasi Manusia (Human Rights Committee/HRC). pembentukannya berdasarkan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1976. "Masalahnya, apakah China telah meratifikasi ICCPR?" katanya.
Jika meninjau piagam PBB, ungkapnya, takkan menuju pada mekanisme ganti kerugian. Sebab, mekanisme itu tidak dibentuk konvensi-konvensi HAM, melainkan merujuk Pasal 55 dan Pasal 56 Piagam PBB tentang memajukan pemecahan masalah internasional dan penghormatan HAM global, kebebasan dasar bagi semua, serta mandat yang dimiliki Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC).
"Jadi, jika negara tergugat tidak meratifikasi ICCPR, maka hanya dapat dilakukan pelaporan dengan mekanisme Charter Based berdasarkan Piagam PBB. Namun, hal itu perlu tinjauan lebih lanjut dan membutuhkan waktu sangat lama," bebernya.
Pun tidak mungkin menggugat China ke pengadilan penjahat perang internasional di Nuremberg, Jerman. Alasannya, harus mengikuti mekanisme International Criminal Court (ICC). "Masalahnya, baik China maupun Amerika Serikat, bukan negara yang masuk sebagai anggota ICC," jelasnya.
Tak sekadar itu. Gugatan melalui resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB juga bakal sukar, mengingat China menjadi negara anggota dan memiliki hak veto. "Jadi, memang semua jalur hukum akan sulit," ungkapnya.
Sejumlah pihak menggugat China terkait pandemi Covid-19. Jaksa Agung Missouri, misalnya, melayangkan gugatan perdata ke pengadilan federal atas tuduhan kelalaian dan mengakibatkan kematian ribuan orang, serta kerusakan ekonomi hingga puluhan miliar dolar AS.
Ribuan warga AS juga mengajukan gugatan (class action) terhadap China. Mereka ditangani firma hukum Berman Law Group di Miami, Florida dan menuntut ganti rugi miliaran dolar AS untuk para korban.
Gugatan berikutnya dilayangkan lembaga pemikir Inggris, Henry Jackson Society. Menurutnya, negara-negara G7 bisa menggugat ganti rugi ke China hingga £3,2 triliun. Sementara di Jerman, gugatan ganti rugi diajukan tabloid Bild dengan menerbitkan surat tagihan €24 miliar untuk kerugian pariwisata selama Maret-April 2020.
Israel juga menuntut ganti rugi kepada pemerintah China, Wuhan Institute of Virology, dan militer China People Liberation Army (PLA) karena dianggap sengaja menutup-nutupi kebenaran informasi penyebaran Covid-19 sejak pertengahan Desember 2019. Pun tidak adanya upaya memadai untuk menginformasikan yang sebenarnya kepada dunia internasional.
Gugatan kepada pihak sama diajukan asosiasi advokat India, Ia menyampaikan komplain atas masalah pelanggaran HAM.