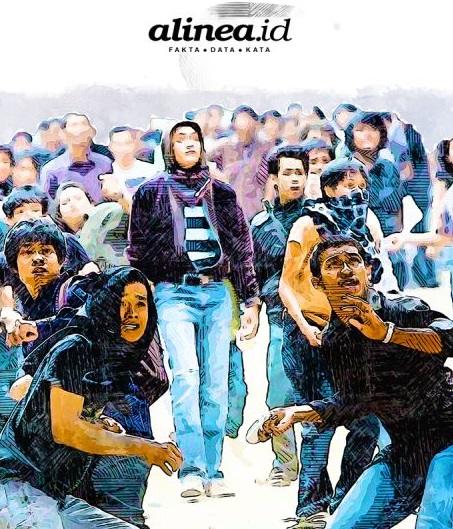Akar patriarki yang kuat di balik KDRT di Madura
Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi dalam waktu berdekatan di Madura, Jawa Timur. Kasus pertama, seorang suami berinisial AR, 28 tahun, yang menganiaya istrinya berinisial NS, 27 tahun. Penganiayaan itu dilakukan antara Juni dan Oktober 2024 di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Dalam penganiayaan pertama, korban mengalami luka bekas cekikan di bagian leher dan lebam di wajah. Kejadian KDRT kedua terjadi pada 4 Oktober 2024. Saat itu, NS dan AR terlibat cekcok. Lalu, AR memukul wajah korban yang menyebabkan mata sebelah kanan mengalami memar.
NS kemudian dibawa ke Puskesmas Kecamatan Batang-Batang. Namun, sesampainya di puskesmas, AR mencabut selang oksigen NS, sehingga korban meninggal pada Sabtu (5/10). Motif tersangka melakukan itu karena NS menolak berhubungan badan.
Tak lama berselang, kejadian KDRT kedua terjadi di Kecamatan Manding, Sumenep, Jawa Timur pada Rabu (9/10). Saat itu, korban SW, 40 tahun, dianiaya suaminya berinisial E, 39 tahun. Akibat penganiayaan, empat jari tangan kiri korban putus dan di bagian perut terdapat luka robek.
Menanggapi kasus KDRT yang menyebabkan korban jiwa tersebut, sosiolog dari Universitas Trunojoyo Madura, Iskandar Dzulkarnain menilai, peristiwa itu merupakan puncak gunung es dari banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan. Menurutnya, KDRT hingga menelan korban jiwa bermula dari konstruksi kekerasan yang dinormalisasi dalam rumah tangga.
“Fenomena KDRT yang tidak dilaporkan karena masih dianggap masalah dan aib keluarga yang tidak perlu dilaporkan ke khalayak ramai, termasuk ke kepolisian,” kata Iskandar kepada Alinea.id, Sabtu (12/10).
Iskandar mengatakan, KDRT yang banyak terjadi di Madura merupakan buah dari kuatnya akar patriarki yang tertanam. Seorang suami kerap kali diposisikan sebagai “raja”, yang tidak boleh dibantah atau dilawan perintahnya.
“Setiap petuah dan kehendaknya (suami harus dituruti), termasuk dalam hal ini kadang kala keluarga suami mendukungnya,” ujar Iskandar.
Sebenarnya, kata Iskandar, budaya Madura tradisional sudah memiliki katup pengaman KDRT. Misalnya, pola permukiman tradisional Madura bernama tanèyan lanjhang atau halaman panjang yang biasanya digunakan untuk suami agar tinggal di keluarga istri.
“Sebenarnya itu salah satu solusi terbaik untuk menghindarkan terjadinya KDRT. Pola permukiman tersebut, kini sudah mulai menghilang,” kata Iskandar.
Iskandar memandang, untuk mengatasi KDRT semakin brutal, sebenarnya tokoh agama, aparat desa, dan masyarakat merupakan mereka yang ikut bertanggung jawab mencegahnya.
“Terutama orang tua suami untuk memberikan pendidikan pranikah, (seperti) arti dan makna menjaga keluarga yang berbahagia dan saling menghargai antara suami-istri,” tutur Iskandar.
Sementara itu, komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Rainny Marike Hutabarat memandang, KDRT yang jamak terjadi di Madura bertalian erat dengan budaya patriarki, yang berkelindan dengan budaya maritim dan agama. Secara umum, dalam budaya maritim laki-laki berperan sebagai nelayan, kepala keluarga, pencari nafkah, dan pemimpin pada komunitasnya.
“Selain itu, tradisi pernikahan Madura mengharuskan perempuan memberi mahar kepada laki-laki dan aturan poligami yang diizinkan agama,” ujar Rainny, Minggu (13/10).
“Kondisi sedemikian merentankan perempuan terhadap kekerasan.”
Kondisi perempuan yang tersubordinasi di hadapan laki-laki, memperlemah posisi tawarnya. Terlebih dalam kondisi kesulitan ekonomi, yang terjadi akibat rendahnya tingkat pendidikan perempuan ketimbang laki-laki.
Rainny melanjutkan, kondisi struktural dan kultural yang membuat posisi perempuan di Madura dalam bahaya KDRT, menandai negara mesti mengambil langkah untuk mencegah jatuhnya korban perempuan dan anak perempuan.
“Komnas Perempuan mendorong pemerintah setempat untuk mengeluarkan kebijakan perlindungan perempuan dan anak perempuan terhadap kekerasan, di antaranya memperkuat koordinasi antarpihak agar layanan bergerak proaktif, terpadu, dan memudahkan korban mengurus kasusnya, tanpa harus mengalami banyak kerugian waktu, ongkos, dan ekonomi akibat meninggalkan pekerjaan dan rumah tangga,” tutur Rainny.
Dia mendesak pemerintah memperluas jangkauan dan koordinasi layanan pengaduan, baik berbasis komunitas, masyarakat, maupun negara, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dari kepolisian.
“Sementara puskesmas terdekat perlu diperkuat untuk menerima kebutuhan layanan konseling atau penanganan psikis dan fisik bagi perempuan korban kekerasan,” kata Rainny.
Rainny juga mendorong pemerintah desa untuk mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan gender dalam kebijakannya. “Pelibatan substantif kelompok-kelompok perempuan dalam musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) desa dan memfasilitasi layanan pengaduan kekerasan secara terpadu dan terjangkau,” ujar Rainny.
Tak kalah penting, mencegah kekerasan perempuan di lembaga pendidikan, seperti sekolah dan pesantren. “Pengelola perlu mengeluarkan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan dan membentuk satuan tugas penanganan kekerasan, termasuk kekerasan seksual di sekolah atau pesantren,” ucap Rainny.
Di sisi lain, untuk penanganan pelaku KDRT, kata dia, harus mengacu pada undang-undang menyoal kekerasan terhadap perempuan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekersan Seksual.
“Komnas Perempuan mengingatkan negara untuk mencegah impunitas pelaku, menjalankan rehabilitasi pelaku agar kekerasan tidak berulang di kemudian hari,” ucap Rainny.
Di samping itu, ujar Rainny, Komnas Perempuan pun mendesak agar ada pemberatan terhadap pelaku femisida—kejahatan kebencian berbasis jenis kelamin. “Karena pelaku femisida umumnya telah melakukan penganiayaan, sebelum pembunuhan,” ujar Rainny.