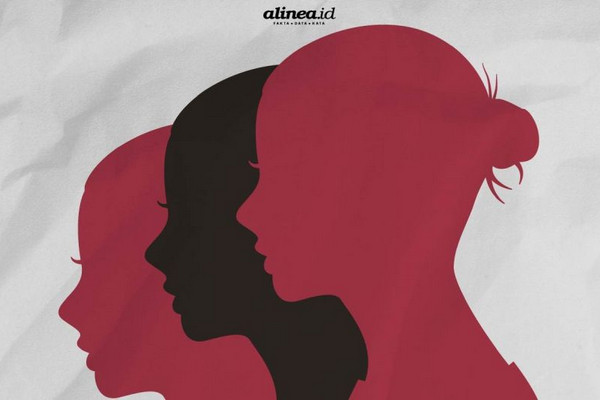Alasan mengapa seseorang melakukan kekerasan politik
Calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, menghentikan pidatonya soal imigrasi ilegal, saat peluru menyasar telinga kanannya, di depan pendukungnya di Pennsylvania, beberapa waktu lalu. Suara tembakan beberapa kali terdengar.
Tak lama, pelaku penembakan dilaporkan tewas dalam baku tembak dengan pasukan pengamanan Presiden Amerika Serikat, Secret Service. Seorang pendukung Trump dilaporkan tewas karena insiden itu. Federal Bureau of Investigation (FBI) menjelaskan, penembak itu bernama Thomas Matthew Crooks, 20 tahun. Ia tinggal sekitar 35 mil dari lokasi penembakan.
Ada beberapa penelitian yang mengungkap motivasi seseorang yang berkontribusi terhadap kekerasan politik. Dalam penelitian yang diterbitkan jurnal Psychology of Violence (2024), para peneliti menemukan, persepsi pribadi tentang keyakinan menjadi korban bisa secara signifikan memengaruhi sikap terhadap tindakan kekerasan politik.
Riset itu dilakukan lewat tiga penelitian berbeda. Pertama, melakukan survei terhadap 393 peserta dari Amazon’s Mechanical Turk. Mereka menemukan korelasi antara sifat korban dan dukungan terhadap kekerasan politik.
Sampel diperluas pada penelitian kedua, menjadi 1.000 peserta yang direkrut melalui lembaga riset YouGov, dengan mengonfirmasi temuan sebelumnya sekaligus memeriksa korban persaingan antarkelompok. Para peneliti menemukan, sifat korban secara langsung terkait dengan dukungan terhadap kekerasan politik dan secara tak langsung lewat sifat kompetitif korban, meski tak berkorelasi dengan tindakan politik tanpa kekerasan.
Penelitian ketiga menggunakan manipulasi eksperimental untuk membangun hubungan sebab akibat, yang menunjukkan, korban kompetisi antarkelompok meningkatkan dukungan terhadap kekerasan politik, terutama di antara mereka yang punya sifat sebagai korban yang tinggi.
“Eksplorasi terhadap sifat korban ini menambah pengetahuan dengan menunjukkan, mereka yang terus-menerus merasa menjadi korban dalam kehidupan sehari-hari lebih cenderung mendukung kekerasan politik, terutama ketika mereka juga mencari makna dalam hidup,” tulis PsyPost.
Penelitian kedua yang menyinggung kekerasan politik terbit di jurnal Plos One (Januari, 2024). Dalam penelitian itu, para periset dari University of California menemukan, kelompok tertentu di Partai Republik pro-Trump, yang dikenal sebagai MAGA—akronim Make America Great Again—Republicans, lebih cenderung mendukung kekerasan politik dibandingkan kelompok lain. Kelompok ini besarnya 15% dari populasi orang dewasa Amerika Serikat, memiliki keyakinan berbeda mengenai ras dan demokrasi.
Penelitian ini berdasarkan survei yang dilakukan lembaga riset Ipsos pada 13 Mei-2 Juni 2022, melibatkan 8.620 peserta dari kelompok perwakilan nasional. Hasilnya, anggota MAGA dari Partai Republik, sebut penelitian itu, lebih cenderung merasakan adanya ancaman serius terhadap demokrasi Amerika, mendukung adanya pemimpin yang kuat dalam menjaga demokrasi, dan mendukung warga bersenjata yang berpatroli di tempat pemungutan suara.
Terkait kekerasan politik, 58,2% anggota MAGA Partai Republik percaya, tindakan tersebut dibenarkan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Namun, kesediaan pribadi untuk terlibat dalam kekerasan tersebut rendah.
“Penelitian ini menunjukkan, meski secara konseptual anggota MAGA Partai Republik lebih mendukung kekerasan politik, terdapat kesenjangan antara dukungan ini dan kesediaan pribadi mereka untuk berpartisipasi,” tulis Psy Post.
Tampaknya, penelitian ini ada korelasinya dengan pelaku penembakan Trump, Crooks. Meski belum diketahui motifnya, menurut Daily Mail, Crooks tercatat seorang anggota Partai Republik, yang memberikan sumbangan sebesar 15 dollar AS kepada komite aksi politik liberal ActBlue pada hari pelantikan Joe Biden.
Penelitian lainnya terbit di jurnal JAMA Network Open (April, 2024) yang ditulis para peneliti dari The University of California Davis School of Medicine. Para peneliti mengungkap, seseorang yang baru saja membeli senjata api, sering membawanya di ruang publik. Selain itu, memiliki senapan jenis serbu lebih cenderung mendukung atau berpartisipasi dalam kekerasan politik, dibandingkan pemilik senjata api lainnya.
Penelitian ini memanfaatkan data dari survei skala besar dan representatif yang dilakukan Ipsos antara Mei dan Juni 2022, melibatkan 12.851 responden. Hasilnya, 38,8% pemilik senjata api percaya kekerasan secara umum dibenarkan untuk mencapai tujuan politik. Dukungan seperti ini terekam dari mereka yang memiliki senapan serbu, sebanyak 42,3%; pembeli senjata api baru, sebanyak 43,9%; dan mereka yang rutin membawa senjata api di ruang publik, sebanyak 55,9%.
Riset ini secara tak langsung terkait pula dengan jenis senjata pelaku penembakan Crooks, yakni AR-15. AR-15 merupakan senapan semi-otomatis serbu yang cukup populer di Amerika. Dikutip dari The Guardian.
M-16 dan AR-15 telah digunakan dalam sejumlah penembakan massal di Amerika, termasuk serangan di Las Vegas pada Oktober 2017 yang menewaskan 60 orang.
Baru-baru ini, dua orang peneliti, yakni Joseph Siev dari University of Virginia dan Richard Petty dari The Ohio State University menerbitkan hasil risetnya di jurnal Science Advance (Juni, 2024). Mereka menemukan, semakin ambivalen seseorang terhadap isu politik, semakin besar kemungkinan mereka mendukung kekerasan dan tindakan ekstrem lainnya yang berkaitan dengan politik.
Ambivalensi merupakan keadaan adanya reaksi, kepercayaan, atau perasaan yang bertentangan secara simultan terhadap suatu objek. Dengan kata lain, ambivalensi adalah pengalaman atau sikap terhadap sesuatu yang mengandung komponen bervalensi positif dan negatif.
Di The Conversation, Siev dan Petty mengungkapkan, mereka mengukur pendapat beberapa ribu orang dalam sejumlah survei tentang salah satu dari beberapa topik, seperti aborsi, pengendalian senjata, dan kebijakan pandemi Covid-19. Mereka mengukur pula seberapa ambivalen peserta terhadap topik tersebut.
Lalu, mereka menanyakan kesediaan peserta untuk kemungkinan terlibat dalam berbagai tindakan guna mendukung pendapat mereka, seperti memilih calon yang disetujui peserta, menyumbangkan uang, atau menjadi sukarelawan. Tindakan lain yang lebih ekstrem, seperti melakukan kekerasan terhadap lawan politik mereka.
“Ketika kami menganalisis hubungan antara ambivalensi masyarakat dan kesediaan mereka untuk terlibat atau mendukung setiap perilaku, kami menemukan, hasil dalam semua penelitian bergantung pada ekstremitas perilaku tersebut,” tulis Siev dan Petty di The Conversation.
“Seperti yang diperkirakan, masyarakat yang lebih ambivalen kurang bersedia mendukung atau terlibat dalam tindakan moderat, seperti memberikan suara.”
Namun, kata mereka, masyarakat yang merasa lebih ambivalen juga lebih bersedia mendukung atau terlibat dalam tindakan ekstrem, terutama bila mereka memiliki keyakinan yang kuat terhadap isu tertentu.
Selanjutnya, Siev dan Petty mencoba memahami mengapa orang-orang yang lebih ambivalen menyatakan lebih banyak dukungan terhadap tindakan politik ekstrem, mulai dari menghadapi lawan politik atau berkampanye untuk menjatuhkan mereka, hingga melakukan kekerasan.
Awalnya, Siev dan Petty menduga, salah satu faktornya adalah ketidaknyamanan psikologis yang dialami orang-orang yang ambivalen.
“Ketika orang merasa tidak nyaman dengan keyakinan mereka, mereka sering mencari cara untuk mengimbanginya dengan memberi sinyal kekuatan. Misalnya, ketika keyakinan mereka ditentang, terkadang orang merespons dengan memberikan dukungan lebih kuat lagi,” ujar Siev dan Petty.
Hasil yang Siev dan Petty temukan konsisten dengan gagasan bahwa orang-orang mungkin mewujudkan ketidaknyamanan mereka dengan mendukung tindakan ekstrem.
“Ketika kami menanyakan seberapa tidak nyamannya perasaan peserta mengenai opini yang mereka miliki soal isu politik, orang-orang yang lebih ambivalen melaporkan, mereka merasa kurang nyaman dengan pandangan mereka, yang juga terkait dengan hal tersebut, bagi mereka lebih mendukung perilaku ekstrem,” tutur Siev dan Petty dalam The Conversation.