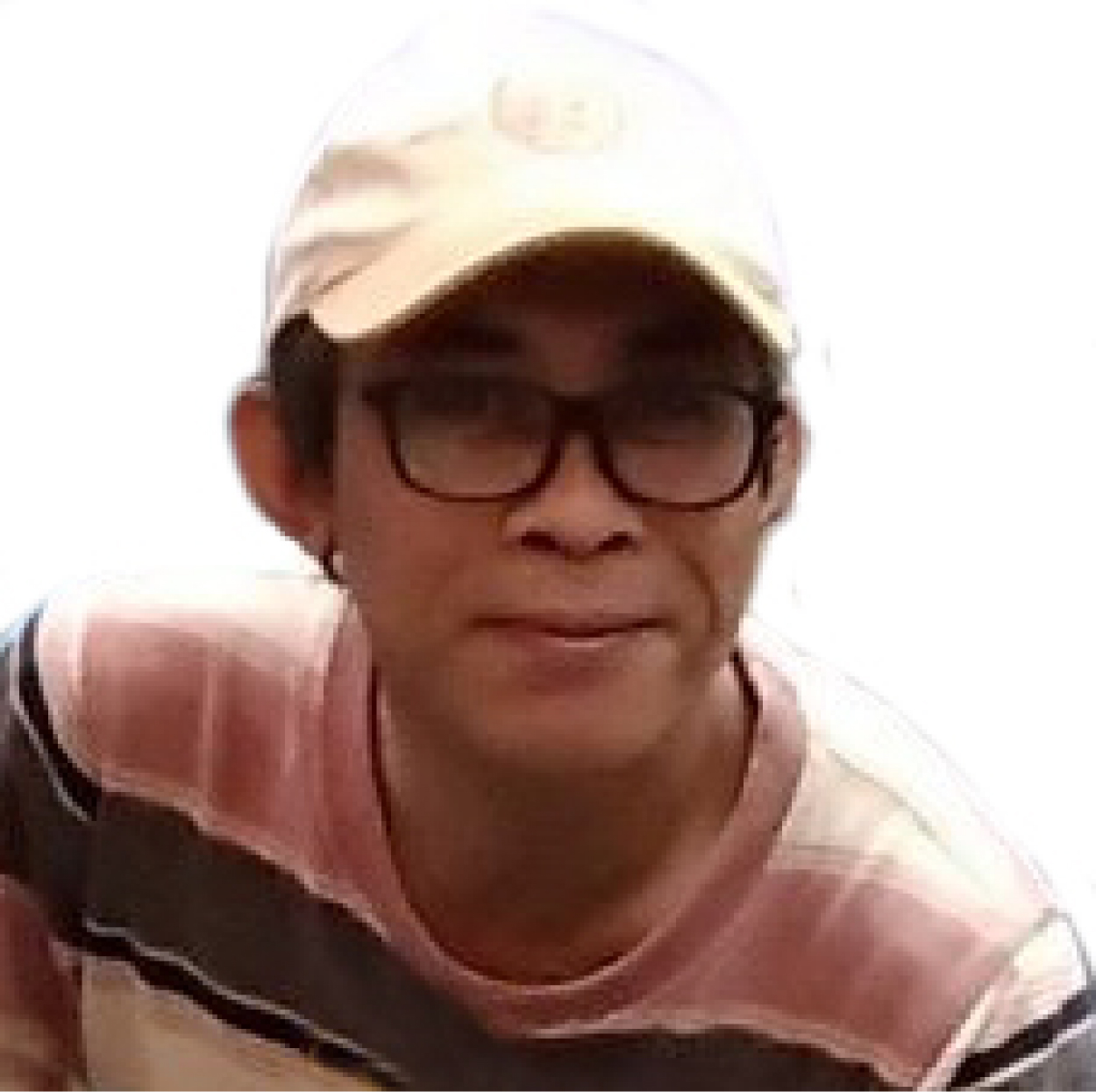Bagaimana Jepang mengembangkan arsitektur tahan gempa lebih dari satu abad?
Seluruh dunia pada pekan ini menyaksikan pemandangan gedung-gedung yang hancur menjadi puing. Bukannya pemandangan dari Gaza, di mana Palestina dibom habis zionis Israel. Tapi di prefektur Ishikawa, pantai barat Jepang, pada hari Senin (1/1) Tahun Baru. Tatkala gempa berkekuatan 7,5 skala Richter mengguncang.
Tingkat kerusakan sepenuhnya masih belum diketahui. Setidaknya 270 rumah di wilayah tersebut hancur, kata pihak berwenang. Kemungkinan angka terakhir jauh lebih tinggi.
Jumlah ini, misalnya, tidak termasuk Suzu atau Wajima, sebuah kota berpenduduk lebih dari 27.000 jiwa yang terletak hanya 32 kilometer dari pusat gempa. Petugas pemadam kebakaran mengatakan, seperti dikutip NHK, di sana sekitar 200 bangunan telah terbakar.
Rangkaian laporan ini menggambarkan tragedi yang dihadapi banyak penduduk di wilayah tersebut. Tidak ada dua peristiwa seismik yang dapat dibandingkan secara langsung. Tapi gempa dengan kekuatan serupa di wilayah lain di dunia seringkali menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar. Seperti gempa berkekuatan 7,6 SR yang menyebabkan runtuhnya lebih dari 30.000 bangunan di Kashmir pada tahun 2005.
Sebaliknya, Ishikawa mungkin selamat dengan mudah, menurut Robert Geller, profesor emeritus seismologi di Universitas Tokyo.
“Bangunan-bangunan modern tampaknya memiliki kinerja yang sangat baik,” ujar Robert kepada CNN sehari setelah gempa terjadi di Jepang. Seraya menyebutkan bahwa rumah-rumah tua “yang beratap genteng tanah liat” tampaknya mengalami kondisi terburuk.
“Sebagian besar rumah keluarga tunggal, meski rusak, tidak runtuh seluruhnya,” katanya.
Pepatah desain seismik menyatakan bahwa gempa bumi tidak membunuh manusia, melainkan bangunan. Jepang, salah satu negara yang paling rawan gempa di dunia. Para arsitek, insinyur, dan perencana kota telah lama berupaya membuat kota-kota tahan bencana terhadap guncangan besar melalui kombinasi kebijaksanaan kuno, inovasi modern, dan peraturan bangunan yang terus berkembang.
Dari “peredam” skala besar, yang berayun seperti pendulum di dalam gedung pencakar langit, hingga sistem pegas atau bantalan bola yang memungkinkan bangunan bergoyang terlepas dari fondasinya, teknologi telah mengalami kemajuan pesat sejak gempa besar Kanto meratakan sebagian besar wilayah Tokyo dan Yokohama hanya dalam waktu 100 tahun di masa lalu.
Namun sebagian besar inovasi berpusat pada gagasan sederhana yang telah lama dipahami: bahwa fleksibilitas memberikan peluang terbesar bagi struktur untuk bertahan hidup.
“Anda akan menemukan banyak bangunan, terutama rumah sakit dan bangunan penting yang penting, berada di atas (bantalan) karet ini sehingga bangunan itu sendiri dapat bergoyang,” kata Miho Mazereeuw. Profesor arsitektur dan urbanisme di Massachusetts Institute of Technology (MIT) ini mengeksplorasi budaya kesiapsiagaan Jepang dalam bukunya yang akan terbit “Design Before Disaster.”
“Secara konseptual, semuanya kembali pada gagasan bahwa, alih-alih menahan pergerakan bumi, Anda membiarkan bangunan tersebut ikut bergerak,” imbuhnya.
Prinsip ini telah digunakan di Jepang selama berabad-abad. Banyak pagoda kayu tradisional di negara ini, misalnya, yang selamat dari gempa bumi (dan kemungkinan besar akan hancur akibat kebakaran atau perang), meskipun bangunan modern tidak selamat.
Misalnya saja pagoda Kuil Toji setinggi 55 meter, yang dibangun pada abad ke-17 di dekat Kyoto — pagoda ini terkenal utuh setelah gempa besar Hanshin tahun 1995, yang juga dikenal sebagai gempa Kobe, sementara banyak bangunan di dekatnya runtuh.
Arsitektur tradisional Jepang memiliki banyak kesamaan dengan negara tetangganya, Korea dan China. Meskipun arsitektur tradisionalnya berbeda karena mencerminkan tingginya frekuensi gempa bumi di negara tersebut.
Secara khusus, tingkat kelangsungan hidup pagoda yang luar biasa telah lama dikaitkan dengan “shinbashira” – pilar utama yang terbuat dari batang pohon dan digunakan oleh arsitek Jepang selama setidaknya 1.400 tahun.
Baik ditancapkan ke tanah, bertumpu pada balok, atau digantung di atas, pilar-pilar ini menekuk dan melentur sementara masing-masing lantai bangunan bergerak ke arah yang berlawanan dengan yang terdekatnya. Gerakan goyangan yang diakibatkannya — sering kali disamakan dengan gerakan ular yang merayap — membantu melawan kekuatan getaran dan dibantu oleh sambungan yang saling bertautan, braket yang longgar, serta atap yang lebar.
Bangunan-bangunan di Jepang masa kini mungkin tidak semuanya menyerupai pagoda, namun gedung pencakar langit tentu saja mirip.
Meskipun negara ini memberlakukan batasan ketinggian yang ketat yaitu 31 meter hingga tahun 1960-an, karena bahaya yang ditimbulkan oleh bencana alam, para arsitek telah diizinkan untuk membangun gedung tersebut. Saat ini, Jepang memiliki lebih dari 270 bangunan dengan tinggi lebih dari 150 meter, terbanyak kelima di dunia, menurut data dari Council on Tall Buildings and Urban Habitat.
Memakai kerangka baja yang menambah fleksibilitas pada beton yang sangat kaku, para perancang bangunan bertingkat tinggi semakin berani dengan pengembangan beban penyeimbang skala besar dan sistem “isolasi dasar” (seperti bantalan karet yang disebutkan di atas) yang berfungsi sebagai peredam kejut.
Perusahaan properti di balik gedung tertinggi baru di Jepang, yang dibuka di pembangunan Azabudai Hills di Tokyo bulan Juli lalu, mengklaim fitur desain tahan gempa – termasuk peredam skala besar – akan “memungkinkan bisnis untuk terus beroperasi” jika terjadi peristiwa seismik sekuat rekor gempa Tohoku 9,1 skala richter yang terjadi pada tahun 2011.
Namun di banyak tempat di Jepang yang tidak memiliki gedung pencakar langit, seperti Wajima, ketahanan terhadap gempa lebih ditujukan untuk melindungi bangunan sehari-hari – rumah, sekolah, perpustakaan, dan toko. Kesuksesan Jepang bergantung pada kebijakan dan teknologi.
Salah satu alasannya adalah sekolah arsitektur Jepang telah memastikan – mungkin karena sejarah bencana alam di negara tersebut – bahwa mahasiswanya diberi pemahaman pada bidang desain dan teknik, kata Mazereeuw, yang juga mengepalai Urban Risk Lab MIT, sebuah organisasi penelitian yang meneliti risiko seismik dan iklim yang dihadapi kota.
“Tidak seperti di kebanyakan negara, sekolah arsitektur Jepang menggabungkan arsitektur dengan teknik struktural – di Amerika Serikat, Anda mengambil kelas teknik struktur tetapi kursusnya sangat rumit,” katanya, seraya menambahkan bahwa di Jepang kedua disiplin ilmu tersebut “selalu terikat satu sama lain.”
Para pejabat Jepang, selama bertahun-tahun, juga berupaya belajar dari setiap gempa besar yang pernah dihadapi negara tersebut, dengan melakukan survei terperinci dan memperbarui peraturan bangunan.
Proses ini dimulai setidaknya pada abad ke-19, kata Mazereeuw, menjelaskan bagaimana penghancuran luas bangunan batu bata dan batu bergaya Eropa baru pada gempa bumi Mino-Owari tahun 1891 dan gempa besar Kanto tahun 1923 menghasilkan undang-undang baru tentang perencanaan kota dan bangunan perkotaan.
Evolusi peraturan bangunan sedikit demi sedikit berlanjut hingga abad ke-20. Namun peraturan yang diperkenalkan pada tahun 1981 yang dikenal sebagai “shin-taishin,” atau Amandemen Standar Bangunan Tahan Gempa Baru – yang merupakan respons langsung terhadap gempa bumi lepas pantai Miyagi tiga tahun sebelumnya – terbukti menjadi titik balik.
Menetapkan persyaratan yang lebih tinggi untuk daya dukung bangunan baru dan memerlukan “pergeseran lantai” yang lebih besar (berapa banyak lantai yang dapat berpindah relatif satu sama lain), antara lain, standar baru ini telah terbukti sangat efektif sehingga rumah-rumah dibangun sesuai dengan standar sebelum tahun 1981 ( dikenal sebagai “kyu-taishin,” atau “sebelum tahan gempa”) jauh lebih sulit untuk dijual dan lebih mahal untuk diasuransikan.
Ujian nyata pertama terhadap peraturan ini terjadi pada tahun 1995 ketika gempa bumi besar Hanshin menyebabkan kerusakan luas di bagian selatan prefektur Hyogo. Dampaknya sangat nyata: 97% bangunan yang runtuh dibangun sebelum tahun 1981, menurut Global Facility for Disaster Reduction and Recovery.
Pertanyaan yang telah lama meresahkan para insinyur dan seismolog Jepang tetap ada: Bagaimana jika gempa bumi besar langsung menghantam kota seperti Tokyo, sesuatu yang telah diperingatkan oleh para pejabat di ibu kota Jepang bahwa kemungkinan terjadinya gempa bumi sebesar 70% dalam 30 tahun ke depan?
“Tokyo mungkin cukup aman. Tetapi tidak ada cara untuk mengetahui secara pasti sampai gempa besar berikutnya benar-benar terjadi,” kata Geller dari Universitas Tokyo.