
Democratic Policing: Gagasan wujudkan kepolisian yang demokratis
Saat berpidato di forum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) akhir 2018 lalu di Jakarta, Ketua PPAD Letnan Jenderal TNI (Pur) Kiki Syahnakri menyinggung buku Democratic Policing (2017). Ia menilai, buku yang ditulis Hermawan Sulistyo dan Tito Karnavian tersebut adalah produk intelektual yang ngawur dan berbahaya.
Namun, Kiki tak pernah menyebutkan secara detail di bagian mana yang membuatnya khawatir akan membahayakan negara atau militer. Lantas, apa sebenarnya yang dikhawatirkan Kiki tentang buku menyoal paradigma “kepolisian yang demokratis” setebal 489 halaman ini?
Isi buku
Buku ini terdiri dari tujuh bab, yang membahas tentang democratic policing dari level ide hingga praktik.
Di bab pertama, menjelaskan tentang perubahan dunia yang niscaya, terutama pada paruh kedua abad ke-20. Konsekuensi logis perubahan berupa demokratisasi yang sudah bergulir sejak Uni Soviet bubar, membuat institusi semacam Polri perlu melakukan adaptasi. Terlebih ketika dihadapkan pada tantangan baru, seperti kasus-kasus hak asasi manusia (HAM).
Policing terhadap kasus HAM tak direduksi sebatas penghormatan secara konvensional, tetapi diperluas hingga mencakup hak asasi ekonomi, sosial, dan kebudayaan.
Di bab kedua, penulis membahas tentang sejarah gagasan democratic policing, yang gaungnya baru terdengar dua tahun terakhir. Gagasan itu muncul berbarengan dengan berkembangnya sistem demokrasi, yang menjadi landasan kehidupan masyarakat.
Kemudian berkembang hingga era pra-Victoria, ketika Perdana Menteri Britania Raya Robert Peel (1778-1850) membentuk kepolisian modern pertama, yang terorganisir di London, Inggris. Lantaran permasalahan di masing-masing negara semakin rumit, polisi Eropa dan Amerika yang awalnya didesain sebagai perpanjangan tangan rezim, berganti wajah menjadi pengemban amanat rakyat.
Posisi itu membuat loyalitas pertama kepolisian harus bertumpu pada publik. Selain itu, mereka harus bekerja sesuai prinsip demokrasi, profesional, melayani dan melindungi masyarakat, berlandaskan HAM, serta bersikap netral, imparsial, dan tak diskriminatif.
Di bab ketiga, yang berjudul “Polisi di Alam Demokrasi”, mengemukakan tentang situasi keamanan nasional setelah 1998. Kebebasan yang makin terbuka, membuat publik berani bersuara soal pentingnya mengembalikan kepercayaan mereka kepada institusi yang sebelumnya berfusi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
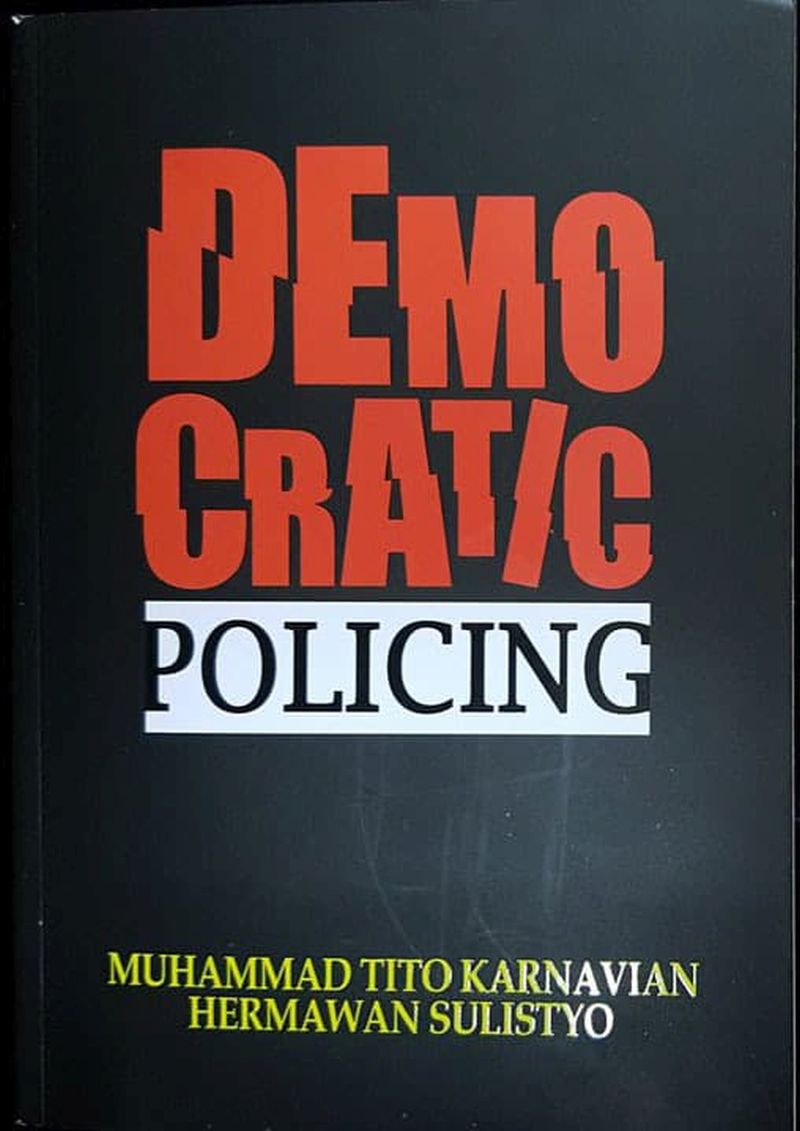
Polri dituntut menjadi pelayan masyarakat sipil, yang tak militeristik, lebih akuntabel, responsif, transparan, dan tak menghalalkan kekerasan. Hal itu ditandai dengan perubahan total struktur, sistem, hingga kultur. Karena sudah menjadi bagian dari masyarakat sipil, maka mereka perlu menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam masyarakat.
Selanjutnya, di dalam bab keempat disebutkan democratic policing menjadi paradigma pemolisian di era demokrasi yang menghormati HAM. Sebab, menjadi penegak hukum profesional yang antipungli dan kompeten saja tak cukup.
Polri harus tertib menjadikan HAM sebagai landasan bertindak dalam penegakan hukum. Regulasi di Indonesia sudah selaras antara fungsi pemolisian dan HAM, semisal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009.
Di bab kelima, dibahas tentang perlunya konsep human security PBB dalam upaya menjunjung tinggi HAM. Kemudian, di bab keenam dibahas standar pelayanan publik dari polisi. Di bab ini, Polri diingatkan kembali soal peranannya sebagai institusi sipil, yang harus tunduk pada birokrasi pemerintahan dan aturan sipil.
Di dalam praktiknya, fungsi pemolisian juga perlu mempertimbangkan partisipasi publik, transparansi terhadap akses informasi, dan pertanggung jawaban kepada publik, bukan penguasa.
Di bab terakhir, dijelaskan tentang polisi sebagai institusi yang harus profesional, modern, dan terpercaya. Di bab ini juga diterangkan desain besar arah kebijakan kepolisian, yang sesungguhnya sudah dicicil sejak institusi ini “bercerai” dengan ABRI (kini TNI).
Saat berpidato di forum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) akhir 2018 lalu di Jakarta, Ketua PPAD Letnan Jenderal TNI (Pur) Kiki Syahnakri menyinggung buku Democratic Policing (2017). Ia menilai, buku yang ditulis Hermawan Sulistyo dan Tito Karnavian tersebut adalah produk intelektual yang ngawur dan berbahaya.
Namun, Kiki tak pernah menyebutkan secara detail di bagian mana yang membuatnya khawatir akan membahayakan negara atau militer. Lantas, apa sebenarnya yang dikhawatirkan Kiki tentang buku menyoal paradigma “kepolisian yang demokratis” setebal 489 halaman ini?
Isi buku
Buku ini terdiri dari tujuh bab, yang membahas tentang democratic policing dari level ide hingga praktik.
Di bab pertama, menjelaskan tentang perubahan dunia yang niscaya, terutama pada paruh kedua abad ke-20. Konsekuensi logis perubahan berupa demokratisasi yang sudah bergulir sejak Uni Soviet bubar, membuat institusi semacam Polri perlu melakukan adaptasi. Terlebih ketika dihadapkan pada tantangan baru, seperti kasus-kasus hak asasi manusia (HAM).
Policing terhadap kasus HAM tak direduksi sebatas penghormatan secara konvensional, tetapi diperluas hingga mencakup hak asasi ekonomi, sosial, dan kebudayaan.
Di bab kedua, penulis membahas tentang sejarah gagasan democratic policing, yang gaungnya baru terdengar dua tahun terakhir. Gagasan itu muncul berbarengan dengan berkembangnya sistem demokrasi, yang menjadi landasan kehidupan masyarakat.
Kemudian berkembang hingga era pra-Victoria, ketika Perdana Menteri Britania Raya Robert Peel (1778-1850) membentuk kepolisian modern pertama, yang terorganisir di London, Inggris. Lantaran permasalahan di masing-masing negara semakin rumit, polisi Eropa dan Amerika yang awalnya didesain sebagai perpanjangan tangan rezim, berganti wajah menjadi pengemban amanat rakyat.
Posisi itu membuat loyalitas pertama kepolisian harus bertumpu pada publik. Selain itu, mereka harus bekerja sesuai prinsip demokrasi, profesional, melayani dan melindungi masyarakat, berlandaskan HAM, serta bersikap netral, imparsial, dan tak diskriminatif.
Di bab ketiga, yang berjudul “Polisi di Alam Demokrasi”, mengemukakan tentang situasi keamanan nasional setelah 1998. Kebebasan yang makin terbuka, membuat publik berani bersuara soal pentingnya mengembalikan kepercayaan mereka kepada institusi yang sebelumnya berfusi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
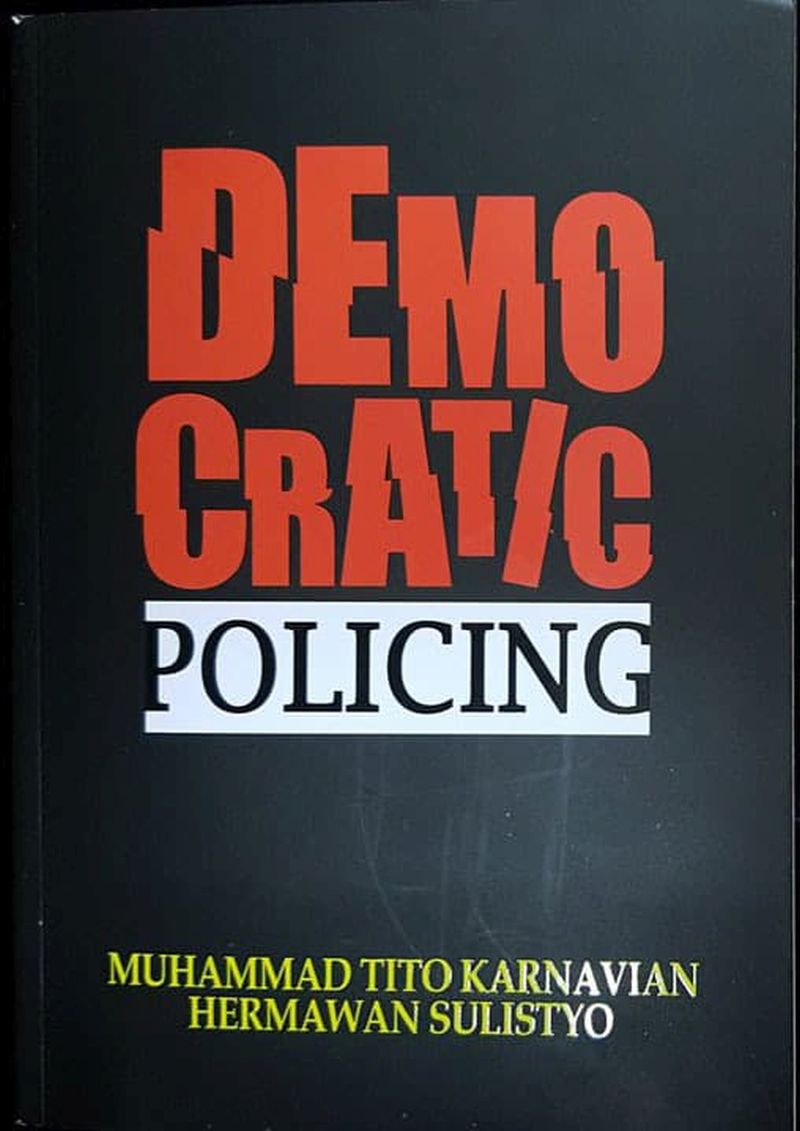
Polri dituntut menjadi pelayan masyarakat sipil, yang tak militeristik, lebih akuntabel, responsif, transparan, dan tak menghalalkan kekerasan. Hal itu ditandai dengan perubahan total struktur, sistem, hingga kultur. Karena sudah menjadi bagian dari masyarakat sipil, maka mereka perlu menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam masyarakat.
Selanjutnya, di dalam bab keempat disebutkan democratic policing menjadi paradigma pemolisian di era demokrasi yang menghormati HAM. Sebab, menjadi penegak hukum profesional yang antipungli dan kompeten saja tak cukup.
Polri harus tertib menjadikan HAM sebagai landasan bertindak dalam penegakan hukum. Regulasi di Indonesia sudah selaras antara fungsi pemolisian dan HAM, semisal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009.
Di bab kelima, dibahas tentang perlunya konsep human security PBB dalam upaya menjunjung tinggi HAM. Kemudian, di bab keenam dibahas standar pelayanan publik dari polisi. Di bab ini, Polri diingatkan kembali soal peranannya sebagai institusi sipil, yang harus tunduk pada birokrasi pemerintahan dan aturan sipil.
Di dalam praktiknya, fungsi pemolisian juga perlu mempertimbangkan partisipasi publik, transparansi terhadap akses informasi, dan pertanggung jawaban kepada publik, bukan penguasa.
Di bab terakhir, dijelaskan tentang polisi sebagai institusi yang harus profesional, modern, dan terpercaya. Di bab ini juga diterangkan desain besar arah kebijakan kepolisian, yang sesungguhnya sudah dicicil sejak institusi ini “bercerai” dengan ABRI (kini TNI).
Bukan gagasan baru
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi mengatakan, buku ini tak lebih dari penegasan kembali gagasan lawas yang sudah dicicil di Indonesia, dalam regulasi yang memayungi Polri. Di luar negeri, gagasan ini bahkan sudah mulai disemai sejak pasca-Perang Dingin.
“Democratic policing adalah keniscayaan di tengah zaman yang terus berkembang dengan problematikanya. Contoh, di perkotaan kita tak membutuhkan banyak polisi karena sistem surveillance (pengawasan) sudah memadai, tapi beda cerita di desa-desa,” kata Muradi, Rabu (30/1).
Hal ini, kata Muradi, sama dengan debat yang terjadi pada 1980 hingga 1990-an, soal siapa yang paling pantas menunggu perbatasan Eropa, militer atau polisi.
“Serta kenapa militer perannya harus meluas pasca-Perang Dingin. Ya seputar itu saja poin pentingnya, polisi dan militer memang harus berubah menyesuaikan zaman,” ujar Pengamat polisi, pertahanan, dan keamanan ini.
Buku ini, kata dia, ditulis dalam bahasa normatif yang memang bisa saja berpotensi memancing kekhawatiran dari sejumlah orang, terutama yang belum baca secara utuh.

Gagasan utopis?
Pengamat terorisme dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, gagasan ini bukan hanya bertengger di menara gading. Menurutnya, sepanjang ada komitmen kuat yang diiringi dengan penjabaran dan pedoman teknis yang jelas dan tegas, katanya, gagasan penulis buku ini sangat mungkin diterapkan.
Masalahnya, kata dia, “polisi pemerintah” semacam Polri sangat sulit berjarak dengan kekuasaan, dan cenderung berkutat pada pengukuran kinerja berbasis angka-angka statistik, seperti keberhasilan dan kegagalan pengungkapan kasus kejahatan.
“Padahal, sebagaimana pada konsep sebelumnya dalam ‘community policing’ atau perpolisian berbasis masyarakat, mestinya ukuran keberhasilan kepolisian adalah adanya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat menjaga keamanan lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan terciptanya kondisi tertib sosial,” katanya, Rabu (30/1).
Bagi Khairul, bila Polri tak bisa menunjukkan mereka mampu menjaga jarak dengan kekuasaan, dan gagal meraih dukungan atau partisipasi aktif masyarakat, maka konsep itu hanya akan ada di atas kertas. Realisasinya pun sekadar formalitas dan seremonial.
Apalagi, kata dia, Polri menghadapi tantangan yang tak ringan. Di tengah ancaman serangan terhadap instalasi dan personelnya, terdapat keraguan atas upaya penegakan hukum dan ketertiban sosial, maupun kemampuannya menjaga keamanan serta mengelola kepatuhan dan rasa takut warga.
Hal itu dimaklumi, mengingat selama lebih dua dekade, Polri ditempa dengan pola pikir yang sekadar berbasis statistik kriminalitas. Namun, lagi-lagi jika berkaca pada sejarah, Polri cenderung menjaga jarak dengan publik, lantaran banyaknya kepentingan yang berseberangan.
Pembaca hanya bisa berharap agar gagasan yang sudah ditegaskan kembali dengan detail oleh Hermawan Sulistyo tidak berakhir sebagai masturbasi intelektual. Apalagi buku ini ditulis bersama Tito Karnavian, yang ada andil langsung dalam menentukan serta menjalankan arah kebijakan Polri.








