
Fenomena cocoklogi versus ilmu pengetahuan
Pada 21 Juni, penceramah Rahmat Baequni ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran hoaks atau berita bohong terkait kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akibat diracun dalam ceramahnya di sebuah masjid di Baleendah, Kabupaten Bandung.
Ceramah itu menjadi polemik setelah rekaman videonya tersebar di media sosial. Usai diperiksa polisi, Baequni mengaku, informasi itu ia dapat dari media sosial.
Sebelumnya, Baequni sempat mengundang polemik lain yang tak kalah bikin geleng-geleng kepala. Ia menganggap, Masjid Al Safar yang ada di area istirahat kilometer 88 B Jalan Tol Purbalenyi arah Jakarta merupakan simbol iluminati—kelompok persaudaraan rahasia kuno.
Perkara ini membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara. Jelas Emil—sapaan Ridwa Kamil—tersulut. Sebab, ia adalah arsitek masjid tersebut.
Di media sosial pun tersebar rekaman video Baequni menjelaskan asal usul nama enam daerah di Nusantara, yang semuanya menggunakan bahasa Arab. Video ini, selain membuat warganet tertawa miris, juga menimbulkan keresahan. Terutama mereka yang bergiat di bidang keilmuan sejarah dan toponimi.
Di dalam rekaman video itu, Baequni menyebut, dahulu Sumatera bernama Asyamatiro—Syumatra; Jawa bernama Al Jawwu; Borneo (Kalimantan) bernama Barru’un—Barnau; Makassar bernama Makassaro—Kassaro yu Kassiru; Maluku bernama Jazirul Muluk; dan Papua Nugini bernama Billadul Nurul Islami.
Bukan cuma di media sosial. Fenomena mencocokan sesuatu, yang kerap disebut warganet dengan istilah cocoklogi, juga dipublikasikan dalam bentuk buku.

Misalnya, buku Hitler Mati di Indonesia (2010) karya Soeryo Goeritno, Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman (2012) karya Fahmi Basya, dan Majapahit Kerajaan Islam (2014) karya Herman Sinung Janutama.
Buku-buku itu menjadi pembicaraan, dan tak bisa dimungkiri laku di pasaran—karena judulnya kontroversial dan mengundang rasa penasaran. Namun, apakah isinya mengacu referensi yang tepat atau hanya mencocok-cocokan semata?
Menanggapi kasus Baequni, penulis Ahmad Yanuana Samantho menilai, motif sang penceramah menyebut Masjid Al Safar dipenuhi simbol iluminati hanya ingin mendeskreditkan Ridwan Kamil di mata umat Islam.
“Ngawur dia. Cocoklogi tanpa dasar pemahaman yang utuh terhadap sejarah dan makna simbol-simbol iluminati divine/Illahiyah freemanson luciferian atau iluminati palsu atau iluminati hitam materialis penyembah setan,” ujar Yanuana saat dihubungi Alinea.id, Senin (24/6).
Yanuana merupakan penulis buku Garut Kota Illuminati: Dari Pencarian Hitler yang Berujung di Indonesia, Emas Para Sultan Nusantara, hingga Indikasi Bangsa Yahudi Keturunan Jawa (2013).
Meski kajiannya hampir mirip dengan pendapat Baequni perkara iluminati, Yanuana mengatakan, ia menulis buku tersebut berdasarkan kajian historis, survei, wawancara, dan literatur menggunakan metode cover both side dan studi komparasi.
Yanuana menjelaskan, iluminati yang otentik berasal dari ajaran para nabi dan wahyu Tuhan. Selanjutnya, filosofi iluminati melintasi zaman Atlantis Nusantara, Mesir kuno, Yunani kuno, India, dan sebagainya.
Akan tetapi, menurut dia, sejak abad ke-17 dan 18, ajaran iluminati dibelokkan menjadi simbolnya kaum renternir Yahudi Kazarian, seperti keluarga Rosthschild, yang hingga kini menguasai perbankan dan keuangan dunia.
Selain menulis Garut Kota Illuminati, Yanuana juga merupakan penulis buku Peradaban Atlantis Nusantara (2011), Sejarah ISIS dan Iluminati (2014), dan Illuminati Nusantara (2015).
Pada 21 Juni, penceramah Rahmat Baequni ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran hoaks atau berita bohong terkait kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akibat diracun dalam ceramahnya di sebuah masjid di Baleendah, Kabupaten Bandung.
Ceramah itu menjadi polemik setelah rekaman videonya tersebar di media sosial. Usai diperiksa polisi, Baequni mengaku, informasi itu ia dapat dari media sosial.
Sebelumnya, Baequni sempat mengundang polemik lain yang tak kalah bikin geleng-geleng kepala. Ia menganggap, Masjid Al Safar yang ada di area istirahat kilometer 88 B Jalan Tol Purbalenyi arah Jakarta merupakan simbol iluminati—kelompok persaudaraan rahasia kuno.
Perkara ini membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara. Jelas Emil—sapaan Ridwa Kamil—tersulut. Sebab, ia adalah arsitek masjid tersebut.
Di media sosial pun tersebar rekaman video Baequni menjelaskan asal usul nama enam daerah di Nusantara, yang semuanya menggunakan bahasa Arab. Video ini, selain membuat warganet tertawa miris, juga menimbulkan keresahan. Terutama mereka yang bergiat di bidang keilmuan sejarah dan toponimi.
Di dalam rekaman video itu, Baequni menyebut, dahulu Sumatera bernama Asyamatiro—Syumatra; Jawa bernama Al Jawwu; Borneo (Kalimantan) bernama Barru’un—Barnau; Makassar bernama Makassaro—Kassaro yu Kassiru; Maluku bernama Jazirul Muluk; dan Papua Nugini bernama Billadul Nurul Islami.
Bukan cuma di media sosial. Fenomena mencocokan sesuatu, yang kerap disebut warganet dengan istilah cocoklogi, juga dipublikasikan dalam bentuk buku.

Misalnya, buku Hitler Mati di Indonesia (2010) karya Soeryo Goeritno, Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman (2012) karya Fahmi Basya, dan Majapahit Kerajaan Islam (2014) karya Herman Sinung Janutama.
Buku-buku itu menjadi pembicaraan, dan tak bisa dimungkiri laku di pasaran—karena judulnya kontroversial dan mengundang rasa penasaran. Namun, apakah isinya mengacu referensi yang tepat atau hanya mencocok-cocokan semata?
Menanggapi kasus Baequni, penulis Ahmad Yanuana Samantho menilai, motif sang penceramah menyebut Masjid Al Safar dipenuhi simbol iluminati hanya ingin mendeskreditkan Ridwan Kamil di mata umat Islam.
“Ngawur dia. Cocoklogi tanpa dasar pemahaman yang utuh terhadap sejarah dan makna simbol-simbol iluminati divine/Illahiyah freemanson luciferian atau iluminati palsu atau iluminati hitam materialis penyembah setan,” ujar Yanuana saat dihubungi Alinea.id, Senin (24/6).
Yanuana merupakan penulis buku Garut Kota Illuminati: Dari Pencarian Hitler yang Berujung di Indonesia, Emas Para Sultan Nusantara, hingga Indikasi Bangsa Yahudi Keturunan Jawa (2013).
Meski kajiannya hampir mirip dengan pendapat Baequni perkara iluminati, Yanuana mengatakan, ia menulis buku tersebut berdasarkan kajian historis, survei, wawancara, dan literatur menggunakan metode cover both side dan studi komparasi.
Yanuana menjelaskan, iluminati yang otentik berasal dari ajaran para nabi dan wahyu Tuhan. Selanjutnya, filosofi iluminati melintasi zaman Atlantis Nusantara, Mesir kuno, Yunani kuno, India, dan sebagainya.
Akan tetapi, menurut dia, sejak abad ke-17 dan 18, ajaran iluminati dibelokkan menjadi simbolnya kaum renternir Yahudi Kazarian, seperti keluarga Rosthschild, yang hingga kini menguasai perbankan dan keuangan dunia.
Selain menulis Garut Kota Illuminati, Yanuana juga merupakan penulis buku Peradaban Atlantis Nusantara (2011), Sejarah ISIS dan Iluminati (2014), dan Illuminati Nusantara (2015).
Cocoklogi dan disinformasi
Arkeolog Djulianto Susantio menilai cocoklogi telah lama menghantui disiplin ilmu arkeologi. Ia mencontohkan penulisan buku Candi Borobudur yang dihubungkan dengan peninggalan Nabi Sulaiman—Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman (2012) karya Fahmi Basya.
Dalam perspektif arkeologis, menurut dia, orang-orang yang berpendapat dan percaya hal itu sangat ultranasionalis. Akibatnya, mereka gemar mengaitkan Indonesia dan Islam.
“Misalnya Majapahit adalah kerajaan Islam, Gajah Mada jadi Gaj Ahmada, Cocoklogi gitu. Padahal di prasasti itu, tulisan Gajah Mada dan Gaj Ahmada lain,” ujar Djulianto saat dihubungi, Senin (24/6).
Dihubungi terpisah, dosen Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, Surabaya, Adrian Perkasa mengatakan, cocoklogi itu mencari pengetahuan menggunakan metode yang berbeda dengan ilmu sejarah. Kerangka metode ilmiah ilmu sejarah mencakup heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi sumber, dan historiografi.
Alat bantunya, antara lain arkeologi, filologi, dan epigrafi. Sementara cocoklogi berupaya mengaitkan sesuatu, memaksakan penafsiran dengan kepentingan tertentu.
“Tidak bisa diperdebatkan, dan mereka tidak berminat diskusi keilmuan. Masalahnya, fenomena cocoklogi demi kepentingan bisnis itu sudah lama. Misalnya, kasus Borobudur yang disebut peninggalan Nabi Sulaiman. Toh, akhirnya bikin tur wisata sejarah,” ujar Adrian saat dihubungi, Senin (24/6).
Ia mengatakan, jauh lebih berbahaya jika fenomena cocoklogi dibalut kepentingan agama. “Ini seperti semuanya harus diislamkan. Semuanya dimualafkan,” tutur Adrian.

Fenomena itu pun dikenal dengan istilah disinformasi—penyampaian informasi yang salah (dengan sengaja) untuk membingungkan orang lain. Selain disinformasi, ada pula istilah misinformasi—kabar bohong yang memelintir kabar yang bisa jadi benar.
Rob Brotherton di dalam bukunya, Suspicious Minds: Why We Believe Conspiracy Theories (2015) menulis, misinformasi terjadi pada abad ke-21, seiring kehadiran internet.
Menurut Rob, jaringan global internet menebar gelombang arus informasi yang kian membludak dan menjungkal secara tak pasti. Maka, muncul pemikiran seolah semuanya tak seperti kenyataan.
Akibatnya, orang percaya ada sisi tersembunyi dari kenyataan. Kepercayaan terhadap jaringan tak kasat mata ini, tulis Rob, secara konstan menyaring, memanipulasi informasi, dan memunculkan kebohongan untuk menyembunyikan kebenaran yang nyata.
Menurut dosen ilmu sejarah Universitas Airlangga Pradipto Niwandhono, masyarakat mudah percaya disinformasi karena persoalan sumber informasinya, bukan substansi pengetahuannya.
Artinya, kata Pradipto, orang yang percaya arsitektur Masjid Al Safar bermuatan simbol iluminati karena hanya percaya pada sosok personal yang menyampaikan pesan itu, dalam hal ini Rahmat Baequni.
“Harusnya para sejarawan lebih tanggap karena akan menyebabkan penyesatan sejarah di kalangan awam. Dampaknya, seharusnya tak terlalu serius karena orang yang belajar sejarah betulan pasti enggak akan terpapar disinformasi seperti itu,” ujar Pradipto saat dihubungi, Senin (24/6).
Sementara itu, ditinjau dari ilmu arkeologi, Djulianto Susantio menganggap kelemahan para arkelog dalam menulis populer menyebabkan masyarakat gagal memahami kajian ilmiah di balik upaya menggapai fakta sejarah.
Terlebih, kata dia, masih ada masyarakat yang salah mempersepsikan Undang-Undang Kepurbakalan, yang saat ini diganti Undang-Undang Cagar Budaya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010). Sehingga, banyak penggalian liar tanpa pengawasan arkeolog, dan menafsirkan sendiri hasil temuannya.
“Kasus Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman, mereka menafsirkan stupa yang rusak sebagai peninggalan Nabi Sulaiman. Diceritakan dibawa terbang dan rusak. Itu saja penafsirannya,” kata dia.
Imbas
Adrian Perkasa khawatir, cocoklogi bisa mengancam perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain, bagi pembaca kritis, justru memantiknya agar mencari sumber referensi ilmiah.
“Orang yang percaya cocoklogi kalau ditanya sumbernya dari mana, jawabnya ‘sudah pokoknya kata ustaz sini’,” ucap penulis buku Orang-orang Tionghoa dan Islam di Majapahit (2012).
Adrian memberikan contoh fenomena Gaj Ahmada, yang diyakini nama sebenarnya Gajah Mada dan beragama Islam. Gaj Ahmada disinggung di dalam buku Majapahit Kerajaan Islam (2014) karya Herman Sinung Janutama.
Menurut Adrian, pemaparan Gaj Ahmada belum bertumpu pada sumber primer. Adrian menuturkan, berdasarkan prasasti Singhasari bertarikh 1351 M, Gajah Mada disebut Rakryan Mapatih Pu Mada. Rakryan adalah sebuah gelar mengenai kedudukan dalam fungsi pengurusan pencapaian tujuan.
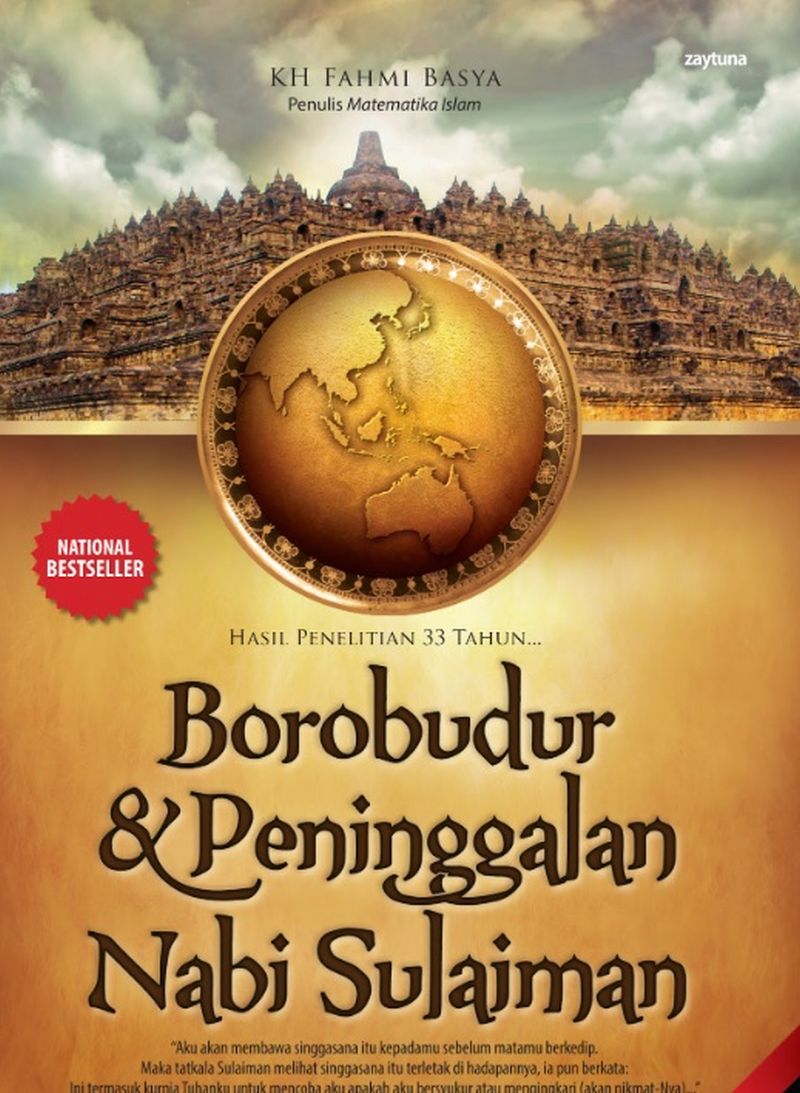
“Yang meneliti Gaj Ahmada tidak menggunakan sumber primer, seperti prasasti,” ujar Adrian.
Ia mengimbau masyarakat tak sekadar menganggap sejarah sebagai seni, tetapi juga ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
Sementara itu, kata Pradipto Niwandhono, disinformasi bisa berdampak terhadap orang yang miskin literasi dan mengharapkan pengetahuan instan. Selain itu, menurutnya, asumsi sejarah Indonesia dikorupsi pengetahuan orientalis Eropa yang merangsang konspirasi politik Islam di Indonesia.
"Islam dianggap tidak memiliki dampak secara politik ataupun terhadap perkembangan peradaban. Tapi sayangnya orang yang berasumsi demikian hanya membalik narasi sejarah tanpa dibekali cukup referensi dan kritisisme terhadap valid tidaknya sumber," ujar Pradipto.
Cara memeranginya
Sebagai seorang pengajar, Herry Anggoro Djatmiko tentu resah dengan ilmu pengetahuan yang dibuat main-main. Namun, guru kelas X-XII di Madrasah Aliyah Subhanah di Kabupaten Batang, Jawa Tengah itu yakin, sejauh pengamatannya belum ada gelagat murid-muridnya terpapar cocoklogi, terutama yang dilontarkan Baequni.
Herry mengaku sudah membekali murid-muridnya agar mampu menangkal disinformasi sejarah dan fenomena cocoklogi. Caranya, ia menekankan pentingnya memilah tokoh yang kompeten dalam bidang sejarah. Ia juga mengajarkan bagaimana memahami fakta sejarah dan mengkritisi sumber sejarah.
"Anak-anak harus diberi pemahaman agar tidak asal mencocok-cocokan saja, tetapi harus pula punya dasar ilmiah, harus ada metodologi dan sumber sejarahnya,” kata Herry saat dihubungi, Senin (24/6).
Menurutnya, sebenarnya pelajaran sejarah di sekolah sudah materi seperti itu. Akan tetapi, ia mengakui, sistem pendidikan Indonesia belum bisa memberikan dasar-dasar yang kuat.
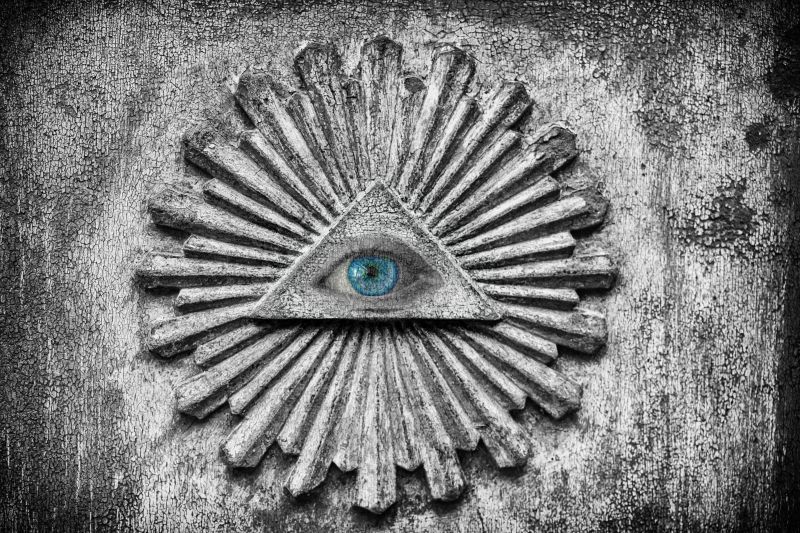
“Anak-anak diberikan pemahaman terkait seperangkat aturan dalam ilmu sejarah, seperti harus ada sumbernya, dan sumbernya itu harus dapat dicocokan, serta kritik apakah sesuai dengan kenyataan. Nantinya juga dapat disintesiskan dengan sumber-sumber yang lain,” ujar Herry.
Walaupun murid-muridnya tergolong anak pedesaan, tetapi Herry menilai mereka sudah cukup kritis karena sangat akrab dengan media online. Beberapa muridnya ada yang menanyakan tentang fakta sejarah.
“Sebetulnya itu rasa penasaran mereka dengan berbagai informasi yang masuk. Kadang-kadang karena informasi itu lebih populer, makanya mereka lebih memperhatikannya daripada pengetahuan yang didapatkan dari sekolah,” ucapnya.
Sementara itu, peneliti sejarah Yahudi di Indonesia Romi Zarman mengatakan, ilmu pengetahuan seakan mati di tangan Baequni yang mengusung cocoklogi kebablasan.
Romi mendorong masyarakat agar keluar dari pusaran ketakutan atas prasangka negatif yang tak mendasar, baik terhadap illuminati maupun Yahudi.
"Berpikir terbuka adalah kuncinya," ujar penulis buku Di Bawah Kuasa Antisemitisme: Orang Yahudi di Hindia Belanda (2018) ini saat dihubungi, Senin (24/6).
Menurut Romi, persoalannya bukan apakah iluminati masih eksis atau tidak, tetapi cara berpikir masyarakat Indonesia yang perlu dikoreksi dan dibenahi.








