
Green Book: Potret satire diskriminasi ras di Amerika
Pada 1962, Amerika Serikat bagian selatan belum ramah terhadap warga kulit berwarna. Tapi, Don Shirley (Mahershala Ali), seorang Afro-Amerika dari New York, nekat menghelat safari musik. Dia melintasi kota “berbahaya”, meniru Nat King Cole, seorang pemusik kulit hitam yang pertama tampil di Auditorium Municipal, Birmingham, pada 1956.
Wajah ganda kemanusiaan
Saat itu, Cole memang habis dihajar kerumunan penonton. Namun, Don optimis, catatan kelam itu tak akan terulang kepada dirinya. Sebab, Don punya dua senjata.
Pertama, Green Book. Kedua, Tony “Lip” Vallelonga (Viggo Mortensen). Green Book merupakan brosur perjalanan paling penting yang dipublikasi khusus oleh pelancong kulit hitam, untuk memberi rasa aman singgah di tempat “ramah”.
Green Book berisi daftar penginapan dan restoran yang mengizinkan kaum kulit berwarna masuk, tanpa khawatir ada penganiayaan, penembakan, penggantungan, dan penikaman massa—di mana pelakunya punya hak impunitas.
Menariknya, Green Book yang punya jargon “Berlibur Tanpa Kejengkelan” ini dilengkapi daftar harga, termasuk fasilitas dan menu restoran.
Sejarahnya, Green Book ditujukan untuk pengendara motor kulit hitam di Amerika. “Buku hijau”. itu dibuat Victor Hugo Green, tukang pos Afro-Amerika kelahiran Harlem, bekerja di Hackensack, New Jersey.
Menurut kritikus film Alissa Wilkinson dalam artikelnya “Green Book builds a feel-good comedy atop an artifact of shameful segregation. Yikes” di Vox edisi 9 Januari 2019, Green mengerjakan proyek itu dari 1938 hingga 1966, tak lama usai Undang-Undang Hak Sipil diteken, setelah jeda Perang Dunia II selama empat tahun.
Sebanyak 22 edisi dan satu suplemen Green Book yang terbit selama kurun waktu tadi, kini sudah dihimpun dan didigitalisasi Pusat Penelitian Budaya Hitam Schomburg di Perpustakaan Umum New York.

Namun, dalam film ini, Green Book tetap nihil—tanpa seorang sopir sekaligus pelayan seperti Tony, family man Italia yang jago berkelahi, berkelakar sepanjang waktu, dan tanggung jawab atas pekerjaannya. Reputasi Tony itulah yang membuat Don tertarik menyewa jasanya, terutama agar dia merasa aman sepanjang pergelaran musik di sejumlah kota.
Apakah asa Don terkabul?
Tidak juga. Baru separuh perjalanan, Don babak belur dihajar kelompok pria di sebuah bar, Louisville, Kentucky hanya karena warna kulitnya berbeda. Untung ada Tony yang pasang badan menyelamatkannya. Di lain waktu, dia dipenjara hanya karena kedapatan menyewa jasa pria kulit putih, yang dianggap tak layak dilakukan “manusia kelas dua” sepertinya.
Diskriminasi pada Don tak sekadar berupa hajar-menghajar, dia dilarang makan di restoran yang notabene telah mengundangnya tampil memainkan piano di sana. Dia hanya boleh menggunakan toilet bedeng dari kayu dekil, di antara semak-semak di halaman tuan rumah yang memintanya tampil bersama Trio Don Shirley.
“Orang-orang kulit putih mengundangku bermain musik hanya demi membuktikan, mereka manusia berbudaya. Di luar itu, aku tetap Negro yang dipandang sebelah mata,” ujar Don suatu malam, setelah berhasil lolos dari bui, karena menelepon adik Presiden Amerika Serikat, Bobby Kennedy.
Sebenarnya Don bisa saja tampil di Carniege Hall, gedung pertunjukan sekaligus rumahnya di New York. Namun, menurutnya, kejeniusan musik di kandang sendiri tak akan cukup. Butuh keberanian untuk mengubah hati orang-orang kulit putih Amerika.
Ya, hal ini memang ajang pembuktian atas pendapat keras kepalanya.
Sementara bagi Tony, hal ini adalah caranya untuk menghidupi istri dan dua anak, sekaligus menjadi “perjalanan spiritual” pribadi. Tony dulunya sangat anti-Negro.
Karena arogansinya itu, dia bahkan membuang dua gelas bekas minum pekerja kulit hitam yang didatangkan sang istri untuk memperbaiki pipa air. Perjalanan dengan Don, membuat matanya terbuka, betapa Amerika punya wajah ganda kemanusiaan.
Pada 1962, Amerika Serikat bagian selatan belum ramah terhadap warga kulit berwarna. Tapi, Don Shirley (Mahershala Ali), seorang Afro-Amerika dari New York, nekat menghelat safari musik. Dia melintasi kota “berbahaya”, meniru Nat King Cole, seorang pemusik kulit hitam yang pertama tampil di Auditorium Municipal, Birmingham, pada 1956.
Wajah ganda kemanusiaan
Saat itu, Cole memang habis dihajar kerumunan penonton. Namun, Don optimis, catatan kelam itu tak akan terulang kepada dirinya. Sebab, Don punya dua senjata.
Pertama, Green Book. Kedua, Tony “Lip” Vallelonga (Viggo Mortensen). Green Book merupakan brosur perjalanan paling penting yang dipublikasi khusus oleh pelancong kulit hitam, untuk memberi rasa aman singgah di tempat “ramah”.
Green Book berisi daftar penginapan dan restoran yang mengizinkan kaum kulit berwarna masuk, tanpa khawatir ada penganiayaan, penembakan, penggantungan, dan penikaman massa—di mana pelakunya punya hak impunitas.
Menariknya, Green Book yang punya jargon “Berlibur Tanpa Kejengkelan” ini dilengkapi daftar harga, termasuk fasilitas dan menu restoran.
Sejarahnya, Green Book ditujukan untuk pengendara motor kulit hitam di Amerika. “Buku hijau”. itu dibuat Victor Hugo Green, tukang pos Afro-Amerika kelahiran Harlem, bekerja di Hackensack, New Jersey.
Menurut kritikus film Alissa Wilkinson dalam artikelnya “Green Book builds a feel-good comedy atop an artifact of shameful segregation. Yikes” di Vox edisi 9 Januari 2019, Green mengerjakan proyek itu dari 1938 hingga 1966, tak lama usai Undang-Undang Hak Sipil diteken, setelah jeda Perang Dunia II selama empat tahun.
Sebanyak 22 edisi dan satu suplemen Green Book yang terbit selama kurun waktu tadi, kini sudah dihimpun dan didigitalisasi Pusat Penelitian Budaya Hitam Schomburg di Perpustakaan Umum New York.

Namun, dalam film ini, Green Book tetap nihil—tanpa seorang sopir sekaligus pelayan seperti Tony, family man Italia yang jago berkelahi, berkelakar sepanjang waktu, dan tanggung jawab atas pekerjaannya. Reputasi Tony itulah yang membuat Don tertarik menyewa jasanya, terutama agar dia merasa aman sepanjang pergelaran musik di sejumlah kota.
Apakah asa Don terkabul?
Tidak juga. Baru separuh perjalanan, Don babak belur dihajar kelompok pria di sebuah bar, Louisville, Kentucky hanya karena warna kulitnya berbeda. Untung ada Tony yang pasang badan menyelamatkannya. Di lain waktu, dia dipenjara hanya karena kedapatan menyewa jasa pria kulit putih, yang dianggap tak layak dilakukan “manusia kelas dua” sepertinya.
Diskriminasi pada Don tak sekadar berupa hajar-menghajar, dia dilarang makan di restoran yang notabene telah mengundangnya tampil memainkan piano di sana. Dia hanya boleh menggunakan toilet bedeng dari kayu dekil, di antara semak-semak di halaman tuan rumah yang memintanya tampil bersama Trio Don Shirley.
“Orang-orang kulit putih mengundangku bermain musik hanya demi membuktikan, mereka manusia berbudaya. Di luar itu, aku tetap Negro yang dipandang sebelah mata,” ujar Don suatu malam, setelah berhasil lolos dari bui, karena menelepon adik Presiden Amerika Serikat, Bobby Kennedy.
Sebenarnya Don bisa saja tampil di Carniege Hall, gedung pertunjukan sekaligus rumahnya di New York. Namun, menurutnya, kejeniusan musik di kandang sendiri tak akan cukup. Butuh keberanian untuk mengubah hati orang-orang kulit putih Amerika.
Ya, hal ini memang ajang pembuktian atas pendapat keras kepalanya.
Sementara bagi Tony, hal ini adalah caranya untuk menghidupi istri dan dua anak, sekaligus menjadi “perjalanan spiritual” pribadi. Tony dulunya sangat anti-Negro.
Karena arogansinya itu, dia bahkan membuang dua gelas bekas minum pekerja kulit hitam yang didatangkan sang istri untuk memperbaiki pipa air. Perjalanan dengan Don, membuat matanya terbuka, betapa Amerika punya wajah ganda kemanusiaan.
Tiga kemenangan di Golden Globe Awards
Film besutan sutradara spesialis komedi Peter Farrely ini sendiri memboyong penghargaan terbanyak di Golden Globe Awards 2019.
Dari lima nominasi, tiga tiket kemenangan diboyong, dalam kategori Best Motion Picture-Musical or Comedy; Best Performance by an Actor in a Supporting Role in any Motion Picture untuk Mahershala Ali; serta Best Screenplay-Motion Picture untuk Nick Vallelonga, Brian Currie, dan Peter Farrelly.
Mengapa film ini begitu spesial, sehingga memenangkan banyak piala?
Beberapa orang melihat film ini sebagai road trip jadul, di mana Google Maps belum ditemukan, yang jenaka dan sudah pasti bertabur musik piano klasik nan indah. Namun, bagi saya, film ini adalah satire yang memperlihatkan masalah serius intoleransi terhadap orang kulit hitam di Amerika.
Kejeniusan Peter Farrely menjungkirbalikkan norma dan peran jamak antara kulit hitam dan putih saat itu memikat saya. Tony “Lip” yang lama bermukim di Bronx, sebagai tokoh utama mewakili kulit putih, tak dicitrakan berkelas seperti stereotipe kebanyakan.

Dia justru menjadi mesin humor sepanjang film, yang gemar bicara semaunya, bertingkah kasar, dan gemar memaki. Dia melipat pizza satu loyang dan menelannya bulat-bulat, mengajari Don yang kikuk, mengganyang ayam goreng dalam mobil, lalu membuang tulangnya ke jalan. Dia juga memukul orang jika diperlukan, serta selalu mengantongi pistol di saku bajunya.
Sebaliknya, Don adalah representasi pria berkelas yang lihai bermain musik, pemegang gelar doktoral, dalam keseharian dia dipanggil "Doc", selalu mengenakan jas dan dasi, kaya raya, serta berbicara terstruktur khas kelas terpelajar di Amerika.
Don berhasil menghentak kesadaran kita, soal peliknya konflik minoritas yang terjadi di Negeri Paman Sam—berbarengan dengan perjuangan Martin Luther King Jr. Menghapuskan kebijakan pemisahan rasial kala itu.
Sebagai film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini lantas menjadi terasa sangat pas memotret intoleransi di Amerika. Ada sebuah pesan penting yang juga relevan di masa sekarang, yakni pandangan bisa saja lahir bukan dari diri, tapi dari konstruksi dan keyakinan umum masyarakat.
“Ada terlalu banyak kesepian di dunia, karena mereka tidak berani untuk memulai duluan,” pesan punch line yang jadi inti film berdurasi 2 jam 10 menit ini.
Saya pribadi segera tiba pada keyakinan, sikap rasis yang sebelumnya dimiliki Tony tak turun dari langit dan melekat begitu saja, tapi terbentuk karena pengalaman kolektif di sekitarnya. Sialnya, meski terkadang hati kecil kita melawan kebencian atau anggapan publik yang keliru, selalu terbentur pada ketakutan untuk memulai.
Satu-satunya kekurangan, film ini sedikit sekali membahas soal Green Book, mengingat judul besar yang ditawarkan adalah buku penting dalam sejarah anti-ras.
Agak disayangkan memang. Publik yang lapar informasi sejarah Green Book tentu ingin tahu sejak kapan buku itu ada, asal muasal, bukan sekadar fokus pada drama batin tokoh Don atau perjuangan Tony untuk memulai langkah pertama: menghapus kebencian yang telah lama mengakar kuat dalam dirinya.




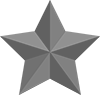 4
4Komedi segar dalam format film perjalanan. Andai sutradara memberi pendalaman lebih pada muasal Green Book, film ini layak dapat nilai 5 sempurna.








