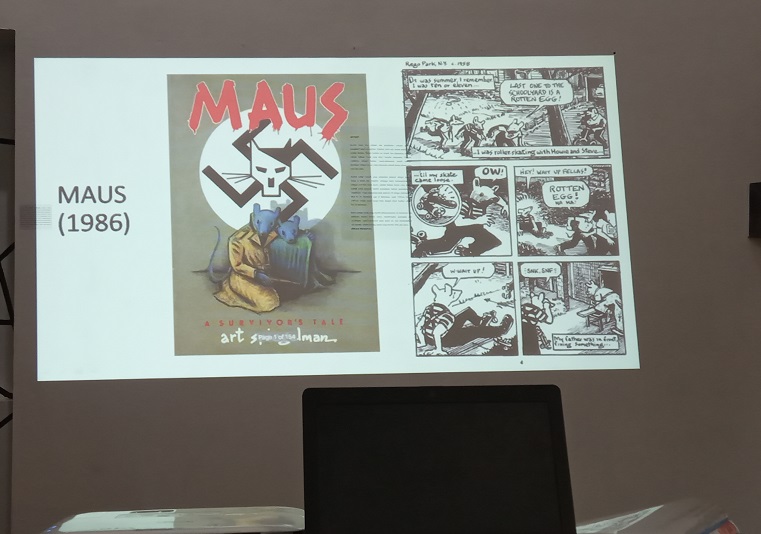Kala Faisal Oddang bicara gender kelima
Berapa banyak orang di Tanah Air berani menyuarakan keresahan yang bersumber dari bisik-bisik publik? Apalagi, jika temanya berkelindan dengan persoalan orientasi seksual. Di era di mana dunia dijejali kalangan moralis cum agamis, identitas dwi gender perempuan dan laki-laki adalah harga final. Jika ada yang mendaku sebagai liyan dari luar dua gender tersebut, maka stigmatisasi miring, cemooh, dan pengasingan bisa saja siap menanti.
Faktanya, di belahan Sulawesi Selatan sana, telah berabad-abad warga setempat diidentifikasi dalam lima gender. Bissu Saidi, dalam wawancara dengan Historia pada 2016 melukiskan keragaman gender di Kota Daeng tersebut, bak lima jari di tangannya.
Jempol itu, kata dia, adalah bura’ne (laki-laki), kelingking adalah makunrai (perempuan), telunjuk adalah calabai (waria), jari manis adalah calalai (tomboi), dan jari tengah untuk bissu. Bissu digadang-gadang menjadi pranata spiritual paling penting yang menghubungkan manusia dengan orang-orang langit. Mereka diberikan amanah menjaga arajang (pusaka kerajaan) dan dilindungi raja-raja saking istimewanya. Laiknya, calabai dan calalai, menjadi bissu yang minoritas, tak membuat mereka dipinggirkan sebagai kaum kelas dua.
Namun, romantisme bissu tak bertahan lama. Kehadiran Kristen dan Islam telah memaksa tiga gender itu menyingkir dari konstelasi publik. Bahkan, begitu Sulawesi Selatan membara lantaran Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/ TII) berkuasa, bissu menjadi salah satu golongan yang wajib ‘bertobat’. Lewat operasi taubat ini, mereka yang mengaku di luar gender perempuan dan laki-laki dikejar. Calalai dipaksa mengenakan baju perempuan, sedang calabai dan bissu harus berpakaian laiknya laki-laki.
Dalam perkembangannya di masa modern, keberadaan bissu sebagai gender kelima tak luput dari pandangan nyinyir masyarakat di luar Sulawesi Selatan, khususnya etnis Bugis. Sebagaimana gender yang berbeda lainnya, mereka disebut “sakit jiwa”, kendati Komisi Internasional tentang Hak Asasi LGBT (The International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) PBB menyebut, mereka hanya varian biasa dari seksualitas dan sosial manusia.
Dikutip dari Kevin Barnhurst dalam bukunya “Media Queered” (2007), pembungkaman komunitas liyan ini turut dilegitimasi media. Meski belakangan media pula yang membuat bissu jadi terasa eksklusif sebagai golongan yang dikomersialisasi dalam perhelatan budaya Bugis. Namun, secara sosiologis, keberadaan bissu dengan identitas gendernya ini belum jamak dimafhumi, sehingga masih jadi lubang besar.
Adalah Faisal Oddang, sastrawan muda kelahiran Kabupaten Wajo, 200 km dari Makassar, yang menarasikan ulang cerita soal bissu dalam perspektifnya. Lewat bukunya “Tiba Sebelum Berangkat” (2018) yang kini sudah dua kali dicetak ulang, ia memotret seluruh agonia bissu yang tercerabut dari sejarahnya sendiri. Debut keenamnya dalam menulis buku itu juga telah diekranisasi dalam ujud film dokumenter.
Penulis kelahiran 18 September 1994 ini sendiri mengaku melakukan riset yang melelahkan demi menelurkan bukunya. Selain membaca disertasi dan buku-buku penunjang, ia juga mewawancarai sejumlah narasumber lokal di Pangkep, Sulawesi Selatan.
Alinea beruntung mendapat kesempatan berbincang dengan laki-laki murah senyum ini di lepas senja di Jakarta. Kebetulan, ia memang tengah bertandang ke Ibu Kota guna menghadiri jamuan cerpen terbaik Kompas—acara apresiasi sastra yang diselenggarakan di Bentara Budaya—dimana namanya didapuk sebagai salah satu pemenang, bersanding dengan Muna Masyari, Budi Darma, Ahmad Tohari, Putu Wijaya Radhar Panca Dahana, Agus Noor, Djenar Maesa Ayu, dan lainnya. Berikut petikan singkat obrolan dengan Faisal, mulai dari “Tiba Sebelum Berangkat”, hingga bicara mimpinya di masa depan.
Faisal ini nama yang sudah tak asing di dunia kesusastraan. Sejumlah buku, cerpen pernah ditelurkan. Sejak kapan sebetulnya Faisal mulai menulis?
Sebenarnya berbicara mengenai proses menulis itu tak sesederhana kamu duduk di depan komputer saja. Itu adalah proses penemuan yang memang dibangun sejak lama. Meskipun saya sadari atau tidak, masa kecil saya menjadi tahap yang berperan besar dalam proses menulis saya. Misalnya, keinginan konyol saya menjadi Wiro Sableng. Lalu mendengarkan drama radio, Saur Sepuh, Tutur Tinular, Angling Dharma, dan sebagainya. Saya pikir itu menjadi suatu alasan mengapa saya suka menulis. Saya sadar, sejak kecil sudah membentuk diri saya menjadi orang yang gemar mendengarkan cerita. Saya juga membentuk diri menjadi orang yang suka menceritakan sesuatu. Jadi hari Minggu ketika pagi saya nonton Wiro Sableng, malamnya saya tergerak untuk menceritakan ulang episode lengkap Wiro Sableng ke orang lain. Itulah yang menggerakkan saya untuk terus bercerita.
Kalau ide menulis, biasanya datang dari mana saja, Faisal?
Saya tidak pernah menanyakan alamat ide menulis, alamatmu di mana, datang dari mana. Sejauh ini saya tidak tahu. Mungkin itu adalah akumulasi dari pengalaman, bacaan, dan tontonan. Akumulasi itu membentuk diri sendiri, menjadi ide. Itu datang dari segala jenis proses yang saya tempuh selama hidup.
Penulis kadang memang diberkahi pengalaman berharga dan beberapa di antaranya diuntungkan dari sisi geografis mereka. Apa Faisal merasa begitu juga, dengan lahir dan besar di Sulawesi Selatan?
Apa yang saya tulis adalah akumulasi dari masa lalu sampai hari ini. Itu terkait dari di mana saya tumbuh, apa yang saya baca, dan lainnya. Itu sumber yang sangat berperan penting. Saya tumbuh dan berkembang di Sulawesi Selatan. Saya tidak punya tendensi menulis lokalitas Sulawesi Selatan itu sendiri. Saya menulis sesuatu yang dekat dengan saya, sebuah keresahan pertama. Persoalan lokal, tidak lokal, itu tidak saya permasalahkan. Saya menulis yang saya inginkan dan resahkan. Soal wacana berikutnya, itu ada di sidang pembaca.
Sastrawan Pramoedya pernah menulis soal Jawa, lalu lebih luas lagi menulis soal Indonesia. Ada keinginan menulis dengan latar di luar tempat tinggalmu?
Keinginan itu pasti ada, saya berharap bisa menulis jauh dari tempat saya tumbuh dan belajar. Saya sadar menulis sesuatu yang jauh dari saya butuh energi lebih besar: membaca, berdiskusi. Saya tidak menutup diri memasukkan sebanyak mungkin kemungkinan di masa depan.
Ceritakan dong bagaimana proses kreatif Faisal menulis?
Bagi saya, yang sangat penting adalah gagasan dan wacana yang mendukung. Tentu saja kebanyakan karya yang saya tulis, dimulai dari wacana kecil, misal soal identitas sebagai orang Bugis. Lalu saya mengembangkan lewat membaca dan berdiskusi dengan orang-orang. Beberapa tahun, saya belajar menulis, saya belajar menulis puisi, cerpen, novel, bukan karena saya merasa mampu. Namun, dengan data yang saya punya, saya punya pertimbangan untuk menyajikannya dalam novel, cerpen, atau lainnya. Misal, wacana bissu, saya kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Ini lahir dalam puisi, cerpen, novel, esai, bahkan makalah.
Berlaku juga untuk novelmu “Tiba Sebelum Berangkat”?
Ini cerita soal bissu yang menjadi salah satu kekayaan gender di Sulawesi Selatan. Bagaimana sejarah dan situasi politik membentuk mereka sebagai individu dan komunitas, serta bagaimana mereka bertahan di zaman yang terus bergerak di tengah perkembangan saat ini. Itu saya respons di novel ini. Bukan sekadar bissu, saya menuliskannya tak sekadar personal, tapi juga peristiwa sejarah dan politik. Mereka bagian dari sejarah, yang dikorbankan penguasa, terasing dari tempat seharusnya. Padahal mereka dalam kearifan lokal Bugis adalah penghubung dengan Tuhan.

Kalau biasa mengangkat soal bissu dan cerita lain dari tempat tinggalmu, lalu tujuan menulismu sebetulnya apa?
Andai saya menulis daftar keinginan, yang pertama adalah sebagai bentuk saya melepaskan diri dari keresahan. Saya tidak bisa bermimpi kaya raya, punya ribuan followers. Hal paling dekat, ya menyampaikan wacana. Ini berlaku pula tentang wacana bissu yang terasing di tempat asalnya. Mereka bahkan belakangan dikomersialisasi dalam pagelaran budaya dan acara lainnya.
Bicara soal bissu dan novel “Tiba Sebelum Berangkat”, apa betul itu karya yang awalnya diikutkan dalam sebuah sayembara, tapi gagal? Jika iya, apakah Faisal memang biasa meniatkan seluruh tulisan untuk diikutkan dalam sayembara sastra atau diterbitkan?
Itu (diterbitkan atau diikutkan sayembara kepenulisan) adalah tahap di atas naskah sudah jadi. Tahap awal saya ya. Kalau diarahkan ke penerbit, ditaruh di koran atau penerbit itu langkah berikutnya untuk menyentuh pembaca yang lebih luas. Banyak sekali jalannya, ya sayembara, terbit di media. Yang penting bagi saya adalah saya mencari pengetahuan dan data sebanyak mungkin, lalu saya menuliskannya.
Buat ranking karyamu sendiri yang kamu favoritkan?
Saya menulis enam buku. Ketika harus diurutkan, semua ada di posisi keenam. Saya tidak menyukai semua buku yang saya tulis. Setelah buku selesai dicetak, kenapa buku saya seburuk ini? Saya tidak pernah merasa puas dengan yang saya tulis. Saya tidak pernah memfavoritkan semuanya. Itu (tidak memfavoritkan) membuat saya ingin menulis lebih baik lagi.
Rendah hati sekali ya Faisal?
Bukan rendah hati, tapi rendah diri (tertawa).
Bagaimana rasanya menjadi muda dan “berbahaya” begini, juga memiliki banyak followers di media sosial?
Followers Instagram itu sebenarnya hasil beli. Rasanya (menjadi penulis muda) biasa saja. Jika kita pembaca sastra Indonesia, sangat banyak penulis muda Indonesia yang karyanya “melampaui zamannya”. Menurut saya banyak penulis muda yang bagus. Jadi menjadi penulis yang kebetulan berusia muda, biasa saja, karena banyak yang begitu.
Sepuluh tahun ke depan tetap menulis atau tidak?
Semoga masih bisa menulis, tapi lebih penting, semoga saya bisa punya kemampuan membaca. Kadang seminggu tak baca apapun, sehari kadang bisa satu buku kalau sekarang.
Ada penulis favorit yang menginspirasimu?
Sejak SD saya membaca novel Enny Arrow, Abdullah harahap. Di perpustakaan sekolah bisa dapat buku macam-macam terbitan Balai Pustaka. Namun, buku paling berpengaruh adalah Ziarah” karya Iwan Simatupang. Itu yang pertama saya baca dari perpus kampus. Juga penulis India Arundhati Roy dalam bukunya “The God of Small Things”. Dua buku ini, saya tidak bisa mengurutkan, menjadi awal saya membaca lebih banyak karya sastra.
Terakhir, menurutmu bagaimana kondisi kesusastraan kita dewasa ini?
Penulis muda banyak, tema beragam. Ini seperti janji untuk masa depan sastra kita yang lebih baik dari sebelumnya. Itu harapannya ada di tangan muda dan kritikus sastra dalam beberapa tahun terakhir.