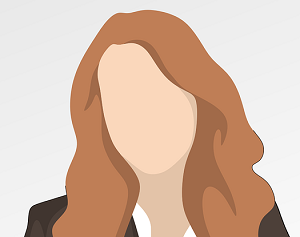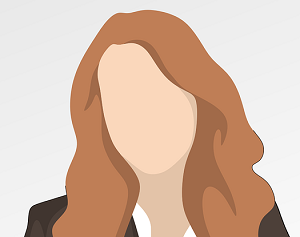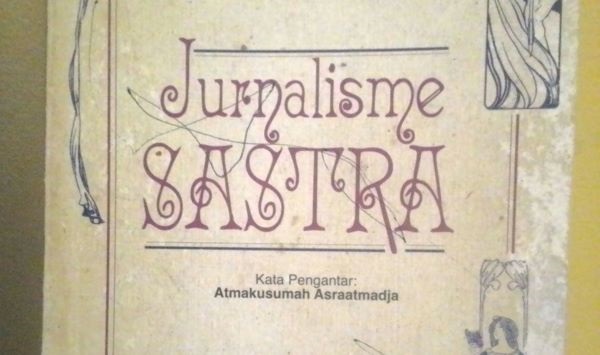Kawin tangkap, selubung kekerasan atas nama adat
“… Berhenti membuat kami merasa seperti barang, yang bisa ditukar dengan hewan, yang dihargai hanya karena kami pung rahim.
Kalau bulan lalu ko kasih sa pung air mata tumpah ke muka bumi, ko kasih sa bulan paling hitam yang ada di dunia, sa tahu itu bukan akhir. Karena sekarang sa ada lihat cahaya. Sa punya banyak teman yang akan mendukung sa punya jalan. Sa pung bulan akan kembali terang.
Ini bukan akhir sa pung dunia.” (2020: 147)
Magi Diela diculik. Adalah teman masa kecil ayahnya, Leba Ali, yang melarikannya secara paksa. Lelaki itu sudah beristri, tapi tetap menginginkan tubuh Magi. Menolak tunduk pada si mata keranjang, Magi memilih jalan pintas. Bunuh diri. Nyawa Magi berhasil diselamatkan. Kasus penculikannya sampai ke tangan polisi. Namun, Leba Ali lolos dari jerat hukum.
Alih-alih geram pada peristiwa nahas yang menimpa anaknya, ayah Magi justru menganggap penolakan Magi pada Leba Ali adalah aib. Bila pernikahan gagal, itu sama artinya dengan ‘bencana’. Magi tak bisa membayangkan seperti apa masa depannya kelak.
Ia hanya ingin lelaki itu membayar trauma yang dideritanya. Ia ingin orang di luar sana melihat bahwa ada yang salah dengan adat ini—kekerasan terhadap perempuan dibiarkan berlangsung atas nama tradisi. Ia berharap tidak ada lagi perempuan-perempuan yang menjadi korban seperti dirinya.
Lewat sosok fiksi Magi Diela, tokoh utama dalam Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam (2020), Dian Purnomo mengangkat fenomena kawin tangkap yang masih bisa ditemui hingga hari ini di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Perempuan diculik untuk dinikahi.
Peristiwa ini acapkali dilihat sebagai tahap awal sebelum prosesi resmi pernikahan digelar secara adat. Namun, banyak kasus membuktikan bahwa kawin tangkap yang pada era modern seperti sekarang dianggap budaya, bagian dari kearifan lokal, justru menjurus pada kawin paksa. Bukan tradisi, melainkan berahi. Ada unsur intimidasi yang pada akhirnya berbuntut perkosaan.
Bahkan, bila pihak lelaki merasa sudah tidak cocok lagi, korban bisa dipulangkan. Ia cukup membayar belis (mahar) sebagai ganti rugi harga diri.
“Bahwa budaya itu masih dibiarkan, tidak bisa dibenarkan,” ungkap Dian di sela-sela diskusi daring bertajuk Seruan Perempuan Merdeka dalam Kisah Novel.
Kawin tangkap, kata Dian, menjadi bukti bahwa kaum hawa dalam masyarakat adat Sumba masih diposisikan sebagai kelompok kelas dua. Mereka tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Pendapatnya tidak dihargai. Hak-haknya tidak dijunjung tinggi.
Penulis kelahiran Salatiga itu pun menegaskan, kultur ini merupakan praktik kekerasan. Idealnya tidak dilegitimasi, apalagi dilegalisasi.
Namun, sebagaimana yang ia tuangkan dalam kisah Magi, orang paling dekat dengan korban sekalipun seolah ‘mendukung’ tabiat ini. Orangtua tunduk pada adat. Teman sepermainan tak berdaya, tak punya suara di hadapan para tetua. Kawin tangkap dianggap sebagai garis nasib. Lebih baik dibanding tidak menikah sama sekali.
Ada fakta lain yang membuat Dian semakin miris. Masyarakat awam yang menyaksikan langsung fenomena ini berseliweran di depan mata pun memilih bersikap apatis. “Saya ingin ada orang yang berpikir tidak seperti itu (menganggap kawin tangkap adalah takdir pilihan Tuhan),” cetusnya.
Magi pun menjadi representasi generasi muda yang identik dengan cita-cita tinggi dan harapan untuk mengubah nasib. Termasuk menjadi bagian dari upaya memajukan tanah kelahirannya. Ia sekolah tinggi dan keluar dari kampung halamannya. Jawa menjadi rujukan untuk me-reset pola pikir dan cara pandang.
“Tidak terbayang di kepalanya, adat akan menjadi batu sandungan di masa depan. Bahwa sesuatu yang sangat ia cintai akan mengganjal cita-citanya sendiri,” jelas Dian.
Mencuri berkah wulla poddu
Masyarakat Sumba menetapkan waktu-waktu terbaik untuk penyucian diri. Dalam bahasa setempat, mereka menyebutnya wulla poddu. Wulla secara literal berarti ‘bulan’ dan poddu bermakna ‘pahit’. Dalam konteks ini, ‘pahit’ sama artinya dengan ‘prihatin’.
Sepanjang wulla poddu yang jatuh antara Oktober-November, masyarakat penganut Marapu harus menjalankan serangkaian upacara ritual dan mematuhi sejumlah larangan. Tidak boleh menggelar pesta adat dan acara meriah lainnya seperti pernikahan. Tidak boleh membangun rumah, meratapi orang yang meninggal dunia ataupun menyelenggarakan perayaan kubur batu.
“Wulla poddu menjadi momen semua orang minta berkah,” tutur Dian, yang menerjemahkan ulang wulla poddu menjadi ‘bulan hitam’ untuk judul buku terbarunya ini.
Ironisnya, kata Dian, bulan yang sejatinya suci ini justru diisi praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan dengan dalih tradisi. “Karena dianggap sebagai bulan berkah, banyak orang dari zaman dulu sampai sekarang masih melakukan kawin tangkap karena berharap mendapat berkah.”
Menggugah jiwa yang ‘mati rasa’
Dalam buku setebal 320 halaman itu pun diceritakan betapa Magi bukan satu-satunya perempuan yang mengalami peristiwa mengerikan ini. Ketika diselamatkan dan menjalani pendampingan untuk memulihkan trauma di rumah aman, ia bertemu perempuan-perempuan yang senasib—ada pula yang lebih malang.
Tapi suara-suara mereka tidak terdengar. Lebih sering, mereka tak sanggup dan tak punya ruang untuk bersuara.
“Di sebuah kelas penulisan, saya mendapat pesan, ‘Kalau kamu ingin membuat cerita yang berdampak, suarakan mereka yang tidak terdengar (suaranya).’ Sehingga yang belum pernah mendengar kasus ini jadi tahu bahwa praktik kekerasan seperti ini ada,” kata Dian.
“Lebih menyedihkan lagi, sesuatu yang sebenarnya pedih dianggap biasa saja. Korban memaknai kekerasan yang dialaminya sebagai sebuah takdir,” tambahnya.
Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam adalah buku kedelapan Dian Purnomo. Ia memang concern pada isu-isu perempuan dan anak. Dian menulis novel ini setelah menyelesaikan program Residensi Penulis Indonesia 2019 selama enam pekan di Sumba.
Dian menekankan bahwa cerita ini adalah fiksi, walaupun terinspirasi dari kisah nyata dari orang-orang dan komunitas yang dia temui di sana. Namun, di sisi lain, ia berharap spirit yang ditiupkannya dalam karakter Magi Diela dapat menggugah semua pihak dari kesadaran palsu tentang ‘berkah’ di balik tragedi kawin tangkap.