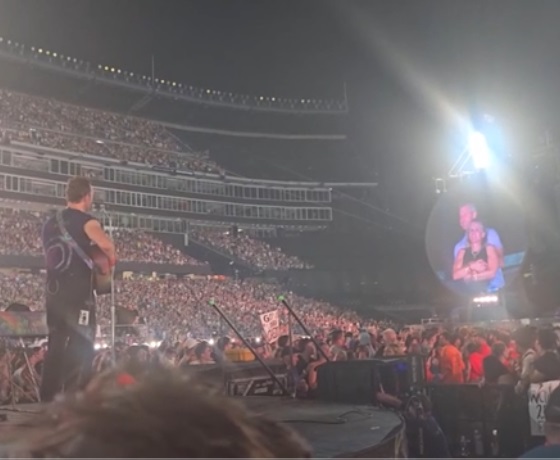Kuasa rezim memberangus musik
Kompleks pertokoan elektronik Glodok, Jakarta Barat, menjadi saksi bisu anggota grup musik legendaris Koes Bersaudara ditahan di sana pada 29 Juni hingga 29 September 1965.
Dahulu, di kompleks pertokoan itu berdiri penjara Glodok. Grup yang beranggotakan Yon Koeswoyo, Yok Koeswoyo, Nomo Koeswoyo, dan Tonny Koeswoyo ini dipenjara tanpa proses peradilan.
Koes Bersaudara dipenjara karena memainkan lagu-lagu grup musik asal Inggris, The Beatles di tempat umum. Menurut Frans Sartono di dalam harian Kompas edisi 16 Mei 1966, saat itu pemerintahan Soekarno melarang pemutaran dan pertunjukan lagu-lagu rock n roll dari Barat. Soekarno menyebutnya, musik ngak ngik ngok.
Pengalaman pahit itu kemudian diabadikan dalam lagu “Di Dalam Bui” yang menjadi bagian album To the So Called the Guilties (1967).
Menggilas musik ngak ngik ngok
Musik dan politik terkadang beririsan. Tak jarang, musisi kena imbas dari arah politik rezim yang bertentangan atau karena mengkritik kebijakan penguasa. Ditangkap dan dipenjaranya Koes Bersaudara pun tak lepas dari semangat revolusi kebudayaan, yang tengah gencar disuarakan pemerintahan Soekarno.
“Dan engkau, hai pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi, engkau yang tentunya antiimperialisme ekonomi dan menentang imperialisme ekonomi, engkau yang menentang imperialisme politik. Kenapa di antara engkau banyak yang tidak menentang imperialisme kebudayaan? Kenapa di kalangan engkau, banyak yang masih rock n roll-rock n roll-an, dansa-dansian ala cha-cha-cha, musik-musikan ala ngak ngik ngok, gila-gilaan, dan lain sebagainya lagi,” kata Bung Karno dalam pidato “Penemuan Kembali Revolusi Kita” pada 17 Agustus 1959 di Istana Merdeka, Jakarta.
Soekarno pun mengulang kembali alerginya terhadap musik dari Barat pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1965 di hadapan Corps Gerakan Mahasiswa Indonesia.
“Jangan seperti kawan-kawanmu, Koes Bersaudara. Masih banyak lagu Indonesia, kenapa mesti Elvis-Elvisan?” kata Bung Karno.
Di dalam buku Musisiku (2007) disebutkan, kesan The Beatles sudah kadung melekat pada Koes Bersaudara. Mereka lantas dicap antirevolusi. Koes Bersaudara juga dinilai sebagai seniman yang berseberangan dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), yang berpengaruh kuat di masa itu.
Muhammad Mulyadi di dalam bukunya Industri Musik Indonesia: Suatu Sejarah (2009) menyinggung soal penerapan kebijakan pelarangan musik zaman Soekarno. Misalnya, Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai lembaga penyiaran pemerintah, menjalankan program “Pembangunan Semesta Berencana Indonesia” dengan visi, musik dan lagu merupakan sebagian dari kebudayaan yang membangun mental. RRI kemudian melarang pemutaran musik yang dianggap bisa merusak kepribadian bangsa. Salah satu yang dilarang adalah pemutaran piringan hitam lagu Diah Iskandar.

“Alasannya, nyanyian Diah Iskandar sering berirama twist dan dianggap meniru Conny Francis, seorang penyanyi asal Barat. Hal itu termasuk dalam kategori lagu-lagu yang tidak sesuai kepribadian bangsa,” tulis Muhammad Mulyadi.
Beberapa grup musik dan penyanyi, yang sebelumnya bernama Barat pun ramai-ramai mengubah menjadi nama Indonesia. Mulyadi menyebut, Jack Lemmers mengganti nama menjadi Jack Lesmana, Gerly Sitompul jadi Mawar Sitompul, The Alulas jadi Aneka Nada, dan The Rhythm jadi Puspa Nada.
Soekarno memandang, tumbuhnya band di Indonesia yang terpengaruh musik Barat, bisa berdampak negatif bagi kehidupan pemuda. Ketika itu, pemerintah mengambil kebijakan dengan dalih melindungi kebudayaan nasional dari pengaruh asing.
Di sisi lain, sebenarnya pelarangan musik Barat zaman Soekarno berefek positif bagi perkembangan lagu daerah, yang dikemas dalam alunan pop. Misalnya, sebut Mulyadi, Teruna Ria mempopulerkan “Bengawan Solo” dengan irama pop keroncong, Taboneo mengubah aransemen “Ampar-ampar Pisang dan “Saputangan Bacumbu Ampa” jadi lagu pop Kalimantan.
Kemudian, Lilis Surjani mempopulerkan lagu pop Sunda “Es Lilin” dan “Neng Geulis”, serta Diah Iskandar menyanyikan “Beas Beureum”. Akan tetapi, menurut Mulyadi, kebijakan kebudayaan yang anti-Barat dijalankan secara tak konsisten.
Mulyadi memberikan contoh, pada malam pementasan amal Parahyiangan di Istora Senayan, 1 September 1964, Guntur Soekarno Putra, putra Soekarno, bersama grup Aneka Nada membawa lagu berirama Amerika Latin dan Spanyol. Padahal, irama Amerika Latin dan Spanyol itu masuk dalam golongan irama cha cha cha.
“Kemudian musik jazz yang berasal dari Amerika tidak dilarang, bahkan disiarkan setiap malam oleh RRI,” tulis Muhammad Mulyadi.
Sensor Orde Baru
Ketika tampuk kekuasaan beralih ke Soeharto, musisi dan lagu yang berseberangan dengan pemerintah pun terkena dampak.
Grup musik D’Lloyd pernah merasakan sensor lagu Orde Baru. Lagu yang dinyanyikannya “Hidup di Bui” (judul lainnya disebutkan “Dalam Penjara Tangerang”) yang masuk dalam rekaman album Melayu 1 dilarang pihak yang berwajib.
“Konon dianggap menyinggung keadaan penjara,” tulis Midi dalam artikel “Yang Dilarang: Bagaimana di Indonesia?” di edisi 16-31 Mei 1976.
Menurut salah seorang personelnya, Bartje van Houten, lagu ini sebenarnya lagu lama yang dinyanyikan kembali. Ia mengaku tidak tahu siapa penciptanya.
Majalah Tempo edisi 9 April 1977 menulis, di dalam lagu itu terdapat lirik yang menyinggung pemerintah terkait penanganan narapidana di penjara Tangerang.
“Apalagi penjara Tangerang. Masuk gemuk keluar tinggal tulang. Karena kerjanya cara paksa. Tua muda turun bekerja,” begitu penggalan lirik yang bermasalah.
Penjara Tangerang merupakan saksi sejarah. Di sana, orang-orang yang dituduh PKI atau terlibat dalam G30S dijebloskan. Kalimat “penjara Tangerang” kemudian diubah menjadi “penjara zaman perang”.

Pelarangan bukan hanya menimpa D’Lloyd. Komedian Betawi Benyamin S pernah mengalaminya. Dikutip dari Midi edisi 16-31 Mei 1976, lagu-lagu Benyamin, seperti “Ondel-ondel”, “Lampunye lagi Mere”, “Dodolidodolibret”, dan “Burung Perkutut” tak boleh diputar di RRI.
“Di samping syairnya yang memberi asosiasi porno, lagu yang mengarah konyol itu kami nilai belum tentu cocok untuk massa pendengar RRI yang skopnya nasional ini,” kata Zaini dari RRI, seperti dikutip dari Midi.
Selain itu, lagu yang digubah komponis Lekra, yakni “Di Tepi Telaga Han-chouw” dan sebuah lagu Jawa berjudul “Noro Karyo” ciptaan Wasito Cokrodipuro, sebut Midi, pada 1976 juga tidak boleh diputar karena alasan berbau Hari Buruh 1 Mei.
Orde Baru pun memanfaatkan ketenaran musisi untuk kampanye politik Golkar. Mereka diikutkan dalam sebuah safari keliling beberapa kota di Indonesia.
Menurut artikel “Dan Oma serta Upit Ikut Kampanye” dalam majalah Tempo edisi 9 April 1977, safari artis muncul menjelang Pemilu 1971. Saat itu, Golkar mengikutsertakan sejumlah penyanyi dalam beberapa kali jadwal kampanye.
Oma Irama—sebelum dikenal dengan nama Rhoma Irama—pun ikut menjadi juru kampanye partai, tetapi bukan Golkar. Ia menjadi kader berpengaruh mendulang suara PPP pada Pemilu 1977.
Andrew N. Weintraub di dalam Dangdut: Musik, Identitas, dan Budaya Indonesia (2012) menulis, karena keterlibatannya dalam PPP, Rhoma dilarang tampil di RRI dan TVRI. Sejumlah lagunya diharamkan pemerintah dan kasetnya disingkirkan dari toko-toko.
“Pada November 1977, video lagu ‘Hak Azasi’, ‘Rupiah’, dan ‘Udang di Balik Batu’ dilarang tayang di televisi karena membeberkan masalah sosial, sehingga menurut Departemen Penerangan, dapat menghasut khalayak dan mengganggu stabilitas negara,” tulis Weintraub.
Pada 1980-an, muncul nama Virgiawan Listanto alias Iwan Fals sebagai penyanyi yang kerap melantunkan lagu bertema protes sosial. Menurut Musisiku, kata dan kalimat yang digores Iwan lugas, gamblang, dan menohok. Ia mampu menjewer penguasa yang duduk dalam singgasana pemerintahan.
“Salah satunya adalah yang tercetus dalam lagu ‘Wakil Rakyat’,” tulis Musisiku.
Karena lagunya, Iwan pernah pula berurusan dengan aparat. Pada April 1984, ia ditangkap dan diinterogasi selama dua minggu usai manggung di Pekanbaru, Riau, menyanyikan “Demokrasi Nasi” dan “Mbak Tini”.
Lagu “Mbak Tini” dinilai menghina Soeharto dan Tien Soeharto. Padahal, lagu itu mengisahkan tentang seorang pelacur yang memiliki warung kopi. Ia punya seorang suami bernama Soehardi, yang berprofesi sebagai sopir truk.
Kritik lebih bebas dan beragam
Pengamat musik Yuka Dian Narendra menilai, menyuarakan kritik sosial dalam karya musik merupakan tugas pokok seniman. Musisi, kata dia, menciptakan karya sebagai pengingat dengan cara mengisahkan kembali realita di masyarakat.
Bukan hanya di Indonesia. Yuka mengatakan, kasus pelarangan terhadap karya musik juga terjadi di negara lain.
“Di Bergen, Norwegia pada 1992, misalnya, terjadi pelarangan terhadap kelompok musik black metal. Pada 1980-an, di Amerika Serikat juga terjadi pelarangan terhadap pertumbuhan musik metal,” ujar Yuka saat dihubungi reporter Alinea.id, Rabu (22/1).
Di sisi lain, menurut dia, kontrol negara harus dilakukan dengan tetap menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi musisi.
Penulis buku Heavy Metal Parents: Identitas Kultural Metalhead Indonesia 1980-an (2018) itu memandang, kritik melalui musik saat ini masih tetap tumbuh. Bahkan, ia mengatakan, kritik itu semakin disadari sebagai hal yang harus disuarakan. Namun, kritik sosial lewat musik dewasa ini, kata Yuka, disampaikan dengan cara yang lebih santun.
Saat ini, tegangan yang muncul antara negara dan musisi, ujar Yuka, bermakna positif dalam membangun kebudayaan yang dinamis.
“Dalam kondisi perbedaan itulah yang merangsang munculnya dialog dan proses mencari kepentingan bersama bagi banyak pihak,” katanya.

Sementara itu, penulis buku Jurnalisme Musik dan Selingkar Wilayahnya (2018) Idhar Resmadi mengatakan, kontrol negara terhadap musik pascareformasi tak lagi seketat era sebelumnya. Tekanan terhadap musisi, kata dia, justru berasal dari sejumlah organisasi massa.
Idhar menuturkan, hal itu pernah menimpa grup musik metal Seringai, yang mendapat protes dari kelompok Islam karena di dalam lagunya kerap menyindir kelompok itu.
“Selain itu, sekitar 2005, band indie asal Bandung Forgotten juga diprotes oleh ormas Islam atas lagu mereka yang berjudul ‘Tuhan telah Mati’ dan ‘Tiga Angka Enam’,” kata Idhar saat dihubungi, Rabu (22/1).
Idhar mengamati, saat ini grup-grup musik indie pun juga melontarkan kritik, dengan ragam isu, seperti korupsi, budaya konsumtif, kerusakan lingkungan, kapitalisme, hingga kesehatan mental. Ia mencontohkan, grup musik asal Bali, Navicula, kerap menyuarakan isu korupsi dan pelestarian alam.
“Dulu, musuh bersamanya negara, terutama di masa Orba. Sekarang tidak lagi, jadi isu yang disuarakan berubah,” kata Idhar.