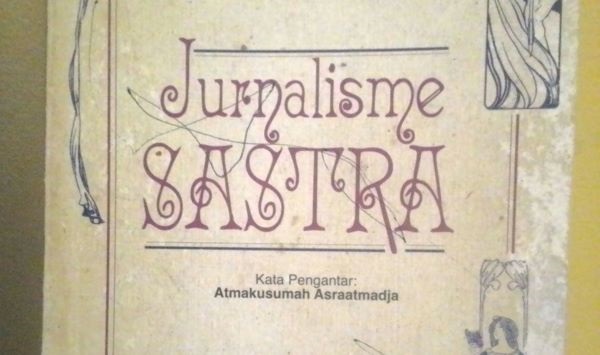Matinya Kepakaran: Taring para pakar di era internet
Debat kedua calon presiden sudah berlangsung. Namun, media sosial masih saja disesaki komentar dari warganet, terkait debat tersebut. Ada yang berkomentar tentang unicorn, tanah milik Prabowo di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur, hingga pernyataan Jokowi terkait infrastruktur.
Dari penelusuran tagar #debatcapres di Tweetbinder, jumlah cuitan mencapai 499. Lima terbesar cuitan, hanya satu yang dari unsur media. Sisanya, akun pribadi yang mendadak jadi pakar. Salah satu akun terbanyak yang berkicau dengan tagar ini adalah @mrizalb.
Ia mengomentari kepiawaian Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam merencanakan masa depan bisnis startup di Indonesia. Ia membandingkan rivalnya, Prabowo Subianto, yang dianggap tak paham unicorn—bisnis startup digital yang punya kapitalisasi melampaui US$1 miliar.
Tak ketinggalan, ia me-retweet pendapat perwakilan relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf, Remaja, yang berisi klaim Prabowo akan segera ditinggalkan pemilih dari kalangan milenial.
Setelah dilakukan penelusuran, akun Twitter Rizal berasal dari Sulawesi Selatan. Ia merupakan relawan Remaja, kelompok milenial pendukung Jokowi-Ma’ruf.
Seringkali kita mendapati warganet yang berkicau mengenai isu politik dan lainnya, padahal tak punya kapabilitas. Ketika mobil yang ditumpangi Setya Novanto menabrak tiang listrik, mendadak banyak orang menganalisis soal mesin kendaraan, potensi tabrakan, dan lain-lain.
Yang relatif paling epik, pada Maret 2018 beredar video Syahroni yang menganalisa telur palsu. Di dalam video Youtube berdurasi 2 menit 38 detik itu, ia membeberkan bukti telur yang beredar di Pasar Johar Baru merupakan telur palsu.
Hal itu membuat orang-orang resah. Usut punya usut, ternyata Syahroni bukan pakar telur atau kuliner. Ia hanya mendemonstrasikan apa yang ia ketahui dari media sosial soal telur. Meski di dalam video Syahroni tampak paham betul menerangkan bedanya warna kuning telur asli dan palsu, cangkang imitasi, dan lainnya. Belakangan, ia meminta maaf kepada publik.
Ketidakpercayaan terhadap pakar
Di Amerika Serikat, kepakaran karbitan pun muncul di media sosial. Penulis buku Matinya Kepakaran; Perlawanan terhadap Pengetahuan yang Telah Mapan dan Mudaratnya (2018)—terjemahan dari The Death of Expertise—Tom Nichols mengambil contoh, pada 1990-an muncul kelompok kecil, termasuk di dalamnya dosen Universitas California, yang menentang konsensus dunia medis bahwa virus HIV adalah penyebab AIDS.
Contoh lainnya, ketika pada 2014 Washington Post menggelar jajak pendapat tentang perlunya intervensi militer Amerika Serikat atas Rusia. Dari jajak pendapat itu, didapatkan fakta, hanya 1 dari 6 responden yang mengetahui persis lokasi Ukraina di peta.
Sisanya, menunjuk Ukraina terletak di Australia atau Amerika Latin. Namun, mereka tetap berkomentar soal pentingnya intervensi. Padahal, bila Amerika salah ambil sikap, maka konflik militer di Eropa perbatasan Rusia itu berpotensi memicu Perang Dunia III.
Yang tak kalah gawat, terjadi ketika Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Trump selalu membuat pernyataan kontroversial. Misalnya, menyebut Barack Obama tidak terasosiasi sebagai warta Amerika, sepakat dengan aktivis antivaksin, dan mengejek lawan politiknya Ted Cruz terlibat dalam pembunuhan John F. Kennedy. Seluruh opini Trump itu ia akui, didapatkan dari tayangan berita Minggu pagi yang disaksikannya.
Ulah Trump itu, disebut Nichols sudah menyuburkan tradisi ketidakpercayaan terhadap pakar di sana. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari gelombang antirasionalisme yang masif, terhitung sejak 1990-an.
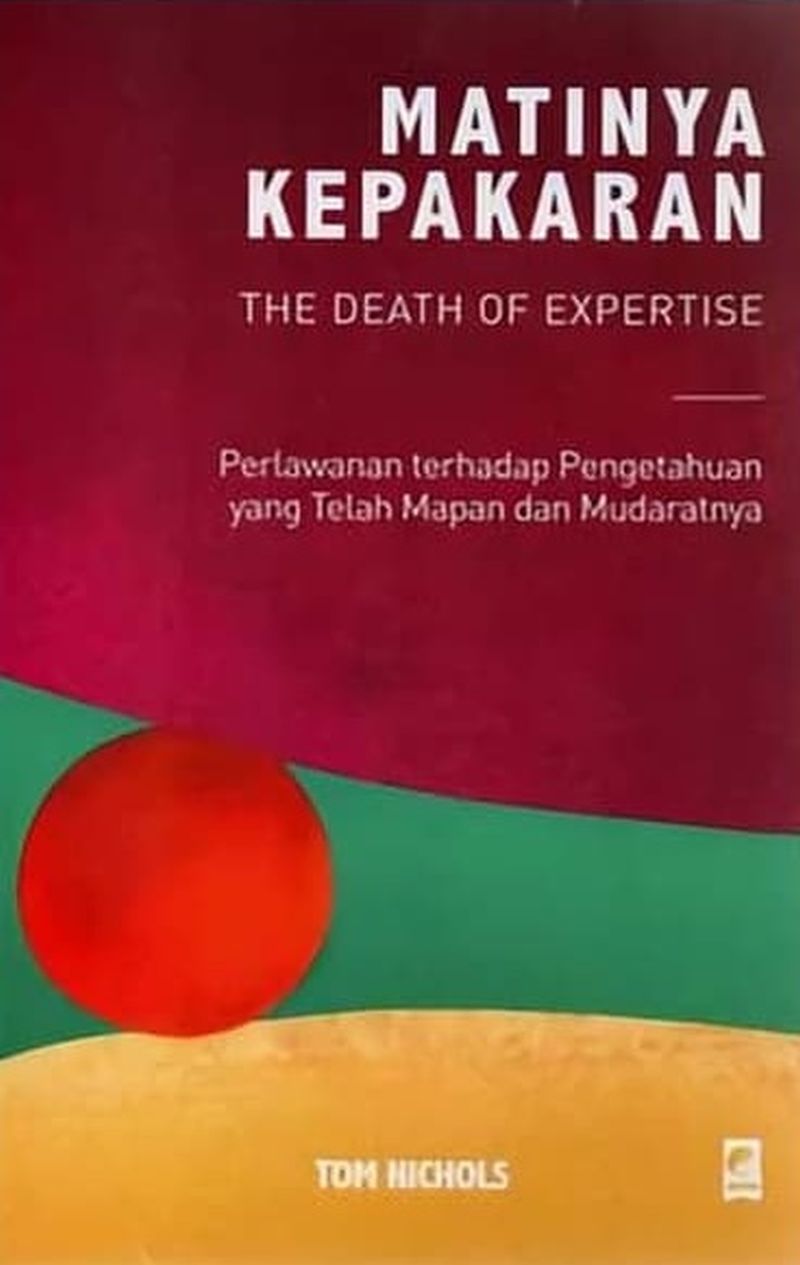
Fenomena itu ditandai dengan meningkatnya emosi di atas nalar sehat dalam debat publik, pengaburan garis antara fakta, pendapat, dan hoaks, serta penolakan terhadap temua ilmiah perubahan iklim dan vaksinasi.
“Orang Amerika telah mencapai titik di mana ketidaktahuan, terutama tentang apapun yang berkaitan dengan kebijakan publik adalah kebajikan yang sebenarnya,” tulis Nichols.
Menurut Nichols, hal itu merupakan cara bagi orang Amerika untuk menegaskan deklarasi kemerdekaan baru mereka. Kebenaran tak lagi menjadi bukti diri. Semua hal bisa menjadi kebenaran subjektif asalkan mereka mau. Cocoklogi dengan logika asal jiplak, sudah jadi santapan sehari-hari dari zaman dahulu.
Internet dan antirasionalisasi
Di sini, peran internet menjadi sangat penting sebagai agen yang membuat gelombang antirasionalisasi kian deras. Informasi terlampau banyak beredar. Sehingga, pakar yang diterjemahkan Nichols sebagai orang yang paham isu spesifik, punya pandangan otoritatif atas isu dan akurat, menjadi tak punya taring menghadapi gempuran hoaks.
“Internet tak hanya membuat kita semua lebih pintar, tapi juga bodoh. Sebab, internet bukan hanya magnet buat orang yang penasaran, tapi jebakan pula bagi orang yang lugu. Internet mengubah semua orang jadi ahli secara instan,” tulis Nichols (hlm. 127).
Masalahnya, kemudahan akses internet membuat orang bebas mengunggah informasi apapun. Sementara, pencarian informasi yang dikontrol algoritma, membuat penggunanya kerap tersesat di mesin perambah. Apalagi jika informasi itu tertuang di media sosial.
Menurut Nichols, alih-alih menjadi wadah diskusi cerdas, platform itu justru menjadi tempat pertemuan rentetan pendapat, rumor, ketidakpastian, informasi tak layak, dan diskusi yang tak logis. Orang pun lebih mudah menyerah pada bias informasi ini.
Bila internet ada andil menjadi wadah terbesar menyuburkan hoaks, maka akademisi dan jurnalis diklaim Nichols juga ikut berperan. Namun, sayangnya realitas di dunia kampus di Amerika Serikat, justru dihadapkan pada mahasiswa yang hanya sibuk mencari jalan keluar terbaik, agar segera lulus.
Sementara itu, para jurnalis saat ini, dengan dalih menyajikan berita secara cepat, tak peduli mewawancarai siapa saja, baik pakar atau bukan, asal komentarnya menghasilkan banyak klik. Dalam proses riset fakta di lapangan pun, tak jarang jurnalis hanya mengandalkan tempelan informasi yang tak diverifikasi lagi.
Faktor terakhir yang menyumbang matinya kepakaran adalah sifat dasar manusia, yakni egois. Mereka hanya mau mendengar informasi yang memang mau didengar. Akhirnya, otak memerintahkan agar manusia mengabaikan suara-suara yang berseberangan dengan keyakinan yang dianutnya.
Secara umum, Nichols mengingatkan kita tentang perlawanan baru terhadap otoritas intelektual di Amerika Serikat, bisa berakar kuat atas nama kebebasan dan egalitarianisme. Hal ini didukung dengan populisme masa kini, yang meningkatkan penghinaan atas para elite politik, ekonomi, dan lain-lain.
Trump adalah contoh paling tepat yang menggambarkan penghinaan atas kaum elite, saat ia hanya mau mendengar media yang memberitakan hal-hal positif tentangnya, dan memusuhi media yang berseberangan. Lantas menyerang lawan politik yang tak berbasis data.
Di sini, pakar menurut Nichols harus turun dari menara gading dan ikut bertanggung jawab agar kelompok antirasionalis ini tak makin menggila. “Kadang obat kegagalan pakar adalah tim pencari fakta yang rekomendasinya dihargai,” tulisnya.