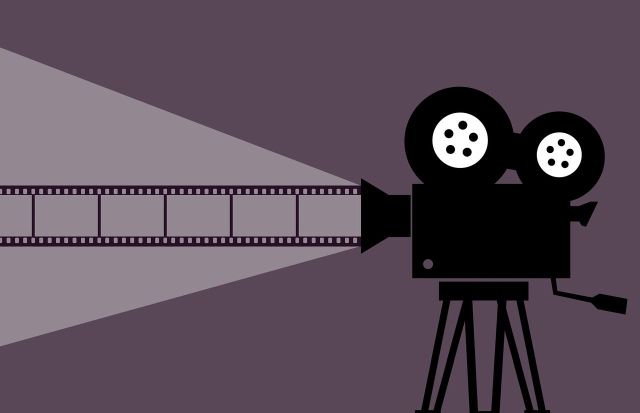Merayakan feminisme bersama Marlina
Marlina (Marsha Timothy) tak pernah menyangka, hari itu kedatangan Markus (Egi Fedly) yang akan membawa petaka pada dirinya. Markus yang mulanya disangka datang sendiri ke rumah Marlina, ternyata diboncengi enam pria di belakangnya. Sebagian pria ditugaskan untuk merampas ternak, sisanya menunggu giliran untuk mencicipi tubuh janda dari pedalaman Sumba itu.
"Kau adalah perempuan paling berbahagia malam ini," ujar Markus atas urusan yang harus dijalani Marlina di atas ranjang.
Kala Marlina membantah Markus dengan mengklaim dirinya perempuan bernasib paling sial, Markus menimpali, "Ah, kau perempuan, sukanya menjadi korban."
Sebuah pernyataan yang langsung menohok, bahwa perempuan sudah selaiknya melayani laki-laki dan menikmati setiap persenggamaan. Tak peduli apakah ia mendambakannya atau tidak. Sama menyakitkannya mendapati kenyataan, perempuan harus menghidangkan masakan terbaik dan minuman hangat pada komplotan bandit tengik, yang terang-terangan mengaku akan memperkosanya.
Ini mengingatkan saya pada realitas di Indonesia, di mana perempuan dalam perkosaan--yang jelas menduduki posisi subordinat, namun tetap disalahkan. Pun dengan stigma kesuksesan perempuan yang hanya diukur dari prestasi mereka, mendapatkan atau didapatkan pria, seperti terhidang dalam berbagai iklan televisi.
Apakah Marlina yang sendiri, yang hanya bisa mendekap mumi suami di pojok ruangan, pasrah? Tidak, ia menolak diam begitu saja. Dengan kecerdikannya, Marlina membunuh empat laki-laki dengan meracuni makanan yang dihidangkan pada mereka.
Di titik inilah saya langsung jatuh cinta pada sosok Marlina. Ya, dia adalah pembunuh yang merontokkan semua patronase laki-laki atas perempuan. Di film ini, justru para lelaki yang tampak tak berdaya. Markus dipenggal kepalanya, hingga dua orang kawanan yang tersisa lari lintang pukang. Inilah akhir babak pertama “The Robbery”.
Tanpa beban, ia menenteng penggalan kepala Markus untuk dibawa ke kantor polisi. Cara Marlina menjinjing penggalan kepala Markus menunjukkan derajat lelaki dengan perilaku bejat seharusnya di bawah perempuan. Hal itu seolah menunjukkan, lelaki yang berlaku semena-mena terhadap perempuan tidak patut pendapat penghargaan.
Menempuh perjalanan dengan medan terjal, sutradara Mouly Surya tak mau menjual sisi dramatis. Namun begitu, amarah luar biasa terpancar dari Marlina—sebuah upaya Mouly untuk tak tanggung mempertontonkan karakter lakon utama.
Kemarahan Marlina tak terbendung lagi. Bahkan di tengah perjalanan, Novi temannya yang tengah hamil tua, mendesaknya untuk melakukan pengakuan dosa di gereja. Marlina tegas menolak karena meyakini apa yang dilakukannya benar.

Salah satu penggalan dalam film "Marlina: Si Pembunuh dalam Empat Babak" (2017).
Amarah Marlina menemukan titik kritis sesampainya di kantor polisi, usai menembus lanskap padang gersang Sumba. Alih-alih mendapat perlindungan dari kawanan perampok yang masih berkeliaran, polisi justru menghina keperempuanannya dengan menyatakan, akan membuktikan kebenaran informasi Marlina dahulu. Ia harus divisum dengan alat yang diperkirakan bisa sampai di Sumba sebulan lagi. Sebuah kritik untuk polisi yang kerap mencibir korban pelecehan seksual, yang kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari.
Film yang dikemas dengan gaya satay western ini secara singkat mengajak penonton mempreteli mitos soal tubuh dan konstruksi perempuan di mata khalayak. Tak hanya ketegaran Marlina yang dipertontonkan, kita juga melihat teman perempuan Marlina dipukul suami karena dituduh berselingkuh. Menurut mitos Sumba, jika bayi mendiami rahim lebih dari sepuluh bulan, berarti bayinya sungsang akibat berhubungan seks semasa kehamilan.
Latar memang diambil jauh dari ibukota, dengan lakon yang mungkin tak pernah mencicipi sekolah, apalagi agenda feminisme dan kesetaraan gender. Namun ia mendobrak nilai-nilai patriarki dengan caranya sendiri. Saat ia dimaki sebagai pembunuh oleh salah satu perampok, sementara pria itu tak menyadari perbuatannya adalah kejahatan, maka pembunuhan adalah solusi. Begitu kira-kira, isi pikiran Marlina.
Perampok yang memaki, Frans akhirnya memang berhasil memaksa Marlina kembali ke rumah dan memperkosanya. Namun Novi spontan menyerang Frans dengan golok, hingga kepalanya tanggal dari badan.
Film dengan kemasan sinematografi Yunus Pasolang ini sekali lagi mengetengahkan agenda feminisme paling dasar yakni kemandirian perempuan dan otoritas atas tubuhnya. Saat ia menolak kedaulatan tubuhnya diobrak-abrik, maka ia sengaja menyimpan golok untuk memenggal kepala si pemerkosa. Kala negara lewat aparat sebagai perpanjangan tangan, absen, maka ia hanya bisa menggantungkan nasib pada dirinya sendiri.
Marlina yang hingga babak ketiga memposisikan diri sebagai korban, baru tersadar, jika ia adalah tuan atas nasibnya sendiri. Ia melawan sebisanya. Ia lahir menjadi manusia baru. Ini senada dengan babak terahir, “The Birth”, di mana Mouly mengakhirinya dengan adegan kelahiran (manusia). Seolah Marlina dan perempuan lain lahir kembali menjadi sosok baru yang berani dan merdeka.
Meski bernuansa gelap, Mouly sempat menyelipkan sejumlah humor satir dan hitam di dalamnya. Palet warna yang kontrasnya khas di tengah latar savanna Sumba memanjakan penonton. Belum lagi bunyi siulan musik besutan Zeke Khaseli dan Yudhi Arfani yang mengingatkan kita pada pemusik spesialis western movie Ennio Morricone.
Dengan kemasan semacam ini, film Marlina tak ubahnya "Django Unchained" dan "Hateful Eight" (Quentin Tarantino, 2012 dan 2015), namun dengan kearifan lokal dan kedekatan isu yang lebih personal, yakni perempuan Indonesia.
Karena keunikan dan kuatnya penceritaan Mouly, tak heran jika kemudian film ini wara-wiri di Cannes, Toronto, Melbourne, dan Busan. Selain itu, film ini juga membuat Marsha Timothy menuai pujian di Cannes atas cara ia melakoni acting. Tak hanya pujian, ibu dari Pearl itu menyabet penghargaan aktris terbaik dari Sitges International Fantastic Film Festival, mengalahkan bintang Nicole Kidman. Ya, film yang mendobrak genre sinema Indonesia yang monoton, dikawinkan dengan acting mempesona, membuat film ini layak jadi tontonan.