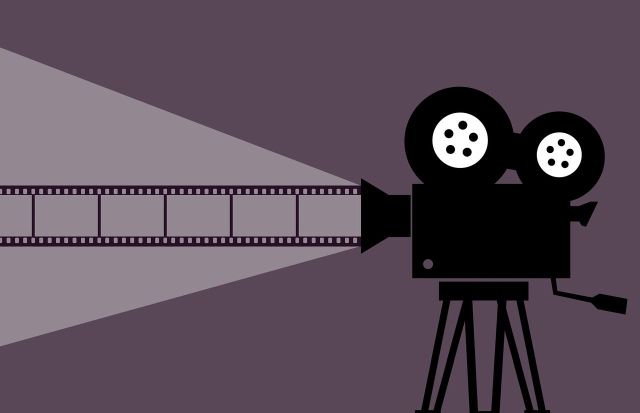Polemik Kiblat dan bagaimana film horor religi yang baik
Film horor Kiblat menuai polemik sebelum tayang di bioskop. Perkaranya, poster promosi film itu di media sosial, sebelum dihapus, dinilai sensitif. Poster tersebut menggambarkan seorang perempuan mengenakan mukena dalam posisi rukuk, tetapi kepalanya menengadah dan berteriak. Di kejauhan, ada sosok tanpa kepala.
Selain warganet, kritik dilontarkan sejumlah figur publik. Salah satunya dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nasif. Lewat unggahan di media sosial Instagram, Minggu (24/3), ia mengatakan sering kali promosi sensitif dan kontroversial dapat menarik perhatian dan banyak penonton. Sering kali juga reaksi keagamaan dimainkan pebisnis untuk meraup keuntungan materi.
“Saya tak tahu isi filmnya, maka belum bisa komentar. Tapi gambarnya seram, kok judulnya kiblat. Saya buka-buka, arti kiblat hanya Kakbah, arah menghadapnya orang-orang salat,” tulis Cholil.
“Kalau ini benar sungguh film ini tak pantas diedar dan termasuk kampanye hitam terhadap ajaran agama.”
Namun, lewat keterangan tertulis yang diterima Alinea.id pada Rabu (27/3), MUI mengkonfirmasi, produser film Kiblat mendatangi MUI. Dalam pertemuan itu, tim produser yang meminta maaf lantaran sudah terjadi kegaduhan menjelaskan isi film, proses pemilihan judul, dan poster.
“Kesempatan pertemuan itu diusulkan oleh Kiai Cholil Nafis agar disiarkan minta maafnya, mengganti judul film dan posternya. Sedangkan isi filmnya tentu diserahkan kepada Lembaga Sensor Film (LSF) untuk menilai atau meloloskannya,” tulis keterangan tertulis MUI.
Menurut kritikus film Hikmat Darmawan mengingatkan agar tak menilai film sebelum menontonnya. Ia tak mempermasalahkan kritik pada materi promosi, seperti poster. Malah, kritik itu bisa menjadi evaluasi dari pembuat film dan LSF bisa bekerja atas dasar masukan masyarakat.
“Yang menjadi masalah di sini kan karena materi promosi film Kiblat, lalu ada seruan-seruan untuk memboikot film-film horor religi. Ini menurut saya bukan hanya terlalu dini, tetapi juga berlebihan,” ucap Hikmat kepada Alinea.id, Rabu (27/3).
Hikmat memandang, industri film adalah industri padat karya. Di dalam tim produksi, melibatkan banyak orang yang menggantungkan hidup. Ada pula bioskop yang harus membayar karyawannya. Ada penginapan yang disewa selama masa produksi.
“Kita harus berpikir sampai dampak luasnya,” kata dia.
“Jadi, jangan sembarangan main larang atau boikot film horor. Kita harus melihat satu per satu kasus aja. Kebetulan Kiblat problematik yang mengeksploitasi subgenre salat. Kalau semua kita generaslisasi itu kan juga enggak bagus efeknya untuk semua.”
Ia menjelaskan, film tersebut memang secara jelas ingin memanfaatkan minat penonton terhadap horor plus religi. “Jadi, ini kan pasar yang memang banyak dieksploitasi. Spesifiknya horor religi Islam,” ujar Hikmat.
Ia menerangkan, film horor religi baru lepas pasca-reformasi. Sebelumnya, film-film yang menampilkan hantu, harus kalah dengan tokoh agama. “Baru tahun 2000-an saya lihat (film) Jelangkung tidak seperti itu karena sudah tidak ada lagi ‘peraturannya’,” tutur Hikmat.
Hikmat menilai, fim Kiblat berbeda dengan film Qodrat atau Pemandi Jenazah. Qodrat dan Pemandi Jenazah memang ada aspek agamanya, tetapi tak ada ritus salat. Atas dasar itu, Hikmat berpendapat, Kiblat adalah film horor religi Islam subgenre ritus-ritus salat.
“Jadi, eksploitasi agama ini memang dilakukan oleh produser Kiblat maupun juga dengan produser drama-drama religi (di televisi),” ujar Hikmat.
Terlepas dari itu, membuat film horor tak mudah. Hikmat mengatakan, biasanya diperlukan riset dengan mengundang banyak tokoh agama yang paham dan relevan. Misalnya, film Qodrat. Kata Hikmat, film tersebut memanfaatkan riset ke mana-mana. Lalu, menyediakan pendamping yang mengajarkan melafalkan ayat-ayat Alquran dengan tepat untuk para pemainnya.
“Itu kan artinya ada ilmunya, ya,” kata Hikmat.
“Kalau film-film yang hanya asal jadi aja gitu, (misal) kita bikin orang lagi salat langsung jadi setan. Nah itu kan sudah pasti menyinggung kan. Sudah pasti itu tidak riset dan filmnya asal-asalan.”
Hikmat menilai, film Qorin terasuk film horor religi yang baik. “Itu (film) kan (berlatar) pesantren perempuan, yang menyelesaikan (masalah) juga perempuan. Jadi, di situ ada pemberdayaan perempuan yang kuat sekali,” tutur dia.
“Bagus dari segi tematik.”
Di sisi lain, supaya film horor berkonsep religi tak menimbulkan kontroversi, Hikmat mengingatkan pentingnya ada pendampingan. Misalkan, jika ingin membuat film tentang agama, maka minta pendapat dari orang yang ahli agama, baik dari tahap produksi hingga promosi.
“Jadi, semuanya tidak sembarangan,” ucap Hikmat.
Batasan formalnya, menurut dia, selama film tersebut tak menyuarakan ujaran kebencian pasti tak menimbulkan polemik. Film Siksa Neraka menjadi salah satu film yang berhasil secara promosi. Film yang dibuat berdasarkan komik Siksa Neraka dan digadang-gadang sebagai film pendidikan itu, ujar Hikmat, memanfaatkan promosi tobat di bioskop.
“(Pemutaran film) premiernya banyak ibu-ibu berjilbab yang masuk dan ini tidak menjadi masalah di Indonesia,” ujar Hikmat.
Namun, Siksa Neraka menjadi masalah saat film itu diputar di Malaysia. Penonton di Malaysia melihatnya sudah menyalahi akidah. Sebab, dalam kepercayaan Islam, siksa neraka baru terjadi setelah hari penghakiman atau kiamat. Bukan usai meninggal dunia. Meski demikian, film Siksa Neraka laris. Di Indonesia, film tersebut ditonton nyaris tiga juta orang.
“Jadi, kita jangan menghakimi atau normalisasi hanya berdasarkan dari materi promosinya saja. Kalau materi promosinya yang bermasalah, ya promosinya saja yang kita kritik,” tutur Hikmat.