
Roma: Obituari memori untuk ia yang tak bernama
Tahi anjing lagi, tahi anjing lagi. Seolah tak pernah habis, kendati Cleo Gutiérrez (Yalitza Aparicio) berkali-kali mengenyahkannya dari lantai. Namun, alih-alih mengeluh, asisten rumah tangga (ART) berambut legam ini tetap menjalankan pekerjaan tanpa banyak omong. Tak hanya membersihkan ampas si anjing, Borras, Cleo merawat empat anak majikan, mencuci baju, membersihkan kamar, menyiapkan makanan, juga menjadi kawan mendengar yang setia. Mungkin karena itulah, Cuarón (Gravity; Children of Men; Harry Potter and Prisoner of Azkaban) repot membuat tribut bagi Cleo, pengasuhnya sejak bocah-yang di kehidupan nyata bernama Libo Rodriguez.
Ini memang film semiotobiografi sutradara Meksiko pertama peraih Oscar tersebut. Mengambil latar di Mexico City pada 1970, Cuarón fokus mendedah sisi perempuan yang seumur hidup tak bernama, tak diketahui tanggal lahir dan asal usulnya, kerap terlupa, tapi susah payah menjadi perekat keluarga. Tak heran, jika Cleo kerap diganjar kecupan dan ucapan “Ayo bangun, Malaikatku,” dari para anak majikan, saking cintanya mereka.
Namun, kehidupan Cleo toh tak berjalan mulus, meski dikelilingi majikan yang memerhatikannya, pasangan suami istri Sofia (Arina de Tavira) dan sang ayah (Fernando Grediaga). Cleo, sebagaimana lazimnya gadis muda juga sibuk berkencan dengan pemuda bernama Fermin (Jorge Antonio Guerrero), rekan sepupu Adelia yang juga menjadi pembantu bersamanya. Fermin, mahir beladiri, juga mahir melarikan diri kala tahu Cleo hamil anak biologisnya.
Menghadapi kenyataan bunting dan ditinggal kabur, kita tak akan disuguhi drama yang mendayu-dayu dari Cleo. Seperti tanpa emosi, perempuan ini tetap pulang ke rumah, irit bicara, dan mencurahkan seluruh emosi dengan termenung depan jendela kamar.
Cuarón sendiri memang tampak berambisi mempersonifikasi malaikatnya itu sebisa ia. Namun, semua tetap samar hingga film purna. Ia tak pernah tahu apa yang dirasakan pembantunya, apakah ia sempat berpikir untuk aborsi, bunuh diri, dan ketika Cleo berkisah soal tanah ibunya yang disita, Cuarón tetap membiarkan semua kepingan cerita itu kabur, tanpa kita tahu kejadian sebetulnya. Dugaan saya, memang hanya itu yang ia ingat soal pengasuhnya. Lagipula, kita bisa memaklumi, dengan mengandalkan memori masa kecil yang berjejalan, tentu Cuarón telah berusaha mati-matian.
Ini berlaku pula ketika ia mengenang usaha Cleo untuk menemui Fermin yang tengah karantina untuk kompetisi beladiri nasional di lokasi antah berantah. Nyaris tanpa emosi, Cleo memberitahukan kabar kehamilan ini pada Fermin. Dingin. Namun, Fermin yang justru kepanasan dan bertingkah menyebalkan dengan kabur sekali lagi. Ia bahkan menghardik Cleo sebagai pembantu kurang ajar, mengancam akan memukulnya, dan tak mengakui jabang bayi di kandungan Cleo. Kalau saya jadi Cleo, tentu sudah habis saya memaki Fermin. Namun, di sisi lain, kita justru melihat ketenangan luar biasa dari Cleo, yang ditolak mentah-mentah. Ini benar-benar membuat saya terusik.
Memang, bisa jadi Cleo pulang dengan masygul, tapi kita tak pernah benar-benar tahu. Yang penonton tahu hanya, Cleo tetap diterima dengan suka cita oleh keluarga Cuarón. Ia ditemani untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit.
Suatu hari, ketika Cleo tengah berbelanja dengan nenek majikan, Teresa, ia terjebak pada aksi protes mahasiswa. Keduanya tahu aksi massa telah ditekan keras oleh pemerintah Meksiko, tapi kali ini jauh lebih buruk dari sebelumnya, karena tentara dan paramiliter dor mati para pengunjuk rasa itu. Bahkan mereka dikejar hingga ke tempat persembunyiannya di rumah sakit. Peristiwa Corpus Christi 1971, yang terkenal dengan aksi kejar-kejaran seru dan penembakan mahasiswa di Negara Latin ini.
Sialnya, di hari jahanam itu, bayi Cleo meminta dilahirkan. Terkencing-kencing, ia menuju ruang bersalin dan mendapati bayinya mati. Tentu ini menjadi bagian paling mengharukan bagi saya, apalagi ketika ia untuk pertama dan terakhir memeluk mayat anak perempuannya yang kaku.

Namun, bukan Cleo namanya jika ia tak setegar karang. Di saat ia sendiri terseret drama kehidupan pribadi pun, ia masih harus menjadi saksi bisu perselingkuhan majikan prianya, yang konon tak pernah pulang lagi ke keluarga itu. “Kita perempuan memang akan selalu sendiri,” ceracau Sofia pada Cleo yang juga punya nasib serupa dicampakkan pria begitu saja. Di bagian ini, saya kembali berhasrat untuk memaki laki-laki kembali. Emosi sekali rasanya.
Bagian yang hilang
Cuarón memang ingin menguraikan kembali kenangan pada pengasuhnya. Namun, meski terganjal detail cerita, ia tetap memukau dengan caranya mengemas sinematografi Roma. Film ini sekilas mengingatkan kita pada neorealisme Italia, termasuk penggunaan warna hitam putih. Cuarón yang di film ini merangkap penulis naskah, sinematografer, dan co-editor, menghindari keriuhan blockbuster dengan menyajikan cerita sederhana, minim dialog, nyaris nir-dramatisasi.
Gambar yang ia produksi juara. Ia berhasil mengunci perhatian saya, bahkan ketika film belum berumur tiga menit. Tampak lantai yang tergenang air dipotret lewat kamera statis, dan terdapat pantulan pesawat dari genangan air itu. Bagaimana kamera bergerak berikutnya, tak usah ditanya. Saya bahkan menilai, film ini adalah produk paling artistik selama 2018 yang ditayangkan Netflix, bahkan kanal lainnya. Kamera berjalan pelan ke seluruh ruangan mengikuti gerak tokoh, kadang long shoot diambil sehingga membuat saya enggan melepaskan pandangan.
Tak hanya itu, cara sutradara memvisualisasikan latar 1970-an di Meksiko pun tak tanggung-tanggung. New Yorker bahkan mencatat, dari hasil wawancara dengan Cuarón, peristiwa bersejarah Corpus Christi pun membuat ia mengerahkan 1.000 ekstras agar tampilannya lebih meyakinkan dan intens. Beberapa orang mungkin akan melihat film ini sebagai tontonan yang menjemukan dan bertempo lambat, tapi rasanya dengan kualitas sinematografi memikat begini, jadi setimpal.
Meski gambar yang dihasilkan relatif indah, tapi bukan berarti film ini tanpa cela. Adegan klimaks di mana Cleo mati-matian menerjang ombak demi menyelamatkan dua anak majikan yang nyaris raib tergulung lautan sangat mantap, tapi kita tak diberi konteks cerita. Sama seperti kita tak diberi konteks,
Adegan ini sangat nampol, meski di sisi lain kita tak tahu konteksnya. Sama seperti kita dibiarkan mengira-ngira siapa sebenarnya, bagaimana sosok Cleo alias Libo ketika sutradara ini masih bocah. Kita hanya dicekoki stereotipe yang kelewat umum laiknya film yang diproduksi sutradara kelas menengah, di mana majikan menjadi begitu pengertian pada ART tapi tak pernah memberi ruang lebih bagi mereka untuk berbicara.
Sementara para ART dilukiskan sebagai kelas pekerja dengan karakter super tabah dan apa adanya. Untuk film yang berfokus di Cleo tapi tak memberi gambaran utuh soal dirinya, jelas ini menjadi bagian yang terasa menganggu.




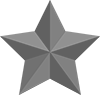 4
4Film paling artistik di 2018, tapi gagal mendedah sosok Cleo secara utuh.








