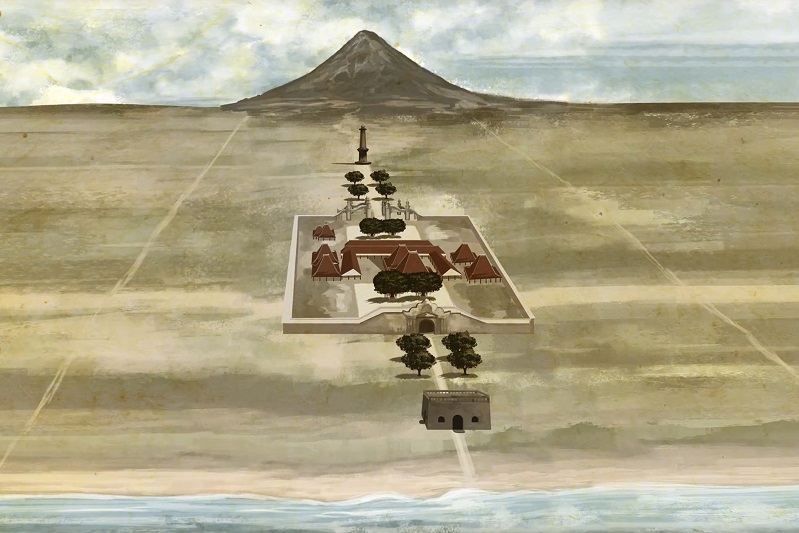Serangan budaya populer Jepang terhadap anak muda
Satria, seorang mahasiswa Universitas Airlangga, mengenal animasi asal Jepang—dikenal dengan istilah anime—sejak ia duduk di bangku sekolah dasar. Awalnya, ia terkesan dengan anime Clannad, yang kemudian membuatnya menyukai anime bergenre drama romantis lainnya.
Satria juga gemar ikut acara bertema Jepang. Misalnya, saat masih duduk di bangku SMA, ia pernah ikut acara Japanese World di Universitas Airlangga. Kegemaran Satria makin menggila. Ia kemudian suka ragam budaya populer Jepang, mulai dari film, gim, cosplay, idol, hingga masakannya.
Di kamarnya, karakter anime pun mudah ditemukan. Sebuah figur aksi Asuna Yuuki, salah satu karakter fiksi anime Sword Art Online berdiri di atas lemarinya. Stiker dan poster Asuna Yuuki pun menempel di pintu dan dinding kamarnya.
Bukan cuma memajang karakter anime kesukaannya, Satria pun bangga mengenakan jubah karakter anime Himouto! Umaru-chan. Ketika tidur, ia menggunakan penutup mata bergambar Ken Kaneki, salah satu karakter anime Tokyo Ghoul dan berbantal Dakimakura Rem anime Re: Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu.
Bahkan, Satria memiliki karakter gadis dalam anime yang ditetapkan sebagai waifu—pelesetan wife (istri), yakni Rikka Takanashi, salah satu karakter dalam anime Chuunibyo Demo Koi ga Shitai.
Serupa dengan Satria, Albi, seorang pekerja kantoran di Surabaya juga menyukai idol Jepang. “Idol Jepang itu imut dan menggemaskan,” kata Albi ketika ditemui reporter Alinea.id di Surabaya, Jumat (8/6).
Ia juga gemar mengoleksi segala yang berhubungan dengan ikon budaya populer Jepang. Albi mengaku punya guling Dakumakura Megamin anime Konosuba dan figur aksi anime Gundam.
Ketika mengikuti acara bertema Jepang, Albi kerap mengincar lomba cosplay—sebuah istilah bagi orang yang hobi berkostum ala karakter dalam anime, manga, maupun gim. Ia sering mempublikasikan hasil swafoto bersama cosplayer di akun Facebook-nya.
Anime dan cosplay

Budaya populer Jepang sendiri terdiri dari berbagai jenis produk budaya, seperti anime, manga (komik), Japan music (J-pop), dorama, dan gim. Anime merupakan yang paling populer.
Nobuyuki Tsugata dalam tulisannya “Bipolar Approch to Understanding the History of Japanese Animation” di buku Japanese Animation: East Asian Perspectives (2013) menulis, anime berupa film pendek berdurasi sekitar dua hingga lima menit pertama kali diproduksi di Jepang pada 1917.
Kartunis Shimokawa Oten dan Kouchi Junichi, serta pelukis dan pengusaha majalah seni Kitayama Seitaro mempelopori penciptaan anime, yang terinspirasi animasi pendek Prancis dan Amerika.
“Shimokawa memproduksi Imokawa Mukuzo dan Genkanban no Maki, sedangkan Kouchi merilis Namakura Gatana, dan Kitayama meluncurkan Saru Kani Gassen,” tulis Nobuyuki.
Dosen Sastra Jepang dari Universitas Airlangga Rahaditya Puspa Kirana mengatakan, penayangan anime di stasiun televisi swasta merupakan gerbang awal masuknya budaya populer Jepang di Indonesia.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Budianto di dalam tulisannya “Anime, Cool Japan, dan Globalisasi Budaya Populer Jepang” yang terbit di Jurnal Kajian Wilayah Volume 06 Nomor 02 Desember 2015 menulis, anime merupakan cultural super power Jepang.
Pada 1970-an, Jepang sudah mengimpor serial anime ke Korea Selatan. Memasuki 1990-an, anime sudah tersiar di berbagai negara, termasuk Indonesia.
“Anak-anak generasi 1990-an yang sudah mengenal anime, kini telah beranjak dewasa dan mengekspresikan kesukaannya dengan membuat acara bertema Jepang,” kata Rahaditya saat dihubungi, Senin (17/6).
Beragam acara bertema Jepang memang diadakan di beberapa tempat. Di Jakarta misalnya, ada Nakama Festival yang digelar setiap tahun di Ancol, Jakara Utara, dan Ennichisai yang dihelat di Blok M Square, Jakarta Selatan.
Di kampus-kampus pun ada acara bertema Jepang. Misalnya, Harumatsuri di Universitas Muhammadiyah Hamka (UHAMKA), Jakarta, dan Isshoni Tanoshimimashou di Universitas Brawijaya. Di dalam acara bertema Jepang ini, bukan saja mengulik soal anime, tetapi juga cosplay.
"Cosplay memang sekadar hobi. Salah satu alasanya adalah menyukai anime dan karakternya. Jadi, perwujudannya melalui cosplay," ujar Rahaditya.
Menurut Lima Kamila Ramasari di dalam tulisannya “Presentasi Diri Pecinta Budaya Populer Jepang melalui Cosplay” di buku Komunikasi Budaya dan Dokumentasi Kontemporer (2019), cosplay dalam praktik komunikasi, bukan sekadar permainan kostum belaka.
Cosplay, tulis Lina, adalah hobi guna menyalurkan ekspresi diri. Selain dalih mengasah kreativitas, cosplayer biasanya berharap bisa terkenal.
“Dikarenakan cosplay ini merupakan aktivitas yang unik dan tidak biasa, bahkan terkadang mengundang tanggapan negatif dari pihak luar. Ya, bagi sebagian orang yang tidak memiliki hobi serupa dengan cosplay, kegiatan cosplay merupakan kegiatan yang aneh bahkan tidak jarang mendapat cibiran. Tak jarang dianggap sebagai sikap kaum muda Indonesia yang menandakan lunturnya kecintaan mereka terhadap budaya sendiri,” tulis Lina.
Satria dan Albi, yang menggemari ragam bentuk budaya populer Jepang kerap disebut dengan istilah wibu. Secara harfiah, wibu—dalam bahasa Inggris weaboo—adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang yang sangat cinta dengan budaya Jepang.
Akan tetapi, Albi menolak disebut wibu. “Ada beberapa orang tidak suka dipanggil wibu, lebih enak panggil otaku,” ujar Albi.
Menurut Albi, istilah wibu dan otaku berbeda. Baginya, wibu menggambarkan seorang pecinta budaya Jepang, sedangkan otaku mendefinisikan kegemaran atau hobi tertentu yang bersinggungan dengan budaya populer Jepang.
Albi mengatakan, istilah wibu baru ramai sekitar tahun lalu. Sementara Satria percaya, istilah wibu kondang berkat Youtuber Ericko Lim. Di akun Youtube-nya, Ericko membuat beberapa video terkait wibu.
Rahaditya menuturkan, istilah wibu dan otaku memang disematkan untuk para penggemar budaya populer Jepang. Namun, kedua istilah itu secara harfiah sebenarnya tak berarti penggemar budaya populer Jepang.
Otaku, kata Rahaditya, sebenarnya dalam bahasa Jepang artinya mengacu pada rumah. "Sedangkan wibu, secara akademisinya belum ada yang membahas, sehingga tidak tahu itu istilah apa," kata Rahaditya.