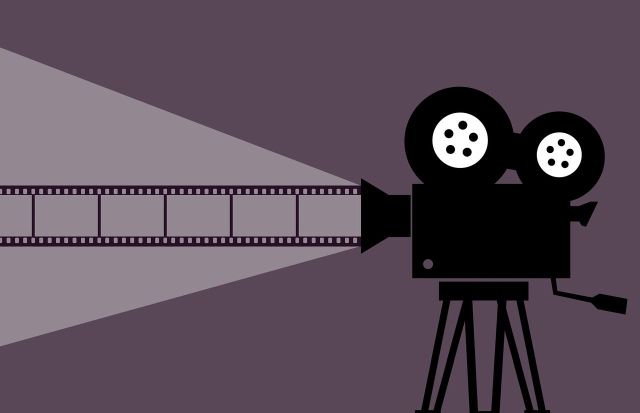Sultan Agung: Drama tanggung dan ambisi Hanung
"Sultan Agung" adalah usaha ke-6 sutradara Hanung Bramantyo membuat karya biopik. Film-film yang berkisah tentang kerajaan di Indonesia masih terbilang relatif sedikit jumlahnya dibandingkan dengan drama-drama percintaan. Walaupun mengambil kisah sejarah kerajaan Mataram, tentu kita tak boleh percaya sepenuhnya pada apa yang terjadi di film.
Cerita dari "Sultan Agung" sendiri bermula dengan kisah Mas Rangsang (Marthino Lio) yang menimba ilmu di Padepokan Jejeran dengan berguru kepada Kyai Jejer (Deddy Sutomo). Di padepokan tersebut, ia berjumpa dengan cinta masa remajanya, Lembayung (Putri Marino).
Ia terpaksa meninggalkan Lembayung karena ayahnya Panembahan Hanyokrowati wafat. Mas Rangsang pun tak bisa menolak permintaan Ki Juru Mertani (Landung Simatupang) yang memintanya naik sebagai raja. Pasalnya, jika kekuasaan jatuh pada Pangeran Martopuro yang memiliki keterbatasan mental, Mataram bakal tamat.
Mas Rangsang akhirnya naik takhta, dengan nama Susuhunan Hanyokrokusumo (Ario Bayu). Scene beralih dan raja baru tersebut langsung menghadapi dua utusan VOC yang menawarinya bekerja sama, permintaan bekerja sama itu ditolak mentah-mentah oleh Susuhunan Hanyokrokusumo. Di situ ia mencium niat buruk VOC yang bakal menjadikan Mataram sebagai budak mereka.
Di titik itulah, Susuhunan Hanyokrokusumo memutuskan menyerang Batavia dengan mengirim segenap tentara Mataram serta rakyat jelata yang terkena wajib militer. Dua gelombang penyerbuan yang dilakukan Susuhunan Hanyokrokusumo menemui kegagalan. Berbulan-bulan lamanya proses tersebut ditampilkan oleh hanung dengan perdebatan, keragu-raguan, dan pengkhianatan.
Walaupun menemui kegagalan, Susuhunan tetap teguh dan tak kehilangan akal. Ia memerintahkan tentaranya mencemari sungai Ciliwung dengan mayat-mayat busuk yang menyebabkan wabah kolera. Susuhunan berkeyakinan jika aksi tersebut bukanlah untuk tujuan jangka pendek semata, tetapi untuk anak-cucunya hingga ratusan tahun mendatang.
Susuhunan berkali-kali menegaskan dalam film jika kita bukanlah bangsa budak dan tak sudi diinjak-injak martabatnya. “Mukti utowo mati” menjadi jargon Susuhunan menyemangati bala tentaranya.
Saya yang menikmati film ini di awal menjadi skeptis di tengah-tengah hingga akhir film. Sampai di tengah film, pengembangan karakter Sultan Agung yang perlahan berubah menjadi dingin saya sambut antusias. Alasannya, tak banyak film Indonesia yang berani mengorbankan protagonis utamanya perlahan berubah menjadi antagonis seperti di Citizen Kane (1941) atau There Will Be Blood (2007).
Sayangnya, Sultan Agung tak menghadirkan hal itu dan ekspektasi saya berlebihan. Di akhir film, Sultan Agung tetaplah digambarkan sebagai orang yang baik budinya. Padahal, Ario Bayu memiliki potensi untuk menjadi raja yang dingin dengan ego yang besar.
Commodus sebagai antagonis pun tak hanya sekali dua kali lewat lalu tertawa seperti Jan Pieterszoon Coen di Sultan Agung. Penggambaran karakter Jan Pieterzoon Coen pun masih sekelas tokoh antagonis di sinetron, terlalu hitam-putih dan tak penting.
Walaupun terdapat intrik drama, jangan berharap akan menemui konflik seperti dalam Gladiator. Adegan dalam Sultan Agung seolah melompat terlalu cepat, dari scene satu ke yang lainnya, seakan fokus Hanung terbelah. Intrik, taktik, pengkhianatan, atau apapun yang dihadirkan Hanung dalam Sultan Agung jadi terasa nanggung dan tidak maksimal. Apapun yang dibangun Hanung setelah drama percintaan Mas Rangsang dan Lembayung muda tampak berantakan.
Dari tengah hingga akhir film, terlalu banyak tokoh yang muncul dengan dialog yang tidak terlalu kuat. Istri Susuhan atau Ratu Batang (Anindya Putri) misalnya muncul hanya sekadar muncul tanpa dialog kuat. Ia pun digambarkan tak memiliki konflik dengan siapapun atau menjadi tokoh yang berpengaruh bagi Susuhunan. Ratu Batang hanya berguna memberikan anak bagi Susuhunan dan menemani Susuhunan makan.
Yang membekas selain percintaan Mas Rangsang dan Lembayung muda adalah akting Ario Bayu sebagai Sultan Agung itu sendiri. Sorot matanya yang tajam, suaranya yang gahar, membuat peran ini seolah memang ditakdirkan untuknya. Sayangnya, akting Ario Bayu yang mumpuni mesti berakhir menjadi sesuatu yang klise.
Peperangan melawan VOC juga terasa kurang menggigit dengan koreografi yang biasa saja. Ketika pasukan Mataram mengepung benteng VOC dan kalah, bagaimana perjuangan Lembayung dan kawan-kawan berhasil keluar dari gerbang benteng yang dikunci tak ditampilkan oleh Hanung, alih-alih scene langsung meloncat ke tenda pasukan di hutan.
Ada beberapa kejanggalan yang mengganggu saya sewaktu menonton film ini. Yang pertama adalah penggunaan Bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang di film berlatar tahun 1600-an. Penggunaan Bahasa Indonesia tersebut membuat saya bertanya-tanya, apakah memang Bahasa Indonesia yang banyak diserap dari bahasa Melayu telah sampai di tanah Mataram dan digunakan sebagai bahasa percakapan sehari-hari pada medio 1600-an?
Suara sumbang memang sudah sering didapatkan Hanung ketika ia menggarap film berjenis biopik. Banyak yang menuduh Hanung terlalu malas melakukan riset. Hal mengganggu lainnya dari film ini adalah pemilihan cahaya yang tampak tak alami. Hutan tropis yang semestinya remang-remang menjadi tampak terlalu terang di malam hari.

Terakhir, yang mengganggu adalah alis dari Lembayung dewasa atau Adinia Wirasti. Siapapun yang menonton Sultan Agung dan memerhatikan alis Lembayung dewasa, tentu akan langsung tahu jika alis tersebut digambar, tampak tak alami di zaman kerajaan seperti itu dan tak masuk ke logika. Bagaimana bisa pendekar masih sempat menggambar alis ketika perang akan dimulai.
Mungkin, yang mesti dihargai adalah bagaimana Hanung menampilkan sisi patriarkis yang coba dilawan Lembayung dengan ikut dalam perang melawan VOC. Hanung menunjukkan betapa tidak setaranya Mataram pada perempuan. Hanung, setidaknya membuat saya bersimpati pada Lembayung yang ikut berperang dan diremehkan jenderal-jenderal Mataram.
Dengan kualitas sejumlah film biopik garapan Hanung yang kerap berantakan, apakah kita masih layak menonton karya ia berikutnya? Yang jelas, saya khawatir jika "Bumi Manusia" karya Pramoedya Ananta Toer akan berakhir seperti "Sultan Agung" di tangan sineas ini.