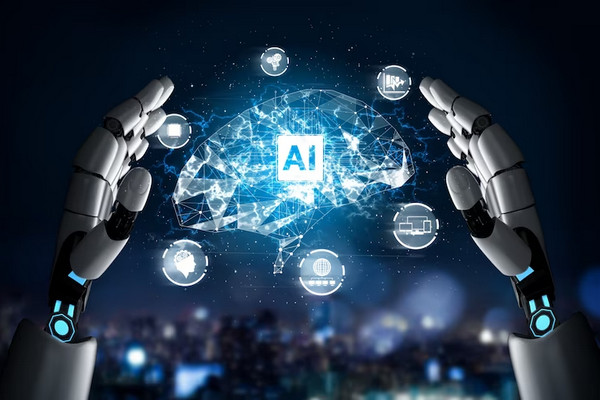Urgensi regulasi terkait AI
Pada Juni 2023, Uni Eropa mengambil langkah cepat menerapkan aturan soal cara perusahaan menggunakan teknologi artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Dikutip dari CNN, ini adalah aturan pertama soal AI di dunia dan diharapkan bisa membuka jalan bagi standar penggunaan teknologi global, mulai dari chatbot seperti ChatGPT hingga deteksi penipuan di bank dan prosedur bedah.
Sejumlah negara pun mulai berusaha mengatur AI. Australia misalnya, pada April lalu tengah berkonsultasi dengan badan penasihat sains di negara itu demi mempertimbangkan langkah berikutnya. China juga mengeluarkan tindakan sementara mengelola industri AI.
Amerika Serikat lebih progresif. Pada akhir Oktober lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengeluarkan peraturan presiden atau executive order untuk mengatur AI.
Dikutip dari Mashable, tiga dari 10 mandat Joe Biden dalam executive order, antara lain pengembangan sistem AI harus membagikan hasil dari pengujian keamanan teknologinya ke pemerintah, pengujian keamanan teknologi AI mesti memenuhi standar tinggi yang ditetapkan National Institute of Standards Technology, dan perusahaan wajib mengutamakan keamanan dalam pengembangan model AI untuk sains dan proyek yang terkait biologi.
Bagaimana dengan Indonesia?
Berbicara dalam Forum Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika (FEDK) VI di Jakarta, Selasa (31/10), Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Mira Tayyiba menyatakan, datangnya teknologi baru, seperti AI, perlu dipelajari dahulu. Jika memang dibutuhkan, bakal ada regulasi.
Pemerintah tengah menyusun Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial tahun 2020-2045. Menurut Mira, dokumen itu menggarisbawahi pentingnya pengembangan dan penerapan AI yang beretika dan menekankan pengaturan kebijakan terkait AI.
Banyak negara khawatir AI bisa melakukan berbagai pelanggaran. Semisal pencurian data dan privasi. Di samping ada pula kekhawatiran AI bisa mengambilalih pekerjaan. Apalagi, teknologi itu kian populer dengan munculnya ChatGPT yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, regulasi soal AI ada dua jenis. Pertama yang bersifat sukarela, yakni etika. Kedua, yang bersifat “memaksa”. Ia menjelaskan, dalam strategi nasional tentang kecerdasan buatan ada empat yang ditekankan.
“Satu itu adalah infrastruktur dan data harus kita siapkan. Kedua, pengembangan talenta. Ketiga, etika dan kebijakan. Keempat, adalah pengembangan industri dan riset,” ujar Usman kepada Alinea.id, Senin (16/10).
“Nah, etika ini sedang kita susun. Jadi, sedang menyusun regulasi yang (sifatnya) sukarela tadi.”
Regulasi etika, kata Usman, tengah disusun biro hukum Kemenkominfo. Sementara regulasi yang “memaksa” bentuknya peraturan perundang-undangan. Usman menyebut, sebenarnya sudah ada regulasi terkait AI yang sifatnya memaksa. Misalnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Kemudian terakhir, (ada) Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur pemisahan antara e-commerce dan media sosial. Itu juga sebetulnya pengaturan di bidang AI,” ujarnya.
“Jadi, sudah ada. Dan saya kira, akan lahir ya undang-undang baru (soal AI).”
Ketua Cyber Law Center Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran (Unpad) Sinta Dewi mengatakan, regulasi terkait AI sangat penting. “Diperlukan aturan etika dulu,” ujarnya, Jumat (3/11).
Ia menuturkan, yang mengurus aturan soal AI cukup satu lembaga di bawah satu kementerian, semisal Kemenkominfo, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian, atau (Kemenperin). Bisa pula di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Standar etika yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan responsibility,” tuturnya.
Sementara itu, co-founder dan spesialis pemeriksa fakta Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Aribowo Sasmito mengatakan, regulasi soal AI cukup penting. Namun, menurutnya, yang jadi masalah adalah regulasi kerap tertinggal dengan inovasi.
“Contohnya berkaitan dengan ojek atau taksi daring. Regulasi kesulitan mengatur karena aplikator bukan perusahaan transportasi, tetapi memiliki armada,” kata dia, Rabu (1/11).
“Di beberapa negara lainnya regulasi juga kesulitan mengikuti (inovasi).”
Meski begitu, Aribowo menegaskan, diregulasi atau tidak, tak akan secara signifikan bisa mengurangi dampak negatif AI. Salah satunya penyebaran hoaks. Alasannya, jika disebarkan di ranah daring, kesulitannya ada berbagai cara untuk menghindar dari aturan atau regulasi.
“Menggunakan akun palsu misalnya. Bukan berarti tidak perlu diregulasi karena sekecil apa pun hasil dari regulasi, masih lebih baik daripada tanpa berupaya apa pun,” kata Aribowo.
Aribowo menyarankan, sebaiknya regulasi terkait AI tetap bisa menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sedangkan tindakan dalam bentuk hukuman adalah upaya terakhir.
“Karena meskipun upaya hukum efektif (tangkap, sidang, penjara), tetapi efektifitasnya sifatnya instan atau jangka pendek,” ujarnya.
“Efektifitas jangka panjang yang terbaik adalah dengan cara edukasi, sehingga masyarakat paham untuk membedakan konten asli atau hasil buatan AI.”