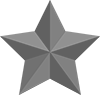Kejujuran menjadi kunci dalam memoar Paul Kalanithi, "When Breath Becomes Air" (WBBA). Sebelum menjadi pasien kanker, Paul adalah seorang ahli bedah saraf dengan prestasi mentereng. Hanya tinggal menunggu hitungan waktu saja, ia akan menyelesaikan pelatihannya dan mendapat promosi. Namun, dalam usia yang masih muda, 36 tahun, ia menjalani dua eksistensi sekaligus. Di satu waktu ia jadi ahli bedah saraf yang mengobati pasien, di lain sisi ia pasien yang mencoba bertahan hidup.
Pengalaman Paul mungkin akan terasa mengganggu, ketika pembaca tahu penulisnya sedang sekarat dan di akhir buku kita akhirnya tahu Paul mati. Namun, Paul menulis memoarnya dengan sangat baik. Ia tak mencoba mengasihani diri, mendramatisir kanker dan kematian, atau mendadak menjadi motivator kehidupan dengan memoarnya.
Secara jujur, Paul menulis kanker telah menghancurkan hidup dan karirnya. Paul sadar jika hidup seorang pasien tidak akan pernah sama lagi usai vonis penyakit mematikan dijatuhkan. Hal itu telah dipelajarinya jauh-jauh hari ketika ia masih menjadi dokter.
Paul menuliskan pengalaman hidupnya sejak masa kanak-kanak di WBBA. Sejak kecil ia dicekoki ibunya dengan bacaan-bacaan sastra babon, seperti karya T.S. Eliot, Aldous Huxley, Alexandre Dumas, dan masih banyak lagi. Paul menulis memoar ini dengan mengalir mengikuti masa kecilnya sebagai keluarga imigran India yang tinggal di Amerika, hingga ia masuk ke Universitas Stanford dan Universitas Yale.
Ia memiliki karir yang menarik untuk ditengok. Di masa mudanya, ia terobsesi dengan dunia sastra dan mengambil jurusan Sastra Inggris serta Biologi Manusia saat berkuliah di Stanford University. Setelahnya, ia mengambil master dalam sejarah dan filsafat di Cambridge University.
Dengan mengambil kuliah-kuliah tersebut, ia berharap menemukan jawaban yang bisa membuat hidupnya menjadi bermakna. Khususnya, dari studi-studi terhadap penulis, seperti T.S. Eliot dan Vladimir Nabokov. Namun, yang ia temukan hanya kekecewaan atas krisis eksistensialnya.
Paul menulis, “Saya sudah menghabiskan begitu banyak waktu untuk belajar sastra di Stanford dan sejarah pengobatan di Cambridge, untuk membantu saya memahami kematian lebih baik, tetapi saya hanya mendapatkan perasaan tak mengetahui apa-apa tentang mereka.”
Selepas itu, ia masih terus mencari jawaban atas pertanyaannya, “Apa yang membuat hidup layak dijalani di hadapan kematian? Apa yang Anda lakukan saat masa depan tak lagi menuntun pada cita-cita yang diidamkan, melainkan pada masa kini yang tanpa akhir? Apa artinya memiliki anak, merawat kehidupan baru saat kehidupan lain meredup? Apa yang membuat hidup manusia bermakna, meskipun mereka tahu suatu saat akan mati dan membusuk?” Pertanyaan-pertanyaan seputar eksistensi manusia itulah yang dihadapi Paul di memoarnya ini.
Paul akhirnya memutuskan menjadi ahli bedah saraf karena ingin menemukan jawaban atas pertanyaannya, “Apa yang benar-benar bermakna dalam kehidupan.” Bedah saraf sendiri di Amerika memiliki reputasi sebagai spesialisasi yang paling sulit. Bosnya bahkan sampai mengatakan jika “dokter bedah saaraf bukan hanya ahli bedah terbaik, tetapi juga dokter terbaik di rumah sakit.” Bosnya juga menyarankan Paul untuk makan dengan tangan kirinya, agar ia mahir menggunakan kedua tangannya, atau ambidextrous.
Transisi yang dituliskan Paul dari pria sehat yang menjadi sekarat digambarkan dengan dirinya yang kuat menanggung 100 jam kerja per minggu, berubah menjadi ringkih. Waktu memang tak memihak Paul. Ia menulis, “Sebelum kanker saya didiagnosis, saya tahu suatu hari saya akan mati, tetapi saya tidak tahu kapan. Setelah diagnosis, saya tahu suatu hari saya akan mati, tapi saya tidak tahu kapan.”

Paul, istri, dan anaknya./ Furnishmyway
Memoar Paul mendesak pembaca jika kita selalu menghadapi ketidakpastian dan kematian setiap harinya, sama seperti Paul. Pertanyaan yang sebenarnya kita hadapi, tulis Paul, bukanlah seberapa lama, tetapi bagaimana kita akan hidup, dan jawaban-jawaban itu tidak ditemui Paul di buku-buku teks medis.
Memoar ini sendiri terbit sepuluh bulan setelah Paul meninggal. Lucy Kalanithi, istri Paul, menulis epilog dalam memoar ini. Jika Paul menulis secara filosofis tentang kehidupannya, Lucy membagi detail cerita dan emosinya saat merawat Paul. Walaupun memoar ini memiliki potensi untuk menjadi begitu muram, Paul membuat memoar lebih dari sebentuk perayaan kehidupan.
Untuk seorang dokter, tulisan Paul terasa mengalir. Keputusan Paul untuk kembali ke jalan agama di akhir hayatnya membuat kisahnya terdengar klise.