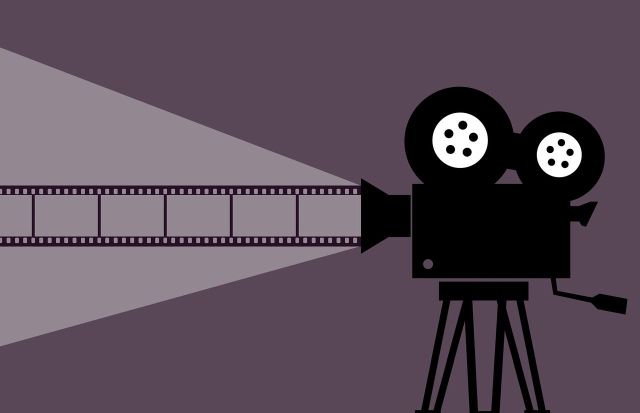Lonceng sensor orang tua
Dalam Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988), Romo Adelfio seminggu sekali mendatangi bioskop setempat. Sebelum sebuah film diputar di Giancaldo, Sicilia, Italia, ia akan memeriksanya. Bila muncul adegan ciuman, ia membunyikan lonceng. Tukang proyektor harus menggunting adegan itu. Begitulah, berkat lonceng sensor sang romo, orang Giancaldo belum pernah menyaksikan adegan ciuman di layar perak.
Lembaga Sensor Film (LSF) berperan mirip dengan Romo Adelfio bagi masyarakat penonton film di Indonesia. Lembaga ini bertugas menetapkan status edar film dan meluluskan sebuah film secara utuh atau setelah memotong bagian yang dianggap tidak layak untuk ditayangkan kepada umum. LSF juga menetapkan penggolongan usia penonton bagi film bersangkutan.
Tugas LSF relatif memudahkan orang tua dalam memilih film yang akan ditonton bersama anak. Masalahnya, di satu sisi, tidak sedikit orang tua yang mengabaikan penggolongan usia penonton bagi suatu film. Lumayan sering kita mendengar cerita tentang orang tua yang mengajak anak di bawah umur menonton film yang diperuntukkan bagi penonton dewasa.
Di sisi lain, penggolongan usia penonton kerap tidak cukup menggambarkan muatan dan kualitas film. Film yang direkomendasikan untuk “segala umur” biasanya ditandai oleh apa yang tidak terkandung di dalamnya: tidak ada kata-kata kasar, kekerasan, dan adegan seks. Sampai di situ masih cukup dimaklumi. Sayangnya, film semacam itu juga cenderung dibesut kurang serius. Kisahnya mudah ditebak, pesannya menggurui, dan secara teknis serba tanggung. Dengan kata lain, film yang kurang berkualitas.
Orang tua masih memiliki PR untuk mengembangkan sensor mandiri terhadap film tontonan anak. Bagaimana memilihkan film yang bukan hanya cocok bagi anak, tetapi sekaligus berkualitas?
Ada cara yang cukup merepotkan. Orang tua mesti menonton terlebih dahulu film yang bersangkutan. Langkah ini tentu menguras waktu dan dana ekstra. Namun, tidak ada salahnya dicoba, bukan?
Ada alternatif yang lebih ringan. Untuk film Barat, periksalah judul tersebut di situs seperti Kids-In-Mind, Common Sense Media, atau bagian Parents Guide di IMDb. Selain uraian tentang muatan film, biasanya tersedia juga ulasan tentang kualitas film bersangkutan. Jika perlu referensi tambahan, bacalah ulasan kritikus profesional, seperti yang bisa ditemukan di Metacritic.
Bagaimana orangtua dapat menjadi pendentang lonceng sensor yang arif dan cerdas bagi anak? Bagaimana memilihkan film yang berkualitas dan sekaligus mencerahkan bagi anak? Banyak pendekatan yang dapat dilakukan, tetapi tulisan ini hendak menawarkan dua pertimbangan yang saling melengkapi.
Pertama, film yang menampilkan protagonis anak belum tentu cocok untuk anak. Tidak sedikit film dengan protagonis anak, tetapi menyampaikan isu yang keras dan berat, yang selayaknya baru dikonsumsi oleh orang dewasa.
Film drama perang Turtles Can Fly (Bahman Ghobadi, 2004), misalnya. Seluruh jalinan kisahnya secara konsisten disorot dari sudut pandang anak—tentang nasib mereka sebagai pengungsi dalam perang di Irak. Pada klimaksnya, kita terkesima menyadari betapa keji neraka peperangan mencabik-cabik kepolosan mereka. Namun, apakah ini film anak? Sebagai orang tua, saya tidak tega mempertontonkannya pada anak yang belum akil balig.
Keluarga Cemara (Yandy Laurens, 2019) mengisahkan perjuangan keluarga Abah yang mendadak bangkrut. Meskipun melibatkan tokoh Cemara yang masih bocah, film ini cukup pelik untuk dicerna anak kecil. Namun, bagi mereka yang telah beranjak remaja, film ini dapat jadi pemantik diskusi yang menarik tentang dinamika kaya-miskin.
Kedua, orang tua justru ditantang untuk berani memaparkan realitas pada anak. Pandangan CS Lewis tentang buku anak yang baik tampaknya tepat pula diterapkan untuk film segala umur yang bagus.
Menurut Lewis, penulis cerita anak yang baik memperlakukan pembacanya secara serius. Menampilkan adegan kekerasan hanyalah salah satu perwujudannya. Ia bekerja menurut landasan yang sama, landasan kemanusiaan yang universal, yang dapat dipahami baik oleh anak maupun orang dewasa.
Pendekatan komunikasi semacam ini memberi ruang untuk menampilkan adegan “kematian, kekerasan, kesakitan, petualangan, kepahlawanan dan kepengecutan, kebaikan dan kejahatan” secara proporsional dan wajar. Jika tidak, menurut Lewis, kita justru “memberikan gambaran yang palsu kepada anak dan mencekoki mereka dengan escapisme (hiburan/khayalan untuk menghindari kenyataan hidup yang tidak menggembirakan).”
Dalam My Neighbor Totoro (Hayao Miyazaki, 1988), tokoh ibu digambarkan sakit. Kondisi ibu ini menjadi bagian penting dalam perjalanan cerita.
Lassie (Charles Sturridge, 2005) dipuji karena tidak memandang remeh anak. Sturridge berhasil menampilkan gambaran yang jujur tentang bagaimana anak berada di tengah orang dewasa, bagaimana mereka juga terpapar pada realitas hidup yang keras seperti pengangguran atau perang. Penonton tidak hanya diajak memahami pergumulan anak seusia mereka, tetapi juga belajar menyikapi masalah orang dewasa dan masalah binatang.
Orang tua diundang untuk arif dan cerdas dalam memilih dan memilah di antara kedua perbedaan itu. Di satu sisi, kita perlu melindungi anak kecil dari masalah orang dewasa, dari perkara hidup yang sukar dan tidak jarang membingungkan. Tidak membebani mereka dengan perkara yang terlalu berat untuk mereka tanggung.
Di sisi lain, melindungi anak bukan berarti mengisolasi mereka dari dunia. Sebaliknya, sejak dini orang tua mesti secara arif dan cerdas membekali dan mempersiapkan anak dalam menghadapi realitas hidup—secara proporsional dan wajar tadi. Pemilihan film yang tepat dan berkualitas dapat menjadi alat bantu untuk itu.