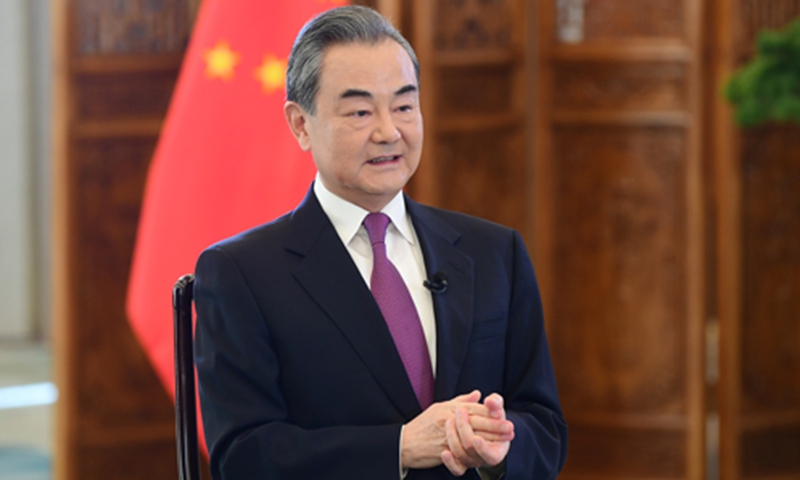Mengapa RI undang AS investasi di Natuna?
Kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo ke Indonesia pada 29 Oktober 2020 dimanfaatkan untuk menjajagi kerja sama bilateral kedua negara, khususnya dalam bidang investasi.
Menlu Retno Marsudi menawarkan AS untuk berinvestasi di Natuna dan pulau-pulau terluar Indonesia. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa di Natuna? Kenapa Indonesia tidak menawarkan proyek itu kepada China? Bukankah selama ini investasi di Indonesia lebih banyak didominasi China? Bahkan China menduduki peringkat kedua investasi di Indonesia setelah Singapura dan nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tulisan ini akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan tersebut.
Kunjungan Menlu AS ini hanya selang kurang dari dua minggu pascakunjungan Menhan Prabowo Subianto ke AS. Sempat memicu polemik, kunjungan Prabowo ke AS merupakan respons atas undangan Menhan AS Mark Esper. Melihat sikap AS yang belakangan mulai agresif mendekati Indonesia, hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, di mana pengaruh China kian meluas. Terlebih lagi melihat hubungan Indonesia-China yang kian ‘mesra’, AS tidak bisa membiarkan Indonesia sebagai mitra strategisnya jatuh terlalu jauh ke dalam pusaran pengaruh China. Kedatangan Mike Pompeo ke Indonesia, dengan demikian, tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik itu.
Tawaran investasi di Natuna kepada AS tidak bisa dibaca semata-mata dari perspektif ekonomi. Tawaran itu bukan dari dari Kementerian Perekonomian atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melainkan dari Kementerian Luar Negeri. Artinya, tawaran itu bisa dibingkai dalam kerangka kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia (foreign economic policy). Sebagai bagian dari kebijakan luar negeri, undangan investasi itu mengandung pertimbangan-pertimbangan politik di samping tentu saja ingin meraih keuntungan ekonomi.
Pemilihan Natuna sebagai wilayah yang ditawarkan Indonesia kepada AS bukan tanpa alasan. Yang paling menentukan adalah kawasan itu menjadi garis singgung (fault line) perseteruan Indonesia-China dalam isu Laut China Selatan. China kerap melakukan pelanggaran kedaulatan di Natuna dengan dalih kawasan itu merupakan traditional fishing ground. Di samping itu, pada peta 2009 yang dirilis pemerintah China, kawasan Natuna termasuk ke dalam ‘sembilan garis putus-putus’ (nine dash line) di mana hal ini bertentangan dengan hukum internasional (UNCLOS).
Pemerintah Indonesia tegas menentang kebijakan agresif China di Natuna. Meskipun demikian, Indonesia tidak menggunakan pendekatan koersif, misalnya penggunaan kekuatan militer untuk merespon maupun mencegah China memasuki ZEE Indonesia. Di samping kekuatan militer Indonesia ‘tidak ada apa-apanya’ secara relatif dibanding kekuatan militer China, kedua negara menjalin hubungan bilateral yang cukup erat terutama sejak era pemerintahan Jokowi. Itulah sebabnya hubungan Indonesia-China diwarnai oleh ambiguitas. Di satu sisi erat secara ekonomi tetapi di sisi lain agak tegang secara politik-keamanan.
Indonesia tidak mau secara head to head menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengancam kepentingan ekonominya dengan China. Oleh sebab itu, Indonesia memilih pendekatan yang dianggap lebih ‘aman’ dari sisi geopolitik dan geostrategis. Mengundang AS berinvestasi di Natuna adalah gesture diplomasi bahwa Indonesia bermaksud mengimbangi dominasi China di kawasan Laut China Selatan melalui strategi soft balancing.
Strategi ini mengacu pada opsi diplomatik untuk mengimbangi musuh dengan cara nonkoersif, seperti menjalin koalisi secara diam-diam dengan negara lain dalam rangka menetralisir atau mencegah dominasi negara lain (Paul, Wirtz and Fortmann, 2004). Soft balancing dibedakan dengan hard balancing, di mana lebih menonjolkan pada cara-cara nonmiliter dan pola hubungan menang-kalah (zero sum game).
Dengan menghadirkan kekuatan pengimbang China di Natuna, Indonesia tidak perlu repot-repot menghadapi China ketika negara itu mulai menunjukkan sikap agresif di kawasan. Dengan kata lain, Indonesia melimpahkan ‘tugas’ melindungi kawasan Natuna kepada kekuatan adidaya lain, yakni AS.
Dalam literatur ilmu hubungan internasional, strategi ini dikenal dengan ‘buck-passing’, yaitu suatu negara menyerahkan tanggung jawab membendung ancaman kepada negara lain (Mearsheimer, 2001). Paribahasa Jawa menyebut strategi ini dengan ‘nabok nyilih tangan’ yang secara harfiah berarti “memukul dengan meminjam tangan orang lain.” Strategi ini akan menghindarkan si pelaku dari tanggung jawab.
Strategi ini terlihat cerdas. Pertama, Indonesia jelas tidak perlu lagi bersitegang secara frontal dengan China. Mengingat sudah sering sekali China melakukan pelanggaran wilayah di Natuna, Indonesia merasa frustrasi sebab nota protes diplomatik, kecaman, maupun ‘diplomasi kapal meriam’ (gunboat diplomasi) yang selama ini diterapkan Indonesia tak efektif meredam agresifitas China. Kedua, AS tentu tidak akan membiarkan China mengganggu kawasan Natuna karena (jika investasi terealisasi) terdapat aset-aset nasional AS yang harus dilindungi di kawasan itu. Bisnis di luar negeri merupakan kepentingan vital AS sehingga mengganggu kepentingan ini sama saja menabuh genderang perang. Dengan logika ini, China akan berpikir berkali-kali untuk mengganggu Natuna.
Namun demikian, strategi ini bukannya tidak mengandung kelemahan. Risiko terbesar adalah perang antar negara adidaya di Laut China Selatan. Mengundang AS ke wilayah konflik sama saja membenturkan dua kekuatan adidaya untuk berebut dominasi. Selama puluhan tahun AS sudah melibatkan diri di Laut China Selatan karena kawasan itu merupakan jalur penting bagi pelayaran internasional. Kepentingan AS menjamin kebebasan bernavigasi di Laut China Selatan.
Menghadirkan AS di Natuna berpotensi memperuncing rivalitas China dan AS. Konsekuensinya, kebijakan itu juga berisiko merenggangkan hubungan Indonesia-China karena Indonesia dianggap tidak konsisten dalam isu Laut China Selatan. China berharap Indonesia dapat menyelesaikan masalah Natuna secara bilateral, tidak perlu melibatkan negara lain. Kehadiran AS di Natuna justru semakin mempertajam perbedaan kedua negara yang akan berimplikasi pada banyak hal, terutama prospek stabilitas dan perdamaian di Laut China Selatan.