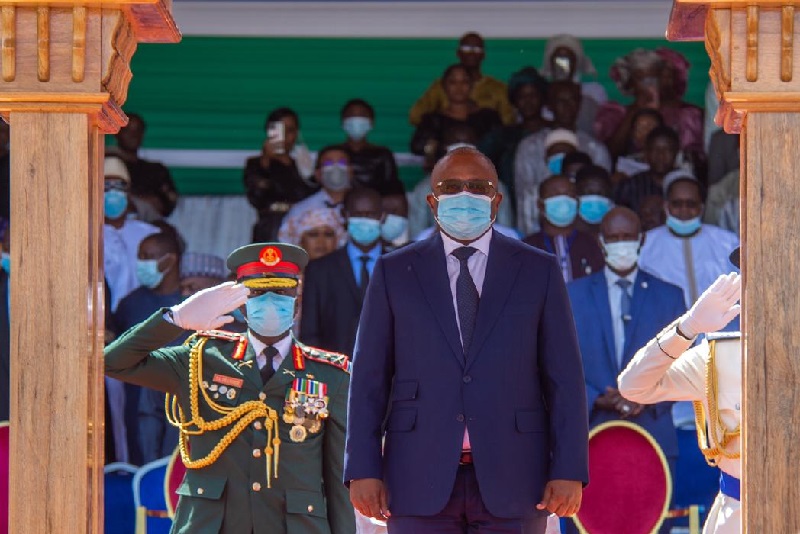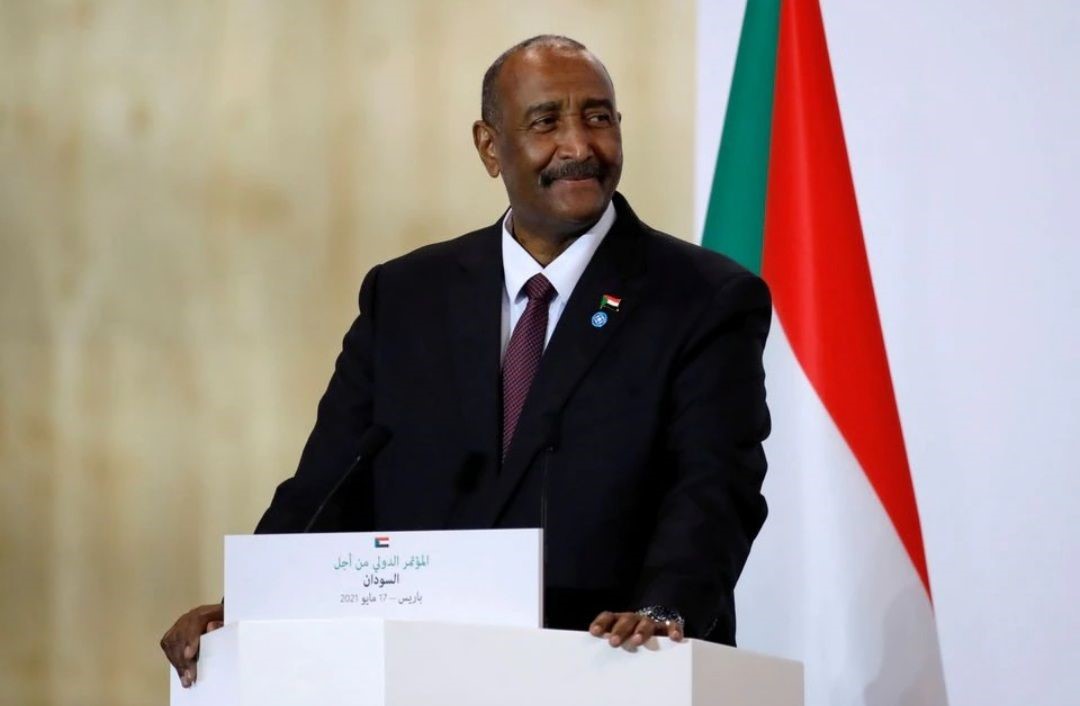Peluang intervensi militer di Myanmar
Kekerasan aparat keamanan Myanmar terhadap para demonstran prodemokrasi kian menjadi-jadi. Puluhan nyawa telah menjadi korban. Banyak video yang beredar menunjukkan aksi kekerasan aparat kepada warga sipil. Dengan kekuasaan masih dipegang kubu militer, stabilitas keamanan di Myanmar tampaknya masih sulit dikatakan kondusif selama beberapa waktu ke depan.
Dunia internasional tidak tinggal diam menyikapi hal itu. Negara-negara Barat menerapkan kebijakan sanksi ekonomi dengan harapan memaksa Myanmar untuk menghentikan aksi kekerasan.
Sementara itu, Indonesia dan ASEAN memilih pendekatan yang lebih lunak dengan upaya diplomasi senyap (quiet diplomacy). Indonesia berharap pemerintahan junta militer Myanmar bersedia menahan diri dari cara-cara kekerasan.
Akan tetapi, semua pendekatan itu tampaknya tak membuahkan hasil. Pihak militer bergeming pada pendiriannya. Aksi kekerasan juga terus berlanjut. Kubu prodemokrasi mendesak komunitas internasional menerapkan R2P (Responsibility to Protect) untuk memberi lampu hijau bagi intervensi militer. Kyaw Moe Tun, Duta Besar Myanmar untuk PBB dalam pidatonya 26 Februari meminta dunia internasional melakukan segala cara untuk melawan junta militer. Akibat pernyataannya itu, ia dipecat dari kedudukannya di PBB.
Memahami R2P
Sebenarnya apa itu R2P yang diminta kubu prodemokrasi di Myanmar? R2P adalah suatu norma internasional yang mengatur tentang tata laksana pencegahan kejahatan negara terhadap warganya sendiri. Norma ini diadopsi PBB pada 2005 namun bukan sebagai hukum internasional yang mengikat (nonbinding). R2P lebih mencerminkan komitmen internasional untuk melindungi hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan negara. Fokus pencegahan R2P adalah kejahatan berat, yaitu genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnis.
Prinsip dasar R2P adalah gagasan bahwa kedaulatan merupakan tanggung jawab (sovereignty is responsibility). Adalah Kofi Annan, Sekretaris Jenderal PBB periode 1997-2006 yang mencetuskan ide perlunya perubahan definisi kedaulatan dari hak istimewa negara ke tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya (Annan, 1999). Selama berabad-abad, konsep kedaulatan selalu diasosiasikan dengan kebebasan negara melakukan apapun yang dikehendaki selama masih di dalam wilayahnya, termasuk melakukan tindak kekerasan kepada warga negara atas nama keamanan nasional, stabilitas, dan sejenisnya.
R2P memiliki tiga pilar yang secara praktis diterapkan secara bertahap. Pilar pertama adalah prinsip bahwa setiap negara bertanggung jawab melindungi warga negaranya dari empat kejahatan berat yaitu genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnis. Pilar kedua berbunyi, komunitas internasional turut serta membantu negara dalam melaksanakan tanggung jawab itu apabila negara bersangkutan tidak mampu. Pilar ketiga, jika suatu negara gagal melaksanakan tanggung jawab itu (artinya membiarkan terjadinya empat kejahatan berat tadi atau jusrru menjadi pelakunya), maka komunitas internasional harus melakukan aksi kolektif untuk menghentikannya sesuai Piagam PBB (ICISS, 2001).
Dalam konteks kekerasan yang terjadi di Myanmar, Pilar I sudah dilanggar. Junta militer telah melakukan tindak kejahatan yang tergolong kejahatan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998. Menurut aturan itu, kejahatan kemanusiaan diartikan sebagai “serangan sistematis atau meluas kepada warga sipil.” Sedangkan Pilar II R2P sejatinya sudah diterapkan Indonesia melalui pendekatan diplomasi senyap. Indonesia percaya diri menggunakan pendekatan ini karena dinilai ‘cukup berhasil’ ketika menangani isu Rohingya. Sayangnya, pendekatan ini agaknya kurang efektif untuk menghadapi kerasnya pendirian pihak junta militer.
Sekarang tersisa Pilar III, yakni aksi kolektif dunia internasional. Pilar ketiga ini kerap diasosiasikan dengan aksi militer. Padahal penggunaan kekuatan militer adalah opsi terakhir (the last resort) apabila seluruh opsi gagal. Aksi kolektif yang dimaksud di dalam Pilar III sebenarnya beragam, mulai dari aksi diplomatik, kemanusiaan, sampai penggunaan sarana militer. Dalam konteks Myanmar, langkah diplomatik Indonesia sebenarnya juga sudah konsisten dengan Pilar III ini. Namun semuanya tampak sia-sia sejauh ini. Alhasil, tuntutan kelompok pro-demokrasi terdengar masuk akal.
Kendala implementasi R2P
Meskipun aspirasi kubu prodemokrasi Myanmar untuk mengimplementasikan R2P begitu kencang, namun pelaksanaan R2P memerlukan mandat DK PBB. Tidak diperkenankan negara individual atau aliansi militer internasional melakukan R2P karena bertentangan dengan Piagam PBB.
Namun justru karena inilah maka R2P cukup sulit diterapkan di Myanmar. Pertama, DK PBB dipastikan akan kesulitan mengeluarkan resolusi yang memberi restu pelaksanaan R2P. Hal ini lebih dikarenakan kendala klasik. Di tubuh DK PBB, Rusia dan China memiliki sikap yang cenderung bertentangan dengan negara-negara Barat lainnya seperti AS, Inggris, dan Prancis. Sudah barang tentu resolusi DK PBB menyangkut isu Myanmar bakal diveto oleh Rusia dan China. Hal ini bukannya tanpa preseden. Pada 2017, kedua negara ini juga menghalangi resolusi dewan yang menyebut kekerasan terhadap etnis Rohingya sebagai kejahatan kemanusiaan dan pembersihan etnis.
Kedua, tidak adanya kepentingan strategis Barat di Myanmar. Intervensi militer dalam kerangka R2P kerapkali dilakukan oleh negara-negara Barat. Afrika adalah kawasan dimana R2P paling banyak diimplementasikan. Libya misalnya, yang pada 2011 DK PBB memberi mandat dilakukannya intervensi militer dengan pelaksana utama adalah NATO. Sejumlah pakar mensinyalir Barat berkepentingan atas kekayaan minyak Libya dan ambisi untuk mendongkel Moammar Khadafi karena dianggap ‘duri dalam daging’ oleh negara-negara Barat. Kontras dengan itu, Myanmar tidak terlalu menjanjikan keuntungan strategis bagi Barat.
Ketiga, intervensi militer tidak memiliki preseden di kawasan Asia Tenggara. Prinsip non-intervensi yang diadopsi ASEAN menjadi norma hubungan antarnegara yang sangat dijunjung tinggi. Keterlibatan Barat di kawasan ini (pasca Perang Dingin) hanya sebatas menjalin hubungan diplomatik dan pertahanan dengan beberapa negara anggota ASEAN. Keterlibatan AS di kawasan ini juga hanya terkait isu sengketa Laut China Selatan. Kecuali itu, intervensi militer pernah terjadi di Timor Timur pada 1999-2000 tetapi itupun merupakan bentuk dari operasi penjagaan perdamaian (peacekeeping operation) PBB dan bukan R2P mengingat R2P baru diadopsi PBB pada 2005.
Keempat, intervensi militer dapat memperburuk keadaan Myanmar. Penerapan R2P terutama Pilar III tentang penggunaan cara-cara koersif untuk menghentikan kekerasan terhadap penduduk sipil sangat beresiko. Meskipun alasannya kemanusiaan, namun intervensi militer berpotensi meminta korban jiwa jauh lebih banyak. Salah satu pelajaran penting dari penerapan intervensi militer dalam bingkai R2P di Libya oleh NATO adalah meningkatnya eskalasi konflik antara kubu pemerintah melawan pemberontak. Kelompok pemberontak akan meningkatkan perlawanan kepada pemerintah untuk mengundang intervensi asing sehingga tujuan politik mereka akan tercapai yaitu menumbangkan status quo (Kuperman, 2013).
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa intervensi militer di Myanmar kecil kemungkinan akan terlaksana. Dunia internasional, terutama negara-negara Barat, lebih memilih pendekatan ‘jalan tengah’ dengan penerapan sanksi ekonomi yang lebih keras ketimbang mengirim pasukan ke Myanmar. Indonesia dan ASEAN lebih memilih langkah-langkah diplomatik sesuai dengan ciri khas mereka. Meski mereka tahu bahwa aneka strategi itu tidak efektif, setidaknya hal itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Sebagaimana pernyataan Edmund Burke, negarawan Irlandia abad-18 yang tersohor, “the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.”