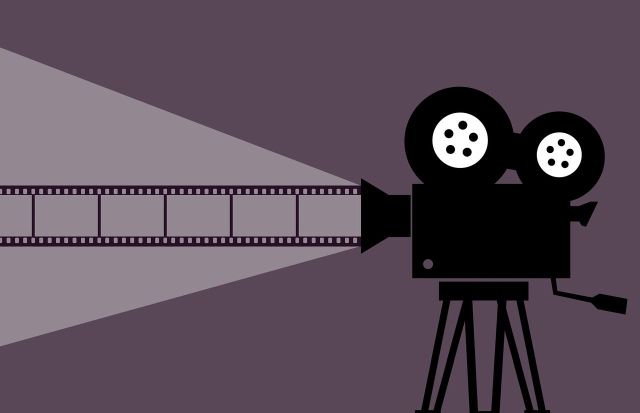Sila Pancasila dalam kisah sebuah keluarga
*Penulis, penerjemah, editor, dan tukang nonton.
Pemantik angan itu tak lain dua paket karya gemilang Krzyztof Kieślowski, sutradara Polandia, "Dekalog" (1988-1989) dan trilogi "Three Colors" (1993-1994). "Dekalog" adalah sepuluh drama seri televisi, masing-masing berdurasi satu jam, yang diinspirasi oleh Sepuluh Perintah Allah dalam Kitab Keluaran. Adapun "Three Colours" adalah tiga film berdasarkan tiga warna bendera Republik Prancis (biru, putih, merah) yang melambangkan semboyan negara itu: kemerdekaan, kesetaraan, dan persaudaraan.
Kedua paket film itu sama-sama merupakan penafsiran yang longgar atas sumbernya. "Dekalog" tidak menyodorkan khotbah moralis hitam-putih; "Three Colours" juga tidak berisi ceramah tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik. Sebaliknya, keduanya menawarkan cerita memikat tentang tokoh-tokoh yang mesti bergelut dengan tantangan etis yang nyata, pelik, dan ironis.
Dalam film kedua "Dekalog", misalnya, seorang perempuan mendatangi dokter, bertanya apakah suaminya yang sedang sakit akan mati atau bertahan hidup. Jika suaminya sembuh, ia akan melakukan aborsi. Jika suaminya mati, ia akan mempertahankan kehamilannya. Perempuan ini mengandung benih laki-laki lain.
Ada pula model yang lebih rileks. Film komedi India "Lage Raho Munna Bhai" (Rajkumar Hirani, 2006) menampilkan Munna Bhai yang dapat melihat roh Mahatma Gandhi. Melalui interaksinya dengan Gandhi ini, ia mulai menerapkan ajaran Gandhi untuk menolong orang-orang di sekitarnya memecahkan masalah mereka.
Nah, mungkin ada sutradara Indonesia yang tertarik mengambil langkah serupa, menggarap lima film berdasarkan masing-masing sila Pancasila? Atau, menghadirkan sosok Soekarno dalam latar kekinian, berdialog dengan anak muda era milenial, bersama-sama menggumuli isu-isu kontemporer dalam terang nilai-nilai Pancasila?
Menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila 2018, angan itu terjawab. Beredar "Lima", sebuah film yang berangkat dari lima sila ideologi negara kita: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Film ini dikerjakan secara keroyokan oleh lima sutradara, yaitu Shalahuddin Siregar, Tika Pramesti, Lola Amaria, Harvan Agustriansyah, dan Adriyanto Dewo.
Berbeda dari "Dekalog" dan "Three Colours", "Lima" tidak menafsirkan tiap sila Pancasila menjadi satu film tersendiri. Lima dibesut sebagai satu film utuh yang mengandung lima bagian. Masing-masing bagian mewakili satu sila, tetapi tetap berkelindan dengan bagian-bagian lainnya.
Bagian pertama, berpangkal pada kematian Maryam (Tri Yudiman). Ketiga anaknya—Fara (Prisia Nasution), Aryo (Yoga Pratama), dan Adi (Baskara Mahendra)—berdebat tentang cara yang layak untuk memakamkan sang ibu. Maryam perempuan Muslim, tetapi pernah menjadi Kristen, lalu berbalik kembali menganut Islam, bahkan sudah naik haji. Fara juga Muslim, tetapi Aryo dan Adi beragama Kristen. Bagaimana mereka menyelesaikan persoalan pelik ini?
Kisah terus bergulir sesudah pemakaman. Masih dalam suasana duka, masalah demi masalah mendera mereka. Adi seorang korban perundungan dan menjadi saksi kejahatan massal. Fara, pelatih renang, berhadapan dengan dilema ketika mesti memilih atlet yang layak dikirim ke pelatnas. Aryo ditelikung oleh mitra bisnisnya sehingga jadi pengangguran. Lalu, mereka mesti membahas warisan sang ibu.
Keluarga ini juga memiliki pembantu setia, Bi Ijah (Dewi Pakis). Di bagian akhir, Bi Ijah mesti mengatasi masalah gawat gara-gara ulah kedua anaknya di kampung.
Secara keseluruhan, film ini lumayan memuaskan, menawarkan penafsiran yang cukup segar terhadap sila-sila Pancasila. Dengan berpangkal pada pergumulan hidup satu keluarga, bagian demi bagian dapat terangkai menjadi kesatuan kisah yang runtut.
Sukses utama film ini adalah keberhasilannya untuk tidak berceramah, tetapi secara lentur menuturkan kisah. Dengan niat awal mengangkat nilai-nilai Pancasila, ada kekhawatiran "Lima" bakal terjebak jadi film yang penuh petuah. Kekhawatiran itu tertepis. Film ini berhasil menghadirkan tokoh-tokoh yang membumi, dengan pergumulan yang riil dan relevan dengan situasi kekinian. Nilai-nilai Pancasila tidak dilontarkan secara frontal dalam bentuk ceramah, tetapi secara laten menjiwai keputusan yang diambil oleh masing-masing tokoh.
Namun, dengan durasi hanya 110 menit, dan mesti mencakup kelima sila, eksplorasi kisah jadi kurang detail. Ilustrasi atas tiap-tiap sila belum merata. Penggambaran sila pertama kuat, tajam, dan terhitung berani mempersoalkan problem-problem toleransi beragama. Sebaliknya, sila kedua terkesan kurang tuntas. Kejahatan keji yang disaksikan Adi kurang jelas duduk perkaranya dan, alih-alih terkena getahnya, polisi secara relatif gampang melepaskan Adi. Bagian terakhir juga terasa bergegas mengejar ending yang manis. Jadi berangan lagi, mudah-mudahan nanti ada yang mau bikin film Pancasila satu sila satu film.
Di luar itu, "Lima" menawarkan sejumlah aspek yang menawan. Komposisi gambar demi gambar tampak terjaga, rapi, dinamis, dan menggarisbawahi emosi adegan yang ditampilkan. Lihatlah bagaimana kamera mengajak kita menyaksikan proses penyucian jenazah Maryam. Bergerak lembut, merekam rambut, raut wajah, dan tubuh yang terbujur kaku. Sakral dan magis. Adegan ini kian mencekam dengan iringan khidmat suara berat Syaharani mengalunkan tembang berlirik Islami. Lalu, tautkan dengan adegan di pemakaman, yang ditutup dengan sebuah kidung Kristiani.
Para pemain berdialog dan berakting secara wajar. Adegan mengalir dari keharuan, ketegangan, hingga kejenakaan, ganti-berganti. Ada adegan lembut seperti saat Adi mengenakan kuteks dan Aryo merengkuhnya. Adegan pembahasan warisan bercampur antara perbantahan menegangkan dan sikap konyol notaris yang memancing tawa, mengalir asyik dari ruang tamu ke dapur. Ada pula sisipan flashback yang indah: saat Fara melihat Adi bermain piano dan saat Bi Ijah mencuci piring dengan Maryam.
Beberapa kutipan dialog tak sekadar motivasional mengelus perasaan, tapi menyentak memantik refleksi. “Haram? Aku lahir dari perut Mama juga, Mbak. Sama kayak Mbak. Kenapa sekarang aku jadi haram, terus Mbak halal?” kata Aryo menggugat. Atau, ucapan Fara, “Sesama keluarga tidak saling meninggalkan.” Terkesan klise, tetapi ketika diucapkan seorang majikan kepada pembantu rumah tangganya, nuansanya jadi berbeda.
Pada akhirnya, film ini dapat menjadi pangkalan yang asyik untuk memperbincangkan kembali penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kita. Bagaimana jika kita diperhadapkan pada situasi serupa? Pilihan mana yang akan kita ambil? Nilai-nilai apa yang melandasi keputusan kita?
"Lima" secara lembut mengingatkan, problem besar bangsa ini terletak pada pemahaman dan pengamalan sila pertama. Selama nilai keagamaan lebih ditinggikan dari nilai kemanusiaan; selama kesalehan pribadi lebih diagungkan daripada, bahkan jika perlu dengan mengorbankan, kesalehan sosial; selama prinsipnya manusia-untuk-agama, bukan agama-untuk-manusia, bangsa ini akan susah beranjak ke mana-mana.
Ketuhanan dalam aspek kesalehan pribadi mestinya seperti akar pohon, yang menghunjam dalam-dalam, kuat mencengkeram, menyediakan dasar yang teguh, bukan mencuat ke permukaan, merintangi, dan bahkan melukai. Kesalehan sosial yang perlu mekar mengembang di ranah kehidupan bersama, merangkul satu sama lain sebagai keluarga.