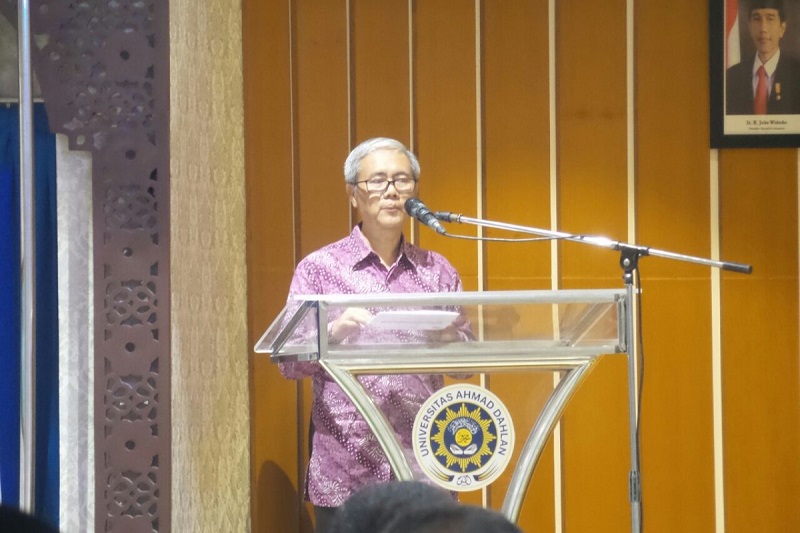Zayn Malik: Saat politik identitas naik pentas
Beberapa waktu lalu, saat Zayn Malik dalam sebuah wawancara mengaku dia tak lagi beragama Islam, sontak itu menjadi trending topic. Apalagi di antara para zquad--julukan bagi penggemarnya, ada yang bisa menerimanya apa adanya, ada pula yang merasa sedih, bahkan menghujatnya. Kenapa masyarakat, khususnya generasi milenial begitu reaktif merespons ini?
Era Robinson Crusoe sudah lewat
Di dalam mata kuliah ‘Komunikasi’ yang saya ampu, saya sering mengatakan, “No man is an island” untuk menunjukkan sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri dan menyendiri—meskipun terpaksa—seperti Robinson Crusoe. Apalagi di zaman digital seperti sekarang.
Apa saja yang kita lakukan dan ucapkan, bahkan tidak melakukan dan mengucapkan apa pun, bisa jadi konsumsi publik di media sosial. Hal inilah yang sekarang sedang ramai di jagad maya. Pencetusnya adalah wawancara Zayn Malik dengan Vogue, yang menyatakan dengan terus terang dirinya bukan penganut Islam.
Apa salahnya berterus terang?
Seolah ada hukum tidak tertulis, kehidupan pribadi selebriti menjadi konsumsi publik. Malangnya, publik seakan-akan punya hak mendiktekan keinginan terhadap idola mereka. Kita tentu tahu deretan artis yang dulu takut ketahuan kalau sudah pacar agar tidak ditinggal penggemar.
Sebaliknya, ada penggemar fanatik yang tidak rela jika idolanya putus dengan pacarnya. Demikian juga dengan Zayn Malik. Saat dikabarkan putus dengan Gigi Hadid, yang ternyata hanya berlangsung tujuh minggu, fansnya keberatan. Saat akhirnya mereka mengunggah foto kemesraan mereka di sosial media, zquad maupun zigi, para penggemar Zayn dan Gigi, bersorak. Bahkan, ada yang menganjurkan mereka agar segera menikah. Lihat, sampai pernikahan pun maunya mereka yang tentukan.
Jika dulu Zayn tidak mau berterus terang tentang agamanya, dan terus saja menimbulkan asumsi dan spekulasi, dia memutuskan untuk terbuka. Nah, saat terbuka inilah dia mendapatkan ‘serangan’ yang mungkin sudah dia perhitungkan. Jawabannya elegan. Dia mengatakan, agama dan kepercayaan seseorang adalah pribadi. Yang jelas dia mempercayai adanya Tuhan tetapi bukan seperti yang orang lain harapkan.
Di zaman yang begitu maju seperti sekarang ini ternyata masih banyak orang yang menganggap kafir orang yang agama atau kepercayaannya berbeda. Bagaimana jika yang dituduh kafir membalas dengan kata ‘tapir’? Pasti penyayang binatang yang mencak-mencak dan berdemonstrasi. Apa salahnya tapir sehingga disematkan ke binatang yang ‘lembut’ dan ogah berkelahi ini? Sudah cukup kambing berbulu hitam saja yang dijadikan sasaran saat pengecut tidak mau mengaku salah.
Berbeda, so what gitu lo?
Di tengah suhu ‘politik identitas’ yang menghangat—atau bahkan sudah memanas dan siap membakar siapa saja—kita perlu kembali merenungkan arti perbedaan. Di keluarga besar saya sendiri, perbedaan itu tidak saja dipahami dan ditoleransi, melainkan dihidupi. Kami boleh berbeda agama dan keyakinan, tetapi tetap yakin satu hal. Kami satu keluarga!
Dari masa kecil sampai sekarang, saya justru menemukan momen berbahagia saat setiap anggota keluarga yang berbeda agama merayakan hari rayanya. Bagi saya, artinya kumpul-kumpul dan makan-makan. Sebelum zaman maraknya wisata kuliner, saya sudah bisa menikmati berbagai macam makanan di rumah sendiri.
Menepuk air di dulang
Terpercik muka sendiri. Pepatah klasik itu tetap valid sampai saat ini. Jika kita melontarkan kotoran ke orang lain, sebagian bisa jadi mengenai diri sendiri. Jika perbedaan kita anggap aneh, bahkan musuh, tunggu saja kehancuran kita.
“Wah, indah sekali ya?” ujar istri saya antara pertanyaan dan kekaguman saat kami menikmati hamparan tulip warna warni di musim semi.
Mereka bisa berjajar rapi di tempat masing-masing tanpa bersaing satu sama lain. Petani mengatur bunga tulip itu yang sejenis dan sewarna dalam satu petak yang panjang. Jauh lebih indah dari permadani di ruang tamu rumah saya atau di gedung-gedung istana negara. Bagaimana kalau dicampur? Tidak masalah. Di salah satu petak, petani sengaja mencampur beberapa bunga tulip jadi satu. Semacam ‘show room’. Indah sekali!
Seandainya bunga itu iri dengan warna dan keindahan bunga lain, bisa jadi mereka saling melempar lumpur dan akibatnya sama-sama kotor. Yang memulai pasti malu sendiri.
Hal inilah yang saya baca saat masih kecil. Sebagai predator buku, masa kecil saya didominasi kegiatan membaca. Salah satu science fiction yang saya baca memberikan sindiran telak bagi intoleransi.
Seorang manusia bumi mendarat di sebuah planet. Astronaut itu segera menjelajahi planet yang baru diinjaknya. Di sebuah ‘jalan’ yang sepi dia bertemu dengan penduduk lokal. Dia tidak mampu menahan tawa saat melihat telinga ‘orang’ itu menghadap ke belakang. Anehnya, meskipun ditertawakan, makhluk planet itu diam saja.
Semakin mendekati ‘pusat kota’, penduduk bumi itu justru semakin tertekan menahan malu. Apalagi saat dia masuk ke sebuah ‘plaza’ yang luas. Semua penghuni melihatnya dengan pandangan aneh. Mengapa? Karena mereka semua memiliki telinga menghadap ke belakang. Pertanyaannya, siapa ‘makhluk aneh’ sekarang? Siapa yang menertawakan siapa?
Syal persahabatan
Saya masih ingat benar, momen yang indah sekaligus mengharukan dalam kehidupan saya sebagai penulis. Suatu ketika saya harus berpisah dengan seorang sahabat penulis. Sebelum berpisah, di atas panggung, dia memberikan saya ulos yang saya simpan sampai sekarang. Warna-warni ulos itu mengingatkan saya bahwa perbedaan itu menjadi indah jika dirajut dengan semangat kebangsaan dan rasa cinta.
Di saat lain, setelah menginap beberapa hari, saya memberi nyonya rumah yang ramah dengan buku-buku terbaru saya. Saat saya hendak kembali ke bandara, ibu itu memberi saya syal yang merupakan hasil tenunan tradisional yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Pada saat saya menulis ini, pemberitaan di tanah air, khususnya di kalangan dunia hiburan, Vicky Prasetya sedang bermusuhan dengan Angel Lelga. Pasalnya, Vicky marah karena Angel dianggap menyembunyikan laki-laki di rumahnya. Meskipun ada yang menganggapnya settingan dan cari sensasi belaka, bahkan ada warganet yang menyentil pemerintah dengan unggahan “Mana revolusi mental”? Bagi saya penghormatan terhadap perbedaan memang seharusnya dimulai dari lingkungan paling kecil: diri sendiri dan keluarga.
Bijak menggunakan telunjuk
Ketimbang saling tuding dan saling tunjuk, apalagi saling tanding dan saling tonjok, bukankah lebih baik kita merajut kembali tenun kebangsaan. Jangan sampai anjuran indah ini hanya berhenti di tataran wacana. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang harus memulainya?
Seorang filsuf junior tidak tahan lagi dengan keadaan negerinya yang porak poranda karena dehidrasi moral dan degradasi mental. Dia ambil megafon dan teriak-teriak di jalan raya agar masyarakat berubah. Apa yang dia dapatkan? Cemooh, umpatan, hujan air ludah, bahkan lontaran batu.
Dengan tubuh legam dan belepotan, dia mulai merenungkan hal ini dalam-dalam. Merasa buntu, dia menemui gurunya. Gurunya memberinya satu sendok brotowali dan segelas kecil air. Dia diminta mencampur brotowali itu ke dalam gelas, mengaduknya dan meminumnya.
Dia segera memuntahkannya kembali karena begitu pahitnya. Gurunya memberinya satu gelas besar penuh brotowali dan menyuruhnya menuangkannya ke telaga di depan gubuk sang guru serta mengaduknya.
“Sekarang cedoklah air itu dan minumlah,” perintah gurunya.
Dengan taat, filsuf muda itu melakukan perintah gurunya.
“Apa yang engkau rasakan?”
“Segar!”
“Sudah tahu jawaban saya atas persoalan yang membuat kepalamu pening?”
“Ya, Guru,” ujar murid itu dengan sikap hormat. “Untuk mengubah keadaan sekitar saya harus memulai dengan diri saya sendiri, yaitu memperluas wadah batin saya.”