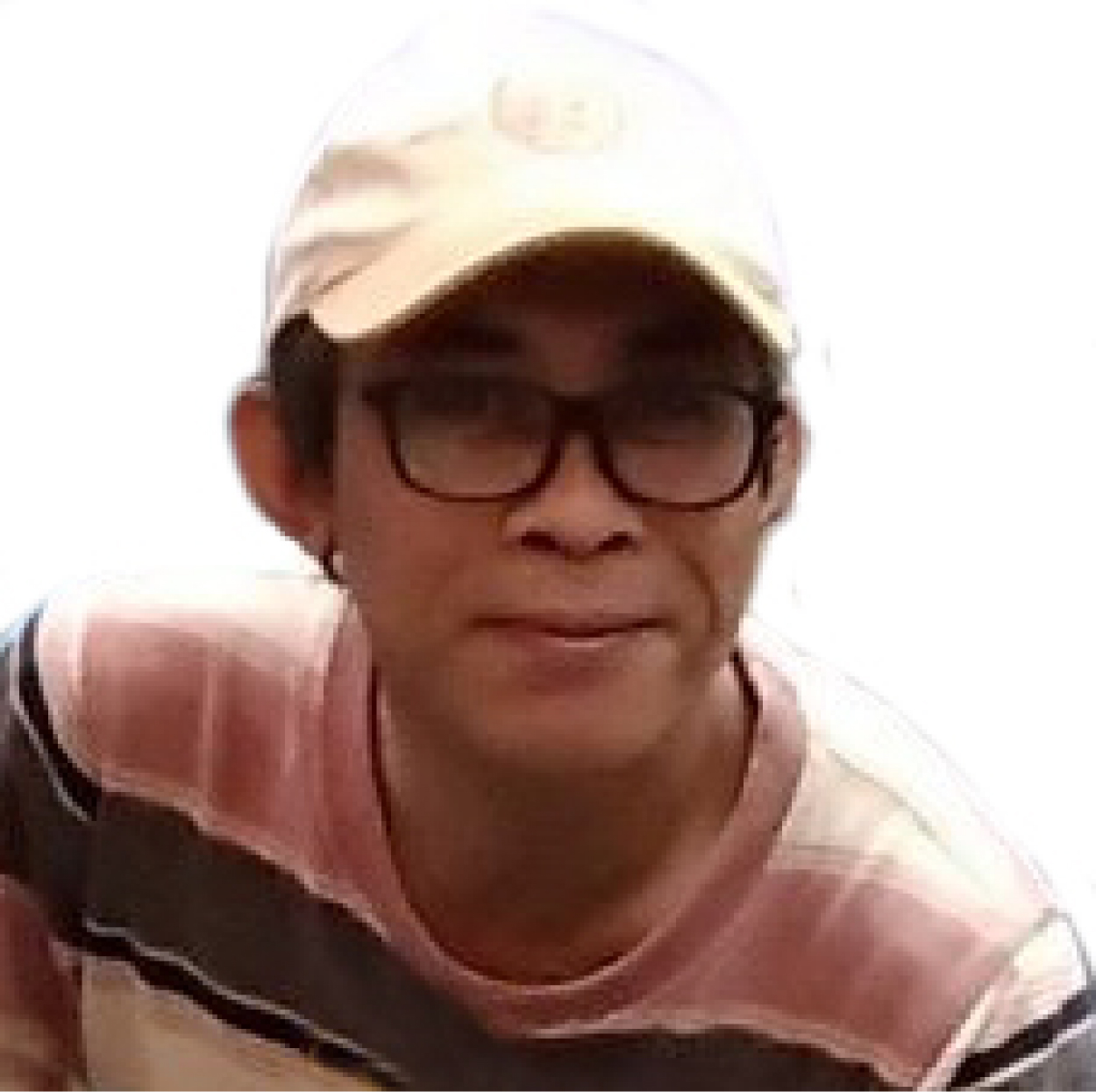Bagaimana lead berita harus ditulis? Lead berita ternyata boleh dibuat seperti ini:
"Badut terpeleset, singa mengaum, dan artis trapeze yang gemerlap melayang-layang di atas penonton saat terompet membunyikan mars Sousa kemarin. Bella Si Badut menggiring kelompok sirkus Big Apple kembali memasuki kota".
Cukupkah informasi kepada publik dituangkan lewat rumus 5W1H (What-Who-When-Where-Why-How) semata? Tidak, terkadang itu saja belum cukup.
Mungkinkah teknik menulis ringkas "menghabisi ruang" secepatnya dengan cara "menjejalkan" sebanyak mungkin atau seluruh pokok pikiran dalam karangan berita sejak paragraf pertama sedikit-banyak diubah penulis berita dengan cara yang agak lain? Ya, mungkin saja.
Buku berjudul Jurnalisme Sastra karya Septiawan Santana Kurnia (2002) seperti oksigen mengalir ke ruang hampa pembaca yang menginginkan lebih dari sekadar kabar baik. Panduan mengenai apa dan bagaimana (know-how) dalam sejenis kitab dikarang seorang pengajar jurnalistik kawakan yang enteng pula untuk konsumsi kalangan umum.
Wartawan senior Atmakusumah Asraatmadja menulis kata pengantar buku ini melalui pertanyaan krusial: "Mengapa tidak dicoba upaya mengembangkan jurnalisme kesastraan untuk menembus kemungkinan kebosanan di kalangan para pembaca?" Jadi, buku ini dikarang bagi wartawan demi memenuhi selera pembaca yang mungkin bosan. "Untuk itu," kata Atmakusumah, "semoga buku ini dapat menjadi salah satu bahan tuntunan." Harapan itupun dipenuhi Septiawan, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, menuntun dengan bijak tanpa menggurui majelis pembaca.
Sepuluh bab kemudian, Septiawan membeberkan bagaimana teori praktis menulis dalam teknik penyampaian dengan penuh nuansa "bersuhu sejuk dan tenang dingin". Ada kompromi di garis batas antara cerita dengan berita. Runtuhnya demarkasi semu yang membedakan fiksi dan fakta.
Warta bernuansa sejuk, jauh dari tata kalimat beku kaku ilmiah macam tertera dalam buku teks, tapi justru tidak menjauhkan prinsip-prinsip akurasi pengetahuan.
Kelahiran jurnalisme sastra mulai populer pada tahun 1960 sampai 1970-an seiring munculnya gerakan New Journalism di Amerika Serikat. Di mana berbagai tulisan bercorak sastra dalam berita banyak didapati di koran dan majalah.
Cara menulis jurnalisme sastra terhitung mulai istilah itu dialiterasikan ke bahasa Indonesia dari "literary journalism" barangkali baru tahun 1997 diperkenalkan intensif sejak terbitnya sebuah buku terjemahan, Pedoman untuk Wartawan. Penyuntingnya memunculkan istilah itu ketika menerjemahkan uraian Wai Lan J. To tentang kegunaan jurnalisme ini bagi para wartawan Asia dan Dunia Ketiga.
Sebelum zaman itu, sajian teks berita yang terasa bermuatan pesan penting dan memiliki kesan kuat telah dinikmati pembaca dari goresan pena Mahbub Djunaedi, Sju'bah Asa, Umar Kayam, Seno Gumira Ajidarma wartawan harian Merdeka, Yudhistira ANM Massardi, dan beberapa wartawan lain. Jurnalisme sastra jadinya diasah tajam dengan mata pena oleh para wartawan yang berbasis pula sebagai sastrawan.
Inti kekuatan jurnalisme sastra ialah dari caranya yang bertutur. Lebih dari itu, warta-kabar-berita sastrawi bahkan mungkin lebih melampaui medium pembatas antara penulis terhadap pembaca. Sejenis kontemplasi yang menjadi cara atau metode tutur yang menyampaikan respek tersendiri ke hadirat rakyat-pembaca yang menyukai bahasa. Itulah jurnalisme sastra.
Buku: Jurnalisme Sastra
Karya: Septiawan Santana Kurnia
Kata Pengantar: Atmakusumah Asraatmadja
Halaman: 328
ISBN: 979-686-629-3
Penerbit: Gramedia Pustaka Utama
Tahun: 2002.