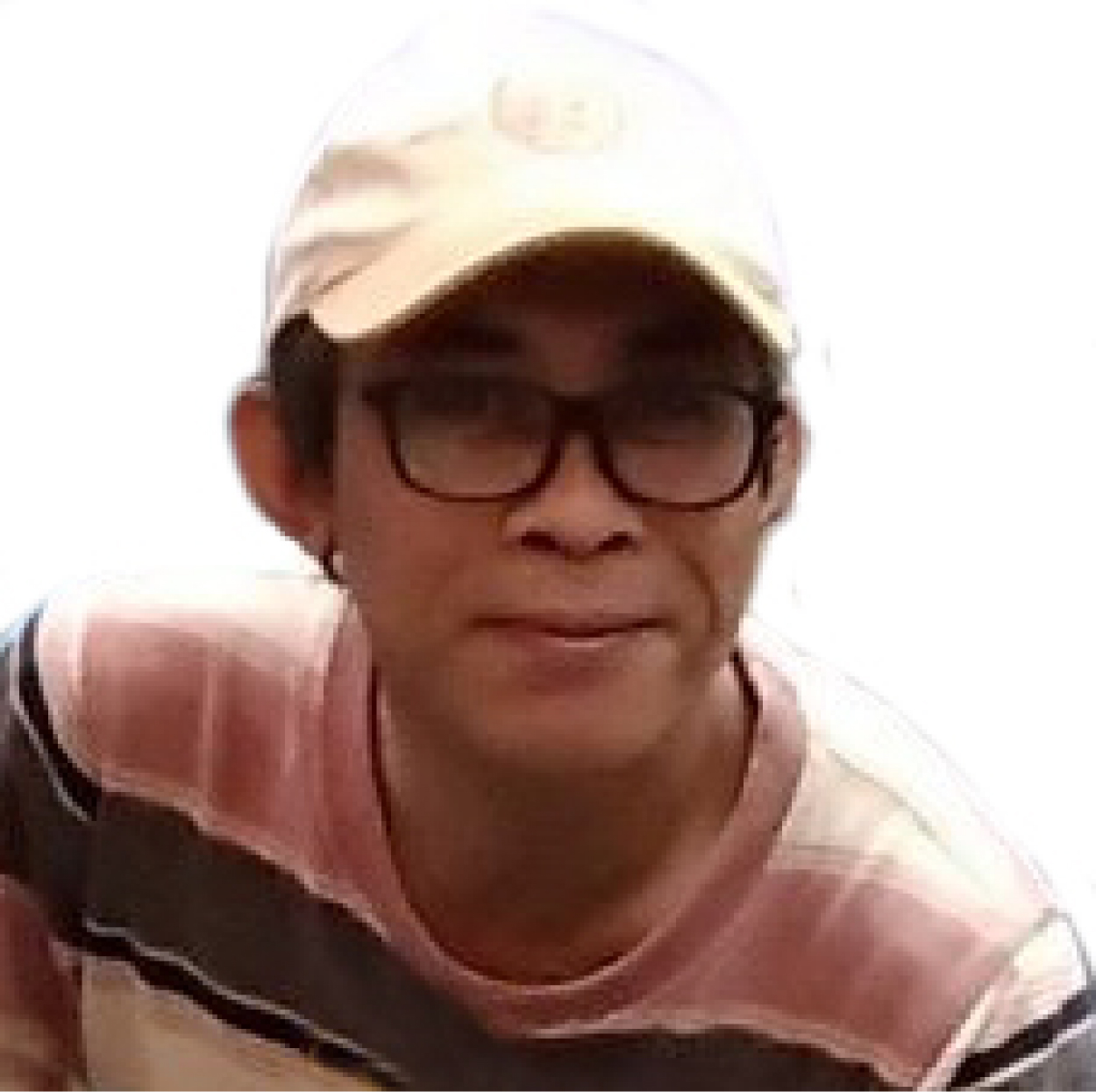Dua tahun kudeta Myanmar: Kesaksian korban dalam bencana
Dua tahun setelah kudeta militer Myanmar, seorang pekerja pabrik muda yang menjelma pejuang perlawanan berduka atas kehilangan kakinya dalam pertempuran. Seorang mantan diplomat sudah empat tahun tidak bertemu keluarganya. Seorang ratu kecantikan menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di Kanada musim dingin. Seorang guru yang diasingkan bermimpi untuk kembali ke sekolah.
Kudeta 1 Februari 2021, yang menggulingkan pemerintahan terpilih peraih Nobel Aung San Suu Kyi, telah meninggalkan jejak kehidupan yang terbalik setelahnya.
Kelompok pemantau konflik yang berbasis di Amerika Serikat, Acled, mengatakan sekitar 19.000 orang tewas tahun lalu ketika tindakan keras terhadap protes menyebabkan banyak orang mengangkat senjata melawan militer.
Sekitar 1,2 juta orang telah mengungsi dan lebih dari 70.000 meninggalkan negara itu, menurut PBB, yang menuduh militer melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Militer Myanmar mengatakan sedang melakukan kampanye yang sah melawan "teroris". Pihak tentara tidak menanggapi permintaan komentar oleh Reuters.
Kisah empat orang mencerminkan krisis yang diperingatkan oleh utusan khusus PBB pekan lalu telah mengambil "bencana besar" pada populasi.
Pejuang Pemberontak
Aye Chan mendengar rentetan tembakan yang diikuti dengan ledakan.
"Saya tidak tahu apakah saya tertembak atau tidak," kata pria berusia 21 tahun itu kepada Reuters, mengenang serangan militer tahun lalu yang membuatnya kehilangan kakinya.
Ketika dia mencoba berdiri, kakinya tidak berfungsi. Seorang kawan membawanya ke rumah sakit di mana dia terbangun dan menemukan tubuhnya telah diamputasi dari lutut ke bawah.
Seorang pekerja pabrik, yang membuat mie instan sebelum kudeta, telah menjadi bagian dari massa besar yang turun ke jalan untuk menuntut pemulihan demokrasi setelah kudeta.
Ketika kelompok protes mulai mengangkat senjata, dia bergabung dengan mereka.
Pertama kali di garis depan, jantungnya berdebar kencang.
"Kemudian saya melihat sekeliling pada rekan-rekan saya dan mereka tersenyum dan tertawa. Saya tidak takut."
Sementara moral di antara pasukan perlawanan tinggi, katanya, mereka kalah dengan tentara yang diperlengkapi dengan baik.
"Saat mereka menembak, mereka menembak terus-menerus, kami bahkan tidak bisa mengangkat kepala," katanya. "Kami juga harus menghemat peluru."
Sekarang, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, memasak, dan berbagi makanan dengan teman-temannya. "Saya mencoba menjalani hidup saya sebahagia mungkin," katanya. "Saya tidak bisa melakukan hal-hal yang saya lakukan sebelumnya."
Reuters tidak mengungkapkan keberadaannya untuk alasan keamanan.
Dia tidak menyesal bergabung dengan perlawanan.
"Jika saya cukup pulih, saya akan kembali berperang. Ini sampai mati."
Diplomat
Aung Soe Moe, 52, menjadi sekretaris utama di kedutaan Myanmar di Jepang saat kudeta terjadi.
Sebulan kemudian, dia bergabung dengan ratusan ribu pegawai pemerintah yang berhenti untuk bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil, yang bertujuan melumpuhkan kemampuan militer untuk memerintah.
Istrinya, yang terjebak di Myanmar bersama putrinya setelah pandemi Covid-19, mendorongnya untuk angkat bicara. Mereka kemudian melarikan diri melintasi perbatasan ke Thailand, di mana banyak dari Myanmar mencari perlindungan tetapi terjebak tanpa dokumen. Dia belum melihat mereka sejak 2019.
Sendirian di Tokyo, dia harus pindah dari apartemennya yang mewah dengan tiga tempat tidur di halaman kedutaan. Dengan hilangnya sumber pendapatannya, penduduk Myanmar lainnya di Jepang menawarkan uang untuk menutupi kebutuhan pokoknya dan menyewa flat studio yang sempit.
Pemerintah Jepang memperpanjang visa diplomatik Aung Soe Moe sehingga ia dapat tetap tinggal di Tokyo, tetapi ia tidak dapat bekerja dan visa tersebut akan berakhir pada bulan Juli. Kementerian luar negeri Jepang menolak berkomentar tentang statusnya nanti.
"Saya sangat menderita, tapi tidak ada yang lebih buruk daripada kehilangan masa depan rakyat Myanmar," katanya kepada Reuters.
Dia menjadi sukarelawan beberapa hari dalam sepekan melakukan tugas-tugas administratif seperti menulis postingan media sosial untuk Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar -- sebuah pemerintahan sipil paralel yang dibentuk setelah kudeta.
Dia khawatir dunia akan melupakan Myanmar, terutama sejak perang di Ukraina.
“Tapi rakyat Myanmar belum menyerah pada kebenaran,” katanya. "Kami tidak akan pernah menyerah!"
Ratu Kecantikan
Ketika militer merebut kekuasaan, Han Lay yang berusia 23 tahun, seorang model yang akan mengikuti kontes kecantikan internasional di Thailand.
Setelah memprotes dengan teman-temannya, dia memutuskan untuk menggunakan platformnya untuk berbicara tentang Myanmar. Malam sebelumnya, dia tidak bisa tidur karena kegembiraan dan kekhawatiran, katanya.
Di atas panggung, dia menahan air mata saat berbicara tentang kekerasan militer pada hari ketika lebih dari 140 demonstran tewas. Klip itu menjadi viral.
Di Myanmar, militer menuduhnya menghasut.
Dia ditahan di bandara di Bangkok selama beberapa hari, memohon di media sosial untuk tidak dikirim kembali ke Myanmar.
Akhirnya dia terbang ke Kanada dan menetap di London, Ontario, di mana dia tinggal bersama keluarga Burma-Kanada, pengungsi dari pemberontakan demokrasi 1988 yang juga dihancurkan oleh militer.
Dia bilang dia kesepian ketika dia pertama kali tiba tetapi menyesuaikan diri.
“Saya lahir di Myanmar, dan keluarga saya, teman-teman saya, dan masa depan saya, semuanya ada di Myanmar... Saya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu mereka, saya merindukan mereka setiap hari,” katanya.
Seorang Guru
Seorang guru sekolah menengah telah tinggal di kota perbatasan Thailand sejak melarikan diri dari penangkapan di Myanmar tahun lalu.
Seorang wanita kurus dengan rambut hitam panjang, dia bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil (CDM) yang muncul setelah kudeta. Dia meminta untuk tidak disebutkan namanya, karena takut pembalasan militer.
“Saya tahu bahwa hidup saya akan menjadi sulit jika saya bergabung dengan CDM,” ujarnya. "Tapi jika kita tidak memberontak, masa depan kami tidak akan baik-baik saja."
Dia bergabung dengan protes jalanan dengan mengenakan seragam guru hijau dan putihnya, dan meninggalkan negara itu setelah tindakan keras tersebut.
Seperti banyak pengungsi Myanmar di Thailand, dia tidak berdokumen dan hidup dalam ketakutan akan penangkapan.
Dia mencari nafkah dengan merajut tas dan pakaian, berpenghasilan kurang dari US$10 seminggu, dan bergantung pada sumbangan makanan dari pemerintah sipil paralel.
"Saya akan menjadi anggota CDM sampai mati," katanya. "Seseorang harus melewati saat-saat baik dan buruk.
Seragam hijau-putihnya aman di Myanmar, katanya, disimpan dengan rapi, kalau-kalau dia kembali.(tbsnews)