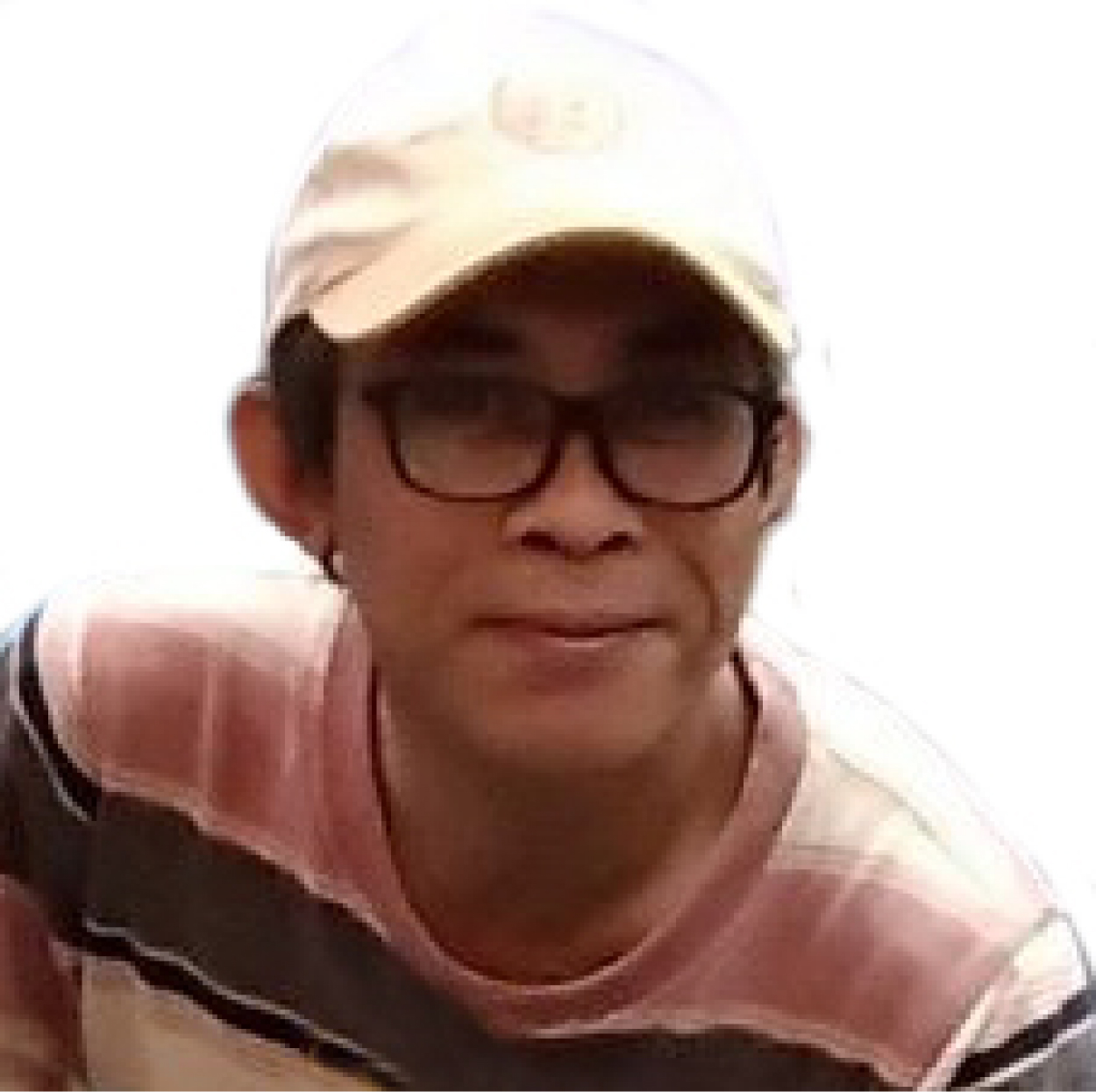Kepercayaan publik mengoptimalkan fungsi jurnalisme
Banyak pengalaman di negara-negara demokratik membuktikan jurnalisme adalah bagian yang esensial dari demokrasi. Jadi adalah public goods seperti juga layanan-layanan publik yang lain. Seperti air minum, listrik, internet.
Artinya, sebuah produk atau layanan, yang dibutuhkan oleh komunitas atau masyarakat untuk berfungsi. Tapi kunci public goods jurnalisme hanya bisa berfungsi kalau ada public trust, bila masyarakat percaya pada esensi jurnalisme. Itu kerumitan khas dari pers di hari-hari ini.
"Kalau kita berlangganan air atau internet, kita tidak perlu percaya perusahaan atau pada produknya. Tapi kalau jurnalisme, itu hanya bisa menjadi optimal (dan) berfungsi, bila ada public trust terhadap keberadaannya. Itu pentingnya jurnalisme publik. Di situ baru perdebatannya akan menjadi kompleks. Bagaimana kemudian bisnis media, teknologi digital, memungkinkan distribusi jurnalisme untuk kebaikan atau kemashlahatan bagi masyarakat umum?" kata wartawan dan Direktur Utama Tempo.co Wahyu Dhyatmika.
Berbicara pada Sabtu (12/3/2022) dalam kuliah tamu Komunikasi Universitas Airlangga, Wahyu banyak memberi pertanyaan untuk memancing diskusi. Dengan begitu, dia menyingkapkan bahwa pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang esensi jurnalisme itu jadi makin relevan ditanyakan, yang tentunya juga akan bisa didiskusikan.
"Karena selain kita bicara disrupsi digital yang mengubah model bisnis, cara kerja, konsumsi informasi, pandemi Covid-19 membuat akselerasi perubahan itu. Memungkinkan perubahan yang tadinya diproyeksikan akan berlangsung agak lama itu dipaksa lebih cepat. Perubahan-perubahan mendasar itu misalnya dari cara orang membaca," sambungnya.
Transformasi digital di media
Diuraikan, sepanjang tahun 2021, sejumlah media cetak berhenti terbit, termasuk koran legendaris The Jakarta Post yang jadi full-digital. Tempo memiliki koran yang berhenti cetak dan berpindah ke digital. Sebelumnya media-media cetak lokal sepenuhnya berubah ke digital juga.
"Apakah beralih ke platform digital itu menandakan sebuah transformasi ke arah yang lebih positif atau justru sebaliknya? Apa yang disebut transformasi digital untuk media? Apakah hanya beralih platform, yang tadinya cetak menjadi online? Apakah itu cukup untuk disebut menjadi digital? Atau ada syarat atau indikator lain yang harus dipenuhi sebuah media untuk disebut sebagai sebuah media digital?" tanya Wahyu.
Dikatakannya, tantangan bagi jurnalis Indonesia yang paling mengemuka di era TikTok, Instagram, dan ketika orang-orang pindah ke media sosial (medsos) ialah apakah jurnalisme bisa tetap relevan.
"Relevansi jurnalisme (dipertanyakan) ketika publik misalnya tidak lagi terpatok membaca agenda setting media. Kalau dulu yang disebut penting di publik atau masyarakat, kalau sudah jadi headline di Harian Kompas atau sampul Majalah Tempo, berarti itu isu penting."
"Sekarang sebaliknya, isu penting setelah trending (di medsos). Kemudian media konvensional, mainstream media, mengambil peran sebagai explainer, menjelaskan background konteks dari isu-isu yang trending tersebut. Artinya, sudah bukan lagi (sebagai) gatekeeper (penjaga gerbang). Peran gatekeeper, (atau) yang memastikan informasi penting itu adalah informasi yang dimuat oleh media, sekarang sudah tidak lagi relevan. Apakah itu membuat jurnalisme masih relevan?" cetusnya.
Menurut Wahyu, ketika disrupsi digital terjadi, diketahui salah satu dampak terbesar adalah pendapatan utama media kemudian beralih. Dulu, media hidupnya hanya dari iklan dan langganan atau pembeli eceran. Sekarang, 70 persen pendapatan iklan media pindah ke perusahaan digital seperti Google dan Facebook. Itu yang mengambil alih.
Katanya, terjadi karena Google-Facebook bisa lebih massif dengan perangkat infrastruktur teknologi dan platform yang dikunjungi oleh sebegitu banyak users. Dampak dari sebuah iklan di medsos atau platform digital menjadi lebih massif dengan harga yang jauh lebih murah. Membuat beriklan di media massa kehilangan daya tariknya untuk sejumlah klien atau pengiklan guna mencapai reachout thread (jangkauan utas) yang paling luas.
"Dari sisi eceran juga begitu, tidak ada lagi kebiasaan yang umum bahwa berita itu harus dibeli. Justru kebiasaan yang timbul dari disrupsi digital adalah informasi itu gratis, termasuk berita. Sehingga upaya untuk membuat atau mempertahankan model langganan menjadi lebih sulit. Itu membuat tantangan yang lain bagi media. Bagaimana membuat media bisa berkesinambungan secara ekonomi ketika model bisnisnya berubah?" serunya.
Masih menurut Wahyu, ketika jurnalisme berorientasi pada kebutuhan pembaca, apakah itu hal yang positif atau justru pers kehilangan rohnya? Fungsi jurnalisme itu terletak pada gatekeeper-nya, agenda setting, pada fungsinya untuk menciptakan opini atau bukan di situ?
Dia menanyakan: Di mana sebetulnya roh jurnalisme ketika fungsi-fungsi pembentukan opini, gatekeeper, dan agenda setting itu tidak ada lagi? Apakah kemudian jurnalisme menjadi tidak penting? Yang membuat jurnalisme itu punya marwah, disegani, ternyata tidak lagi relevan, maka apa yang membuat jurnalisme penting? Apa fungsi explainer tadi?
Hilangnya penjaga gerbang
"Jadi ketika misalnya ada sebuah twit yang muncul di medsos, sebuah postingan, meme yang menghebohkan, kemudian media menulis ada apa di balik semua itu, menjelaskan konteksnya, background, kronologis, relevansi, kepentingan, menjelaskan segalanya. Apa itu disebut sebagai jurnalisme di era digital?" ujarnya.
Wahyu menjelaskan, itulah berbagai pertanyaan menantang yang harus dijawab oleh para wartawan, pemilik media, penerbit, produser, dan lainnya. Pertanyaan lain yang tidak kalah penting terlihat dari beberapa coverstory Majalah Tempo ketika dia menjadi Pemimpin Redaksi.
"Tahun 2017-2019 itu saya Pemimpin Redaksi di Tempo.co. Setelah itu sampai Juli 2021 di Majalah Tempo. Ini (yang kami kerjakan di kedua media tersebut) sebetulnya fungsi investigative reporting, watchdog journalism, jadi ini fungsi lain, yang tadi juga menjadi roh dari jurnalisme. Fungsi menjaga akuntabilitas dari penguasa, siapapun penguasanya, siapapun pemerintahnya," tegasnya.
Wahyu menggamblangkan, ada fungsi publik yang dilakukan pemerintah dan harusnya bertanggung jawab terhadap legislatif misalnya. Tapi siapa yang mengawasi ketiga pilar itu? Legislatif, yudikatif, dan eksekutif; siapa yang mengawasi mereka? Ada pilar keempat, yaitu pers yang menjalankan jurnalisme. Jadi ketika model bisnis sudah terdisrupsi, bagaimana mempertahankan model-model investigative reporting ini? Ini lagi-lagi sebuah tantangan.
"Kita lihat beberapa media sudah mencoba menjawab tantangan itu. Kita lihat misalnya setahun terakhir, ada beberapa ikhtiar seperti Project Multatuli, salah satu yang menarik, dari teman-teman eks-Jakarta Post dan eks-Tempo. Mereka membuat model bisnis membangun komunitas pembaca yang bersedia menyokong pendanaan dari liputan-liputan investigasi mereka," ucapnya.
Sementara, diungkapkan, model yang dikembangkan Tempo berupa grant journalism (jurnalisme hibah), jadi Tempo sengaja mencari lembaga-lembaga donor yang misinya sesuai dengan kehidupan Tempo. Maka beberapa liputan lingkungan di Tempo dibiayai sepenuhnya oleh lembaga-lembaga donor internasional. Sejauh mana model-model ini berkelanjutan dan bisa mempertahankan independensi, suatu prinsip penting juga dalam jurnalisme, dengan berbagai model bisnis baru ini?
"Semua jurnalisme tidak lagi hanya berbasis teks dan foto, tapi juga muncul di YouTube, dan popularitasnya diukur dari berapa yang menonton. Apakah itu kemudian lebih efektif untuk menyampaikan informasi yang penting? Apa algoritma di medsos cukup transparan sehingga penerbit atau konsumen berita punya kekuasaan memadai untuk menentukan apa yang harus muncul di screen Anda?"
"Sejauh mana algoritma itu mengambil alih, menentukan apa informasi yang Anda terima? Sejauh mana Anda memiliki kekuasaan itu? Siapa sekarang gate keeper-nya, ketika misalnya rata-rata pengunjung media itu tidak langsung datang ke media tersebut, bukan direct traffic tapi referral traffic, dari medsos, atau organic traffic dari search engine?" dia bertanya.
Sementara itu, katanya, sebetulnya yang datang langsung ke situs media rata-rata hanya 10-20 persen, yaitu mereka yang langsung mengetik nama medianya di browser. Atau langsung dari app yang sudah di-download. Selebihnya datang dari berbagai link yang disebar di sejumlah platform.
"Kalau begitu, siapa yang menguasai algoritma, yang menentukan mana link yang muncul di screen kita, di feed kita? Kalau ada perubahan algoritma yang membuat feed atau konten-konten dari publisher untuk tidak muncul, atau untuk tidak muncul sesering yang seharusnya, maka itu akan membuat pembaca berita-berita jurnalistik menurun juga secara signifikan," jabarnya.
Wahyu menilai interelasi antarplatform atau users versus platform juga salah satu isu yang penting ketika membahas jurnalisme digital di era sekarang. Itu semua terangkum dalam paparannya sebagai pemicu diskusi pada topik tentang 'Jurnalisme Indonesia Kini: Tantangan, Peluang dan Ancaman bagi Jurnalis.'