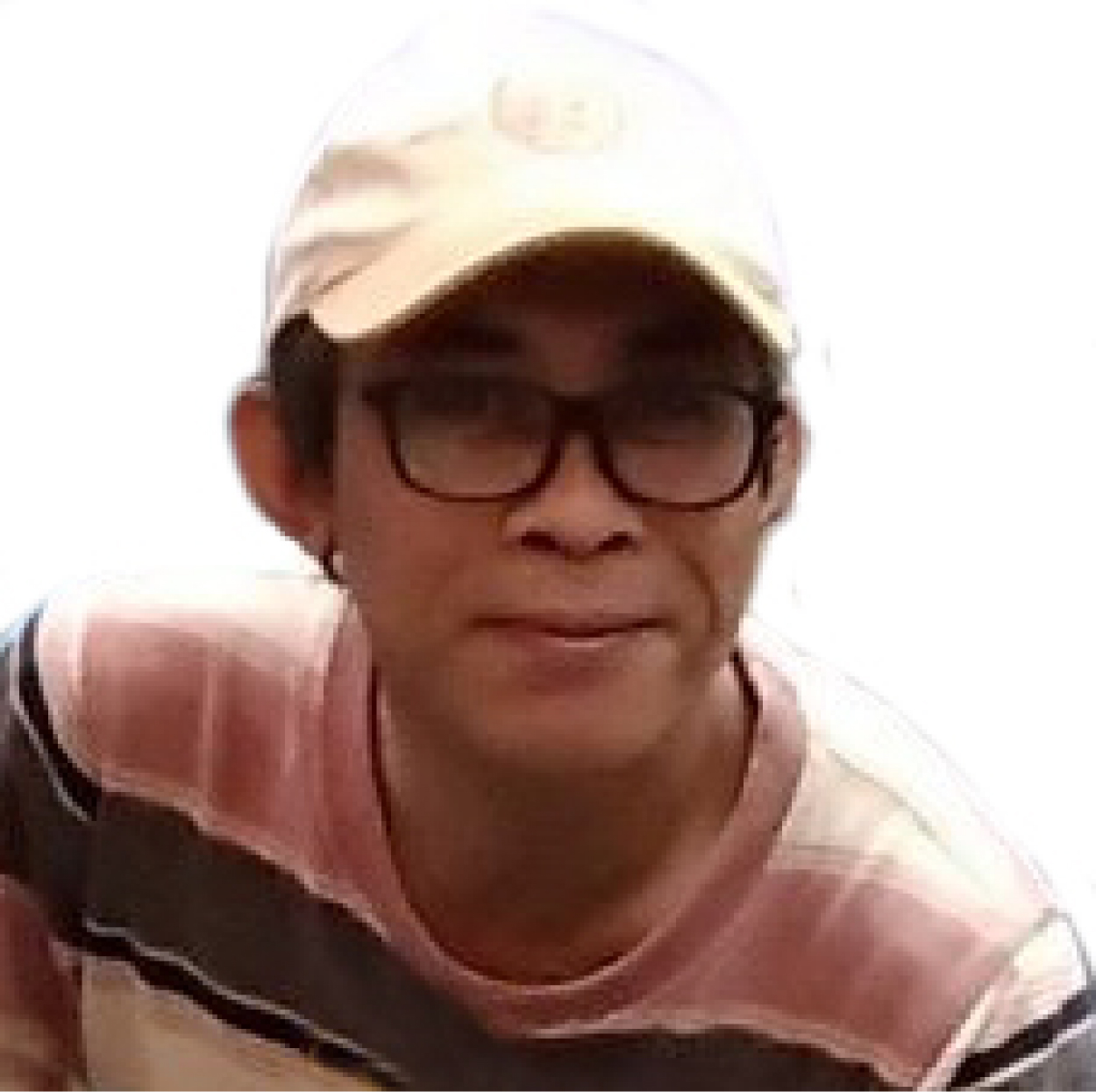Isu krisis iklim diterpa misinformasi yang bersifat menebarkan keraguan. Berbagai info sesat tersaji, bahkan di media, dalam konteks global. Platform media sosial yang sehari-hari melekat di tangan seperti Google dan Facebook, keduanya sangat berperan besar dalam menyuburkan misinformasi krisis iklim.
"Salah satu platform media di mana informasi-informasi yang menyesatkan tentang krisis iklim itu beredar paling banyak di Facebook," kata Aulia Dwi Nastiti, peneliti di Remotivi, sebuah lembaga studi dan pemantauan media, menjabarkan data riset peliputan media global.
Menurut Nastiti, penelitian itu dari Center for Countering Digital Hate (CCDH: organ non-pemerintah Inggris). Ditemukan bahwa sumber-sumber informasi yang menyesatkan lebih cenderung sebagai disinformasi dalam kampanye yang sistematis. Terbanyak dari sepuluh media genre konservatif yang disebut The Toxic Ten (sepuluh media penyangkal krisis iklim).
Diketahui, ternyata Facebook mendapat banyak sekali iklan dari mereka (The Toxic Ten). Begitu juga dengan Google. Jadi, sekarang kampanye soal krisis iklim itu mulai banyak yang menargetkan platform media yang besar seperti Facebook.
"Media besar (Facebook) harus ikut bertanggung jawab karena memberi panggung kepada The Toxic Ten media ini," tegasnya.
Contoh lain kampanye sistematis disinformasi, yang pernah dimuat The Guardian, bahwa dari tahun 80-an ternyata perusahaan-perusahaan minyak dunia seperti Shell, ExxonMobil, dan perusahaan tambang Freeport sering memasang iklan propaganda.
Dalam artian, membuat orang-orang meragukan krisis iklim, misalnya melalui iklan bahwa krisis iklim tidak membahayakan atau tidak relevan dengan industri minyak dunia. Pernyataannya: Krisis iklim ada tapi tidak ada kaitan dengan industri minyak.
"Salah satu kesalahan besar media juga adalah memberi panggung, dan mendapat uang dari kampanye-kampanye sistematis buat mengecilkan urgensi perubahan iklim. Ini fenomena di media level global," cetus Nastiti dalam diskusi daring, Selasa (5/3).
Ia kemudian beralih perhatian ke media di Indonesia. Katanya, media-media di Indonesia salah satu hobinya kalau meliput soal bencana alam itu seringkali menonjolkan sensasi bukan sains.
"Kalau misalnya melihat di akhir tahun biasanya seringkali di media-media online banyak sekali berita yang ada kunci: 'bencana dan indigo.' Seringkali media seperti meramal, tahun depan bencana apa, terus sumbernya adalah peramal atau anak indigo. Ini kan cuma menonjolkan sensasi, tidak ada sains sama sekali," dalih Nastiti.
Padahal, tambahnya, fenomena bencana alam itu sebenarnya adalah momen atau peluang di mana media semestinya bisa mengedukasi publik bahwa bencana terkait sistematisnya dengan perubahan iklim. Krisis iklim sudah menjadi fenomena dalam jangka panjang ke belakang.
Kesalahan media berikutnya di Indonesia, yang dia lihat, yaitu juga mengamplifikasi agenda-agenda yang mengecilkan urgensi krisis iklim.
"Ironisnya, agenda yang berusaha mengecilkan urgensi ini juga seringkali keluar dari pernyataan pemerintah sebagai pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab. Kan dibilang kalau kebijakan pemerintahlah yang paling berdampak?" ujar Nastiti.
Diteruskannya, tidak jarang pernyataan pemerintah justru seolah mengecilkan urgensi krisis iklim. Itu kemudian ditelan mentah-mentah oleh media, tanpa upaya untuk mengkritisi. Baru-baru ini, yang paling ramai, perdebatan soal laju deforestasi antara KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) kontra Greenpeace.
Terus ada juga sejumlah pernyataan pemimpin KLHK yang kontroversial. Misalnya seperti: Karena ada Undang-undang Cipta Kerja, jangan risau mengkomodifikasi hutan.
Pemimpin KLHK terlihat menonjolkan prestasi pemerintah, terus menggiring publik untuk beranggapan bahwa krisis iklim tidak separah yang dibayangkan. Sekaligus memunculkan persepsi bahwa narasi soal krisis iklim, yang selalu digaungkan organ non-pemerintah atau digemakan bahkan oleh publik itu sendiri, bahwa orang-orang begitu khawatir, terlalu membesar-besarkan masalah.