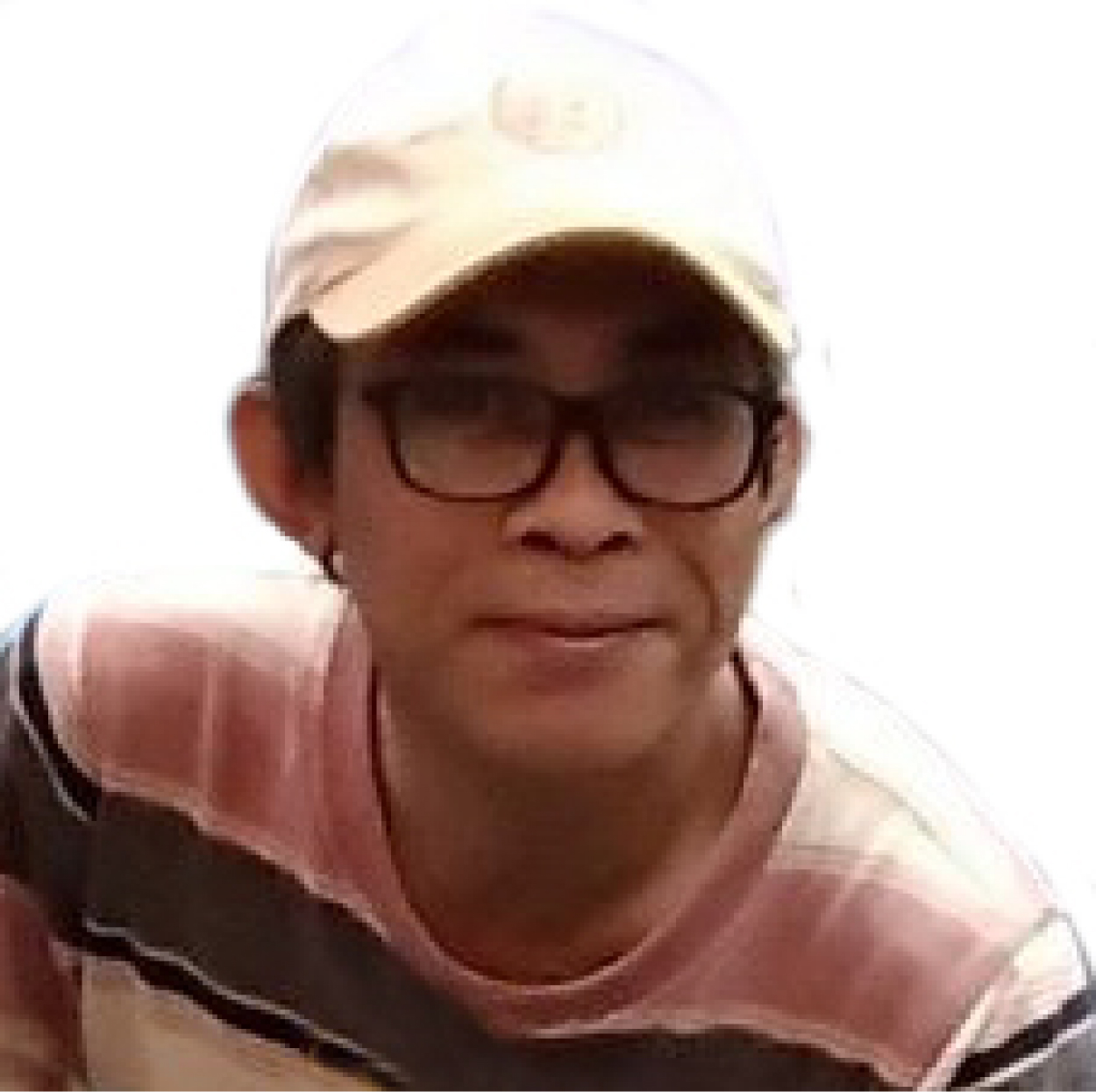Tren pamer sepeda agar diapresiasi di media sosial
Perubahan perilaku dalam berkomunikasi adalah topik yang tidak akan ada habisnya untuk dibahas. Karena manusia pada dasarnya selalu akan berubah dan beradaptasi terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Termasuk ketika terjadi pandemi Covid-19, yang tidak hanya berdampak pada isu kesehatan, ekonomi, tapi juga gaya hidup menuju new normal. Pada akhirnya, orang mencari bagaimana gaya hidup new normal itu. Tren gaya hidup sehat jadi berkembang. Dan tren yang paling besar pada saat itu adalah tren bersepeda.
Latar itu diuraikan oleh Rizki Saga Putra dalam karya ilmiahnya, 'Presentasi Diri dalam Interaksi Bermediasi Teknologi (Studi Kasus Konten Instagram Bersepeda di Masa Pandemi)'. Rizki berbicara dalam serial seminar nasional Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) U di tayangan kanal FISIP UI, Senin (27/5).
Saat pemerintah menetapkan kebijakan seperti Work From Home, local lockdown, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dan istilah-istilah lainnya, otomatis mobilisasi masyarakat juga terbatasi.
"Masyarakat kita ini alih-alih disuruh membatasi kegiatan di luar, malah atas dasar ingin menjaga kesehatan justru memilih berolahraga di luar. Salah satunya, bersepeda," ujar Rizki.
Kenapa bersepeda? Alasannya simpel, sepeda itu dirasa merupakan kegiatan olahraga individu dan dinilai bersifat rekreasi. Dari situ mulai tren sepeda semakin lama semakin meledak.
Sebenarnya tren sepeda sebelum pandemi sudah ada. Pada saat itu, trennya sepeda lipat seperti Brompton. Saat terjadi pandemi, tren justru makin masif berkembang. Orang semakin ingin menunjukkan diri ikut berpartisipasi dalam tren bersepeda menuju new normal lewat sosial media, khususnya Instagram.
Banyak yang posting membeli sepeda lipat, terus gowes ke mana-mana, tidak beberapa lama beli sepeda Road Bike, ikut peleton di Senayan, dan sebagainya. Kenapa mereka menunjukkan di media sosial? Alasannya simpel, karena kegiatan masyarakat pada saat awal pandemi itu terbatasi.
"Akhirnya switching dari konvensional ke digital. Otomatis insting manusia untuk diakui keberadaannya juga ikut pindah ke media sosial. Bahkan fenomena yang terjadi tidak cuma media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan sebagainya. Screenshot dari hasil aplikasi tracking kesehatan seperti Endomondo, Strava, Relive, itu juga dimasukkan ke media sosial," cetusnya.
Semua itu dilakukan, kata Rizki, untuk memperoleh kesan positif oleh orang-orang yang melihat. Misalnya, hari ini seseorang sudah bersepeda 50 kilometer, besok posting lagi: sudah sepedaan 100 km. Hari ini, average speed 20, besok 30 km per jam, dan seterusnya.
"Dari fenomena ini akhirnya saya coba kupas dari sisi dramaturgi, yang fokus kepada panggung depan. Karena pada dasarnya dalam interaksi sosial antarmanusia, kita sebagai aktor yang bermain di atas panggung, mempresentasikan diri kita, dan berharap penonton akan menerima dengan kesan positif, serta terhadap manipulasi simbol yang kita lakukan," serunya.
Rizki mengutip itu sebagai konsep dari Erving Boffman, yang sifatnya konvensional. Di mana proses itu terjadi lebih kepada interaksi tatap muka baik antara individu maupun dengan banyak audiens. Lantas, bagaimana kalau presentasi diri itu dilihat dari perilaku manusia di media sosial?
"Karena pada dasarnya kita sebagai manusia itu akan selalu berubah peran, tergantung siapa penonton kita. Misalnya kita mau mengobrol sama teman kita lagi makan siang. Pasti sikap dan perilaku kita akan sangat berbeda ketika misalnya kita pertama kali ketemu sama calon mertua. Kita sebagai aktor akan memposisikan diri sebagai orang yang layak disukai," imbuhnya.
Menurut Rizki, kondisi perubahan peran serta aktor ini justru sangat sulit dilakukan dalam interaksi bermediasi teknologi. Dalam hal ini, media sosial. Karena pasti kalau kita posting sesuatu, yang melihat postingan kita itu tidak cuma orang terdekat kita, bahkan orang yang tidak kita kenal pun bisa melihat postingan kita.
"Maka dalam penelitian ini saya coba telaah dengan mengadaptasi beberapa konsep yang diinisiasi oleh Michael Devito tentang presentasi diri dalam komunikasi bermediasi teknologi. Sekaligus mau melihat apa saja strategi yang membentuk presentasi di media sosial melalui bersepeda," ungkapnya.
Untuk itu, Rizki menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus supaya penelitian ini bisa mendapat gambaran menyeluruh atas fenomena ini. Data yang diambil berupa data primer dari wawancara beberapa narasumber dan data sekunder dengan observasi media sosial serta berita-berita terkait tren bersepeda.
"Hasil penelitian yang diperoleh itu sejujurnya membuat saya agak terkejut. Ternyata lebih baik kreasi konten Instagram mereka itu butuh modal dan usaha yang besar buat saya. Pada akhirnya memunculkan istilah Bike to Content di media sosial, jadi orang-orang pada saat itu bersepeda tidak cuma berolahraga, tapi juga bikin konten di Instagram," tuturnya.
Para pegiat sepeda mencari latar foto, misalnya di kafe, taman rekreasi, pusat perbelanjaan yang mewah di Jakarta, misalnya. Jadi banyak yang berbondong-bondong gowes pagi atau sore, mencari sarapan atau ke tempat-tempat yang hits di Instagram cuma buat berfoto ke depan Kafe A. Atau di tengah-tengah gedung Kuningan atau di Bintaro, yang waktu itu sampai sekarang, biasa disebut Gang Potlot atau Bintaro Loop. Bahkan ada beberapa foto di area wisata yang tutup selama pandemi seperti foto-foto di Ragunan, Sunda Kelapa, segala macam.
"Latar foto ini pada dasarnya memberikan simbol bahwa seseorang di masa pandemi ini berolahraga sepeda di Gang Potlot, terus ngumpul di Senayan City, berlanjut ngopi di Starbucks, misalnya," ujar Rizki.
Di sisi lain, sambungnya, latar belakang ini juga menyiratkan selain sehat, orang-orang Ini juga masih melakukan kegiatan sosialita di kawasan elite.
"Belum lagi foto mereka dengan menggunakan sepeda yang mahal. Awal pandemi, saya ingat, waktu itu sepeda lipat itu jadi incaran, khususnya merek-merek seperti Brompton misalnya yang pasti harganya sudah 'digoreng' habis-habisan," katanya.
Rizki mengungkapkan, masih banyak orang yang membeli, padahal harga sepeda yang tadinya mungkin Rp10 juta, bisa jadi Rp30 juta, dari Rp30 juta melonjak Rp100 juta. Sudah tidak masuk akal, tapi mereka rela membeli. Ini menurut pengakuan narasumbernya: merasa sepeda lipat itu "kurang serius" akhirnya masyarakat banyak yang beralih ke Road Bike.
"Kalau kita melihat komentar-komentar di media sosial, banyak yang bilang: 'Wah itu sih sepeda sultan!' Untuk menggambarkan betapa mahalnya jenis sepeda itu sampai dikatakan cuma sultan yang bisa membeli. Belum Lagi apparel yang dipakai seperti jersey-jersey merek premium, yang harga satuannya sekitar Rp2-3 jutaan," tukasnya.
Belum lagi sepedanya yang di-update misalnya pakai Gear Set Wireless. Sudah begitu sepedanya full carbon, jadi enteng, dan bisa melaju lebih kencang. Ketika mereka posting juga ditambah caption cek akun ofisial brand yang dipakai untuk memvalidasi bahwa mereka membeli barang asli bukan barang KW (palsu).
"Pada dasarnya pamer kegiatan ini bukan semata-mata hanya ingin disukai, tapi juga ingin diapresiasi di media sosial," kata Rizki, Magister Komunikasi Universitas Indonesia, yang bergairah dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab akademik.