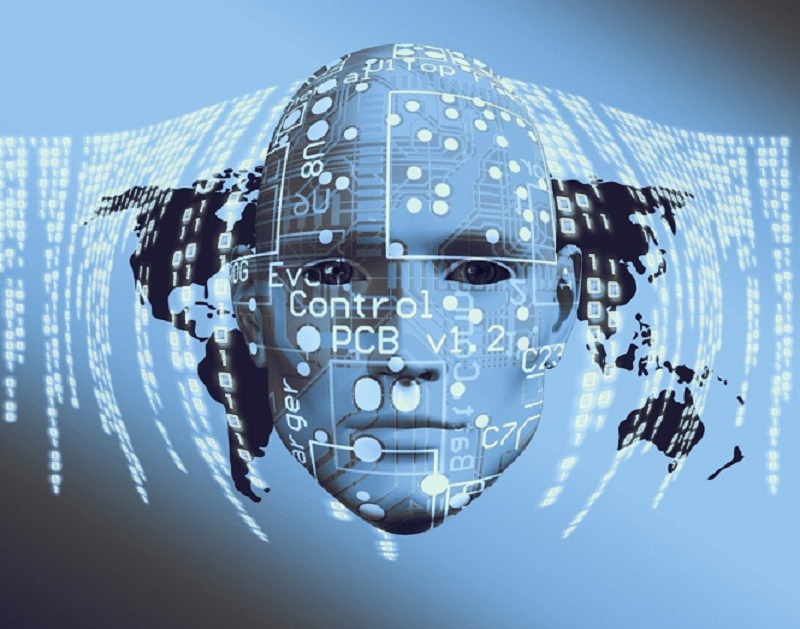Bukit Algoritma dan skandal di lembah teknologi
Saat kali pertama menginjakkan kaki di Stanford University, Elisabeth Holmes adalah mahasiswi yang kepalanya penuh dengan gagasan-gagasan futuristik. Masih berusia 18 tahun, ia bahkan punya mimpi menciptakan sebuah patch (tambalan) digital yang mampu memindai infeksi di tubuh penggunanya dan menginjeksi antibiotik.
Holmes terobsesi dengan ide itu. Pada suatu kesempatan, ia curhat ke Phyllis Gardner, seorang profesor bidang medis di Stanford University. Sang profesor bilang tak mungkin antibiotik yang ingin diinjeksi ke tubuh pengguna bisa disimpan dalam sebuah patch kecil.
"Dia seorang anak muda yang hanya punya pengalaman ikut pelatihan engineering mendasar dan sama sekali tidak punya pengalaman medis," kata Gardner saat mengenang Holmes seperti dikutip dari The Wallstreet Journal.
Meski gagasannya dianggap mustahil, Holmes menolak kalah. Pada 2003, Holmes drop out dari Stanford University dan merintis perusahaannya sendiri, Theranos. Setelah memeroleh investasi yang cukup, ia memulai eksperimen untuk merealisasikan gagasan tersebut.
Pada 2014, Holmes menamai alat yang ia kembangkan TheraPatch. Namun, sebagaimana ramalan Gardner, TheraPatch ternyata terlalu futuristik. Holmes pun mengerucutkan risetnya pada pengembangan mesin portabel yang bisa menganalisis lusinan tes laboratorium hanya dari setetes darah pasien.
Setelah TheraPatch masuk gudang, Theranos fokus mengembangkan Edison, alat sebesar printer yang didesain untuk mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen dalam darah. Selain itu, Theranos juga mengembangkan miniLab, sebuah laboratorium superkecil yang memungkinkan robot-robot bekerja untuk mengetes sampel darah.
Pada akhir 2013, Theranos mulai menawarkan tes darah murah ke publik. Bekerja sama dengan Walgreens Boots Alliance Inc, Theranos membuka gerai di Phoenix, California dan Pennsylvania. Ketika itu, kehadiran Theranos digadang-gadang bakal menghancurkan bisnis tes darah senilai US$75 juta yang dimonopoli segelintir perusahaan raksasa di AS.
Investasi ke Theranos terus mengalir. Pada 2014, Fortune melaporkan Theranos meraup sekitar US$400 juta dari penjualan saham ke publik (IPO). Perusahaan rintisan itu diperkirakan bernilai US$9 miliar dan kekayaan Holmes ditaksir mencapai US$4,5 miliar.

Pada tahun yang sama, Theranos merampungkan markas barunya di 1701 Page Mill Road, Palo Alto, Silicon Valley, Bay Area, California, AS. Holmes dilaporkan menghabiskan US$26 juta untuk membangun gedung baru itu. Sewa gedung dan lahan diperkirakan sebesar US$1 juta per bulan.
Kejayaan Theranos dan Holmes hanya berumur pendek. Pada Oktober 2015, jurnalis investigasi Wall Street Journal (WSJ), John Carreyrou merilis laporan yang menunjukkan teknologi yang dikembangkan Theranos hanya "tipu-tipu".
Dari serangkaian email perusahaan, Carreyrou menemukan bahwa hasil tes yang dijalankan Edison tidak akurat. Pada salah satu email, Chief Operations Officer (COO) Theranos, Sunny Balwani--ketika itu kekasih Holmes--terlihat berupaya menginstruksikan agar hasil tes dari Edison tidak dilaporkan kepada pemerintah.
"Sejumlah mantan pegawai mengatakan Balwani memerintahkan agar personel lab berhenti menggunakan Edison untuk tes darah dan hanya melaporkan hasil dari instrumen yang dibeli Theranos dari perusahaan lain," tulis Carreyrou.
Holmes tentu saja tak tinggal diam. Dalam berbagai kesempatan wawancara dengan media, Holmes mencoba menepis semua tudingan miring terhadap Theranos dan teknologi yang tengah ia kembangkan.
"Artikel (WSJ) itu cukup brutal. Inilah yang terjadi ketika kamu bekerja untuk memperbaiki sesuatu. Pertama, mereka pikir kamu gila, kemudian mereka mencoba melawan kamu, dan akhirnya kamu mengubah dunia," kata Holmes dalam Mad Money di CNBC.
Setelah artikel itu, Carreyrou menulis dua artikel lainnya yang mengungkap kebohongan-kebohongan Theranos lainnya. Laporan investigasi WSJ itu viral. U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) kemudian menggelar penyelidikan terhadap Theranos.
Pada 2018, SEC mendakwa Theranos dan Holmes melakukan penipuan dengan merilis klaim-klaim palsu mengenai keampuhan teknologi yang mereka kembangkan. Holmes--dulu pernah dibanding-bandingkan sebagai titisan Steve Jobs--kini duduk di kursi pesakitan. Mimpi mengubah dunia ambyar.
Pada 2019, kisah Holmes dan Theranos diabadikan oleh HBO dalam film dokumenter bertajuk The Inventor. April lalu, Bad Blood, film berbasis kisah hidup Holmes, juga telah tayang di bioskop. Holmes diperankan artis pemenang Oscar, Jennifer Lawrence.
![]()
Lembah skandal dan kegagalan
Meski jadi salah satu yang paling menggemparkan, Theranos hanya satu dari sekian banyak startup yang gagal dan bangkrut di Silicon Valley. Holmes juga bukan satu-satunya wirausahawan muda yang bisnisnya dipenuhi skandal di utopia teknologi itu.
Sebelumnya, Sillicon Valley juga pernah punya David Billow, co-founder dan CEO Secret, perusahaan pengembang aplikasi bertukar pesan rahasia di IOS dan Android. Sebelum melahirkan Secret, Billow adalah salah satu teknisi di Google.
Kehadiran Secret kali pertama dilaporkan TechCrunch pada Desember 2013. Pada awal 2014, aplikasi itu meluncur untuk kalangan terbatas di Sillicon Valley. Tak butuh lama, Secret langsung jadi sensasi dan mulai meraih popularitas di jagat maya.
Tak seperti aplikasi serupa lainnya, semisal Whisper dan Yik Yak, Secret didesain terutama untuk berbagi bersama teman-teman kolega saja. Pembatasan seperti itu membuat Secret menarik dan adiktif bagi para pengguna.
Secret pun berkembang cepat. Pada masa kejayaannya, Secret pernah punya 15 juta pengguna dan meraup investasi hingga US$35 juta. Namun, Secret juga dibekap kontroversi setelah aplikasi itu dijadikan medium untuk menyebar fitnah dan perundungan.
Pada Januari 2015, di tengah derasnya kritik terhadap aplikasi itu, Byttow memutuskan menghentikan operasional Secret. "Ini (anonimitas) adalah pedang bermata ganda, yang harus digenggam dengan hati-hati," kata Byttow saat mengumumkan pembubaran Secret.
Ketika itu, Byttow diduga telah mengantongi jutaan dollar, sebagian digunakan untuk membeli sebuah mobil Ferari, dari para pemodal Secret. Bill Maris, salah satu investor menyamakan penutupan Secret yang mendadak sebagai sebuah kasus perampokan bank.
Skandal dan kegagalan tak hanya membekap perusahaan rintisan di Sillicon Valley. Perusahaan-perusahaan raksasa atau yang dulu pernah besar pun mengalaminya. Di Yahoo, misalnya, kegagalan merupakan buah dari kekeliruan memilih bos.
Pada awal 2012, Yahoo menunjuk Scott Thompson sebagai CEO. Setelah hanya empat bulan menjabat, Thompson ditendang karena kedapatan memalsukan ijazahnya. Dalam dokumen SEC, Thompson menyatakan memegang gelar akuntansi dan ilmu komputer dari Stonehill College. Padahal, Thompson hanya mengantongi gelar S1 akuntansi.
Penerus Thompson, Marissa Mayer tak lebih baik. Kepemimpinan bekas petinggi Google di Yahoo itu diwarnai pesta-pesta koktail, gugatan hukum dari sejumlah eks pegawai pria, akuisisi terhadap perusahaan rintisan yang kemudian kebanyakan mati, dan skandal pembobolan data 500 juta pengguna pada 2014.
"Dia berperilaku bak CEO perusahaan senilai US$30 miliar. Padahal, kalau kepemilikan di Alibaba dan Yahoo! Jepang dikeluarkan dari hitungan, Yahoo hanya perusahaan senilai US$3 miliar," kata Eric Jackson, salah satu investor Yahoo, saat mengomentari pesta super mewah bergaya Great Gatsby yang digelar Mayer saat ultah Yahoo ke-20 pada 2015.
Mayer dilaporkan menghabiskan miliaran dollar untuk membangkitkan Yahoo dari keterpurukan. Sayangnya, berbagai upaya itu gagal. Pada 2017, Mayer mundur dari posisinya sebagai CEO. Yahoo kini dijual ke Verizon, raksasa telekomunikasi AS. Meskipun masih mempertahankan Yahoo email, Yahoo Group kini dihapus.
Selain lembah kegagalan, Sillicon Valley juga dikenal dengan sebutan Brotopia atau tanah bagi kaum lelaki. Dalam survei bertajuk "Elephant in the Valley" yang dirilis pada 2016, Trae Vasallo dan sejumlah rekannya menemukan bahwa mayoritas perempuan yang bekerja di Silicon Valley mengalami diskriminasi karena jenis kelamin mereka.
Dalam survei itu, Trae dan kawan-kawan mewawancarai lebih dari 200 perempuan yang telah 10 tahun bekerja di Silicon Valley. Sejumlah statistik mengemuka. Sebanyak 47% responden, misalnya, mengaku kerap ditugasi pekerjaan-pekerjaan "receh" seperti mencatat hasil rapat atau membeli makanan.
Selain itu, 66% responden menyatakan mereka tak pernah diajak dalam even-even penting perusahaan karena gender. "Sebanyak 75% perempuan juga ditanyai tentang kehidupan rumah tangga mereka, status perkawinan, dan anak-anak mereka saat wawancara kerja," tulis Trae cs.
Dalam sejumlah kasus, skandal pelecehan seks yang melibatkan petinggi perusahaan di Silicon Valley juga terkuak. Pada Oktober 2018, misalnya, New York Times merilis laporan mengenai pelecehan-pelecehan seksual yang melibatkan petinggi Google.
Salah satu kasus menjerat pencipta software Android, Andy Rubin. Di antara beragam laporan lainnya, Rubin dilaporkan memaksa salah satu rekan kerjanya di Android untuk seks oral di sebuah hotel. Meskipun hasil investigasi Google membuktikan itu, Rubin hanya diminta mundur baik-baik dengan pesangon fantastis sebesar US$90 juta.

Eksodus di Sillicon Valley
Dalam sebuah unggahan di medium.com, pendiri Karbon, Stuart McLeod mengatakan hidup di Sillicon Valley "tak lagi menyenangkan". Menurut dia, reputasi Sillicon Valley terus terancam karena rentetan skandal yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di antaranya kontroversi kebocoran data Facebook-Cambridge Analytica dan isu pelecehan seksual di Google.
"Dan para pemimpin di dunia teknologi itu tidak berbuat apa-apa. CEO-CEO perusahaan besar tetap dengan gaya hidup mewah mereka, membuang-buang duit, dan berebut kuasa. Anggota kongres Ro Khanna bahkan mengakui bahwa sebagian insinyur di Silicon Valley adalah yang paling egois di seluruh dunia," tulis Mcleod.
Karbon adalah perusahaan yang memproduksi aplikasi manajemen kerja khusus untuk firma-firma akuntansi. Pada 2019, McLeod memindahkan bisnisnya ke Lake Tahoe, Nevada. Selain karena gerah dengan skandal, ia mengaku keputusan relokasi diambil karena biaya hidup di kawasan Bay Area tak lagi masuk akal.
"Saya harus membayar US$60 ribu untuk pajak per tahun dan sekitar US$20 ribu untuk perawatan properti. Ketika akan mengirimkan anak-anak ke sekolah menengah, harga sekolah swasta itu US$40 ribu per anak dan saya punya tiga. Kamu setidaknya harus menghasilkan sekitar US$1 juta per tahun untuk tinggal di sana," jelas dia.
Bukan hanya Mcleod saja yang merasa begitu. Hasil survei Brunswick Group--sebuah firma yang berbasis di Inggris--terhadap ratusan pekerja di Bay Area yang dirilis pada akhir Maret 2019 menunjukkan bahwa sebagian pekerja muda di Silicon Valley serius mempertimbangkan untuk relokasi.
Dalam survei bertajuk "Siliconfidential" itu, sebanyak 41% pekerja di Bay Area berusia 18-34 tahun menyatakan berniat untuk pindah. Pada rentang usia 35-44 tahun, sebanyak 26% responden menyatakan hal serupa. Namun, mayoritas responden berusia di atas 45 tahun tak berniat untuk hengkang.
"Saya kenal sejumlah enterpreuner di jaringan saya yang juga memutuskan pindah...Jika tren ini terus berlanjut, Silicon Valley yang kita kenal sekarang mungkin bisa saja hanya jadi sejarah," ujar Mcleod merujuk pada hasil survei tersebut.

Pada 2020, eksodus dari Silicon Valley juga masih berlanjut. Tesla, Oracle, Londonsdale VC, The Dropbox, Filetrail, DZS Inc, dan QuestionPro, misalnya, sudah memindahkan kantor pusatnya atau sebagian bisnisnya keluar dari Silicon Valley.
Hewlett Packard (HP) Enterprise bahkan telah mengumumkan rencana untuk merelokasi markasnya dari San Jose ke Houston, Texas. Padahal, para pendiri HP, Bill Hewlett and Dave Packard, adalah perintis Silicon Valley. Garasi tempat Hewlett dan Packard bekerja di Palo Alto pada 1938 kini bahkan dijadikan ikon Silicon Valley.
Jika Silicon Valley tengah ditinggalkan para pebisnis dan para geeks, Indonesia malah baru mewacanakan membangun Silicon Valley-nya sendiri. Awal April lalu, pendiri Inovator 4.0 Budiman Sudjatmiko gembar-gembor bakal mendirikan pusat fusi sains dan teknologi di Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat.
Untuk merealisasikannya, Budiman menggandeng PT Bintangraya Lokalestari yang lahannya bakal dipakai. Saat ini, proyek itu punya nama beken Bukit Algoritma. Investor-investor, diklaim politikus PDI-Perjuangan itu, juga sudah ngantre.
Jika tidak ada aral melintang, pengerjaan Bukit Algoritma diperkirakan bakal rampung dalam 11 tahun. Yang jadi pertanyaan, mampukah bukit teknologi bikinan Budiman cs itu menghasilkan para jenius "gila" seperti di Silicon Valley?