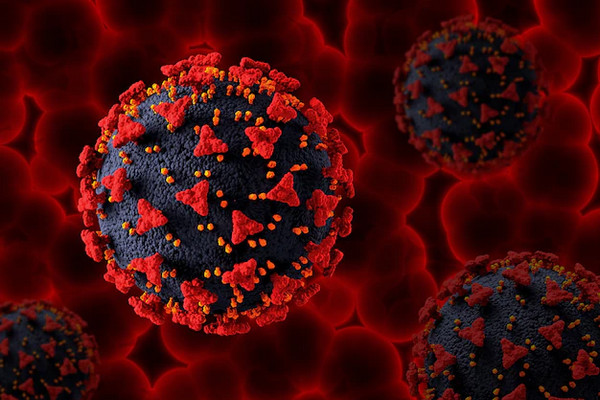Cara berjuang masyarakat adat melawan Covid-19
Bagi masyarakat Suku Osing dan Madura di Desa Papring, Banyuwangi, Jawa Timur, pandemi SARS-CoV-2 yang menyebabkan Coronavirus disease 2019 (Covid-19) mengembalikan tradisi mengelola lumbung pangan yang disebut jurung. Dalam tradisi ini, warga menyiapkan benih jagung untuk persiapan bila masuk musim tanam kembali.
Menurut Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Papring Widie Nurmahmudy, pandemi menyadarkan warga Suku Osing untuk beradaptasi. Tradisi jurung, ujar Widie, sebelumnya berangsur telah ditinggalkan sejak 2000-an.
“Tradisi penyimpanan ini setidaknya telah membantu petani dalam mempersiapkan bekal makanan jagung selama masa pandemi,” kata Widie ketika dihubungi reporter Alinea.id, Senin (25/5).
Widie menjelaskan, sebelum melaksanakan tradisi jurung, warga mengawalinya dengan ritual adat bersih desa. Ritual itu dilakukan pada April 2020, sebulan setelah ada kabar kasus pertama warga Indonesia terinfeksi Coronavirus jenis baru.
Ritual tersebut dilakukan dengan formasi empat penjuru mata angin, mengikuti protokol kesehatan, yakni jaga jarak fisik antarorang. Biasanya, ritual itu diikuti 300 kepala keluarga.
“Setelah ritual bersih desa, kampanye penyimpanan hasil pertanian, seperti jagung, kacang, jahe, cabai, dan tomat dilakukan lebih masif sebagai upaya antisipasi pangan bagi warga Kampung Papring,” tuturnya.
Peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Rusli Cahyadi menggarisbawahi, kemandirian pangan sebagai ciri khas masyarakat adat.
“Tantangan kita ialah bagaimana memproduksi sumber daya yang kita miliki untuk konsumsi dalam negeri, sebagaimana corak hidup masyarakat adat,” ucap Rusli saat dihubungi, Kamis (28/5).
Benteng pertahanan

Selain menguji daya bertahan hidup masyarakat adat, seperti yang dilakukan Suku Osing dan Madura, pandemi Covid-19 yang sudah menyebar di semua provinsi di Indonesia juga membuat masyarakat adat berjuang menangkal penularan virus mematikan yang menyerang sistem pernapasan itu.
Kearifan lokal menjadi senjata utama dalam pertarungan melawan penyakit menular tersebut. Suku Dayak Kanayatn di Desa Sepahat, Kalimantan Barat misalnya, melakukan ritual balala atau tolak bala selama tiga hari berturut-turut.
“Semua orang berada di dalam rumah selama tiga hari itu,” ujar Ketua Sekolah Adat Samabue di Desa Sepahat, Modesta Wisa, dalam diskusi daring bertajuk “Peranan Pranata Pendidikan Adat/Sekolah Adat dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”, Selasa (19/5).
Mereka pun melakukan karantina wilayah di akses-akses jalan masuk permukiman. Akses keluar-masuk hanya diperbolehkan bagi penduduk setempat yang memiliki keperluan mendesak, seperti membeli kebutuhan sembako.
“Mereka membuat pagar pembatas, setiap minggu ada waktu gilir jaga di pintu masuk,” ujar Modesta.
Sementara Direktur Sokola Institute Saur Marlina Manurung, akrab disapa Butet Manurung mengatakan, Suku Anak Dalam di Jambi—atau disebut pula Orang Rimba—menganggap penyakit menular yang berasal dari luar, tidak bisa diobati. Sebab, mereka tidak mengenal vaksin.
Butet menyebut, Suku Anak Dalam rentan dan tak bisa mengatasi penyakit secara tradisional. Terutama penyakit baru seperti Covid-19. Akibat pandemi Covid-19, menurut Butet, mereka jadi tak mau ada orang luar datang ke permukiman.
“Saya pernah satu hari datang ke rimba, mereka baik-baik saja. Tapi keesokannya, mereka batuk-batuk. Lalu, mereka menyalahkan saya,” ujar Butet saat dihubungi, Jumat (29/5).
Antropolog yang merupakan perintis dan pelaku pendidikan alternatif bagi masyarakat terpencil di Indonesia ini mengatakan, Orang Rimba mengetahui informasi pandemi Covid-19 dari guru-guru di Sokola Rimba dan Mijak Tumpang—Orang Rimba yang tengah berkuliah di kota. Biasanya, aktivis Sokola Rimba melakukan kegiatan di rimba selama tiga minggu.
“Dari situ, mereka mengerti bahwa orang terjangkit itu masa inkubasinya dua minggu. Setelah tahu, mereka memberitahu ke kepala sukunya. Mereka lalu masuk, tinggal lebih dalam ke rimba, dan minta tolong jangan ada yang tengok,” katanya.
Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ahsanta, Jambi, yang berasal juga Orang Rimba, Mijak Tampung mengatakan, sejak ratusan tahun silam Orang Rimba sudah mengenal apa yang saat ini disebut isolasi.
Mereka menyebutnya besesandingon. Tradisi ini merupakan bentuk isolasi warga yang sakit dipisahkan dari kelompok yang sehat.
“Seperti makan dilarang bersama, dilarang menggunakan pakaian dan barang bersama, tidak boleh tidur di rumah bekas orang yang punya penyakit,” tutur Mijak saat dihubungi, Jumat (29/5).
Mijak mengatakan, aturan dalam besesandingon harus sampai sehat baru bisa lagi berinteraksi dengan warga. Biasanya, orang akan “diasingkan” karena sakit, atau istilah mereka sesandiko, sekitar dua minggu.
“Mereka tidak bisa melakukan kontak dan saling memberikan barang kepada yang sehat, kecuali orang yang sehat ke orang sakit diperbolehkan,” ujarnya.
Jika orang yang sakit ingin memberikan makan ke orang yang sehat, tutur Mijak, makanan itu harus direndam dahulu di sungai yang mengalir selama beberapa jam.
“Cara ini sangat efektif untuk memberantas virus atau penyakit yang lain,” kata Mijak.
Butet menjelaskan, besesandingon dilakukan dengan menjaga jarak fisik 20-50 meter dari orang yang sakit. Menurut perempuan yang membuat Sokola Rimba sejak 1999 itu, Orang Rimba percaya semua penyakit bermuara ke hilir atau laut, dibawa oleh sungai.
“Yang sakit besesandingon tinggal di hilir, yang sehat di hulu. Kalau ada Orang Rimba dari luar, mereka harus tinggal di hilir,” tutur Butet.
Orang yang sakit dikarantina, dipisahkan di tempat khusus. Namun, mereka tak keluar dari rimba sama sekali.
“Maka, enggak mungkin Corona masuk ke situ, tanpa ada orang masuk dari luar,” ujarnya.
Sejak pandemi mengancam, sebut Butet, Suku Anak Dalam pun lebih aktif behuma betanom—kegiatan menanam ubi, tembakau, dan buah-buahan dengan cara tumpang sari di hutan.

Lebih sigap
Menurut Wakil Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan, upaya pencegahan penularan Coronavirus dalam lingkungan masyarakat adat jauh lebih ketat dibandingkan antisipasi warga di perkotaan. Hal itu, secara tak langsung didorong kesadaran akan ketersediaan fasilitas kesehatan yang minim di daerah pedalaman.
Upaya menggelar upacara adat tolak bala dan semacamnya, kata dia, menjadi sebuah respons mendasar terhadap ancaman wabah penyakit, serupa menangkal roh-roh jahat.
“Tolak bala ini untuk meningkatkan kewaspadaan bahwa ada musuh yang harus dihadapi dan diwaspadai,” ujar Abdon saat dihubungi, Selasa (26/5).
Kehidupan masyarakat adat yang sosial-komunal memungkinkan seringnya bertemu dan kontak fisik. Hal itu, kata Abdon, menimbulkan risiko penularan yang masif dan mengganggu kehidupan mereka.
“Banyak masyarakat adat ini dalam suku-suku yang berjumlah kecil, terutama di Indonesia Timur. Bila kemasukan virus, bisa punah mereka. Maka, bagi mereka tak ada pikiran kecuali mencegah penularannya,” katanya.
Potensi pangan dari alam yang bisa diracik menjadi ramuan tradisional, sebut Abdon, sangat dibutuhkan untuk memperkuat kekebalan dan daya tahan tubuh. Ia berharap, potensi ini bisa dikembangkan pemerintah sebagai bekal revitalisasi industri obat-obatan dalam negeri.
“Sistem pangan adat ini bisa jadi fondasi pangan Indonesia ke depan. Adat itu bukan hiasan, tapi pertahanan yang bisa diandalkan menghadapi bencana yang serius,” ujarnya.
Sementara itu, antropolog sekaligus Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Herry Yogaswara, ada dua konteks kerawanan masyarakat adat menghadapi pandemi. Pertama, kerawanan eksternal. Mereka dikunjungi orang dari luar dengan beragam tujuan, seperti wisata, pembangunan jalan, dan industri.
“Nah, kontak dengan mereka (orang luar) ini yang berbahaya,” kata Herry saat dihubungi, Jumat (29/5).
Kedua, kerawanan internal. Ia menuturkan, masyarakat adat sulit melakukan jaga jarak karena kehidupan mereka berguyub. Mereka biasa kontak fisik dengan jarak yang sangat dekat.
“Masyarakat adat punya pertahanan khusus dalam masa pandemi. Selain menggelar sejumlah ritual semacam tolak bala, muncul kemandirian mengelola sumber daya alam untuk kebutuhan pangan,” ujar Herry.

Di samping itu, Herry mengungkapkan, masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal untuk menghindari penyakit, seperti menghirup aroma daun tertentu atau memakai ramuan untuk memperkuat daya tahan tubuh.
Akan tetapi, agar keselamatan mereka lebih terjamin, Herry menyarankan pemerintah untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang baik dan mudah bagi masyarakat adat.
“Tugas pemerintah ialah mengurangi kerawanan dan meningkatkan ketahanan masyarakat adat,” katanya.
Butet pun menampik pandangan yang beranggapan masyarakat adat yang bersentuhan dengan alam, tak punya daya dan kerangka pertahanan diri secara mandiri. Justru alam, kata Butet, merupakan bekal dan kekuatan utama bagi manusia untuk bertahan hidup.
“Kita banyak belajar dari komunitas adat dalam menghadapi pandemi dan pencegahan dampak ke depannya. Kalau kita tidak bisa memelihara alam, alam juga tidak akan pelihara kita,” tuturnya.