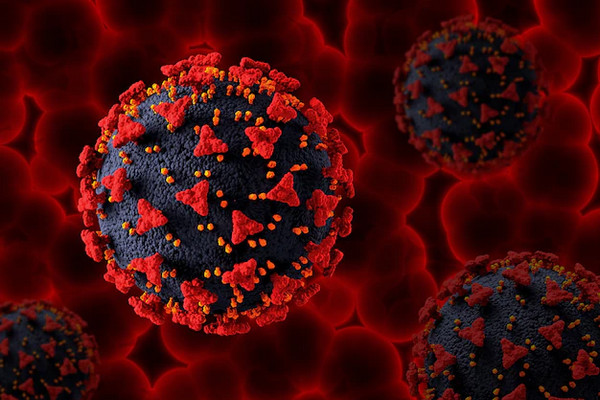Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menetapkan situasi darurat terkait penyebaran coronavirus (Covid-19) yang per Selasa (31/3) sudah menjangkiti 1.528 orang di Indonesia.
Jokowi menginstruksikan para pembantunya segera memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di seluruh Indonesia, dan jika perlu disertai dengan kebijakan darurat sipil.
“Saya minta pembatasan sosial berskala besar. Physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” tutur Jokowi dalam rapat terbatas (Ratas) penanggulangan Covid-19 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3).
Hal tersebut kemudian diluruskan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman yang menyebut, kondisi darurat sipil hanya akan dilakukan sebagai opsi terakhir dalam upaya pencegahan coronavirus. Pertimbangan darurat sipil diusulkan pemerintah hanya untuk memastikan penerapan PSBB bisa berjalan efektif.
“Namun darurat sipil adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak digunakan dalam Covid-19,” tutur Fadjroel melalui keterangan tertulis di hari yang sama.
Jika ditelaah lebih seksama, pernyataan Fadjroel itu tidaklah serta-merta menihilkan kemungkinan pemerintah menerapkan status darurat sipil jika penyebaran Covid-19 semakin parah. Sebab, mau tidak mau dan suka tidak suka, pemerintah tetap meletakkan status darurat sipil itu pada opsi terakhir penanganan Covid-19.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, wacana darurat sipil sebagai kebodohan paling berbahaya yang telah dilakukan pemerintah. Keputusan ini akan membuat banyak orang semakin kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.
Sementara di sisi lain, pemerintah belum bisa memberikan bantuan secara menyeluruh bagi masyarakat yang terdampak corona. Pada kondisi yang sangat parah, status darurat sipil justru bisa menimbulkan konflik sosial di masyarakat.
“Dan dalam kondisi yang ekstrem bisa terjadi kerusuhan sosial, khususnya konflik yang sifatnya horizontal,” tutur Bhima saat dihubungi Alinea.id, Selasa (31/3).
Wacana darurat sipil hanyalah cara pemerintah untuk menghindar dari tanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok masyarakat jika terpaksa harus dilakukan lockdown atau karantina wilayah.
Pemerintah, ingin mengganti istilah karantina wilayah dengan frasa darurat sipil yang mengacu pada Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 karena perpu tersebut tidak mewajibkan pemerintah menanggung biaya hidup masyarakat jika statusnya diberlakukan.
Sebagai perbandingan, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah diwajibkan memenuhi kebutuhan medis, kebutuhan dasar, kebutuhan pangan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya kepada masyarakat selama karantina wilayah atau lockdown berlangsung.
Sebaliknya, dalam Pasal 15 Perpu Nomor 23 Tahun 1959, pemerintah justru berhak mengambil atau menyita harta atau barang milik masyarakat yang diduga akan/dapat digunakan untuk menganggu keamanan.
“Jadi mereka (pemerintah) menghindari tanggung jawab untuk karantina wilayah sesuai dengan UU Karantina Kesehatan karena pemerintah ingin lepas tanggung jawab terkait kebutuhan pokok. Maka yang diberlakukan adalah darurat sipil,” pungkas Bhima.