
Video call sex: Antara syahwat dan “jebakan Batman” pemerasan
Rama, bukan nama sebenarnya, mengaku beberapa kali mengakses layanan seks online untuk sekadar mencari hiburan. Ia mencari pemuas syahwat ke sebuah grup di media sosial. Ia pernah bergabung ke dalam sebuah grup yang berisi konten porno di aplikasi Line.
“Hanya bayar Rp150.000 kita bisa dapat video terbaru,” ujar pemuda asal Cikarang, Jawa Barat ini kepada Alinea.id, Jumat (17/9).
“Tapi itu biasanya jam 11 ke atas, live orang lagi mesumnya.”
Tak hanya menjadi member salah satu grup di Line, Rama juga membuka aplikasi Gogo Live dan Camfrog untuk mencari layanan video call sex (VCS).
“Nah, kalau aplikasi ini, kita bayar sama admin-nya dulu Rp150.000, terus bayar Rp100.000 sama ceweknya,” kata dia.
Mencari nafkah dan modus penipuan
Di sisi lain, Anggi—nama samaran—kerap mempromosikan layanan VCS di media sosial Twitter. Perempuan 22 tahun ini juga menampilkan beberapa video dan foto vulgar di akun Twitter miliknya untuk menarik perhatian pelanggan yang butuh layanan seks virtual.
“Rp150.000 per jam, full body,” ujar Anggi, Rabu (15/9), menyebut tarif layanan VCS-nya.
Selain VCS, perempuan yang tinggal di Jakarta ini juga membuka layanan prostitusi online alias open BO dengan tarif Rp500.000 sekali kencan. Ia mengatakan, terjun ke praktik jual-beli syahwat lantaran ingin meraup uang. Namun, ia mengaku pandemi ikut menggerus pendapatannya dari kencan sesaat. Maka, ia mencoba peruntungan ke jasa VCS.

Meski demikian, ia menuturkan, bukan perkara gampang mencari pelanggan di media sosial. Sebab, belakangan banyak pemain baru yang turut meramaikan jasa VCS ranah maya.
Fitri, bukan nama sebenarnya, juga mencari penghidupan melalui jasa VCS. Perempuan asal Tangerang, Banten itu pun mematok tarif sebesar Rp150.000 sekali layanan.
“Rp150.000 itu full bugil. Mau (bayar) via rekening atau pulsa,” tutur Fitri, Kamis (16/9).
Berdasarkan pantauan Alinea.id, akun Twitter milik Anggi sering promosi ke pengguna Twitter. Sedangkan unggahan Fitri di akun Twitter miliknya terkait promosi jasa VCS, diunggah ulang sesama penyedia layanan VCS.
Fitri kerap mengunggah tangkapan layar berupa testimoni konsumen yang sudah menggunakan jasanya. Namun, ia enggan menjawab soal penghasilannya dari layanan VCS.
Meski begitu, layanan VCS tak melulu mendatangkan kenikmatan bagi Rama. Ia pernah apes karena diperas. Kisah bermula ketika Rama berkenalan dengan seorang perempuan di sebuah aplikasi pertemanan pada awal Februari 2021.
“Awalnya tukeran nomor WA (WhatsApp) dan dia cerita soal susahnya cari kerja di Jakarta,” ucap Rama.
Lalu, percakapan berlanjut di aplikasi pesan WA. Perempuan itu lantas menawarkan sebuah foto tanpa busana. Kemudian, foto tanpa busana itu dikirim ke Rama.
“Dari situ, saya udah punya perasaan enggak enak karena saya enggak minta,” kata dia.
Tak sampai dua menit foto itu dikirim, perempuan tersebut langsung meminta sejumlah uang kepada Rama. “Percakapan berisi foto tersebut pengen dia share ke media sosial, biar saya malu,” tuturnya.
Terus menerus diancam, akhirnya Rama menuruti permintaan perempuan itu. “Saya kasih Rp150.000, daripada ribet nanti,” ujar dia.
Sejak saat itu, Rama mengaku kapok berhubungan dengan akun penyedia layanan seks berbasis virtual. “Ternyata banyak sindikat penipuan dan pemerasan di situ,” ucap Rama.
Dari penelusuran Alinea.id, memang ada beberapa akun Twitter yang ternyata menipu dengan modus menyediakan layanan VCS. Akun ini memeras korbannya dengan cara merekam aktivitas pelanggan, lalu mengancam akan menyebarkan video pelanggan bila tak menuruti permintaan.
Misalnya, salah satu akun Twitter yang menawarkan layanan VCS, yang dihubungi Alinea.id. Pelaku meminta tarif Rp100.000 per jam. Pelaku meminta melakukan transfer uang.
Kemudian, pelaku berupaya menyelidiki identitas terlebih dahulu, dengan meminta menunjukkan nama asli yang tertera di bukti transfer. Setelah itu, pelaku menampilkan video bugil, hanya berdurasi tak sampai satu menit.
Pelaku lantas meminta transfer uang lagi, sebesar Rp100.000 bila ingin melanjutkan VCS. Pelaku terus mendesak agar mengirim sejumlah uang, dengan dalih proses transaksi belum berakhir.
“Rp100.000 itu hanya biaya privasi. Harus lanjut, Rp100.000 atau kirim pulsa kalau mau selesai,” katanya.
Hingga akhirnya, pelaku mengirim sebuah video yang ia rekam saat VCS dilakukan, sembari mengancam akan menyebarkannya jika tak menuruti permintaan transfer uang. Tak berhenti di situ, pelaku kemudian mengirim pesan ancaman, menggunakan nomor WA yang berbeda-beda.
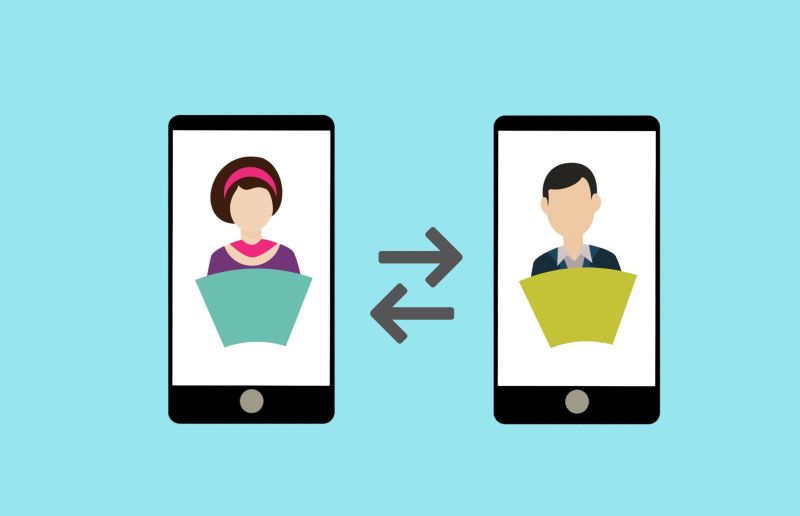
Jerat hukum
Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga (Unair) Bagong Suryanto membenarkan, praktik jual-beli syahwat di media sosial menjamur belakangan ini. Ia menyebut, pandemi menjadi pendorong utama layanan VCS berkembang di media sosial.
“Kita memang memasuki era masyarakat digital. Jadi, banyak hal bergeser ke ranah virtual. Pandemi mempercepat pergeseran ke arah sana,” kata Bagong saat dihubungi, Kamis (16/9).
Bagong menyarankan masyarakat berhati-hati dengan praktik layanan VCS karena rentan terjadi tindak kejahatan berupa pemerasan, dengan modus mengancam menyebar video ke media sosial.
"Kalau sudah mengarah ke sana, cyber crime harus turun. Penanganannya harus jalur hukum," kata Bagong.
"Konsumen perlu sadar risikonya.”
Sementara itu, Kepala Departemen Hukum Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual (TIK-KI) Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran (Unpad) Sinta Dewi mengatakan, praktik pemerasan dengan mengancam menyebar aktivitas VCS bisa dikenakan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Pasal itu menyebut apabila seseorang mendistribusikan konten pornografi itu bisa kena hukuman enam tahun penjara,” kata Sinta saat dihubungi, Sabtu (18/9).
Akan tetapi, ia menjelaskan, aktivitas VCS sendiri tak dapat dipidana, jika berdasarkan persetujuan dari masing-masing pihak dan tak disebarkan.
“Atau dengan kata lain, hanya untuk kepentingan pribadi,” ujarnya. “Di dalam UU Pornografi kalau untuk personal, tidak masuk delik.”
Persoalannya, pemerasan bermodus menyebar aktivitas VCS bisa pula menjerat korban. Pangkalnya, di dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE, terdapat frasa “mentransmisikan”, yang bisa mengkategorikan korban sebagai pihak terkait.
"Jadi, dia (korban pemerasan) bisa kena (pidana) juga, walaupun sebenarnya korban," kata Sinta.
Menurut Sinta, frasa “mentransmisikan” dalam pasal tersebut dapat merugikan korban pada kasus penyebaran konten porno. Padahal, yang perlu dijerat hukum adalah pelaku pemerasan dan penyebar konten porno, yang dihasilkan dari layanan VCS.
“Di sini ada grey area (wilayah abu-abu). Kalau dia diperas kan dia merupakan korban,” ucap Sinta.
Lebih lanjut, Sinta mengatakan, dalam melakukan VCS bisa jadi aktivitas seks direkam, tanpa diketahui. Kemudian disebarkan untuk memeras.

“Itu namanya doxing,” tuturnya.
Persoalan tindakan menyebarluaskan informasi pribadi secara publik di media sosial atau doxing, disebut Sinta patut menjadi perhatian banyak pihak. Namun, sayangnya sejauh ini doxing di media sosial belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan.
Ia menuturkan, doxing dengan tujuan kejahatan, seperti memeras seseorang, perlu segera diantisipasi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Sebab, seiring perkembangan teknologi informasi, sudah banyak pihak menjadi korban doxing.
“Biasanya doxing itu banyak terjadi pada bekas pasangan, bekas suami-istri, yang merekam aktivitas keintiman mereka,” ujar dia.
"Kemudian ketika terjadi perceraian, salah satu pihak mengancam bakal disebarkan video intimnya.”
Sinta menyarankan masyarakat agar tak mudah tergiur dengan penyedia layanan VCS di media sosial karena berisiko terjadi tindak kejahatan. Ia memandang, literasi digital di masyarakat masih kurang. Hal itu menyebabkan orang merasa dunia siber adalah dunia yang bebas dan rahasia.
“Padahal sebaliknya. Dunia siber itu sebuah dunia di mana kita dimata-matai dan diawasi oleh banyak orang. Termasuk orang jahat,” kata Sinta.








