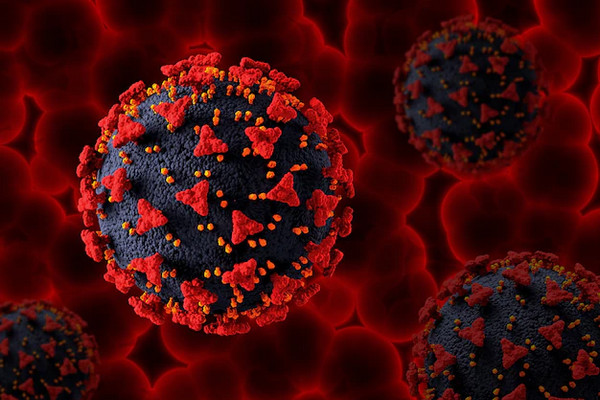Mereka yang melawan stigma dan berusaha sembuh dari Covid-19
Pada 2 Maret 2020, pemerintah mengumumkan dua warga Indonesia tertular coronavirus jenis baru atau Covid-19. Salah satu dari dua orang tersebut adalah Sita Tyasutami.
Sita mengatakan, bersama ibu dan menyusul kakaknya, mereka kemudian menjalani perawatan intensif di ruang isolasi Rumah Sakit Penyakit dan Infeksi (RSPI) Sulanti Saroso, Jakarta Utara.
Ia berkisah, gejala yang dialaminya adalah kesulitan menarik napas panjang. Saat menarik napas, Sita merasa, ada bunyi dari paru-parunya. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bunyi itu timbul karena kondisi di dalam paru-paru yang terkandung cairan. Kala itu, Sita pun merasa kondisi kesehatannya menurun.
Stigma
Perjuangan Sita untuk sembuh dari infeksi virus SARS-CoV-2 itu bertambah sulit karena muncul stigma warga terhadap statusnya sebagai pasien. Di tengah masa isolasi di rumah sakit, Sita merasa tersinggung dengan warga yang merendahkan profesinya sebagai seorang penari, dihubung-hubungkan dengan penyakit yang tengah dideritanya.
“Saya sempat menutup akun media sosial untuk menghindari komentar negatif yang menyudutkan saya,” kata dia saat dihubungi reporter Alinea.id, Sabtu (4/4).
"Mereka membombardir kami di media sosial, mencari celah untuk menjatuhkan dan menghakimi kami sebagai pasien. Jadi, kami sebagai pasien menjadi korban dua kali. Kami berperang melawan virus dan berperang melawan netizen."
Beruntung, Sita mendapat dukungan semangat dari kakaknya, Ratri Anindyajati—yang juga menjalani isolasi di RSPI Sulanti Saroso.
Ratri mengungkapkan, komentar negatif publik yang menyalahkan mereka sebagai penyebar virus, membuat hati mereka terpukul. Ia mengatakan, tekanan juga datang dari sejumlah media yang tak akurat menyampaikan informasi. Misalnya, kata dia, sebuah siaran televisi yang menyebut pasien 01 dan pasien 02 dalam kondisi kesehatan masih tidak membaik.
“Saat menonton berita itu di TV, kami jadi bertanya-tanya karena justru kondisi kami semakin membaik,” ucap Ratri saat dihubungi, Sabtu (4/4).
Berbeda dengan Sita, Ratri justru merespons warganet yang menyudutkan mereka dengan informasi valid. Ia membuat dan mengirimkan pesan positif tentang kondisi mereka di ruang isolasi melalui akun Instagram-nya.
“Kami merasa privasi kami jadi terganggu banget. Untungnya banyak juga yang membela hak privasi kami,” tutur Ratri.

Perlahan, mental Sita, Ratri, dan ibunya kembali bangkit. Sita dan Ratri dinyatakan sembuh dari Covid-19, dan diperbolehkan pulang pada 13 Maret 2020. Ibunya menyusul tiga hari kemudian.
“Seharusnya Covid-19 dipandang sebagai sebuah problem kemanusiaan yang membangun keprihatinan bersama,” ujar Sita.
Stigma bukan hanya terjadi pada pasien Covid-19. Hal itu pun menimpa tenaga kesehatan yang tengah berjuang merawat pasien.
Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah mengatakan, beberapa perawat dan dokter di RSUP Persahabatan, Jakarta mendapat tudingan miring dari warga sekitar tempat tinggal mereka di kawasan Jakarta Timur. Mereka pun terpaksa menginap di rumah sakit selama dua malam.
“Mereka tidak diterima di kosannya. Bukan diusir, tapi disindir-sindir,” kata Harif saat dihubungi, Jumat (3/4).
Untungnya manajemen RSUP Persahabatan menyikapi hal ini dengan menyediakan hotel dan transportasi antar-jemput bagi petugas medis mereka.
Harif menegaskan, penyediaan tempat tinggal khusus bagi tenaga kesehatan yang menangani penyakit menular seperti coronavirus merupakan standar dalam operasional dan teknis pelayanan.
“Setelah bertugas selama 14 hari kerja, maka 14 hari berikutnya itu masa karantina. Masalahnya kemarin kan belum disiapkan fasilitas tempat tinggalnya,” ucapnya.
Ia mengatakan, prosedur seperti itu sudah dipraktikkan di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, sebagai salah satu rumah sakit darurat Covid-19.
Minimnya informasi
Menurut Harif, stigma sebagian masyarakat terhadap tenaga kesehatan terjadi karena keterbatasan alat pelindung diri (APD) beberapa minggu yang lalu. Warga pun tak mendapatkan informasi yang jelas, sehingga timbul prasangka.
“Mereka jadi berasumsi dan takut kalau-kalau terpapar dari dokter dan perawat. Kalau APD lengkap, masyarakat akan merasa aman,” ujarnya.
Perlakuan diskriminatif dan stigma, menurut dia, bisa diredam dengan ketersediaan informasi yang memadai. “Diskriminasi itu hanya ekses dari ketakutan warga. Sama dengan jenazah yang ditolak, itu karena ketidakmengertian warga dari protokol penanganan jenazah pasien Covid-19,” katanya.
Coronavirus juga membuat Wakil Ketua Ombudsman Lely Pelitasari Soebekty dan anggota Ombudsman Ninik Rahayu mengisolasi diri di sebuah rumah sakit di Jakarta. Menurut anggota Ombudsman Alamsyah Saragih, mereka positif Covid-19 tanpa ada gejala.
“Mereka berdua terpapar virus tetapi tanpa gejala. Ini yang disebut orang tanpa gejala. OTG (orang tanpa gejala) ini statusnya tetap ODP (orang dalam pemantauan). Tidak otomatis orang yang sudah positif itu pasti parah kondisinya,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (3/4).
Menurut Alamsyah, kurangnya informasi detail tentang status OTG membuat masyarakat cenderung takut dan cemas dalam menghadapi pandemi. Akibatnya, stigma mudah dilekatkan terhadap orang-orang yang sudah positif terjangkit Covid-19.
“Orang-orang kemudian menjadi menolak orang yang sudah jadi pasien. Ini akhirnya membuat orang semakin stres, imunitas menurun. Apalagi warga ikut-ikutan meneror,” ucapnya.

Kesimpangsiuran informasi medis malah menimpa penyanyi Melanie Subono. Setelah kembali dari Arab Saudi dan Spanyol, ia mengecek kesehatan di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ia merasa ada gangguan kesehatan yang mengarah ke gejala tertular coronavirus.
“Saya diare, batuk. Dari beberapa gejala itu, saya berpikir untuk memeriksakan diri,” kata Melanie saat dihubungi, Sabtu (4/4).
Pada 23 Maret 2020, Melanie mendapati, hasil tes itu kemungkinan ia terjangkit coronavirus. Namun, ia tak diberi penjelasan oleh dokter yang memeriksanya.
“Saya hanya diberikan kertas dengan penjelasan ODP plus,” ujarnya.
Ia lalu mencari tahu, bertanya pada kenalan dokter yang bertugas di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dari kenalannya itu, ia mengetahui status ODP plus termasuk sebagai pasien dalam pengawasan (PDP), dengan tingkat akut yang rendah.
“Tidak merusak paru,” kata Melanie.
Mengendalikan informasi
Sementara itu, dokter spesialis paru di RSUP Persahabatan, Erlang Samoedro menjelaskan penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu merusak organ dalam tubuh, seperti jantung, paru-paru, dan saluran pencernaan.
“Fungsi paru-paru bisa menurun, tergantung pada luas paru-paru yang terkena serangan virus ini,” kata Erlang saat dihubungi, Jumat (3/4).
Erlang mengatakan, dampak yang timbul dari seseorang yang sudah sembuh dari coronavirus adalah paru-paru pasien akan mengalami proses fibrosis, yang menyebabkan terjadinya peradangan. Selain itu, penurunan luas atau volume paru-paru juga berkemungkinan menjadi “jejak” yang menetap.
“Sebagaimana umumnya penyakit yang menimbulkan luka akan ada bekasnya,” ucapnya.
Ia menyarankan, pasien yang sembuh agar menjalankan perilaku hidup sehat, seperti tidak merokok.
Terkait stigma terhadap pasien Covid-19, sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Nadia Yovani mengatakan, terdapat pola umum dalam cara berpikir masyarakat terhadap penyakit ini.
Terlebih lagi, sifat penularan penyakit ini mengancam keselamatan orang. Masyarakat lalu membangun pemahaman atas suatu penyakit, dengan standar moral tertentu.
“Di Indonesia, penyakit menular itu selalu punya tempat yang berbeda bagi masyarakat pada umumnya, seperti halnya kusta lalu yang belakangan adalah HIV,” ucap Nadia saat dihubungi, Minggu (5/4).
Nadia mengungkapkan, sifat menular dalam kasus Covid-19 semakin membuat orang takut. Akibatnya, masyarakat menstigma orang-orang yang tertular. Di sisi lain, Nadia menilai penyampaian informasi terkait Covid-19 malah seringkali membentuk cara berpikir yang defensif.
“Fungsi literasi dari pemberitaan kepada masyarakat itu bagai pedang bermata dua untuk masyarakat Indonesia,” tuturnya.
Setiap hari, kata dia, media massa menjejal laporan angka penularan dan meninggal dunia karena Covid-19. Menurut dia, penyampaian informasi perlu dikendalikan secara baik dan terstruktur, dengan lebih ditujukan membangun harapan kesembuhan.
Belum lagi, ujar Nadia, sosialisasi dari pemerintah yang meminta masyarakat agar melakukan social distancing, membuat masyarakat mengkonstruksikan nilai bahwa penyakit itu berbahaya dan bisa mengancam hidup mereka.

Ia mengingatkan, sikap publik terhadap Covid-19 berbeda dibandingkan respons atas penyakit berbahaya, tetapi tidak menular. Misalnya, pada penderita kanker, masyarakat dinilai cenderung lebih menaruh belas kasih.
“Ada baiknya bahwa informasi itu di-framing, diolah dengan memilah dan memilih. Konsepnya memberikan konstruksi yang tepat tentang penyakit ini, tidak saja dari sisi karakternya yang menular, tetapi juga memberikan informasi harapan bahwa penyakit ini bisa ditangani,” katanya.
“Juga ada upaya-upaya pencegahan secara aktif.”
Lebih lanjut, Nadia mengusulkan lembaga pemerintah yang menangani informasi bagi publik semestinya punya hak siaran khusus, yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi positif. Peran ini juga diperlukan untuk menangkal kabar-kabar bohong dan menyesatkan.
“Cara itu harus diupayakan agar di masyarakat bisa berkurang stigmanya terhadap penyakit ini,” ujarnya.