
Di balik selimut patung Bunda Maria: Pemilu 2024 dan wajah buruk intoleransi
Maraknya peristiwa-peristiwa bernuansa intoleransi yang terjadi di berbagai daerah sejak awal 2023 tak lagi mengagetkan bagi Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan. Menurut Halili, peristiwa semacam itu memang cenderung marak menjelang perhelatan pemilihan umum (pemilu).
"Gejala ini (maraknya peristiwa intoleransi) pernah terjadi pada 2018, yakni saat sebelum Pemilu 2019. Sepertinya, menjelang (Pemilu) 2024 ini, ekskalasinya itu cenderung meningkat," kata Halili kepada Alinea.id, Senin (27/3).
Teranyar, peristiwa bergenre intoleransi terekam terjadi di Dusun Degolan, Bumirejo, Kulonprogo, Jawa Tengah, akhir Maret lalu. Ketika itu, sekelompok orang yang mengatasnamakan sebuah partai politik Islam menggeruduk rumah doa Sasana Adhi Rasa ST. Yakobus di dusun tersebut.
Mereka keberatan dengan keberadaan patung Bunda Maria setinggi enam meter di rumah doa tersebut. Patung itu dianggap mengganggu kekhusyukan ibadah puasa. Pengelola rumah doa mengalah dengan memasang terpal pada patung tersebut.
Menurut Halili, kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama terekam mengalami eskalasi sejak awal 2023. Peningkatan jumlah kasus terjadi tak lama setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan arahan agar pemda dan Forkompimda menjamin hak beragama dan beribadah seluruh warga negara pada pertengahan Januari.
Kasus penutupan patung Bunda Maria di Kulonprogo, menurut Halili, merupakan bukti pemda dan Forkopimda mengabaikan arahan Presiden. "Beberapa kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Sintang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Malang, Kota Lampung, dan Kabupaten Bogor," kata dia.
Kasus-kasus itu, kata Halili, merupakan pertanda bahwa sikap intoleran masih terus tumbuh di masyarakat. Merujuk catatan Setara Institute, ada 171 peristiwa dan 318 tindakan intoleransi yang terjadi pada 2021. Angka itu relatif tak jauh berubah dari tahun-tahun sebelumnya.
Ironisnya, aktor negara turut jadi pelaku tindakan intoleransi. Pada 2021, misalnya, ada 102 peristiwa intoleransi yang dalangnya ialah aktor negara, semisal polisi dan pemerintah daerah. Sebanyak 216 dipicu aktor-aktor nonnegara.
"Pada level negara, ada regulasi peraturan bersama 2 menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang kadang menjadi alat untuk melarang kelompok minoritas mendirikan rumah ibadah. Itu selalu jadi alasan untuk memberikan pembatasan-pembatasan kepada kelompok minoritas karena aturan ini menghendaki persetujuan mayoritas," ujar Halili.
Peraturan yang dimaksud Halili ialah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006. Lazim disebut SKB 2 menteri, regulasi itu kerap disalahgunakan kelompok intoleran untuk melarang kaum minoritas beribadah. "Keberadaan PBN itu tidak sinkron dengan arahan presiden," imbuh Halili.
Lebih jauh, Halili menduga kelompok intoleran sedang mencari panggung jelang Pemilu 2024. Menurut dia, kelompok-kelompok tersebut kerap memicu peristiwa intoleransi untuk mendongkrak pamor dan menaikkan daya tawar mereka di mata para calon pemimpin. Harapannya, jasa mereka bakal dipakai di pemilu.
"Jadi, ada konsolidasi yang mereka upayakan di antara mereka sendiri melalui isu-isu minoritas. Desain besarnya adalah untuk konsolidasi kelompok-kelompok itu menjelang pemilu untuk meningkatkan daya tawar mereka. Tindakan intoleransi di beberapa tempat itu sebenarnya instrumen untuk konsolidasi kelompok mereka," ucap Halili.
Ironisnya, pemerintah cenderung canggung ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok intoleran. Menurut Halili, para pejabat tak berani tegas terhadap kelompok-kelompok intoleran lantaran khawatir kehilangan konstituen jelang pemilu.
"Pemerintah menjaga mayoritas karena pemilih terbesar mereka mayoritas. Padahal, sebenarnya kelompok-kelompok konservatif ini juga bukan mayoritas. Mereka mengklaim saja. Mereka ini sedikit, tapi berisik. Kemudian pemerintah seperti tersandera dengan politisasi mereka," kata Halili.
Lantas bagaimana dengan Pemilu 2024? Halili menilai polarisasi di kalangan masyarakat bisa jauh lebih parah ketimbang Pemilu 2019. Tanpa merinci, ia menyebut ada parpol peserta Pemilu 2024 yang terang-terangan mengusung semangat politik identitas.
"Sebagai contoh, Anies Baswedan menyebut bila politisasi itu tidak bisa dihindarkan. Dalam konteks Indonesia, itu agak berbahaya karena politik identitas itu akhirnya mendorong penggunaan sentimen dan kebencian terhadap minoritas. Politik identitas diperbolehkan ketika politik identitas itu tidak ada kebencian," ujar Halili.
Halili mengatakan Setara Institute tengah memetakan ulang kota-kota toleran di Indonesia. Dari kajian sejauh ini, menurut Halili, tingkat toleransi sejumlah kota besar di Jawa mulai membaik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Seperti misalnya di Bekasi, Bogor, Semarang, Surabaya. Daerah ini yang semula tidak terlalu perhatian dengan indeks toleransi di 2021. Tapi, kami melihat ada upaya untuk memobilisasi program, memobilisasi angaran untuk meningkatkan toleransi," lanjut Halili.
Kepala Humas Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Jeirry Sumampouw mengatakan masih maraknya kasus-kasus intoleransi beragama menunjukkan instruksi Jokowi tak sepenuhnya dipatuhi. Menurut catatan dia, setidaknya ada lima kasus pelarangan aktivitas keagamaan yang terjadi di berbagai daerah sejak rakornas kepala daerah yang dipimpin Jokowi, Januari lalu.
Jeirry mencontohkan pengekangan aktivitas ibadah jemaat Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat. Pada 26 Januari 2023, Forkopimda Sintang menuntut Bupati Sintang menerbitkan surat edaran untuk mengekang kegiatan kelompok Ahmadiyah. Mereka juga meminta agar masjid jemaah Ahmadiyah disegel dengan dalih menjaga ketenteraman.
Selain di Sintang, pengekangan juga dialami jemaat Ahmadiyah Parakansalak, Sukabumi, Jawa Barat, serta Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Larangan ibadah juga dirasakan jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPdI Metland di Cileungsi, Bogor dan Gereja Kristen Injili Nusantara atau GKIN di Bandar Lampung.
"Pelarangan tersebut pada umumnya dilakukan dengan alasan bahwa rumah ibadah belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan atas nama masyarakat mayoritas," kata Jeirry dalam sebuah siaran pers kepada media, Februari lalu.
Jeirry berharap peristiwa-peristiwa intoleransi beragama itu diperhatikan serius oleh pemerintah pusat. Ia juga meminta agar aparat penegak hukum dan pemerintah daerah bersikap tegas terhadap kelompok-kelompok intoleran.
"Meminta pemerintah daerah untuk lebih patuh terhadap konstitusi ketimbang pada kesepakatan para pihak yang sering malah mengangkangi konstitusi sesuai arahan Presiden Jokowi," kata Jeirry.

Belum membudaya
Menurut peneliti Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Syamsurijal, peristiwa intoleransi sebagaimana yang terjadi di Kulonprogo tak tunggal. Ia menyebut peristiwa serupa sudah rutin terjadi di daerah-daerah lainnya.
"Sekitar 2016, terjadi pula penghancuran patung-patung Yunani di salah satu mall di Makassar. Waktu itu, ada banyak kelompok, termasuk Front Pembela Islam (FPI) waktu itu ikut menghancurkan," kata Syamsurijal kepada Alinea.id, Senin (27/3).
Menurut Syamsurijal, ada beragam hal yang membuat perilaku intoleransi masih mewabah di masyarakat. Salah satunya ialah karena toleransi beragama yang kerap diwacanakan di ruang publik masih sebatas narasi. Toleransi belum membudaya.
"Kami menelusuri di banyak tempat di Indonesia, khususnya di komunitas-komunitas lokal punya kearifan lokal bernilai toleransi. Ada di Sulawesi, Papua dan seterusnya dengan berbagai macam tradisinya. Akan tetapi, sering kali tradisi ini tidak dihidupkan sebagai bagian hidup sehari-hari," kata Syamsurijal.
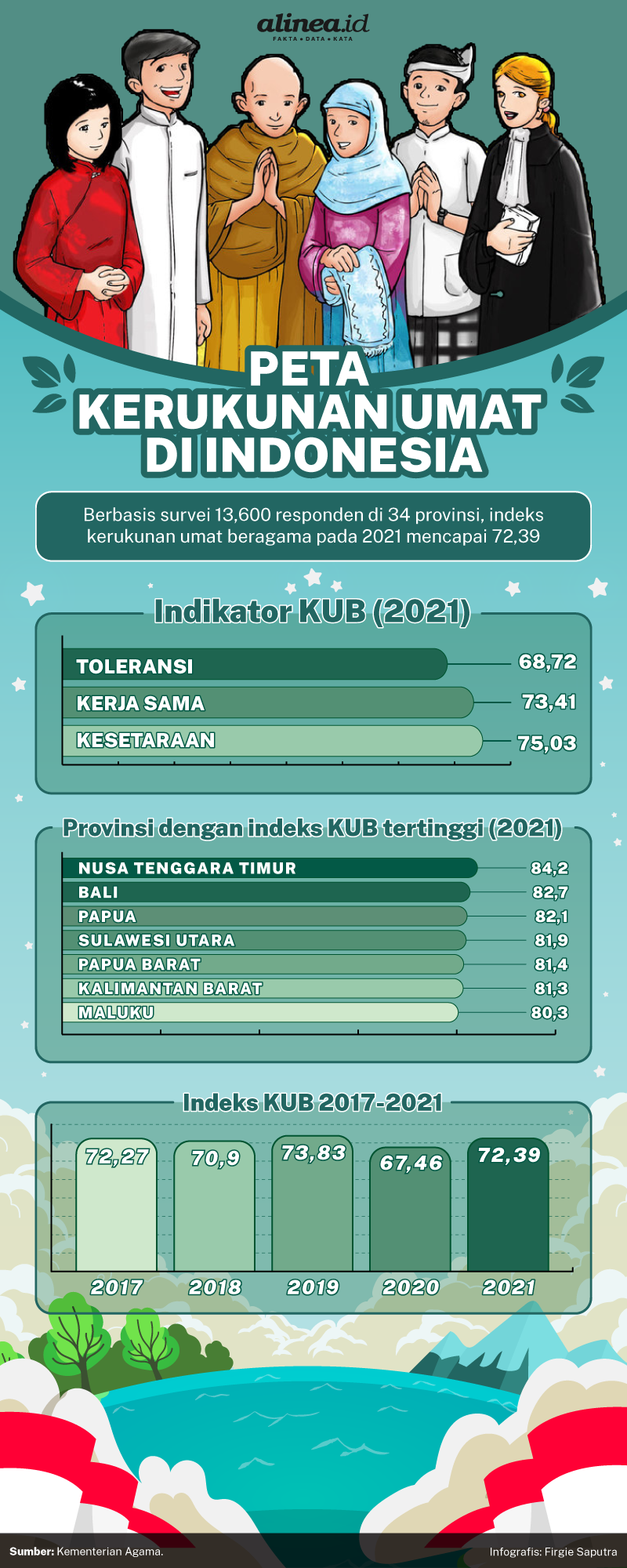
Karena sikap toleran tak mengakar menjadi tradisi, menurut Syamsurijal, publik masih kerap bersikap permisif terhadap peristiwa-peristiwa intoleran. Di lain sisi, kelompok-kelompok intoleran juga kerap memanfaatkan momentum politik elektoral sebagai panggung untuk unjuk gigi dan menekan kelompok minoritas.
"Kelompok minoritas karena dianggap tidak punya efek secara politik. Posisi mereka akhirnya tidak diperhitungkan dalam konteks politik elektoral. Berbeda halnya kalau itu terjadi pada agama-agama yang saya kira jumlahnya cukup besar. Itu biasanya mendapat perhatian dari pemerintah," kata Syamsurijal.
Sikap intoleran, lanjut Syamsurijal, tak semata terkait agama. Di kota-kota yang indeks toleransinya rendah, ada banyak kasus yang menunjukkan kaum mayoritas cenderung menekan kelompok minoritas karena dilatarbelakangi persoalan di luar agama, semisal ekonomi, kemiskinan, dan politik.
"Jadi, bukan agama yang menjadi problem utamanya. Hanya saja isu agama sebagai pemicu antipati terhadap kelompok-kelompok yang lain. Jadi isu agama itu jadi pelarian dari masalah ekonomi dan politik yang menjerat mereka," kata Syamsurijal.
Lebih jauh, Syamsurijal berharap pemerintah serius menghadirkan solusi untuk menekan peristiwa-peristiwa intoleransi. Salah satu cara ialah dengan mendorong sikap toleran membudaya dan dilakoni dalam kehidupan sehari-hari.
"Karena, pada praktiknya, toleransi tidak diserap menjadi sebuah pengetahuan yang dikelola sedemikian rupa oleh negara untuk dikembangkan lebih jauh. Jadi, akhirnya ketika kita datang ke suatu tempat, itu (sikap toleran) hanya sebuah cerita," jelas dia.








