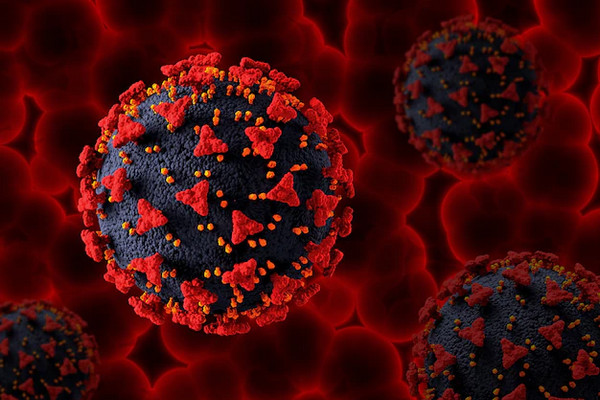Rasisme di balik mewabahnya coronavirus
Novel coronavirus (2019-nCoV), atau nama baru Covid-19 (corona virus desease) dari World Health Organization (WHO), yang berasal dari Kota Wuhan, China, sudah menjangkiti orang-orang di 28 negara.
Selain membuat banyak orang tertular dan meninggal dunia, coronavirus pun menebar sentimen ras alias xenofobia terhadap orang-orang China. Hal yang sama juga terjadi pada orang-orang Vietnam dan Asia Timur karena kemiripan secara fisik.
Misalnya di Australia, dikutip dari SBSNews edisi 31 Januari 2020, di sana semakin banyak laporan tentang anggota komunitas China-Australia dan Asia-Australia yang menjadi sasaran penghinaan dan rasis, dengan sejumlah serangan fisik dan media sosial.
New Straits Times edisi 26 Januari 2020 melaporkan, di Malaysia sebuah petisi menyerukan agar warga China dilarang masuk ke Negeri Jiran dan menyebut, virus baru itu tersebar luas karena gaya hidup tidak higienis orang-orang China.
Di Kanada, seperti dilaporkan CBC edisi 28 Januari 2020, seorang mahasiswa di University of Toronto bernama Frank Ye memberi kesaksian, teman-teman Asia-Kanada menyaksikan orang-orang menjauh dari mereka. Ibunya, seorang perawat di rumah sakit Toronto, diminta seorang pria untuk menggunakan masker karena ada begitu banyak orang China di sekitarnya.
Opindia edisi 30 Januari 2020 melaporkan, di India seorang pemuka agama bernama Ilyas Sharafuddin mengatakan dalam sebuah pidato audionya kalau coronavirus yang mewabah adalah hukuman Tuhan di China karena memperlakukan Muslim Uighur secara tak adil.
Sementara di Amerika Serikat, Business Insider edisi 30 Januari 2020 melaporkan, seorang laki-laki di negara bagian Washington mengatakan bahwa istri dan anaknya yang berusia delapan tahun berdarah campuran, yang tengah berkunjung di supermarket Costco diusir karena ada kekhawatiran coronavirus.
Pers pun tak lepas dari perilaku rasis. Di Prancis, surat kabar Le Courrier Picard edisi 26 Januari 2020, memasang foto seorang perempuan Asia yang mengenakan masker di halaman depan, bertajuk “Siaga Kuning”.
Pada 26 Januari 2020, dua surat kabar asal Australia, yakni Melbourne Herald Sun dan Daily Telegraph Sydney memuat tajuk yang provokatif. Melbourne Herald Sun menulis, “Pandamonium Virus China”, pelesetan dari pandemonium—kekacauan yang sangat—mengacu panda, hewan asal China. Sedangkan tajuk utama Daily Telegraph Sydney menulis, “Anak-anak China Tinggal di Rumah”.
Ketakutan perkara coronavirus dan reaksi berlebihan juga terjadi di Prancis, Finlandia, Belanda, Jerman, Hong Kong, Jepang, Italia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Inggris, dan Korea Selatan.

Praktik rasisme
Perlakuan rasis diakui seorang mahasiswi asal Indonesia yang berkuliah di Ferris State University, Michigan, Amerika Serikat bernama Andri Stephanie. Stephanie pernah menyaksikan sendiri gelagat para pejalan kaki, yang terkesan menghindar ketika berpapasan dengan mahasiswa asal China.
Stephanie mengatakan, berdasarkan pengamatannya, coronavirus bukan cuma membuat stigma terhadap orang-orang China, tetapi juga terhadap orang Asia lainnya, dengan ciri-ciri fisik berkulit kuning langsat, bermata sipit, dan berambut hitam.
“Jadi, enggak hanya orang China, Korea juga kena perlakuan gitu. Cuma enggak terang-terangan. Orang Indonesia di sini kelihatan enggak kayak orang Asia, jadi enggak kena,” tuturnya saat dihubungi reporter Alinea.id, Senin (10/2).
Staf pengajar Jurusan Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Zamzam Fauzanafi yang sedang mendampingi istrinya menyelesaikan studi di University of Nottingham, Inggris juga membenarkan adanya perlakuan rasis terhadap orang-orang China.
Di kota-kota besar, seperti London, kata Zamzam, orang-orang China digambarkan sebagai pembawa wabah coronavirus. Restoran China di Inggris sepi dan mengalami penurunan pengunjung secara signifikan.
“Orang-orang China, Korea, bahkan Malaysia yang hanya karena sosok biologisnya mirip, dikatain orang ‘itu dia si flu China’,” ucapnya saat dihubungi, Senin (10/2).
Pemain sepak bola Tottenham Hotspur, Dele Alli, menurut Zamzam juga menyebarkan rasisme lewat unggahan Snapchat-nya. Kata Zamzam, dalam unggahannya itu, Dele mengenakan masker dan mengejek seorang pria Asia yang duduk di belakangnya.
Perlakuan cenderung rasis pun terjadi di Indonesia. Pada akhir Januari 2020, beberapa warga di Bukittinggi, Sumatera Barat berunjuk rasa di depan hotel tempat turis asal China menginap. Mereka menginginkan wisatawan itu diisolasi di bandara dan dipulangkan ke negaranya.
Awal Februari 2020, terjadi gelombang aksi unjuk rasa ratusan warga di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Mereka menolak karantina terhadap ratusan warga negara Indonesia yang baru dipulangkan dari Wuhan karena takut tertular coronavirus.
Di ranah media sosial, tagar #TolakSementaraTurisChina sempat populer. Menurut riset Indonesia Indicator yang dilakukan dari 24 Januari-3 Februari 2020, tagar itu dicuitkan sebanyak 2.200 warganet. Jumlah itu masih di bawah tagar #2019_nCoV, sebanyak 6.700 cuitan.
Superioritas Eropa
Rasisme terhadap orang pribumi karena penyakit juga pernah terjadi pada masa kolonial. Menurut Purnawan Basundoro dalam buku Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang sejak Kolonial sampai Kemerdekaan (2009), saat penyakit pes mewabah pada 1910-an dan menyebar ke permukiman orang-orang Eropa, pemerintah kolonial menganggap penting menata perkampungan miskin pribumi di Surabaya.
Pemerintah kolonial menganggap, perkampungan pribumi yang kotor dan tak terurus menjadi sumber segala penyakit. Mereka menilai, biang keladinya karena ada perbudakan, banyak anak, seks bebas, kawin muda, dan anak-anak terlantar.
Di sisi lain, Peter Boomgaard di dalam tulisannya “The Development of Colonial Health Care in Java: An Exploratory Introduction” yang terbit di Jurnal Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (1993) menulis, orang-orang Eropa percaya, banyak sekali penyakit yang disebabkan miasma—penyakit yang disebabkan kuman dari rawa atau tanah dan sirkulasi udara yang buruk. Dan, orang-orang pribumi menjadi kambing hitam atas penyakit itu.
Menurut Zamzam, kolonialisme terkait erat dengan rasisme, yang memandang bangsa terjajah dianggap terbelakang. Zamzam mengatakan, dari sisi antropologis, perilaku rasisme orang Eropa disebabkan cara pandang determinisme biologis.
“Bangsa nonkulit putih dianggap berada dalam tahapan evolusi lebih rendah dari bangsa kulit putih,” kata dia.
Oleh karena itu, menurutnya, ekspresi dari rasisme terungkap dari ucapan dan perlakuan bersifat merendahkan karena bangsa nonkulit putih diidentikan dengan “kotor”, “bodoh”, dan “jelek”.
“Dalam kasus coronavirus, orang China sering dianggap sebagai bangsa yang ‘jorok’ dan ‘tidak bersih’, sehingga mereka dianggap pembawa penyakit,” ujarnya.
Zamzam pun memandang, ada unsur ekonomi-politik yang ikut mewarnai rasisme terkait coronavirus. Sebab, bangsa China saat ini identik dengan ekspansi ekonomi yang kuat, serta bisa menekan negara-negara Barat.

Hoaks dan peran media
Pengamat bidang kajian media dan komunikasi dari Universitas Brawijaya Anang Sujoko menilai, hoaks terkait coronavirus di Indonesia bisa melahirkan rasisme terhadap orang China.
“Di media sosial muncul informasi kalau pemerintah China menindas Muslim Uighur. Nah, itulah yang akhirnya dianalisis sendiri oleh para netizen,” kata Anang saat dihubungi, Senin (10/2).
“Akhirnya, dinobatkanlah ‘corona is China’.”
Di sisi lain, Zamzam menuturkan, intensitas penggunaan kata yang bermuatan emosional di media sosial, memungkinkan penyebaran pandangan diskriminatif, rasisme, dan xenofobia, menjadi begitu cepat.
Ia mencontohkan, unggahan rasis yang menjadi populer di Twitter, mampu membuat intensitas emosional meningkat dan meluas ke mana-mana, seolah ada kegentingan.

“Orang jadi takut,” tutur Zamzam.
Anang melanjutkan, analisis warganet yang bersifat “cocoklogi” terkait coronavirus, menciptakan hoaks yang berujung lahirnya sentimen terhadap orang China.
Untuk mengatasi rasisme, ia menyarankan pemerintah agar konsisten memaparkan data dan informasi soal coronavirus secara transparan. Tujuannya, supaya hoaks bisa diminimalisir.
Di samping itu, kata dia, media massa juga berperan menyampaikan informasi terkait coronavirus dengan tidak membangun kekhawatiran berlebihan, tanpa mengurangi pesan untuk selalu waspada. Peran media, sebut Anang, cukup signifikan untuk meminimalisir politik identitas dan mengedukasi masyarakat.
“Artinya, media harus bisa menunjukkan bahwa ini masalah kesehatan, terkait ilmu biologi, dan sejauh mungkin menghindari kata China,” tutur Anang.