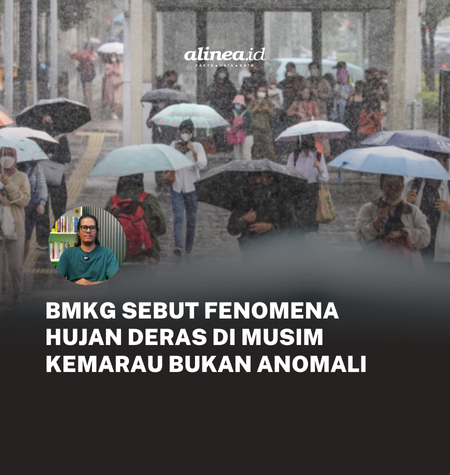Setengah hati menekan gas rumah kaca
Cuaca yang panas terik di Jakarta membuat Ratih Hanifah, 29 tahun, merasa lunglai setiap memulai aktivitasnya bekerja. Ia pun mengeluh pusing hebat. “Panas banget cuacanya, terkadang bisa sampai 38 derajat celsius,” ujar warga Cilincing, Jakarta Utara itu kepada Alinea.id, Senin (23/10).
Selain panas terik, Ratih juga terganggu dengan polusi debu yang sudah menjadi masalah menahun di wilayah pesisir utara Jakarta. Mata Ratih tak jarang berair lantaran paparan debu. Di daerah itu, terdapat pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Derita ditambah dengan krisis air yang menyulitkan warga di sekitar Cilincing.
“Selama musim kemarau, air di Cakung dan Cilincing kering,” ucap Ratih.
Ratih mengaku terganggu lantaran lama hujan tak turun. “Apalagi saat macet, aduh enggak kuat. Biasanya biar enggak nyelekit (terasa) banget (paparan cuaca panas), selalu pakai sunscreen, terus pulang langsung mandi air dingin,” ujarnya.
Meningkatnya gas rumah kaca
Rosihan, 28 tahun, warga Semarang, Jawa Tengah juga mengaku kerap bercucuran keringat setiap berangkat kerja, akibat suhu cuaca yang bisa mencapai 38 derajat celsius. “Saya yang terbiasa sama (cuaca) panas di Semarang merasa kemarau kali ini beda. Panas banget,” kata dia, Senin (23/10).
Pria yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek daring itu mengaku, cuaca terik di Semarang membuat tak nyaman beraktivitas. Untuk meredakan hawa panas, sesekali Rosihan singgah di supermarket, menikmati sejuknya angin air conditioner (AC).
Dalam diskusi virtual di kanal YouTube Forum Merdeka Barat 9, Senin (16/10), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengungkapkan, suhu bumi yang makin panas disebabkan adanya peningkatan gas rumah kaca—gas dalam atmosfer yang menjebak panas—sepanjang musim kemarau.
Adanya peningkatan kadar gas rumah kaca itu diukur di Stasiun Global Atmosphere Watch (GAW), Bukit Kototabang, Sumatera Barat. GAW adalah salah satu dari 30 stasiun dunia yang mengawasi atmosfer.

“Hasilnya, sejak tahun 2004 atau sekitar tahun 2000 sampai tahun 2022 konsentrasi gas rumah kaca, terutama CO2 itu 372 ppm (parts per million/bagian per sejuta),” kata Dwikorita dalam diskusi tersebut.
“Jadi kenaikan selama 18 tahun itu sudah mencapai 40 ppm lebih.”
Sebagai informasi, jenis gas rumah kaca, antara lain karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dinitrogen oksida (N2O), dan klorofluorokarbon. Jenis gas-gas itu dihasilkan dari berbagai aktivitas, seperti penebangan hutan, pemakaian BBM pada kendaraan bermotor, PLTU, pupuk ternak, dan pendingin ruangan atau AC konvensional.
Peneliti Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi (PRKKE) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Agus Nurrohim menduga, meningkatnya kadar gas rumah kaca lebih disebabkan kebakaran hutan di musim kemarau yang panjang. Meski dampak dari penggunaan energi fosil dan PLTU batu bara juga tergolong dominan memengaruhi peningkatan gas rumah kaca.
“Jadi bukan satu-satunya (faktor). Energi itu besar memang, hampir 50%,” ujar Agus saat dihubungi, Senin (23/10).
Terpisah, anggota Komisi VII DPR, Mulyanto berpandangan, penanganan gas rumah kaca tak bisa dilakukan sektoral. "Jadi bukan hanya (diterapkan) di sektor energi, tetapi juga transportasi, industri, dan kehutanan," ucap Mulyanto, Senin (23/10).
Selain itu, penanganannya harus konsisten dan komprehensif. Menekan emisi, kata dia, juga perlu strategi global yang adil. Bukan hanya menekan negara berkembang. Selama ini, menurut Mulyanto, negara maju kerap menuduh negara berkembang sebagai biang kerok peningkatan gas rumah kaca. Namun tanggung jawab negara maju kerap tidak jelas.
“(Perlu) komitmen pendanaan dari negara maju,” kata dia.
“Contohnya komitmen membantu pendanaan murah untuk program ‘pensiun dini’ PLTU melalui skema JETP (just energy transition partnership) sampai hari ini tidak jelas.”
Penghematan dan peralihan energi
Agus memandang, transisi energi terbarukan mesti diakselerasi, guna meninggalkan energi fosil yang menjadi biang kerok gas rumah kaca. Walaupun tantangannya, masih terganjal teknologi yang mahal. Agus mencontohkan teknologi carbon capture storage (CCS) atau penyimpanan emisi karbon pada pembangkit listrik, yang bisa dimanfaatkan kembali menjadi bahan bakar listrik.
"Meski sekarang sedang dikembangkan, teknologi ini masih mahal," ucap Agus.
Namun, ia mengatakan, upaya menekan gas rumah kaca sesungguhnya bisa dilakukan di rumah tangga, dengan menggunakan alat-alat listrik yang hemat energi. Misalnya, memakai AC yang sudah menggunakan inverter dengan energi listrik relatif hemat, ketimbang AC konvensional. Teknologi lainnya yang bisa dipakai di rumah tangga adalah lampu bohlam light emitting diode (LED) yang hemat energi listrik.

“Tapi tantangannya lagi-lagi, alat ini lebih mahal,” kata Agus.
“Publik lebih memilih membeli AC non-inverter, sehingga memakan energi lebih banyak, berimplikasi pada pembakaran pembangkit listrik yang besar dan berdampak pada GRK (gas rumah kaca).”
Selain itu, penghematan juga bisa dilakukan masyarakat, seraya menunggu transisi energi menuju nol emisi tahun 2060 yang menghentikan batu bara sebagai bahan baku energi listrik. “Jadi bukan pada sisi sumbernya saja,” ucap Agus.
Bagi Agus, mengganti kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik yang tengah diupayakan pemerintah belum sepenuhnya tepat mengurangi gas rumah kaca. Soalnya, energi pemasok listrik masih mengandalkan PLTU batu bara.
“Itu (sama saja) memindahkan dari knalpot ke cerobong PLTU karena energi yang digunakan untuk mobil listrik itu masih batu bara,” kata Agus.
Solusinya, kata Agus, pemerintah harus secepatnya membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk menggeser penggunaan PLTU batu bara. Ia menyebut, PLTN merupakan pembangkit yang sepadan mengganti PLTU.
“Karena PLTU itu kan kapasitasnya besar. Energi terbarukan yang mempunyai kapasitas besar untuk mengganti batu bara itu adalah nuklir,” ujarnya.
Akan tetapi, menurut Agus, ada masalah lain dalam transisi energi terbarukan, yakni dukungan riset yang minim. Anggaran meneliti teknologi transisi energi, sebut Agus, sangat cekak. Kondisi ini diperburuk dengan arah riset BRIN yang lebih berorientasi pada teknologi kunci yang sangat sulit digunakan industri lantaran bukan teknologi yang siap diproduksi massal.
Lebih lanjut, Agus menilai, pemerintah belum berani memberikan subsidi pada energi ramah lingkungan. Akibatnya, masyarakat masih ketergantungan dengan bahan bakar fosil. Padahal, semestinya energi terbarukan juga disubsidi untuk mengubah selera konsumen.
“Kalau mau menyiapkan, BBM itu yang masih subsidi, diganti saja, pertalite dengan bioetanol. (Tapi) bioetanol ini mahal sekali,” tuturnya. “Kalau mau disubsidi, itu tadi bioetanol.”
Penerapan pajak karbon yang tak serius, dikatakan Agus, juga merupakan sikap pemerintah yang masih setengah hati menekan gas rumah kaca. Kemungkinan pemerintah khawatir bakal berdampak pada kenaikan harga BBM dan memicu protes masyarakat.
"Karena kalau pajak karbon diterapkan, pasti akan meningkatkan harga. Harga produknya akan naik," ucap Agus.
Di sisi lain, transisi energi terbarukan, menurut Mulyanto perlu cermat, jangan sampai justru memaksa mengimpor komponen perangkat pembangkit energi baru terbarukan kepada perusahaan asing.
“Sangat mungkin dengan penerapan NZE (net zero emissions) ini tarif listrik meningkat, juga terjadi pelonggaran terhadap komponen impor dari perangkat-perangkat pembangkit EBT (energi baru terbarukan),” kata Mulyanto.
Mulyanto mengatakan, saat ini Komisi VII DPR sedang merumuskan regulasi untuk mempersiapkan skenario transisi energi, dengan pembahasan rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan (RUU EBT).
“Targetnya selesai akhir tahun ini,” tuturnya.
“Selain itu juga perumusan RUPTL (rencana usaha penyediaan tenaga listrik) PLN dalam tingkat implementasi.”
Alinea.id sudah berupaya mengkonfirmasi mengenai upaya transisi energi kepada Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yudo Dwinanda Priaadi. Namun, hingga artikel ini dipublikasikan, belum ada jawaban.