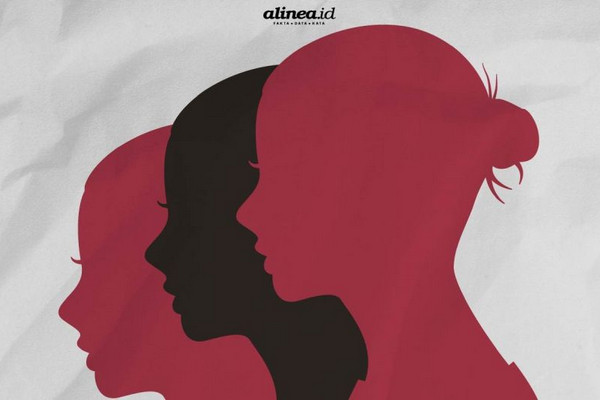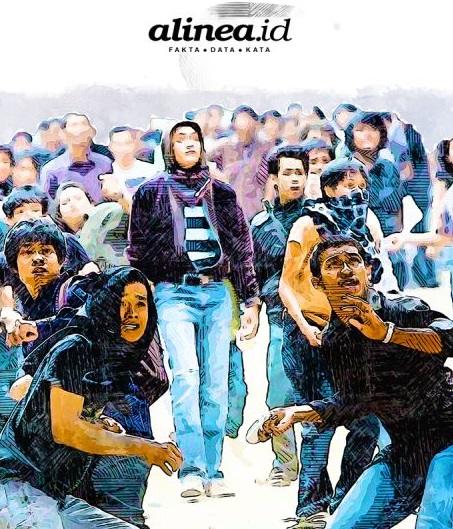Teror kekerasan terhadap perempuan dan anak saat pandemi Covid-19
Pandemi SARS-CoV-2 penyebab Coronavirus disease (Covid-19) mengubah segalanya. Termasuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meningkat.
Pada 7 April 2020, World Health Organization (WHO) mengeluarkan laporan bertajuk “Covid-19 and violence against women: What the health sector/system can do”. Laporan itu menyatakan, kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat dalam keadaan darurat apa pun, termasuk pandemi.
Kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat di China, Inggris, Amerika Serikat, dan negara lain sejak Covid-19 menyebar. Di China, sebut laporan WHO itu, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke kantor polisi di Jingzhou, sebuah kota di Provinsi Hubei, meningkat tiga kali lipat pada Februari 2020 dibandingkan data tahun sebelumnya.
“Dampak kesehatan dari kekerasan, terutama pasangan dalam rumah tangga, pada perempuan dan anak-anak mereka sangat signifikan. Kekerasan terhadap perempuan dapat mengakibatkan cedera fisik, mental, seksual, dan masalah kesehatan reproduksi,” tulis laporan itu.
Sebuah tulisan di jurnal Cadernos de Saude Publica edisi 30 April 2020 berjudul “Violence against women, children, and adolescents during the Covid-19 pandemic: Overview, contributing factors, and mitigating measures” menyebutkan bahwa di Brasil ada peningkatan 17% kasus kekerasan terhadap perempuan pada Maret 2020, saat diberlakukan pembatasan sosial atau lockdown di negara itu.
Di Rio de Janeiro, kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat 50%. Begitu pula di negara bagian Parana, ada peningkatan 15% laporan kekerasan dalam rumah tangga. Kasus mengalami peningkatan juga di Ceara, Pernambuco, dan Sao Paulo.
“Situasi ini semakin serius karena sebagian besar kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan juga melibatkan kekerasan terhadap anak-anak dan remaja,” sebut artikel itu.
Di Inggris, tulis Claudia Garcia-Moreno dalam artikel “Protections for women and girls must be built into response plans” yang dimuat di BMJ edisi 7 Mei 2020, tercatat antara 23 Maret-12 April 2020 terjadi dua kali lipat kasus kematian akibat kekerasan dalam rumah tangga, dalam 10 tahun terakhir.
Sementara di Bangladesh, dalam artikel “Covid-19 lockdown increases domestic violence in Bangladesh” yang ditulis Arafatul Islam di Deutsche Welle (DW) edisi 12 Mei 2020 disebutkan, berdasarkan survei sebuah organisasi hak asasi manusia (HAM) setempat Manusher Jonno Foundation (MJF), setidaknya 4.249 perempuan dan 456 anak-anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di 27 dari 64 distrik di Bangladesh pada April 2020.
“Sekitar 92% anak-anak yang diwawancarai MJF telah dilecehkan oleh orang tua mereka atau anggota keluarga lainnya, 14 diperkosa, 16 menghadapi percobaan pemerkosaan, dua diculik, dan 10 dilecehkan secara seksual,” tulis Arafatul Islam.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak itu terjadi saat pemerintah di masing-masing negara melakukan lockdown dan menganjurkan warganya tetap tinggal di rumah, untuk memutus rantai penularan Covid-19.

Faktor penyebab
Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia. Menurut data dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), pada 16 Maret-19 April 2020 terdapat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam rentang sebulan, lembaga itu menerima 97 kasus kekerasan.
“Biasanya setiap bulan 60-an kasus. Terjadi peningkatan kasus sekitar 50%,” ujar Direktur LBH APIK Siti Mazuma—akrab disapa Zuma—saat dihubungi reporter Alinea.id, Rabu (20/5).
“Korban yang melapor kebanyakan dari Jabodetabek.”
Dari 97 pengaduan itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mendominasi, dengan jumlah 33 kasus. Diikuti kekerasan gender berbasis online (KGBO) 30 kasus, pelecehan seksual delapan kasus, dan kekerasan dalam pacaran (KDP) tujuh kasus.
Selain LBH APIK, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pun mengakui kebanjiran pengaduan. Namun, komisioner Komnas Perempuan Tiasri Wiandani mengatakan, pihaknya belum bisa membuka berapa jumlah pengaduan lantaran masih dalam proses pembuatan laporan.
“Masih ada pelaporan-pelaporan yang belum diinput,” katanya saat dihubungi, Rabu (20/5).
Pemerintah sendiri mengimbau untuk belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah sejak pertengahan Maret 2020. Pada April 2020, ada kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang membuat segala aktivitas warga harus dilakukan di rumah saja.
Terkait kekerasan terhadap anak saat pagebluk, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengatakan, anak rentan menjadi korban kekerasan karena dua faktor. Pertama, konflik dengan relasi orang tua yang sudah retak. Kedua, masalah ekonomi keluarga.
Segalanya menjadi runyam lantaran pandemi menghantam stabilitas ekonomi keluarga. Menurut Susanto, banyak orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), yang ikut serta berdampak terhadap pelemahan kualitas perlindungan anak.
Namun, ia mengaku, hingga kini KPAI masih melakukan riset perihal kasus kekerasan terhadap anak di masa pandemi. Sehingga belum dapat memberikan data detail mengenai hal tersebut.
“Potret kekerasannya seperti apa? Siapa pelakunya? Dan bentuk kekerasan apa yang dominan?” katanya saat dihubungi, Rabu (20/5).
Sementara Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati mengatakan, dari beberapa pengaduan di masa darurat kesehatan, terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak.
“Tapi jumlahnya berapa, saya tidak bisa menyebutkan hari ini,” kata dia saat dihubungi, Selasa (26/5).
Dihubungi terpisah, sosiolog dair Universitas Airlangga (Unair) Bagong Suyanto mengatakan, faktor karantina di rumah menyebabkan terjadinya kekerasan perempuan dan anak. Pemicu konflik, menurut Bagong, suami dan istri enggan mereposisi diri saat banyak melakukan aktivitas di rumah.
"Kalau laki-laki, misalnya berpikir masak, cuci, nyapu, pekerjaan domestik urusan perempuan, laki-lakinya enggak mau bantu pasti akan bertengkar," ujarnya saat dihubungi, Rabu (20/5).
"Sementara harga diri laki-laki juga mungkin tinggi, tapi dia korban PHK, enggak punya penghasilan, merasa setelah di PHK tidak dihormati. Kan bisa saja itu menjadi pemicu.”
Senada dengan Bagong, psikolog keluarga dan anak Sani Budiantini Hermawan pun mengatakan, banyak melakukan aktivitas di rumah bisa menjadi faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebab, hal itu menyebabkan pelaku kekerasan menjadi jenuh, stres, dan mudah tersinggung.
“Apalagi kalau memang sudah ada riwayat di keluarga itu, ada kekerasan dalam rumah tangga,” ucapnya saat dihubungi, Kamis (21/5).
“Anjuran pemerintah di rumah saja ternyata tidak terlalu baik untuk keluarga yang punya riwayat KDRT.”
Kondisi itu diperparah dengan keadaan ekonomi yang sulit, sehingga orang mudah stres karena kebutuhan keluarga tak terpenuhi. Pelaku, kata dia, tak bisa mengatasi emosi dengan baik.
“Jika ada sesuatu yang tak beres, anak dan istri sebagai kelompok rentan yang menjadi korban,” ujarnya.
Mencegah kekerasan
Tiasri mengungkapkan, selama pandemi Covid-19 banyak rumah aman—tempat tinggal sementara untuk memberikan perlindungan terhadap korban—yang tutup. Hal itu menjadi penyebab Komnas Perempuan sulit mendapat pengaduan, sedangkan korban butuh rumah aman. Pandemi juga menyulitkan Komnas Perempuan saat ingin memberikan rujukan ke lembaga pendamping untuk korban.
“Karena ada keterbatasan akses di saat pandemi Covid-19,” ucapnya.
Sementara Zuma mengatakan, meski rumah aman milik pemerintah buka, tetapi sulit diakses karena harus melampirkan surat keterangan bebas Covid-19. Kondisi ini membuat LBH APIK bersama Jakarta Feminist berinisiatif menggalang donasi untuk menyediakan rumah aman.
“Dalam kasus kekerasan rumah tangga, penting untuk memisahkan korban dengan pelaku demi menghindari kejadian yang lebih buruk,” ujar Zuma.
Zuma menerangkan, jika korban tetap tinggal satu atap bersama pelaku, keadaan itu membuat korban kesulitan mengakses layanan konsultasi. Bila ingin melakukan pengaduan, harus menunggu pelaku tidak ada di rumah.

“Jangan sampai korban itu pilihannya ada dua, mati di rumahnya sendiri atau mati karena Covid-19,” katanya.
Zuma mengapresiasi pemerintah yang sudah mengeluarkan protokol penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi Covid-19. Protokol itu diterbitkan Deputi Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun, ia mengingatkan agar penerapannya juga melihat realitas di lapangan.
“Apakah mereka (pemerintah) sudah melakukan penanganan dengan baik kepada perempuan yang mengadu, baik secara online maupun offline?” ujarnya.
Pemerintah, melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga menerbitkan protokol penanganan anak korban tindak kekerasan dalam situasi pandemi Covid-19. Zuma berharap, pemerintah bisa memaksimalkan perannya untuk membantu perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan selama pandemi Covid-19.
Guna mencegah masalah di keluarga yang berujung kekerasan, Bagong berpendapat masing-masing anggota keluarga harus menyadari pentingnya arti kesetaraan.
"Harus ada 'kontrak' antara pasangan untuk saling mau menghargai. Kalau itu tidak ada, sepanjang dia patriarkis, pasti ada kekerasan," ucapnya.
Sedangkan Sani menyarankan perlu ada bonding time—waktu yang dihabiskan bersama-sama dengan keluarga untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Sani mengatakan, hal itu penting agar masing-masing anggota keluarga bisa saling memahami dan komunikasi menjadi lancar.
Setelah hal itu sudah dilakukan, maka ketika ada problem bisa diselesaikan secara baik-baik. Sebaliknya, bila bonding time tidak dilakukan, sewaktu ada problem akan muncul sisi ego dan menyalankan anggota keluarga lain.
“Jadi sebenarnya kebersamaan dulu. Dari situ baru nanti muncul solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah,” ucapnya.