
Ancaman golput dan silent voters dalam pemilu
Di tengah pertarungan antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto, gambar telapak tangan berlatar putih dengan tulisan “saya golput” menghiasi media sosial beberapa bulan menjelang Pemilu 2019. Mereka mengambil sikap tidak memilih siapa pun di pesta demokrasi.
Ada pula warganet yang meski tak memasang foto profil “saya golput” itu, kerap memposisikan dirinya absen dalam pemilu, dengan tulisan-tulisan statusnya. Salah satunya Bilven Rivaldo Gultom atau lebih dikenal Bilven Sandalista.
Tak memilih karena kecewa
Di media sosialnya, Bilven menyuarakan sikapnya untuk tidak memilih alias golput. “Tidak ada pilihan dari pilihan yang tersedia,” kata Bilven saat dihubungi reporter Alinea.id, Senin (15/4).
Menurutnya, ada tiga hal yang membuatnya bersikap absen. Pertama, ia memprotes keadaan politik yang ada. Kedua, ia menghukum mereka yang pernah terpilih karena umbar janji, tetapi setelah terpilih ingkar janji dan mengkhianati suara pemilihnya. Ketiga, ingin menunjukkan gerakan oposisi rakyat yang sebenarnya, karena oposisi yang ada tidak menjalankan fungsinya.
“Kedua pasangan calon harusnya sama-sama dirugikan,” ujar Bilven.
Menanggapi fenomena golput, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin mengatakan, bila golput diartikan sebagai warga yang punya hak pilih, tetapi tak datang ke tempat pemungutan suara (TPS), maka punya dampak signifikan terkait jumlah suara.
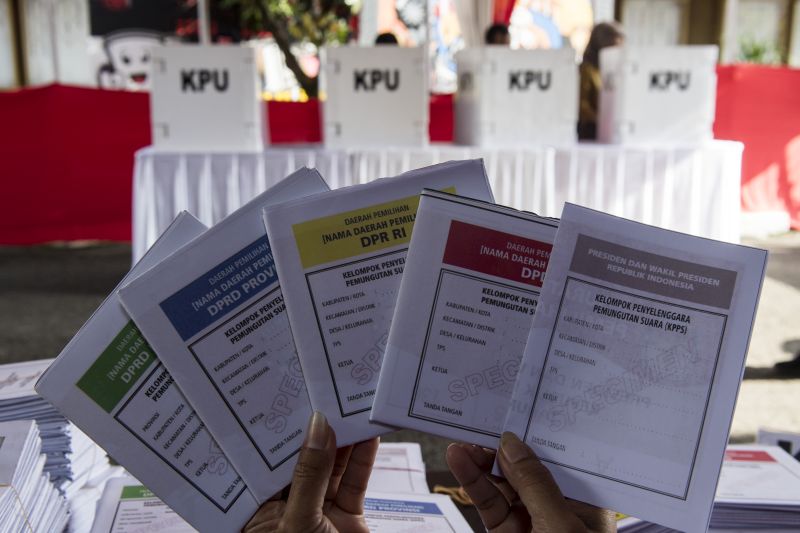
“Semakin besar jumlah golput, semakin punya dampak bagi politik Indonesia,” tutur Usep saat dihubungi, Senin (15/4).
Usep menuturkan, ada tiga alasan mengapa golput tinggi. Pertama, tanda kurang berkualitasnya peserta pemilu. Kedua, tanda kurang melayaninya penyelenggara pemilu. Ketiga, tanda banyak warga berhak pilih yang tak menjadikan pemilu sebagai peristiwa penting.
Menurut Usep, golput bisa saja merugikan dua kubu kandidat bila angkanya 20% golput administratif. Golput administratif merupakan orang-orang yang punya hak pilih, tetapi tak bisa memilih lantaran persoalan administrasi.
“Mengapa tak menginisiasi menjemput bola untuk mendata 20% ini, lalu melayaninya? Bukankah suara dan kursi kekuasaan adalah hal yang paling diinginkan politisi?” kata Usep.
Jika golput 10% bersifat ideologis, Usep menduga yang dirugikan kubu Jokowi. Golput ideologis ini muncul, kata dia, karena kinerja Jokowi pada 2014-2019 cukup mengecewakan kelompok prodemokrasi.
Alasan kedua, sebut Usep, karena Jokowi berpasangan dengan Ma’ruf Amin. Usep mengatakan, banyak pemilih Jokowi pada 2014 yang bosan dengan politik agama di kubu Prabowo. Ketika Jokowi memilih berpasangan dengan Ma’ruf, hal ini menjadi sama saja.
“Jejak rekam Ma’ruf Amin tak bagus dalam perspektif prodemokrasi, khususnya untuk isu keragaman dan kebebasan,” tutur Usep.
Mendekati pencoblosan, golput menjadi ancaman kedua kubu. Alasannya, kata Usep, sangat klise. Kedua kubu membutuhkan suara untuk dikonversi mendapatkan kursi kekuasaan. Usep mencatat, ada dua hal yang paling ditakuti politisi dan partai politik. Pertama, tak bisa ikut pemilu. Kedua, tak dapat suara.
“Sehingga kampanyenya bisa menggunakan banyak cara untuk menyerang golput. Bisa mengancam pidana, bisa ditawari politik uang, bisa mengharamkan golput, juga menyebut golput sebagai sikap bodoh, gila, atau benalu, dan sebagainya,” ucapnya.
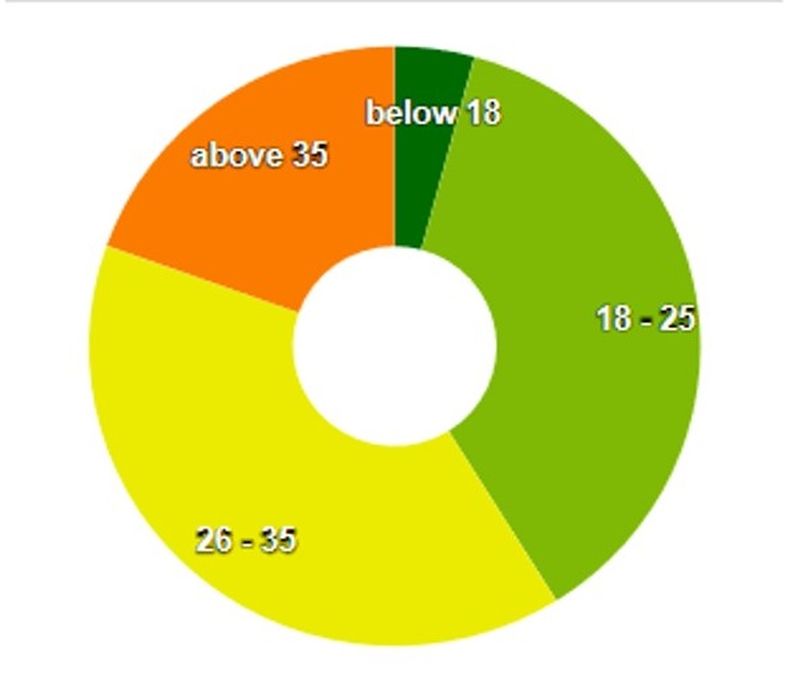
Di tengah pertarungan antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto, gambar telapak tangan berlatar putih dengan tulisan “saya golput” menghiasi media sosial beberapa bulan menjelang Pemilu 2019. Mereka mengambil sikap tidak memilih siapa pun di pesta demokrasi.
Ada pula warganet yang meski tak memasang foto profil “saya golput” itu, kerap memposisikan dirinya absen dalam pemilu, dengan tulisan-tulisan statusnya. Salah satunya Bilven Rivaldo Gultom atau lebih dikenal Bilven Sandalista.
Tak memilih karena kecewa
Di media sosialnya, Bilven menyuarakan sikapnya untuk tidak memilih alias golput. “Tidak ada pilihan dari pilihan yang tersedia,” kata Bilven saat dihubungi reporter Alinea.id, Senin (15/4).
Menurutnya, ada tiga hal yang membuatnya bersikap absen. Pertama, ia memprotes keadaan politik yang ada. Kedua, ia menghukum mereka yang pernah terpilih karena umbar janji, tetapi setelah terpilih ingkar janji dan mengkhianati suara pemilihnya. Ketiga, ingin menunjukkan gerakan oposisi rakyat yang sebenarnya, karena oposisi yang ada tidak menjalankan fungsinya.
“Kedua pasangan calon harusnya sama-sama dirugikan,” ujar Bilven.
Menanggapi fenomena golput, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin mengatakan, bila golput diartikan sebagai warga yang punya hak pilih, tetapi tak datang ke tempat pemungutan suara (TPS), maka punya dampak signifikan terkait jumlah suara.
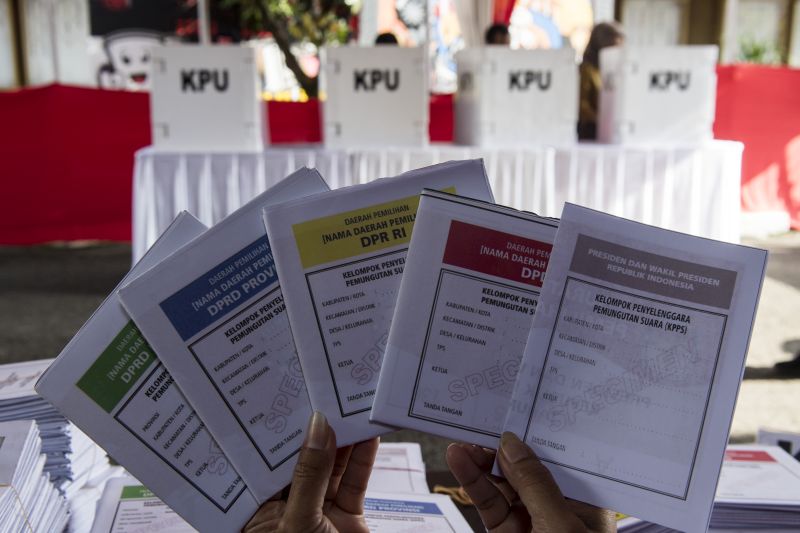
“Semakin besar jumlah golput, semakin punya dampak bagi politik Indonesia,” tutur Usep saat dihubungi, Senin (15/4).
Usep menuturkan, ada tiga alasan mengapa golput tinggi. Pertama, tanda kurang berkualitasnya peserta pemilu. Kedua, tanda kurang melayaninya penyelenggara pemilu. Ketiga, tanda banyak warga berhak pilih yang tak menjadikan pemilu sebagai peristiwa penting.
Menurut Usep, golput bisa saja merugikan dua kubu kandidat bila angkanya 20% golput administratif. Golput administratif merupakan orang-orang yang punya hak pilih, tetapi tak bisa memilih lantaran persoalan administrasi.
“Mengapa tak menginisiasi menjemput bola untuk mendata 20% ini, lalu melayaninya? Bukankah suara dan kursi kekuasaan adalah hal yang paling diinginkan politisi?” kata Usep.
Jika golput 10% bersifat ideologis, Usep menduga yang dirugikan kubu Jokowi. Golput ideologis ini muncul, kata dia, karena kinerja Jokowi pada 2014-2019 cukup mengecewakan kelompok prodemokrasi.
Alasan kedua, sebut Usep, karena Jokowi berpasangan dengan Ma’ruf Amin. Usep mengatakan, banyak pemilih Jokowi pada 2014 yang bosan dengan politik agama di kubu Prabowo. Ketika Jokowi memilih berpasangan dengan Ma’ruf, hal ini menjadi sama saja.
“Jejak rekam Ma’ruf Amin tak bagus dalam perspektif prodemokrasi, khususnya untuk isu keragaman dan kebebasan,” tutur Usep.
Mendekati pencoblosan, golput menjadi ancaman kedua kubu. Alasannya, kata Usep, sangat klise. Kedua kubu membutuhkan suara untuk dikonversi mendapatkan kursi kekuasaan. Usep mencatat, ada dua hal yang paling ditakuti politisi dan partai politik. Pertama, tak bisa ikut pemilu. Kedua, tak dapat suara.
“Sehingga kampanyenya bisa menggunakan banyak cara untuk menyerang golput. Bisa mengancam pidana, bisa ditawari politik uang, bisa mengharamkan golput, juga menyebut golput sebagai sikap bodoh, gila, atau benalu, dan sebagainya,” ucapnya.
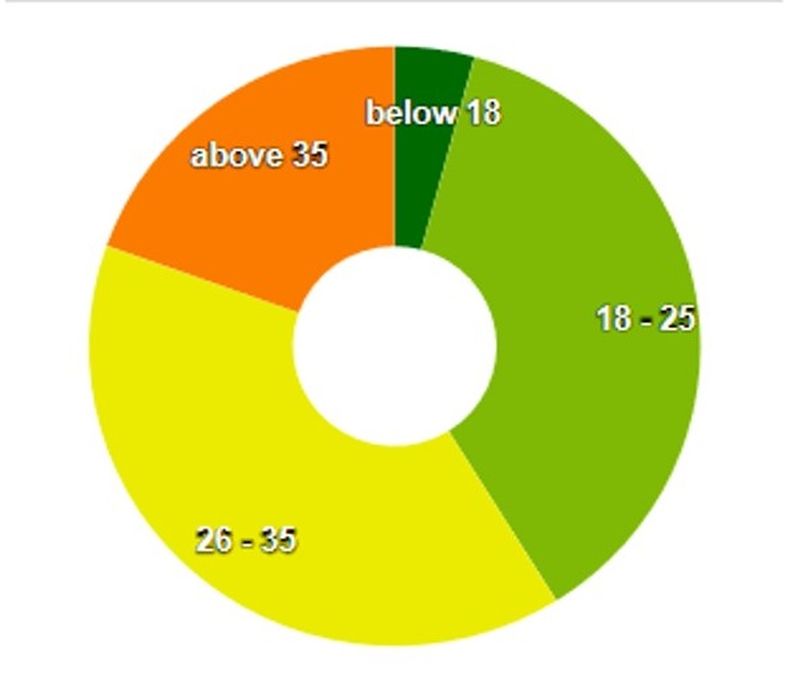
Bersembunyi dalam kerumuman
Selain fenomena golput, dalam pemilu ada pemilih galau (swing voters) dan yang menyembunyikan pilihannya (silent voters). Di saat semua orang berlomba-lomba mengabarkan ia memilih Joko Widodo atau Prabowo Subianto di media sosial, silent voters justru diam seribu bahasa.
Biasanya mereka bekerja di institusi pemerintah. Salah seorang yang tak mau mengungkapkan pilihannya di media sosial adalah Yuli, bukan nama sebenarnya. Selain berprofesi sebagai penulis, kini Yuli bekerja sebagai petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Kepada reporter Alinea.id, meski masih pesimis dengan dua pasangan calon, ia lebih cenderung memilih Jokowi. Ada alasan mengapa Yuli menyembunyikan pilihannya alias memposisikan diri sebagai silent voters.
“KPPS gue hampir 80% memilih kubu 02,” katanya saat dihubungi, Senin (15/4).
Yuli mengakui, masih banyak utang pemerintahan Jokowi, terutama menuntaskan kasus hak asasi manusia. Namun, aktivis 1998 ini tetap berat mendukung Jokowi lagi, ketimbang Prabowo.
“Indonesia butuh sosok untuk mengubah mindset, jadi motivator untuk anak-anak muda. Tidak harus jadi militer, anak pejabat, atau anak bekas presiden di masa lampau untuk bisa berkarier di politik,” ujarnya.
Rahma, bukan nama sebenarnya, yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil juga masih menyembunyikan pilihannya kepada orang lain. Selain alasan ada aturan pemerintah yang mewajibkan PNS netral dalam pemilu, ia juga tak ingin mengumbar pilihannya itu.
“Tapi namanya manusia pasti tetap saja bakalan memihak ke salah satu paslon,” ujar Rahma saat dihubungi, Senin (15/4).
Rahma mengaku, akan mencoblos pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno pada 17 April 2019 nanti. Ia mengatakan, agak takut mengumbar pilihannya itu secara terang-terangan.
“Kalaupun ada aspirasi politik yang ingin saya utarakan, biasanya saya berdiskusi dengan keluarga ataupun teman dekat, dengan intonasi dan tutur kata yang netral. Tidak sebagai pendukung garis keras,” katanya.
Hal senada diungkapkan Sukma, juga bukan nama sebenarnya. Salah seorang PNS di sebuah institusi pemerintah ini harus menutup rapat-rapat pilihannya. Justru dengan diam dan memantau, menurut Sukma, ia semakin tahu mana orang yang benar-benar bijaksana, paham politik, ataupun yang golput.
“Dari sini gue pribadi justru bisa jadi lebih rasional untuk enggak fanatik calon 01 dan enggak terlalu ngerendahin calon 02,” kata Sukma.
Sukma mengatakan, orang-orang terdekatnya mengetahui pilihan politiknya, yakni memilih Jokowi. Terkadang, meski berseberangan pilihan, kata dia, respons yang didapat lebih kepada gurauan daripada perdebatan.
“Kalau sedikit yang tahu itu, bahkan kalau berseberangan sama pilihan dengan dia, ya paling kita cengcengan (saling ledek) aja satu sama lain,” tuturnya.

Menguntungkan oposisi?
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, silent voters bisa datang dari beragam profesi. Ia menuturkan, belum ada penelitian yang mengidentifikasi hal ini.
“Bisa saja dia profesor, tukang becak, atau petani,” kata Emrus saat dihubungi, Senin (15/4).
Silent voters, sebut Emrus, hanya persoalan budaya. Kata dia, ada tiga alasan seseorang tak mau diketahui pilihannya. Pertama, karena tak nyaman untuk menyatakan dukungan ke salah satu kubu. Kedua, karena memang merahasiakannya dari siapa pun. Ketiga, sebenarnya ia adalah pendukung militan salah satu pasangan, tetapi tak mau diketahui militansinya.
Sementara itu, pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satro mengatakan, fenomena silent voters secara jumlah belum bisa diketahui.
“Karena bisa banyak banget,” kata dia saat dihubungi, Senin (15/4).
Menurutnya, konstestasi pilpres saat ini suara perhitungan cepat belum bisa dijadikan acuan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Hendri mengatakan, para silent voters itu belum ingin diketahui pilihan mereka dalam pemilu.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Developing Counties Studies Center (DCSC) Zaenal Budiyono menuturkan, kekuatan silent voters tak bisa diketahui lantaran ketika disurvei mereka tak menjawab pilihannya.
“Alasanya beragam, mulai dari alasan personal, keamanan, hingga melihat tren di sosial media,” katanya saat dihubungi, Senin (15/4).
Menurut dia, silent voters punya kekuatan yang cukup besar untuk menentukan arah hasil pemilihan. Ia mencontohkan kasus Pilkada DKI Jakarta 2017, yang mempertemukan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno. Hasil pertarungan tersebut, hasil akhir pemilihan mampu menjungkalkan hasil survei.
“Sejumlah lembaga survei mengakui ‘gangguan’ silent voters ini, sehingga membuat hasil surveinya jauh dari realitas,” ucapnya.
Lebih lanjut, dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini mengatakan, melihat kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 itu, banyak silent voters digerakkan warga biasa, bukan elite politik. Ia menuturkan, sebelumnya petahana dianggap terlalu kuat dan tak tergoyahkan, tetapi akhirnya kalah.
“Artinya ada ‘agenda bersama’ yang tidak terbaca oleh pollster (lembaga survei), karena bukan agenda partai atau elite. Tapi ini agenda masyarakat biasa,” kata Zaenal.
Zaenal berpendapat, bila melihat tren yang ada di negara lain, silent voters cenderung menguntungkan pihak oposisi.
Kemunculan silent voters, katanya, juga dapat dipengaruhi menyempitnya ruang partisipasi politik yang dimiliki warga, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah banyak memakan korban.
“Banyak voters (pemilih) yang khawatir bila mereka menunjukkan pilihannya secara terbuka. Akhirnya, mereka menyembunyikan pilihannya. Termasuk ke lembaga survei,” ujar Zaenal.








