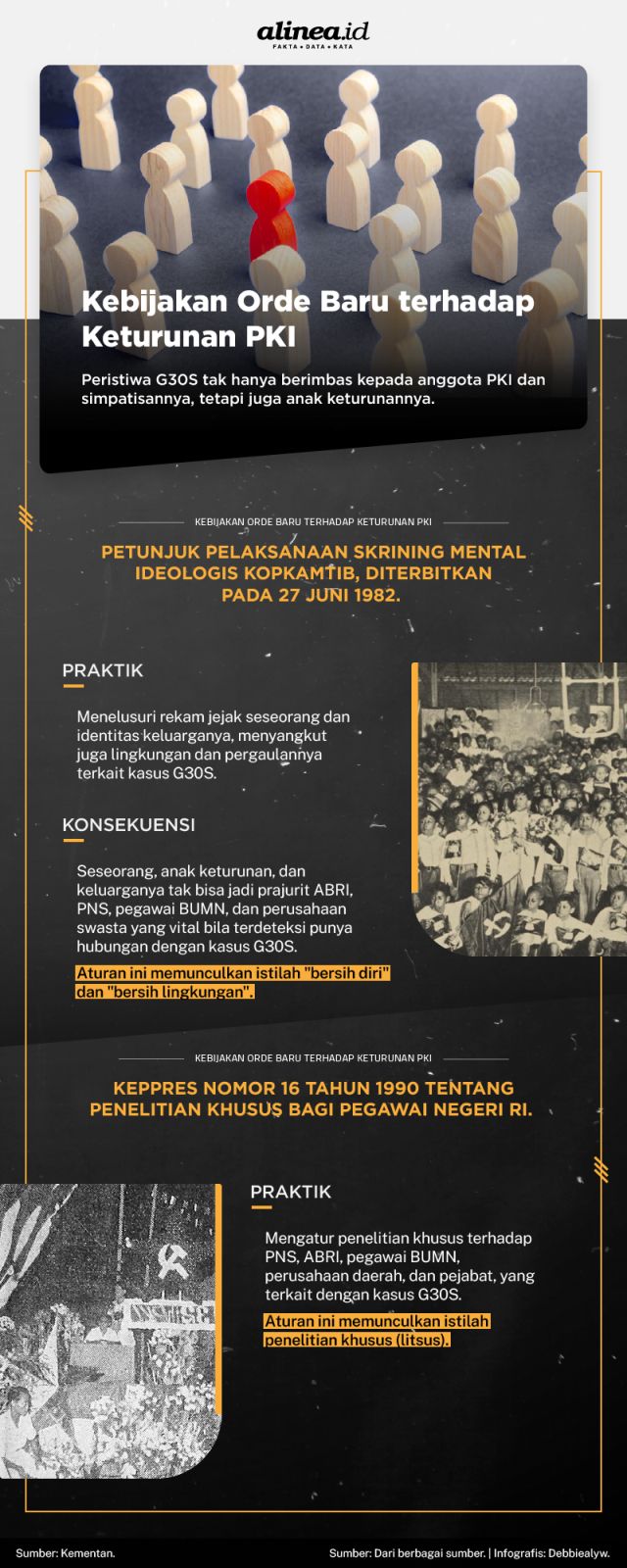Memelihara “dosa turunan” PKI ala Orde Baru
Pada akhir 1987, seorang sarjana ekonomi bernama Surya—nama samaran—berhasil lolos serangkaian tes masuk ke perusahaan minyak milik swasta asing, rekanan Pertamina. Namun, langkahnya terhenti di tes terakhir: skrining mental ideologis.
Kala itu, tim penyeleksi berhasil menemukan rekam jejak ayah mertuanya, yang bekas tahanan politik (tapol) tragedi 1965—atau yang dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S).
“Padahal, ketika ia menikah, ayah mertuanya sudah meninggal,” tulis Tempo, 12 November 1988 dalam artikel “Menembus Tembok Bernama Skrining”.
Pertamina, tulis Tempo, punya perjanjian khusus dengan perusahaan minyak swasta asing itu. Ketika kontrak tak diperpanjang, karyawan lokalnya akan dialihkan ke Pertamina. Hanya saja, perusahaan minyak nasional itu tak akan menerima karyawan yang tak “bersih lingkungan”.
“Bersih diri” dan “bersih lingkungan”
Bersih lingkungan, memiliki istilah pasangan, yakni “bersih diri”. Menurut Hersri Setiawan dalam Kamus Gestok (2003), istilah bersih lingkungan ditujukan pada keluarga eks tapol G30S dan mereka yang terindikasi anggota PKI atau ormasnya. Rezim Orde Baru menganggap orang-orang itu “kotor lingkungan.”
“Adapun luas radius kaitannya sejak tiga generasi, dalam hubungan sanak keluarga horizontal (saudara, istri, mertua, menantu, kawan dekat) dan vertikal (ayah, ibu, anak, dan cucu),” tulis Hersri.

Masyarakat akrab dengan istilah bersih diri dan bersih lingkungan usai pada 27 Juni 1982, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) mengeluarkan petunjuk pelaksanaan—yang intinya melakukan skrining mental ideologis terhadap calon prajurit ABRI, pelamar pegawai negeri sipil (PNS), BUMN, dan perusahaan swasta vital.
“Dalam skrining itu, selain keterlibatan seseorang dengan G 30 S/PKI, diteliti pula identitas keluarganya yang menyangkut keadaan lingkungan, tempat tinggal, dan pergaulan,” tulis Tempo, 12 November 1988.
“Itu meliputi lingkungan keluarga, persaudaraan, dan pergaulan yang dominan atau sangat berpengaruh pada sikap, perilaku, dan mental ideologis seseorang.”
Sebelumnya, terbit juga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G30S/PKI.
Segala peraturan itu dikeluarkan setelah rezim Orde Baru membebaskan tapol di Pulau Buru, dan beberapa penjara serta kamp lain pada 1979. Sejarawan Baskara T. Wardaya dalam tulisannya “Menengok Kembali Pemerintahan Soeharto dan Orde Baru secara Kritis” di buku Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto (2007) menerangkan, rezim Orde Baru tetap menghukum eks tapol itu dengan cara membubuhkan kode ET (eks tapol) di KTP mereka.
Anak keturunan mantan tapol tak punya kesempatan bekerja di sektor publik, jika tak lolos skrining. Apalagi berharap menjadi anggota ABRI.
“Seorang calon prajurit ABRI tak hanya harus bebas dari keterlibatan dengan PKI, tetapi juga tak boleh punya anggota keluarga dan lingkungan yang terlibat G30S/PKI,” tulis Tempo, 17 September 1988.
Tempo menyebut, pernah ada taruna Akabri yang dikeluarkan karena terungkap punya keluarga mantan anggota PKI. Sebelumnya juga ada beberapa perwira menengah lulusan Akabri yang diberhentikan dari dinas aktif karena masalah serupa.
“Anggota ABRI yang masuk kategori C1 harus dipecat. Sedangkan kategori C2 dan C3 dipercepat pensiun, tanpa diizinkan menduduki jabatan apa pun,” tulis Tempo, 12 November 1988.
Pada 1967, kata Soeharto dalam buku Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1989), para tapol diklasifikasi dalam tiga golongan. Mereka yang dianggap terlibat langsung dalam G30S masuk golongan A.
“Golongan B, yang aktif mendukung PKI dan terlibat secara tak langsung dalam G30S, dan golongan C mereka yang sekadar menjadi anggota organisasi massa PKI tanpa memainkan peranan kepemimpinan yang aktif,” ujar Soeharto.
Kepada Tempo, Kepala Staf Kopkamtib Jenderal (Purn) Widjojo Soejono yang menerbitkan petunjuk pelaksanaan skrining mental ideologis mengatakan, penelusuran jejak keluarga hanya diberlakukan hingga generasi kedua. Artinya, anak dari orang-orang yang dituduh terlibat G30S tak diizinkan menjadi anggota ABRI.
“Dalam agama Islam memang tak dikenal istilah dosa turunan. Jadi, ini bisa dianggap bertentangan. Tapi, ini kan kita kaitkan dengan risiko keamanan,” kata Widjojo kepada Tempo, 12 Mei 1990.
Aturan yang tadinya cuma untuk mereka yang akan daftar menjadi prajurit ABRI, lambat laun merembet ke instansi pemerintah dan perusahaan swasta vital. Meski begitu, pemerintah Orde Baru mengklaim, bagi PNS aturan bersih lingkungan agak longgar.
“Untuk PNS, yang terdeteksi golongan C tadi, masih diizinkan bekerja hingga usianya 50 tahun. Namun, mereka tak boleh ada di jabatan strategis,” tulis Tempo, 12 November 1988.
Tampaknya, kebijakan bagi PNS itu dilonggarkan karena rezim Orde Baru membutuhkan mereka yang sudah terlanjur lolos PNS. Jumlahnya tak main-main.
“Menurut laporan terakhir, masih ada 1.000 PNS di semua departemen terdiri atas golongan C2 dan C3 itu,” tulis Tempo.
Skrining mental ideologis itu pun berlaku bagi mereka yang ingin menjadi guru, anggota partai politik dan Golkar, wartawan, lurah, anggota lembaga bantuan hukum, pendeta, hingga dalang.
Meski demikian, ada beberapa anak eks tapol yang berhasil menjadi PNS dengan segala siasat. Sejarawan Amurwani Dwi Lestariningsih mengungkapkannya dalam buku Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan (2011).
Plantungan di Kendal, Jawa Tengah menjadi kamp konsentrasi bagi tapol perempuan yang terindikasi PKI dan anggota Gerwani. Sukini, misalnya. Ia mengganti status orang tua dan desa asal anak-anaknya dalam akta kelahiran dan dokumen lainnya. Dengan siasat itu, anak-anak Sukini dapat diterima sebagai PNS.
Anak eks tapol Plantungan lainnya, Sutiah, juga berhasil lolos skrining. Anaknya tak kesulitan meneruskan sekolah dan mendapat pekerjaan sebagai PNS karena ia mencantumkan data orang tua anaknya dalam dokumen resmi pemerintah, dengan nama saudara jauhnya yang tak pernah terlibat kegiatan organisasi beraliran komunis.
“Pengasuhan anaknya pun diserahkan kepada saudara jauhnya,” tulis Amurwani.
Bersalin nama jadi litsus

Seiring waktu, aturan bersih diri dan bersih lingkungan menimbulkan kegaduhan. Saling tuding tak bersih diri dan tak bersih lingkungan terjadi antara teman sekantor, tetangga, bahkan pejabat. Tak jarang hal itu menjadi alat untuk menjatuhkan lawan politik. Isu tak sedap itu biasanya dilempar melalui surat kaleng.
Wakil Presiden Sudharmono pernah dituduh sebagai mantan anggota Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) dan terlibat peristiwa Madiun 1948. Desas-desus tersebut segera dibantah Sudharmono pada 18 Oktober 1988.
“Isu itu berasal dari surat kaleng. Dan ada yang termakan isu itu,” tulis Tempo, 12 November 1988.
Selain Sudharmono, tulis Tempo, isu tak bersih diri atau tak bersih lingkungan pun menimpa Sekjen DPP PPP Mardinsyah, Sekjen DPP PDI Nico Daryanto, Ketua Umum DPP PPP J. Naro, dan Gubernur Sumatera Barat Hasran Basri Durin.
Karena bersih diri dan bersih lingkungan memiliki kriteria yang sumir dan membuka peluang penyalahgunaan wewenang, Soeharto kemudian menerbitkan kebijakan baru, yakni Keppres Nomor 16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri RI. Kebijakan itu tenar dengan istilah penelitian khusus (litsus).
Pada September 1988 rezim Orde Baru juga menghapus Kopkamtib, diganti dengan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas).
Meski sudah diganti, menurut Abdoel Fattah dalam Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer, 1945-2004 (2005), Kopkamtib dan Bakorstanas pada prinsipnya mengemban tugas yang nyaris sama.
“Diberi kewenangan darurat yang luar biasa untuk mengambil langkah-langkah guna menciptakan stabilitas keamanan,” tulis Abdoel.
Organisasi itu lah yang diberi wewenang mengawasi dan melaksanakan jalannya litsus. Dalam sebuah kesempatan, seperti dilansir dari Tempo edisi 12 Mei 1990, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Moerdiono mengatakan, Keppres Nomor 16 Tahun 1990 dapat meluruskan kesimpangsiuran dan keresahan yang selama ini terjadi tentang ketentuan bersih diri dan bersih lingkungan.
Akan tetapi, prinsip litsus mirip dengan skrining mental ideologis. Beleid yang terdiri dari 14 pasal itu mengatur litsus terhadap PNS, ABRI, pegawai BUMN, perusahaan daerah, dan pejabat, yang terkait dengan G30S.
Dalam wawancaranya kepada Kompas edisi 19 Mei 1990, Ketua Yayasan LBH Indonesia Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan, litsus lebih lunak dari bersih lingkungan.
“Sebab yang diteliti hanya keterlibatan yang bersangkutan, bukan seluruh kerabat atau keluarganya, dalam kegiatan partai terlarang,” kata Abdul Hakim.
Lagi-lagi, hal itu tak berlaku bagi ABRI, yang memberi persyaratan tambahan lebih ketat.
Menurut Hermawan Sulistyo dan Putri Ariza Kristimanta dalam “Intelijen, Arus Demokratisasi, dan Akhir Kekuasaan Soeharto, 1988-1998” di buku Intelijen dan Kekuasaan Soeharto (2022), litsus diterapkan untuk menelusuri data pribadi orang-orang yang bekerja di sektor publik, terutama para pejabat, untuk memperoleh data lanjutan.
“Hasilnya dapat berupa sekadar pengumpulan data, pengumpulan bahan keterangan, tetapi dapat pula langsung diikuti oleh keputusan operasional,” tulis Hermawan dan Putri.
Hermawan dan Putri menyebut, seseorang yang menjalani litsus akan diberi daftar pertanyaan tentang keluarga besarnya, tak hanya keluarga inti. Litsus lalu dimanfaatkan guna membantu tugas intelijen dari tingkat atas hingga bawah.
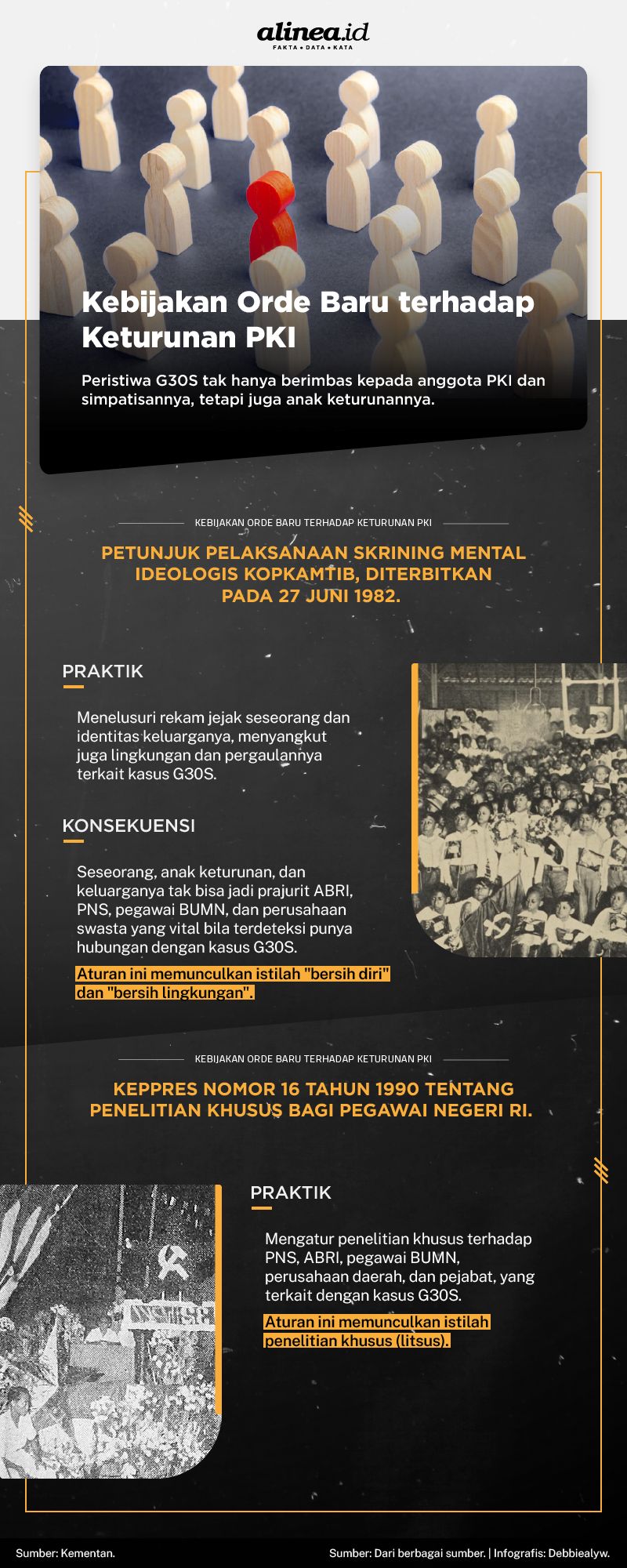
Walau pada praktiknya litsus dikenakan kepada mereka yang dianggap terlibat kasus G30S secara langsung maupun tak langsung, tetapi Hersri mengungkapkan, kegiatan itu juga ditujukan kepada mereka yang diduga terlibat dalam gerakan dan organisasi terlarang lainnya, seperti DI/TII, PRRI/Permesta, Masyumi, dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Dengan kata lain, tak hanya ekstrem kiri, golongan ekstrem kanan pun ikut disisir.
Di masa pemberlakuan litsus, rezim Orde Baru pun banyak menyasar anggota parlemen. Hal ini tentu membuat deg-degan mereka yang duduk di kursi DPR.
Salah satu yang paling masif adalah litsus yang dilakukan Bakorstanas kepada 50 anggota DPR pada 1995. Menurut Kompas edisi 21 Desember 1995, kegiatan itu dilakukan setelah fraksi ABRI di DPR mendapatkan laporan dari Yayasan Solidaritas Masyarakat Demokrat (YSMD) tentang dugaan 50 anggota DPR yang terlibat G30S.
Gelombang reformasi mengakhiri kekuasaan Soeharto dan Orde Baru pada 1998. Pada Maret 2000, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur membubarkan Bakorstanas. Lalu, lewat Keppres Nomor 39 Tahun 2000, mencabut Keppres Nomor 16 Tahun 1990.
Kala itu, mewakili Gus Dur, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dengan dicabutnya Keppres Nomor 16 Tahun 1990 kegiatan litsus tak diperlukan lagi bagi calon PNS, anggota DPR, notaris, dan sebagainya.
“Selama ini (litsus) selalu menjadi momok masyarakat, baik di kalangan PNS maupun politikus,” ujar Yusril, dikutip dari Kompas, 9 Maret 2000.